Pelonggaran Menyingkap Wajah Kota-kota yang Kepayahan
Seiring pelonggaran kala pandemi melandai, kota-kota yang tidak siap dengan infrastruktur utama seperti jaringan jalan, transportasi umum, air bersih, manajemen limbah, ruang publik hingga adaptasi bencana pun kepayahan.
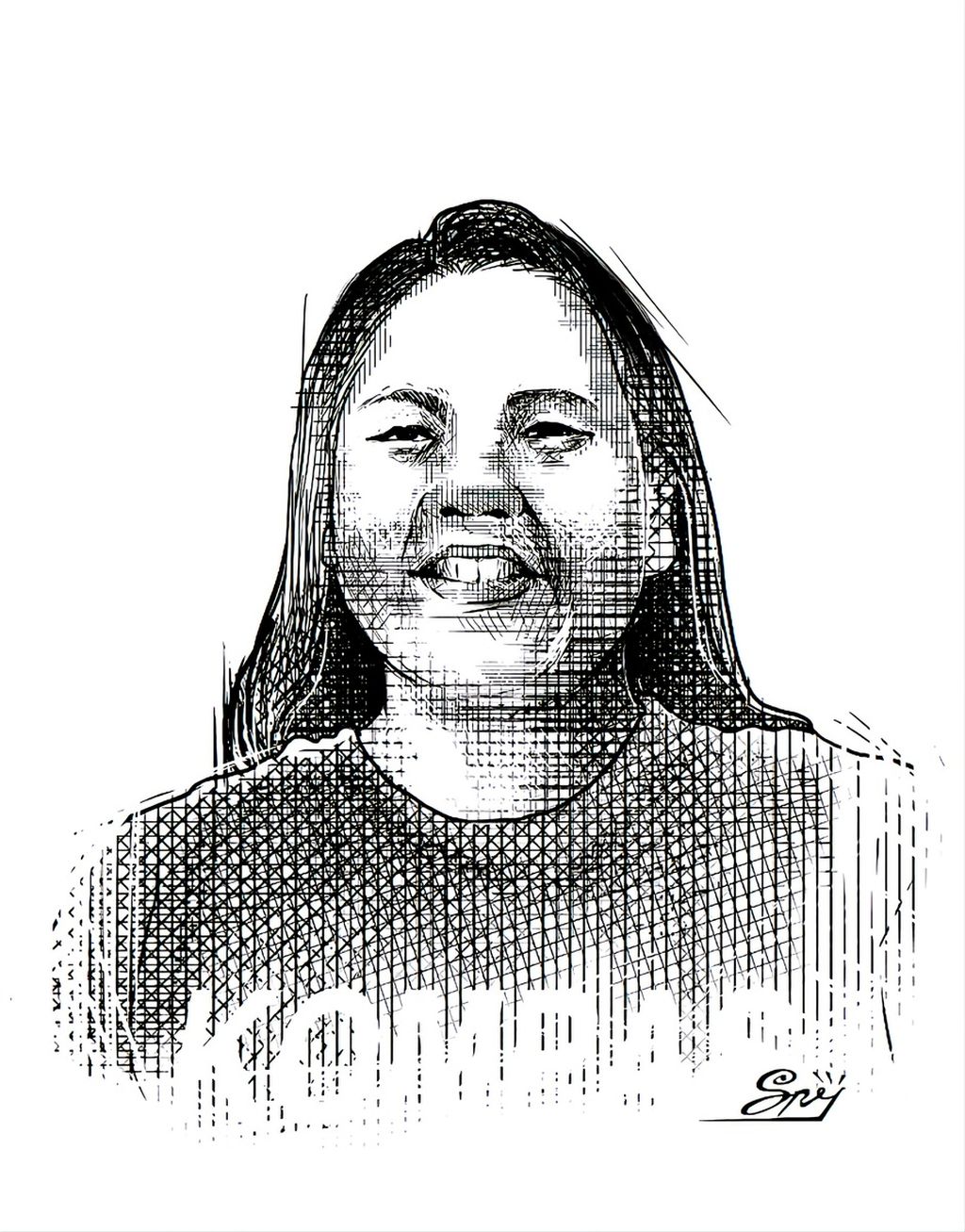
Kepadatan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya, juga keramaian di berbagai kawasan lain di Indonesia selama lebih dari sepekan terakhir, membangkitkan kenangan situasi seperti pada masa sebelum pandemi.
Keluhan susahnya menembus antrean kendaraan saat mengantar anak ke sekolah, ke tempat kerja, atau ke pusat perbelanjaan menyemarakkan percakapan luring maupun daring. Di jalanan, kembali ditemui wajah-wajah tegang pengendara yang didera kemacetan, klakson bersahutan, pertikaian antarpengendara, sesaknya udara yang dipenuhi gas buang mobil, maupun sepeda motor, sampai kesibukan polisi ”cepek” menimba rezeki dengan mengatur arus lalu lintas di persimpangan.
Tak ketinggalan para pengguna setia angkutan umum yang dipaksa merasakan lagi infrastruktur publik tak seragam, belum padu, dan sering kali menyengsarakan.
Saat turun dari KRL di Stasiun Pondok Ranji, Tangerang Selatan, misalnya, keluar dari stasiun yang cukup tertata dan nyaman, para komuter dihadapkan pada jalanan sempit padat tanpa trotoar. Ditambah lagi ada pelintasan sebidang antara rel dan jalan reguler. Antrean kendaraan bermotor nyaris tak putus. Pengguna jalan, terutama pejalan kaki, benar-benar terintimidasi oleh situasi di sana.
Baca juga : Air Tanah Solusi Krisis Air Bersih Perkotaan
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2021%2F11%2F23%2F5fecf627-0a6b-4f95-9971-ae1b43d27643_jpeg.jpg)
Pengendara sepeda motor menunggu kereta melintas di pelintasan kereta di bawah Jalan Layang Roxy, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.
Pengalaman serupa dirasakan banyak pengguna angkutan umum di stasiun-stasiun dan halte-halte bus lain. Ini terjadi karena belum semua halte dan stasiun tersentuh program penataan, apalagi kawasan di sekitarnya.
Pada saat bersamaan, kaum urban dihadapkan pada kekurangan infrastruktur kunci urban lain. Saat hujan deras mengguyur, sampah yang tebal mengendap di setiap saluran, menyumbat aliran lalu meluapkan airnya ke mana-mana. Arus lalu lintas bisa terhenti atau tersendat karena bagian-bagian jalan yang tergenang relatif dalam. Banjir di beberapa permukiman pun berulang.
Di permukiman, tempat-tempat sampah liar seperti lumrah ditemukan di sana-sini seiring tersendatnya layanan pengambilan sampah. Alasannya itu-itu saja, tempat pembuangan sampah tengah overload dan tidak ada alternatif tempat pembuangan lain, apalagi tempat pengolahan sampah terpadu.
Dari sisi air bersih, jaringan perpipaan baru hadir di kota-kota tertentu, meskipun masih jauh dari target melayani 100 persen warga di sana. Sementara, air sumur kadang berbau, tidak jernih, bahkan untuk mencuci piring dan pakaian pun tak layak. Perlu merogoh kocek dalam-dalam untuk bisa mengebor sumur lebih dalam demi menemukan air lebih bersih bersumber air tanah. Atau, untuk belanja air kemasan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ibaratnya sistem saraf dan peredaran darah, infrastruktur utama kota tersebut pada dasarnya harus saling terhubung dan memengaruhi. Tanpa keterpaduan satu sama lain, berarti ada koneksi yang tak tersambung dan bisa membahayakan metabolisme kota.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2020%2F04%2F30%2Fbec06e78-0ebf-43a3-b454-9f972193078c_jpg.jpg)
Aktivitas bongkar muat di gudang perusahaan air minum dalam kemasan di Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (28/4/2020).
Antara Lynch, Grigg, dan IPCC
Dalam buku-buku klasik panduan pembangunan dan penataan kota, selalu diingatkan tentang pentingnya menyediakan infrastruktur utama di perkotaan. Kevin Lynch dalam buku Good City Form (1981) dan Neil S Grigg dalam Infrastructure Engineering and Management (1988) adalah dua di antaranya.
Lynch berpendapatan, kota memiliki lima elemen pembentuk, yaitu vitality, sense, fit, access, dan control. Kelima elemen kualitatif tersebut dikuantitatifkan ke dalam 2 meta-kriteria, yakni efficiency dan justice. Kota sebagai tempat hidup banyak orang haruslah memiliki vitalitas atau daya hidup untuk berkembang, mudah diakses, terkontrol pertumbuhannya, sekaligus mampu memberikan pengalaman yang baik, bahkan indah bagi para penghuninya. Namun, kota dengan berbagai aktivitas maupun fungsi di dalamnya juga harus bisa selalu efisien dan berkeadilan bagi semua.
Oleh karena kota berkorelasi dengan sebuah tempat dengan luas terbatas yang dihuni banyak orang alias berkepadatan tinggi, kota ideal Lynch dapat diwujudkan hanya jika pengelola kota mampu membentuk serta menjalankan sistem-sistem layanan publik dengan baik.
Baca juga: Pekerja Perkotaan, Antara Paksaan Mundur dan Revolusi ”Kerah Baru”
Grigg lebih detail mencoba menuangkan kebutuhan infrastruktur vital kota dalam enam kategori besar, yaitu kelompok jalan, pelayanan transportasi publik, pengelolaan air (mencakup air bersih, air limbah, dan manajemen sungai serta saluran air lainnya), manajemen limbah (khususnya limbah padat, termasuk sampah rumah tangga hingga industri), bangunan dan fasilitas publik, serta produksi dan distribusi energi (di antaranya listrik dan bahan bakar minyak).

Di masa yang lebih modern sekarang, Grigg tak lupa menambahkan kebutuhan akan infrastruktur adaptasi bencana, termasuk terkait pemanasan global dan krisis iklim. Grigg kemudian menelurkan panduan air perkotaan, pengendalian banjir, dan manajemen air untuk industri modern.
Bak gayung bersambut, pada bab 6 laporan riset Panel Antar-pemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC) tentang kota, permukiman, dan infrastruktur kunci yang dipublikasikan Februari 2022, ditegaskan kebutuhan kota-kota di masa sekarang dan akan datang untuk beradaptasi di tengah krisis iklim. Masih berbasis infrastruktur utama urban seperti dicetuskan Lynch dan Grigg, adaptasi iklim IPCC menawarkan pengelompokan infrastruktur utama urban, yaitu yang berbasis sosial, berbasis alam, dan fisik.
Infrastruktur sosial mencakup kegiatan ataupun institusi sosial, budaya, keuangan, serta properti dan domain kebijakan seperti perlindungan sosial, kesehatan, dan pendidikan yang mendukung kesejahteraan kehidupan masyarakat. Infrastruktur berbasis alam berfokus pada pemulihan ekosistem kota dengan memperbanyak ruang terbuka hijau dan perairan terbuka yang membantu menurunkan suhu kawasan dan mengendalikan banjir. Infrastruktur fisik mengacu pada rekayasa menyediakan satu atau beberapa layanan, seperti transportasi publik, pengolahan air limbah, dan energi.
Keterpaduan dan percepatan pembangunan
Benang merah yang turut menghubungkan antara pemikiran klasik Lynch, Grigg, hingga periset-periset abad ke-21 adalah penekanan pada kebutuhan mewujudkan keterpaduan antarinfrastruktur utama. Ibarat sistem saraf dan peredaran darah, infrastruktur utama kota tersebut pada dasarnya harus saling terhubung dan memengaruhi. Tanpa keterpaduan satu sama lain berarti ada koneksi yang tak tersambung dan bisa membahayakan metabolisme kota.
Contoh ketidakpaduan infrastruktur kota, salah satunya bisa dilihat dari demam revitalisasi trotoar yang kini menghinggapi tidak hanya Jakarta, tetapi juga kota-kota lain di Indonesia. Namun, revitalisasi trotoar masih banyak yang sekadar mempercantik kawasan tertentu, tetapi melupakan peran vitalnya sebagai penghubung antara berbagai titik keberangkatan maupun tujuan pergerakan warga.
Baca juga: Sepiring Nasi untuk Kota yang Selalu Lapar
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F01%2F22%2F634a2e15-a7e4-466a-84e9-e1a571899c28_jpg.jpg)
Pejalan kaki menggunakan jalur pedestrian di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Sabtu (22/1/2022). Sejumlah aspek yang menjadi perhatian dalam rencana induk pembangunan jalur pejalan kaki adalah karakter pejalan kaki, kondisi lingkungan, dan konektvitas dengan angkutan publik.
Trotoar masuk dalam infrastruktur utama kelompok jalan. Trotoar dituntut dibangun aman, nyaman, dan dapat diakses penyandang disabilitas. Dengan kriteria itu, trotoar perlu merata di permukiman, pusat bisnis, perkantoran, pusat kegiatan publik, ruang terbuka, juga berbagai fasilitas pendidikan dan kesehatan yang menghubungkannya dengan simpul layanan transportasi publik dan akses bagi pesepeda.
Masih bicara ketidakpaduan infrastruktur utama, lihat saja kabel-kabel listrik, sambungan internet, dan telekomunikasi yang semrawut menjuntai di atas trotoar atau jalan, juga yang tertanam di trotoar ataupun saluran drainase. Kondisi itu sering menjebak kawasan kota itu menjadi rentan. Hujan lebat, tersenggol kendaraan, atau aktivitas lain bisa tak sengaja memutus kabel dan aliran energi, pergerakan orang maupun barang, serta memutus jaringan telekomunikasi.
Ya, inilah wajah perkotaan kita. Sebuah ironi di tengah semarak proyek gedung tinggi, mal-mal megah gemerlap, jalan tol yang seharusnya menjadi alternatif justru terus diperpanjang bahkan berlapis dua, dan latah digitalisasi di berbagai bidang. Di sisi lain, sistem layanan transportasi publik masih teramat rendah cakupan layanannya.
Di sisi lain, pejalan kaki, pesepeda, dan pengguna angkutan umum adalah pejuang aktivitas rendah emisi karbon yang perlu mendominasi perkotaan jika ingin mempercepat krisis iklim berakhir, isu global yang didengungkan sejak lama. Infrastruktur yang menunjang ketiganya seharusnya menjadi fokus pembangunan.
Baca juga: Berpacu Menyelamatkan Kota-kota Pesisir
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2019%2F11%2F23%2F041b9211-558d-4ac8-a573-3ee6d8268802_jpg.jpg)
Jalur sepeda di trotoar ruas Jalan Pintu Satu, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2019).
Senyatanya, kota-kota kita masih tertatih-tatih memupus ketertinggalan dalam penyediaan infrastruktur utamanya. Ketertinggalan itu semakin parah setelah dua tahun terakhir berbagai anggaran pembangunan infrastruktur dialihkan untuk penanganan pandemi.
Ibarat tubuh manusia, infrastruktur utama kota adalah organ-organ vital yang butuh selalu ada serta terjaga fungsinya agar area-area urban pusat pertumbuhan ekonomi negeri tersebut bisa berkembang sehat. Sebaliknya, jika terganggu, membahayakan dan berakibat fatal.
Pemerintah daerah maupun pusat sepatutnya memberi perhatian khusus demi percepatan pembangunan infrastruktur utama tersebut di wilayah masing-masing. Dengan demikian, kondisi yang menghadirkan kembali kepayahan manusia perkotaan di kala pelonggaran pembatasan bergulir seperti sekarang tak terus membebani dan berpotensi menjadi bencana fatal di kemudian hari.
Baca juga: Catatan Urban