Menangkap Peluang Transisi Energi dan Eletrifikasi Transportasi
Dalam beberapa tahun ke depan kita butuh pabrik berkapasitas relatif besar. Dengan asumsi semua bus BBM sudah harus beralih ke EBT pada (awal) 2030, tersisa waktu tujuh tahun. Perlu segera disiapkan regulasi terkait.
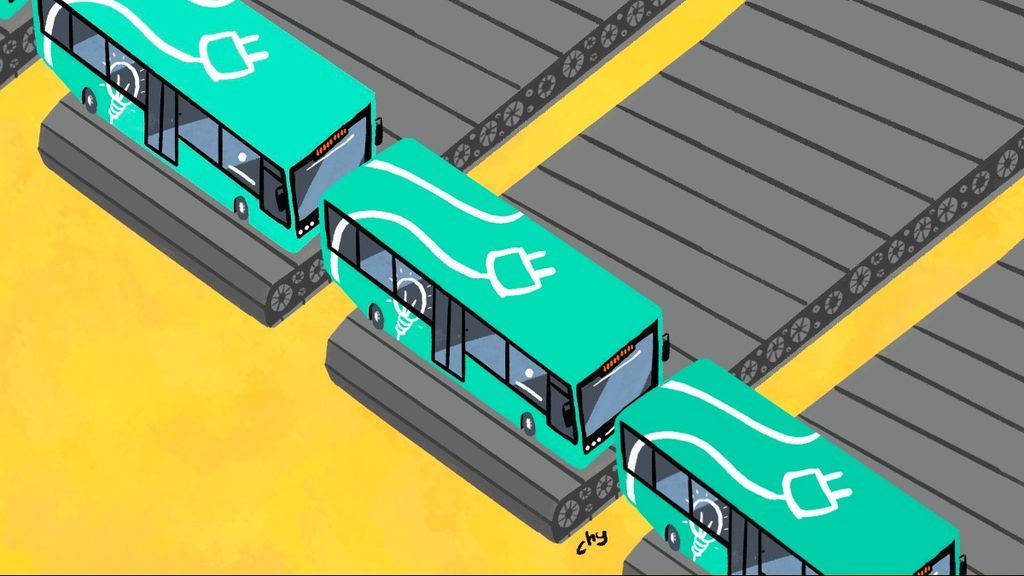
Ilustrasi
Implementasi paradigma ekonomi hijau membutuhkan komitmen yang kuat, kebijakan/regulasi yang tepat dan konsisten, serta ketersediaan dana yang memadai untuk mendukungnya.
Dalam perspektif New Institutional Economics, kebijakan/regulasi tersebut termasuk institusi formal.
KTT G20 di Bali telah membawa angin segar. Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo menandatangani kesepakatan dengan para mitranya dari G7 plus Denmark/Norwegia, untuk pendanaan transisi energi di Indonesia senilai 20 miliar dollar AS.
Dana itu bisa berbentuk utang luar negeri, dana investasi, atau hibah. Program pendanaan ini disebut Just for Indonesia Transition Energy Program’ (JITEP), di bawah program Just Energy Transition Partnership (JETP). Implementasi pendanaan ini akan berlangsung selama 2-5 tahun ke depan.
Dalam beberapa bulan mendatang akan ada satuan tugas (task force) yang khusus membahas secara detail, proyek mana saja yang akan didanai dengan skema JITEP. Dalam program JITEP/ JETP ini Indonesia menggunakan platform Energy Transition Mechanism (ETM) untuk pemetaan proyek.
Baca juga : Krisis Energi Global Mengintai, Transisi Energi Perlu Lebih Dipercepat
Baca juga : Kantongi Dana Lewat G20, Pemerintah Harus Buktikan Keseriusan Transisi Energi
PT Sarana Multi Infrastruktur/SMI (Persero) akan berperan sentral, bekerja sama dengan berbagai lembaga internasional dan domestik, termasuk Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Indonesia Investment Authority (INA).
Di sini antara lain akan dipetakan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mana saja yang akan diprioritaskan untuk dihentikan dan diganti dengan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT), khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), sesuai kriteria terbaru Kementerian ESDM.
Selain itu, juga proyek-proyek yang terkait dengan pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
Elektrifikasi transportasi
Dari 20 miliar dollar AS dana untuk transisi energi di Indonesia, setengahnya dari sektor publik dan setengahnya lagi dari sektor swasta di negara-negara G7. Selain untuk pembiayaan pemensiunan dini/penghentian operasi PLTU, dana transisi itu juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
Ekosistem mobil listrik bisa melibatkan industri baterai kendaraan listrik plus sistem pendingin, industri manufaktur/fabrikasi/perakitan bus listrik, motor penggerak (plus sistem pendingin), powertrain dan kerangka (chassis) bus listrik, pemasok baja dan/atau alumunium, sistem sensor dan sistem kontrol.

Dukungan pendanaan ini menjadi peluang nyata yang perlu dimanfaatkan untuk akselerasi program elektrifikasi transportasi, khususnya transportasi publik berbasis bus. Khusus bus listrik, sudah saatnya kita menjadi produsen, bukan sekadar konsumen.
Sementara untuk membangun ekosistem industri mobil listrik penumpang kelas minibus/SUV/MPV, mungkin bolehlah kita sedikit mengalah dengan menunda atau hanya menjadi bagian dari ekosistem regional/global. Sebab, banyak pemain luar yang sudah siap memproduksi mobil listrik secara massal dan menangkap peluang jelang 2030.
Pabrikan asal Korea Selatan (Hyundai) dan China (Wuling), misalnya, sudah mulai merealisasikan pembangunan ekosistem mobil listriknya sendiri di Indonesia, dengan mengamankan pasokan baterai kendaraan listrik dan bahan bakunya, membangun pabrik, bahkan sudah memproduksi mobil listrik.
Kita dapat menangkap peluang untuk membangun ekosistem bus listrik nasional sedini mungkin dengan memanfaatkan dana transisi energi ini.
Kuasai pasar ASEAN
Kita dapat menangkap peluang untuk membangun ekosistem bus listrik nasional sedini mungkin dengan memanfaatkan dana transisi energi ini. Setidaknya, Indonesia bisa menjadi raja pabrikan bus listrik untuk level ASEAN.
Soal desain dan konstruksi badan bus, cukup banyak karoseri kita yang ‘jago’ dan dapat berperan sebagai bagian dari ekosistem. Sementara perguruan tinggi seperti ITS, UGM, UI, UNS, ITB, dan lainnya di bawah koordinasi Kemendikbudristek juga sangat siap mendukung dengan riset dan pengembangan, bahkan sudah berjalan puluhan tahun.
Untuk mengimbangi baterai yang cenderung berat, dibutuhkan material yang lebih ringan tapi kuat, baik untuk kerangka maupun bodi bus. Ini perlu dukungan riset dan pengembangan, khususnya oleh perguruan tinggi. PT INKA bahkan sudah memproduksi bus listrik dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 65 persen, kendati fasilitas produksinya masih berupa bengkel. Kapasitas produksi masih sangat terbatas.
Dalam pengadaan bus listrik Merah Putih untuk kepentingan KTT G20, PT INKA, selain dengan berbagai perguruan tinggi, juga berkolaborasi dengan sejumlah usaha rintisan (start-up).
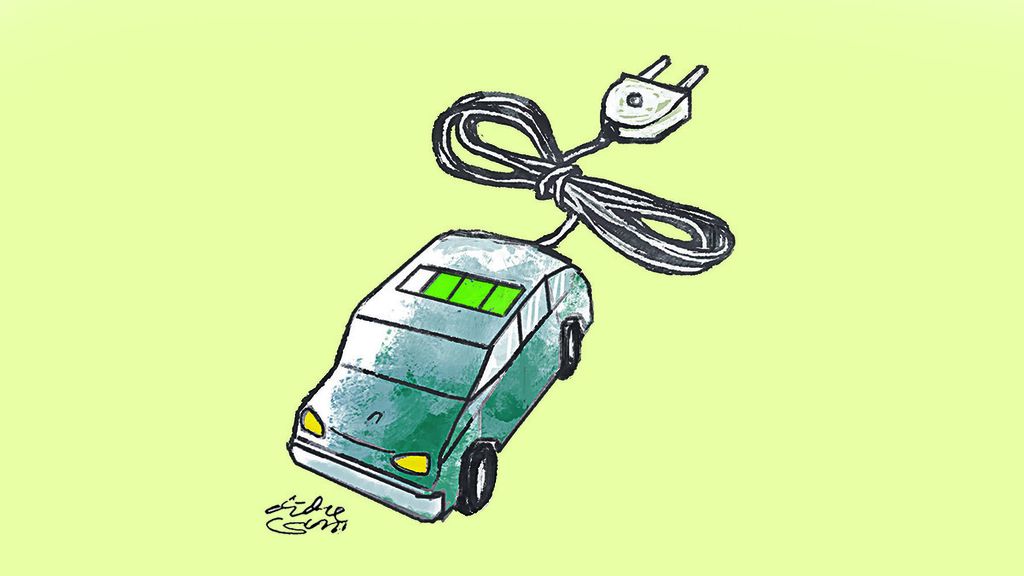
Yakni, Braja Elektrik Motor yang memproduksi motor elektrik, Ultima Desain Otomotif yang menangani baterai, Solusi Produk Indonesia (SPIN) di bidang pemasaran kendaraan listrik, dan Wiksa Daya Pratama yang membuat swap station. Dari bengkel INKA, battery pack dirakit untuk bus listrik tersebut.
Kolaborasi lainnya dengan konsorsium perguruan tinggi adalah pengembangan battery management system (BMS), engineering design, motor listrik dan controller. Selain itu, sistem integrasi dan data, desain; dan tata kelola udara dengan HEPA filter.
Ini contoh yang baik bagaimana ekosistem riset/pengembangan oleh perguruan tinggi bersinergi dengan ekosistem industri bus listrik, kendati skalanya masih kecil. Ini bisa jadi cikal bakal terbangunnya ekosistem bus listrik nasional berskala besar di masa datang.
Investasi bangun pabrik
Dalam beberapa tahun ke depan kita butuh pabrik berkapasitas relatif besar. Bus AKAP/AKDP dan pariwisata serta milik kementerian di Indonesia yang nyaris seluruhnya berbasis BBM, jumlahnya sekitar 30.000. Sementara jumlah bus umum di Thailand, Myanmar, dan Filipina masing-masing sekitar 70.000, 30.000, dan 20.000. Proporsi bus listrik boleh jadi di bawah lima persen saja.
Dalam hal ini kita asumsikan saja pasar mobil listrik Vietnam dan Kamboja akan diambil oleh China, karena kedekatan geografis dan harga bus listrik China yang kompetitif.
Dengan asumsi semua bus BBM sudah harus beralih ke EBT pada (awal) 2030, tersisa waktu tujuh tahun. Ini berarti dibutuhkan lebih dari 20.000 bus listrik baru per tahun untuk mengganti bus BBM di empat negara ASEAN itu saja (termasuk Indonesia), sedangkan Singapura, Malaysia, Brunei, dan Timor Leste, kebutuhannya relatif kecil.
Dalam beberapa tahun ke depan kita butuh pabrik berkapasitas relatif besar.
Belum lagi pasar lain seperti Pakistan dan Meksiko. Konon Pakistan sudah menjajaki kemungkinan pesanan 14.000 unit. Untuk Indonesia saja, kebutuhan bus listrik baru untuk mengganti bus berbasis BBM sekitar 4.000 unit per tahun. Angka ini bisa ditingkatkan dengan berbagai program elektrifikasi bus.
Kementerian Perhubungan, misalnya, membutuhkan sejumlah besar bus listrik untuk program Buy The Service (BTS) di berbagai kota di Indonesia dan pada destinasi-destinasi pariwisata superprioritas. Demikian pula Perum DAMRI dan TransJakarta membutuhkan bus-bus listrik baru untuk mengganti armadanya yang sebagian masih menggunakan bahan bakar fosil.
Pada tahap-tahap awal setidaknya kita dapat menyediakan captive market bagi produsen bus listrik seperti PT INKA guna memproduksi lebih banyak bus listrik, baik secara mandiri atau bekerjasama dalam konteks ekosistem bus listrik yang bisa dikembangkan dengan karoseri, produsen motor penggerak, pemasok baterai, pemasok chasis, dan lainnya.
Dengan demikian, amat beralasan jika pada tahap awal dibangun pabrik dengan kapasitas awal 10.000 unit per tahun. Pada tahap selanjutnya dapat dikembangkan kapasitasnya hingga 50.000 unit bus listrik/tahun. Dengan skala produksi yang relatif besar, biaya produksi per unit bisa ditekan serendah mungkin. Katakanlah antara 100.000 dollar AS sampai 200.000 dollar AS/unit seperti bus-bus listrik China yang berkapasitas tempat duduk kurang lebih 50 penumpang dan jarak jelajah 250 kilometer.

Sebaliknya, dengan skala produksi yang kecil, harga bus listrik buatan lokal dengan panjang 12 meter, ber-AC dan fasilitas ‘standar’ seperti yang digunakan untuk melayani tamu KTT G20, bisa di atas 300.000 dollar AS/unit.
Berapa investasi yang diperlukan? India bisa jadi referensi. India mengeluarkan investasi 600 crore rupee (setara Rp 1,14 triliun) untuk membangun pabrik bus listrik berkapasitas 10.000 unit /tahun. Dalam hal ini India memperoleh bantuan teknis dari salah satu pabrikan bus listrik China, BYD. Untuk Indonesia, mungkin saja biaya investasi bisa di atas itu untuk kapasitas yang sama.
Pembiayaan investasinya dengan memanfaatkan dana transisi energi tersebut. Jika berasal dari sektor publik negara-negara G7, mungkin melalui mekanisme Penyertaan Modal Pemerintah /PMN (APBN). Sementara jika berasal dari sektor swasta G7, bisa melalui meka- nisme Investasi Asing Langsung (FDI).
Dari sisi regulasi dan kebijakan, perlu segera disiapkan regulasi terkait, termasuk aspek keselamatan bus listrik dan sistem insentif (fiskal/nonfiskal) yang bisa mendorong perusahaan-perusahaan transportasi bus (AKAP/AKDP) dan pariwisata untuk segera mulai meng- ganti armadanya dengan bus-bus listrik. Sistem insentif juga perlu dimainkan untuk menggairahkan produsen bus listrik nasional, termasuk ketika masih harus mengimpor komponen tertentu, seperti sistem kontrol.
Jadi, apalagi yang kita tunggu? Lebih cepat dieksekusi, termasuk tahap persiapan, studi kelayakan, dan penyiapan lahan, akan lebih baik. Optimistis!
Wihana Kirana JayaStaf Khusus Menteri Perhubungan

Wihana Kirana Jaya, Guru Besar FEB UGM dan Staf Khusus Menteri Perhubungan.