Aspek Fiskal Program Perlindungan Sosial
Bagaimana pemerintah membiayai program perlindungan sosial terhadap kelompok miskin dan rentan? Perubahan alokasi subsidi BBM menjadi subsidi langsung dan bantuan teknologi digital dapat dipertimbangkan menjadi solusi.

Didie SW
Dalam tulisan sebelumnya, rekan saya, Rema Hanna, mengulas dampak perang Rusia-Ukraina terhadap kelompok miskin dan rentan.
Kelompok miskin amat terpukul akibat kenaikan harga pangan dan energi, khususnya pangan. Alasannya, pangan adalah bagian yang sangat besar dalam konsumsi kelompok miskin.
Lebih jauh Hanna menulis, pemerintah bisa saja tak menaikkan harga dan menanggung beban subsidinya—seperti pada kasus BBM saat ini—tetapi dampaknya harus dibayar di masa depan, misalnya dengan peningkatan pajak di masa depan atau bahkan pemotongan anggaran investasi produktif, seperti infrastruktur atau pengeluaran kesehatan. Padahal, kita tahu bahwa infrastruktur atau investasi kesehatan sangat dibutuhkan untuk mendorong produktivitas di masa depan.
Apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi situasi ini? Rekan saya, Benjamin Olken, menjawab hal itu dalam tulisannya kemarin. Olken menekankan tiga prinsip yang perlu diperhatikan agar kebijakan yang diambil pemerintah untuk masalah ini efektif. Ia menyebut perlunya fokus pemberian bantuan kepada kelompok yang miskin dan rentan; pentingnya membuat program ini bersifat fleksibel; dan indeksasi otomatis. Dengan itu, program bantuan dirancang agar dapat lebih meningkatkan efisiensi sistem perlindungan sosial.
Baca juga: Ekonomi Covid-19 dan Perang Ukraina
Baca juga: Mengatasi Guncangan Harga
Pembiayaan program
Semua rekomendasi kebijakan yang diusulkan Hanna dan Olken membutuhkan dana. Bagaimana membiayainya? Apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) kita memiliki cukup ruang untuk itu? Tulisan saya mencoba menjawab pertanyaan itu.
Pertama, kenaikan harga komoditas dan energi seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi—seperti disebut di atas—ia menimbulkan beban bagi kelompok miskin dan rentan. Namun, di sisi lain—kenaikan harga batubara dan kelapa sawit—memberikan tambahan penerimaan untuk pemerintah (windfall income) dari kenaikan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Pemerintah memperkirakan tambahan penerimaan yang terjadi mencapai Rp 420 triliun tahun 2022. Dari sisi ini, kenaikan harga energi dan komoditas akibat perang Rusia-Ukraina berdampak positif untuk penerimaan pemerintah.
Artinya, pemerintah sebenarnya memiliki kesempatan dari tambahan penerimaan ini untuk digunakan pada investasi produktif, seperti infrastruktur, perlindungan kepada kelompok miskin dan rentan, kesehatan, serta pendidikan.

Didie SW
Kedua, pemerintah juga bisa menjajaki sumber penerimaan lain, seperti pajak ekspor untuk batubara, atau menaikkan lagi pajak ekspor untuk kelapa sawit. Pajak ekspor memiliki dampak distorsi yang lebih kecil dibandingkan dengan pelarangan ekspor atau kewajiban pemenuhan pasar domestik (DMO).
Untuk produk seperti kelapa sawit atau batubara, Indonesia adalah eksportir besar karena itu ia bisa menentukan harga (price setter).
Dalam kasus price setter, pajak ekspor dapat memiliki dampak positif untuk menambah penerimaan negara, menurunkan harga domestik. Memang, di sisi lain, karena Indonesia adalah negara penghasil utama batubara dan kelapa sawit, pajak ekspor akan meningkatkan harga di negara pengimpor. Implikasinya, ekspor Indonesia akan turun.
Seberapa besar? Tergantung seberapa sensitif dampak kenaikan harga terhadap permintaan impor dari Indonesia (elastisitas harga). Tentu perlu dilakukan hitungan lebih rinci. Namun, secara umum—sebagai price setter—pemerintah bisa menarik keuntungan dari kebijakan ini: melalui tambahan penerimaan negara dan penurunan harga domestik.
Selain itu, ia lebih transparan. Tambahan pendapatan dari pajak ekspor ini kemudian dapat digunakan untuk membiayai program bantuan untuk minyak goreng seperti yang diusulkan rekan saya, Olken.
Selain itu, pemerintah bisa mengkaji ulang insentif pajak yang diberikan selama ini.
Ketiga, studi kami (Basri, Felix, Hanna, dan Olken, 2021) menunjukkan bahwa upaya peningkatan penerimaan pajak juga bisa dilakukan melalui reformasi administrasi dalam perpajakan, yaitu memindahkan wajib pajak dari KPP Pratama ke KPP Madya (Medium Size Tax office). Jika hal ini dilakukan, dan diperluas—pemerintah memang sudah mulai menerapkan kebijakan ini sejak pertengahan tahun lalu—penerimaan pajak dapat meningkat secara signifikan tanpa perlu menaikkan tarif, yang dapat menimbulkan beban tambahan bagi pembayar pajak.
Selain itu, pemerintah bisa mengkaji ulang insentif pajak yang diberikan selama ini. Rasio tax expenditure terhadap produk domestik bruto (insentif pajak) sudah relatif besar, (1,52 persen dari PDB) pada tahun 2020. Mengapa begitu banyak insentif pajak diberikan, tetapi dampaknya pada pertumbuhan ekonomi relatif terbatas? Kurangi insentif yang tak efektif, khususnya untuk sektor yang tak ramah lingkungan.
Dengan demikian, ada sumber pembiayaan tambahan bagi kelompok miskin dan rentan, dan saat yang sama mendorong ke arah ekonomi hijau.
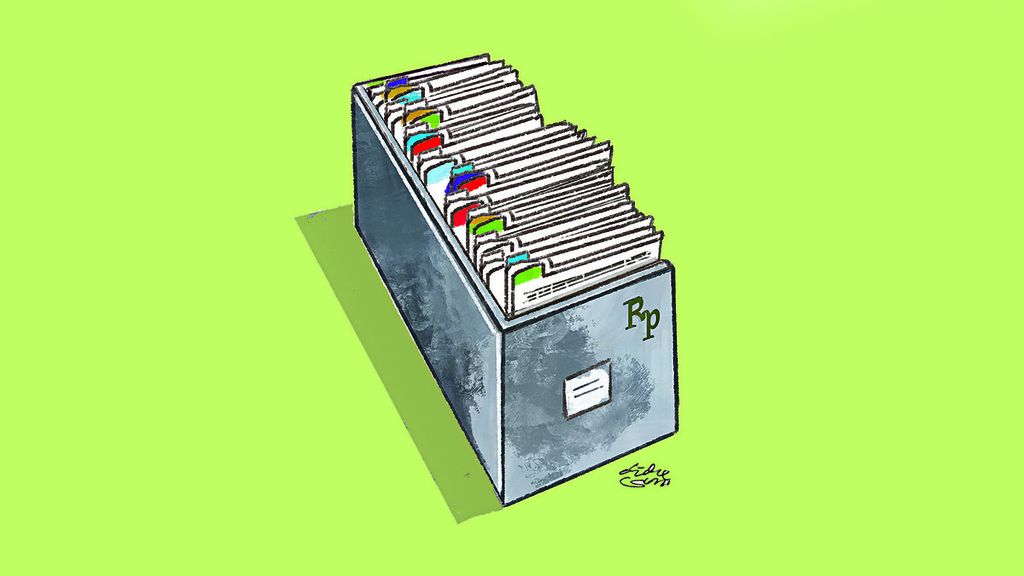
Memanfaatkan ”windfall income”
Keempat, dari sisi belanja pemerintah, hal yang amat penting adalah mengubah sistem perlindungan sosial menjadi tepat sasaran seperti yang diusulkan Olken. Dalam hal ini, perbaikan kualitas belanja dengan cara mengurangi subsidi BBM dan mengalihkannya kepada penduduk miskin dan rentan, dalam bentuk bantuan sosial, adalah solusi yang lebih baik.
Kebijakan ini juga mendorong ekonomi hijau. Coady et al (2019) memperkirakan bahwa menghilangkan subsidi minyak dan gas saja dapat mengurangi emisi karbon global sebesar 5-6 persen pada tahun 2015 dan sebesar 28 persen jika subsidi batubara juga telah dihilangkan.
Oleh karena itu, kami mengusulkan memanfaatkan windfall income untuk alokasi belanja yang produktif dan tepat sasaran, memberlakukan pajak ekspor, melakukan reformasi administrasi perpajakan dan pengurangan tax expenditure untuk sektor tidak ramah lingkungan.
Kelima, seperti dibahas Hanna dan Olken dalam tulisan sebelumnya, pemerintah memang bisa saja memilih untuk menggunakan windfall income untuk mempertahankan harga BBM. Namun, di samping tidak efisien—karena tak tepat sasaran—biayanya juga sangat besar.
Dalam pertemuan di DPR beberapa minggu lalu, pemerintah mengajukan tambahan subsidi energi Rp 520 triliun untuk APBN 2023. Satu hal yang perlu diingat, satu hari boom komoditas dan energi akan berakhir, tetapi subsidi BBM dan listrik—yang berbeda dengan bantuan langsung tunai (BLT) yang sifatnya sementara—secara politis sulit dicabut.
Baca juga: Kebijakan Subsidi Energi Selalu Menjadi Tantangan bagi Pemerintah
Benar bahwa beban subsidi akan mengikuti harga energi, tetapi itu artinya naik turunnya belanja mengikuti naik turunnya penerimaan negara. APBN kita akan bersifat pro-siklus. Padahal, kita ingin APBN yang kontra-siklus. Implikasinya, ruang fiskal tetap tidak bertambah, dan kemampuannya mendorong pertumbuhan ekonomi terbatas.
Selain itu, kita tahu, penerimaan negara bersifat fluktuatif jika bersumber pada sumber daya alam (SDA), sementara belanja pemerintah cenderung stabil atau meningkat. Artinya, ketika boom SDA berakhir, ada risiko defisit fiskal meningkat. Padahal, kita ingin mengembalikan defisit anggaran ke 3 persen PDB mulai tahun 2023.
Implikasinya, pemerintah harus memotong belanja, melakukan kontraksi fiskal. Padahal, pada saat yang sama Bank Indonesia mungkin juga harus menaikkan suku bunga akibat tekanan inflasi. Hal ini akan memukul pertumbuhan ekonomi.
Perluasan perlindungan sosial melalui subsidi terarah seperti yang diusulkan Hanna dan Olken akan memberi ruang fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Perluasan program bansos
Jika program bantuan sosial ingin diperluas kepada kelompok menengah bawah, yang terpukul akibat Covid-19, seperti yang diusulkan Hanna dan Olken, dibutuhkan dana yang lebih besar.
Sebagai contoh, Bank Dunia (2020) memperkirakan ada 115 juta orang yang masuk dalam kategori aspiring middle class (calon kelas menengah). Jika kelompok ini yang ingin dituju, dibutuhkan bantuan sosial untuk sekitar 30 juta rumah tangga (asumsinya satu keluarga terdiri atas empat orang).
Jika nilai manfaat adalah Rp 1 juta per bulan (lebih besar dari BLT saat ini) dan diberikan selama 12 bulan, dibutuhkan dana Rp 360 triliun. Menariknya, jumlah ini lebih kecil daripada anggaran yang diajukan pemerintah untuk subsidi energi 2023 yang sebesar Rp 520 triliun.
Implikasinya, sebagian dari anggaran subsidi yang diajukan pemerintah dapat digunakan untuk investasi yang produktif dan bersifat inklusif sambil pada saat yang sama tetap melindungi kelompok miskin dan rentan.
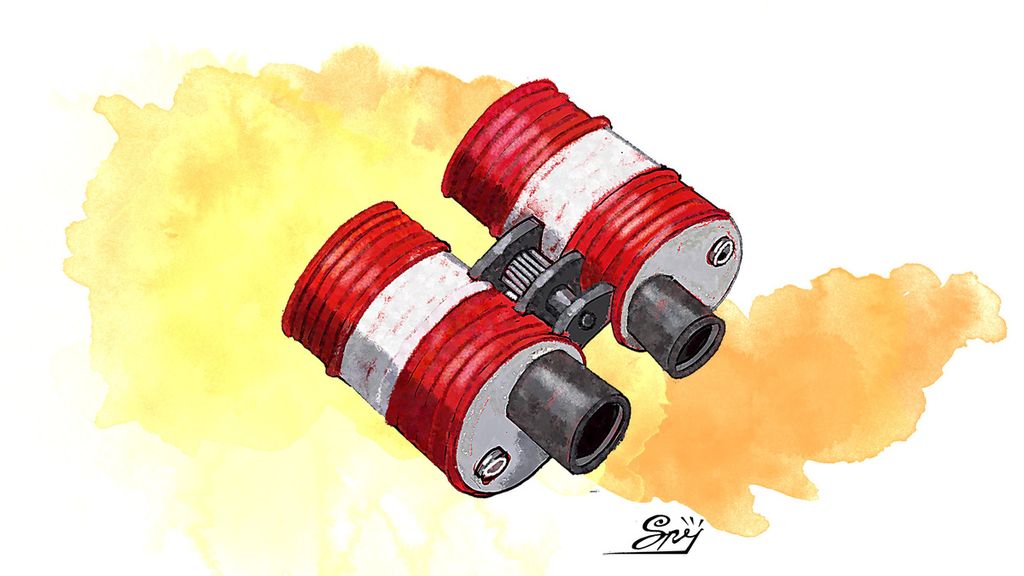
Kami melihat kebijakan perubahan alokasi subsidi BBM menjadi subsidi langsung memiliki tiga keunggulan: ia baik untuk masyarakat rentan, baik untuk fiskal, dan baik untuk lingkungan, karena akan menekan konsumsi bahan bakar fosil (fossil fuel).
Perluasan perlindungan sosial melalui subsidi terarah seperti yang diusulkan Hanna dan Olken akan memberi ruang fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tentu kami paham, sebuah kebijakan tidak berada di ruang hampa. Ada kendala data yang tidak akurat, persoalan koordinasi antarlembaga, atau mungkin tak populer secara politik.
Namun, dengan bantuan teknologi digital, perbaikan data dan narasi yang baik, pemerintah bisa memanfaatkan boom komoditas dan energi, dan pada saat yang sama melindungi kelompok rentan yang disebut oleh Hanna dalam artikelnya.
Muhamad Chatib Basri, Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2018%2F02%2F23%2F7dd5ca98-8284-4fa2-bd98-c12f2d195a5d_jpg.jpg)
Muhamad Chatib Basri