Hari Tani dan Dualisme Hukum Agraria
Dalam konflik agraria di Pulau Rempang, pengadaan tanah bagi investasi menciptakan dualisme hukum agraria antara pengakuan hak atas tanah masyarakat oleh UUPA dan pengabaian hak atas tanah masyarakat oleh pemerintah.
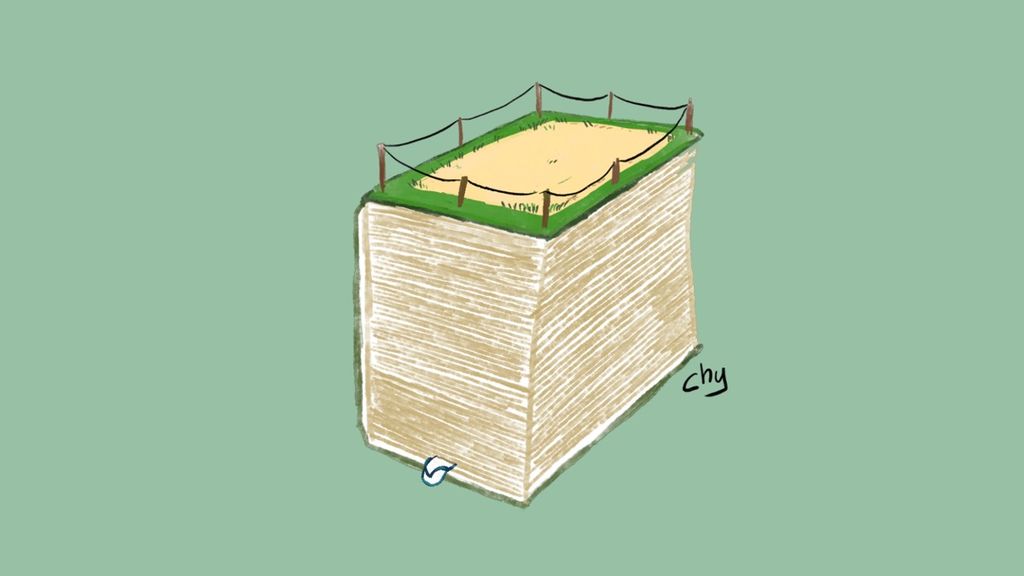
Ilustrasi
Peringatan Hari Tani, 24 September tahun ini, diwarnai berlanjutnya dualisme hukum agraria akibat pemerintah terus membentuk pengaturan jangka waktu hak atas tanah yang lebih lama dari yang telah dibatasi oleh Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA 1960.
Dalam kasus konflik agraria di Pulau Rempang, pengadaan tanah bagi investasi telah menciptakan dualisme hukum agraria antara pengakuan hak atas tanah masyarakat oleh UUPA dan pengabaian hak atas tanah masyarakat oleh pemerintah.
Dualisme ini bertentangan dengan tujuan UUPA untuk menciptakan kesatuan hukum agraria nasional yang sederhana dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Dualisme hak atas tanah
Melalui UU Nomor 25/2007 tentang Penanaman Modal, diberikan fasilitas untuk penanaman modal berupa hak guna usaha (HGU) dengan jangka waktu 95 tahun dengan cara dan dapat diperpanjang dan diperbarui di muka sekaligus.
Pengaturan ini, berdasar putusan Mahkamah Konstitusi (MK)—dalam perkara pengujian UU Penanaman Modal—dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. MK berpendapat, pemberian hak atas tanah dengan jangka waktu yang sangat lama, serta dapat diperpanjang/diperbarui di muka sekaligus, menghambat negara untuk melakukan pemerataan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh hak-hak atas tanah secara adil.
Dalam hal ini, kewenangan melakukan pemerataan kesempatan mendapatkan hak-hak atas tanah secara lebih adil dan lebih merata jadi terhalang.
Pada saat yang sama, keadaan ini juga menghalangi negara dalam memenuhi kewajibannya melaksanakan perintah Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, yaitu ”pemerataan kesempatan untuk menjaga kepentingan yang dilindungi konstitusi”.
Ironisnya, pemberian HGU hingga 90 tahun itu justru dilanjutkan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 7/2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha, dan hendak diperkuat lagi melalui RUU Pertanahan.
Setelah pembahasan RUU Pertanahan di DPR terhenti, melalui UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja, diaturlah soal Bank Tanah. Melalui PP Nomor 64/2021 tentang Bank Tanah, Badan Bank Tanah dapat memberikan jaminan perpanjangan dan pembaruan hak atas tanah di atas hak pengelolaan (HPL). Perpanjangan dan pembaruan hak atas tanah di atas HPL dapat diberikan sekaligus setelah dimanfaatkan dan diperjanjikan.
Dualisme ini bertentangan dengan tujuan UUPA untuk menciptakan kesatuan hukum agraria nasional yang sederhana dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Model perpanjangan dan pembaruan di muka sekaligus, ditambah pemberian hak atas tanah dengan jangka waktu sangat lama, hadir lagi di PP Nomor 12/2023 tentang Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara (IKN).
PP ini mengatur fasilitasi kemudahan berusaha dengan pemberian jangka waktu HGU di atas HPL Otorita IKN, paling lama 95 tahun dalam satu siklus, dengan perpanjangan dan pembaruan HGU bisa diberikan sekaligus setelah lima tahun HGU digunakan dan/atau dimanfaatkan secara efektif sesuai tujuan pemberian haknya.
Dualisme pengaturan hak atas tanah, antara UUPA—sebagai operasionalisasi Pasal 33 UUD 1945—dan putusan MK, dengan beberapa produk hukum terkait penanaman modal dan kemudahan berusaha, justru menciptakan ketidakpastian hukum yang justru akan berdampak pada kepastian usaha.
Solusinya adalah mengharmoniskan produk hukum penanaman modal dan kemudahan berusaha di bidang pertanahan dengan UUPA 1960 dan putusan MK.
Pengakuan hak rakyat
Meski UUPA 1960 telah menghapus konsepsi kolonial atas tanah, konsepsi ini bisa hidup kembali melalui bentuk baru asas domain berupa pemberian konsesi agraria yang terlalu lama dan terlalu luas, serta pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah dan swasta dengan dalih proyek strategis nasional yang mengabaikan hak-hak tradisional yang bersifat turun-menurun.
Dalam kasus Rempang, negara, dalam hal ini pemerintah melalui Badan Pengusahaan (BP) Batam, menjadi pemilik tanah yang bisa menentukan secara sepihak siapa yang harus direlokasi dan siapa yang bisa datang untuk menguasai dan mengelola tanah.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F09%2F16%2F8db51e1a-3498-43fd-9b91-05631c3f5c96_jpg.jpg)
Rombongan Komnas HAM (atas tengah) mendengarkan aspirasi warga terkait konflik agraria dan bentrokan warga di Jembatan Barelang IV dengan aparat pada 7 September lalu, Kampung Pantai Melayu, Kelurahan Rempang Cate, Kecamatan Galang, Kota Batam, Sabtu (16/9/2023).
UUPA 1960 menyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Kesatuan tanah, air, dan rakyat dalam negara bangsa kepulauan dalam kenyataannya ada yang berupa masyarakat (lokal, tradisional, dan adat) yang bermukim dan berpenghidupan di sekitar perairan pesisir dan pulau-pulau kecil secara turun-temurun.
Berdasar kenyataan ini, negara sudah seharusnya memberikan pengakuan atas hak masyarakat itu. Bukan justru mengabaikan dengan alasan ketiadaan sertifikat hak atas tanah.
Justru pemerintah harusnya menjelaskan apakah HPL BP Batam berada atau tidak di atas kampung tua Pulau Rempang? Dan, apakah di atas HPL itu telah diterbitkan hak untuk badan usaha? Sebab, jika sudah diterbitkan hak sejak 2004, kenapa tak masuk dalam mekanisme penertiban tanah telantar dan baru tahun ini hendak dimanfaatkan?
Selain itu, pemberian konsesi di wilayah perairan pesisir dan pulau kecil juga tak boleh melanggar putusan MK bahwa pengusahaan perairan pesisir tak boleh mengabaikan hak individu, hak kolektif, hak masyarakat adat, dan hak-hak lain yang dilindungi konstitusi. Dalam rencana pemberian konsesi di perairan pesisir dan pulau kecil, pemerintah dan pemda, sebagaimana putusan MK dalam pengujian UU Nomor 27/2007, harus melibatkan peran serta masyarakat.
Dalam putusan MK itu dinyatakan, tak melibatkan masyarakat sebagai peserta musyawarah perencanaan adalah melanggar hak-hak konstitusional. Yakni, (1) pembungkaman hak masyarakat; (2) pelanggaran hak publik di kemudian hari; (3) perlakuan yang membedakan; dan (4) mengabaikan hak-hak masyarakat untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif.
UUPA 1960 menyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.
Pengakuan hak masyarakat di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dalam kerangka reforma agraria tidak hanya berhenti pada pemberian hak atas tanah bagi masyarakat.
Pengakuan juga harus diberikan untuk ulayat laut dan teritorial nelayan tradisional yang didukung pembaruan tata kelola perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta wilayah penangkapan perikanan yang menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat adat, nelayan kecil, nelayan tradisional, dan masyarakat lokal, dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Baca juga : Ditunggu, Komitmen Pemimpin Baru Indonesia pada Kepentingan Ekologis dan Masyarakat Adat

Gunawan
GunawanPenasihat Senior IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice) dan Dewan Nasional SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit)