RRI Mati Suri?
Transformasi digital dan persoalan regulasi yang belum selesai menjadi pekerjaan rumah besar RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ditambah lagi ”positioning” lembaga yang acap ditarik ke dalam ruang politik praktis.
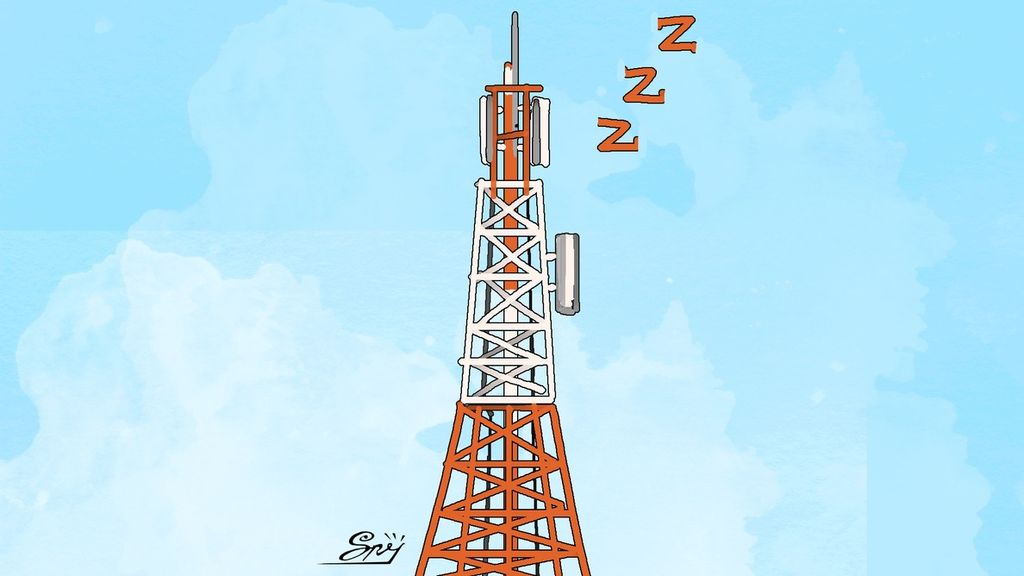
Ilustrasi
"RRI, Sekali di Udara Tetap di Udara”
Transformasi teknologi digital pada ranah media global telah merambah ke industri media konvensional, seperti koran, majalah, televisi, dan radio. Perubahan terjadi mulai dari aspek format program, karakteristik konten, strategi penyiaran, manajemen organisasi, hingga ”performa” lembaga melalui berbagai upaya inovasi dan rebranding.
Koran cetak semakin langka. Siaran radio dan televisi tak lagi mainstream bersandar pada keandalan jaringan terestrial. Peran mainstream-nya sudah diambil alih kanal over the top (OTT). Industri yang tidak tunduk pada sinyal perubahan itu akan tergilas, lalu mati suri, bahkan mati. Maka, hari ini kita menyaksikan konten-konten informasi dan hiburan bertebaran di layar Youtube, Instagram, Tiktok, Twitter, dan masih banyak lagi platform lain.
Terpaan arus transformasi digital memaksa semua media berbenah diri demi mempertahankan eksistensinya. Bagaimana dengan Radio Republik Indonesia (RRI)? Lembaga penyiaran publik (LPP) milik negara pada 11 September ini genap berusia 78 tahun, telah melewati pasang surut sejarahnya.
Sejumlah peristiwa transisi mengantar RRI memasuki gelombang transformasi digital bersama media lainnya. Upaya mengadaptasi perubahan dilakukan RRI dengan terobosan, seperti platform baru RRI Net melalui satelit AsiaSat 9 dan Telkom-4, portal berita pada situs web rri.co.id, serta RRI PlayGo, dan program BeYoung. Namun, itu saja belum cukup karena ada persoalan lain yang masih melilit dan harus dibenahi.
Baca juga : RRI, Tri Prasetya, dan Disrupsi
Regulasi dan kelembagaan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) menegaskan bahwa LPP adalah lembaga penyiaran publik berbentuk badan hukum, didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan publik. Namun, di tingkat praksis, implementasi prinsip LPP masih berbenturan dengan berbagai tafsir pragmatis yang belum final. Seperti persoalan format kelembagaan, struktur birokrasi, tata kelola lembaga, dukungan sarana-prasarana, pendanaan, sumber daya manusia (SDM), dan regulasi yang memayungi.
Dalam konteks kelembagaan, masih ada pandangan demonstratif yang mempertentangkan nomenklatur LPP karena LPP dianggap sebagai ”makhluk” yang tidak dikenal dalam undang-undang kelembagaan negara. Klaim lain menyatakan bahwa LPP dapat disebut sebagai lembaga negara karena salah satu organ lembaganya, yakni dewan pengawas LPP, dipilih DPR dan diangkat Presiden.
Secara anatomi organisasi LPP dikatakan mirip badan layanan umum (BLU), sayangnya belum ada regulasi yang menegaskan status ini. Diperparah dengan alotnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran) yang baru di DPR. RUU Penyiaran tersebut konon sudah masuk-keluar ruang Komisi I DPR dan dibahas dalam program strategis, Program Legislasi Nasional, sejak 2013. Oleh sebab itu, diperlukan arus kuat untuk menekan DPR dan pemerintah segera menyelesaikan UU tersebut secara transparan dan terbuka.
Artinya, secara substansial RUU Penyiaran sudah memasuki fase paripurna. Termasuk di Panitia Kerja Penyiaran Komisi I ataupun di badan legislatif yang bertugas melakukan harmonisasi pasal demi pasal agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan lain. Padahal, jika RUU Penyiaran segera ditetapkan, maka akan menggantikan UU No 32/2002 tentang Penyiaran dan menjadi landasan penyelenggaraan industri penyiaran yang mandiri, sehat, kuat, dan dapat bersaing di dunia internasional.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2018%2F09%2F10%2Feafb0f14-243d-42e6-95e4-d3e4d9c99780_jpg.jpg)
Ruang siaran Radio Republik Indonesia (RRI) Programa 3 yang juga mengatur penyiaran visual, Senin (10/9/2018), di Jakarta. Layanan siaran visual dari RRI tersebut bernama RRI Net.
Dalam kronologi keberpihakan negara, secara regulatif dapat dilihat dari sejumlah aturan yang telah diterbitkan pemerintah untuk memayungi penyelenggaraan penyiaran LPP. Dimulai dari Permenkominfo 23/PER/M KOMINFO/11/2011 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terestrial pada Pita Frekuensi Radio 478-694 MHz, kemudian Permenkominfo 5/PER/M.KOMINFO/2/2012 tentang Standar Penyiaran Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free-to-Air).
Hal mendasar yang tidak boleh diabaikan adalah menentukan pembagian zona melalui Permenkominfo 17/2012 tentang Pelaksanaan Penetapan Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing. Namun, karena dianggap bertabrakan dengan substansi UU No 32/2002, maka waktu itu Mahkamah Agung (MA) melalui PTUN pada 5 Maret 2015 membatalkan 33 keputusan Menteri Kominfo.
Meski landasan formal penyiaran digital di Indonesia mengalami persoalan, persiapan migrasi sistem penyiaran analog ke digital terus dilakukan sambil menunggu revisi UU Penyiaran. Untuk mendukung implementasi siaran digital, terbitlah Permenkominfo No 5/2016 tentang Uji Coba Teknologi Telekomunikasi, Informatika, dan Penyiaran.
Secara regulasi, bayang-bayang hegemoni RUU Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran RPP yang lahir dari rahim UU Cipta Kerja terus menghantui.
Pada 27 Juni 2019, pemerintah kembali mengeluarkan Permenkominfo No 3/2019 tentang Pelaksanaan Penyiaran Simulcast dalam Rangka Persiapan Migrasi Sistem Penyiaran Analog ke Penyiaran Digital. Sampai kemudian melalui UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja, digitalisasi penyiaran di Indonesia memiliki payung hukum jelas berupa undang-undang. Di sinilah persoalan baru LPP RRI menunggu.
Secara regulasi, bayang-bayang hegemoni RUU Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran RPP yang lahir dari rahim UU Cipta Kerja terus menghantui. DPR terutama Komisi I melihat ketentuan yang ada belum mengakomodasi fungsi satuan kerja stasiun-stasiun RRI di daerah, dan ini dapat menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum. Ada bagian pasal yang belum memuat substansi tentang pengaturan cakupan siaran internasional sehingga RRI berpotensi kehilangan perannya untuk menyelenggarakan tugas second track diplomacy ke luar negeri melalui program siaran internasional.
Bukan itu saja, LPP RRI juga akan kehilangan haknya dalam penyelenggaraan penyiaran untuk cakupan wilayah siaran regional dan lokal. Dalam substansi Pasal 72 Ayat (2), misalnya, menunjukkan distorsi terhadap mandat RRI di daerah yang hanya berfungsi sebagai stasiun relai.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2021%2F11%2F24%2F0112cce9-4e65-4b36-abd4-125f71e749be_jpg.jpg)
Menara pemancar Radio Republik Indonesia (RRI) di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan, Kamis (7/9/2017).
Tekanan politis
Seorang pemikir dan filsuf Perancis bernama Paul M Foucault dalam bukunya berjudul Madness and Civilization menjelaskan bagaimana hubungan kekuasaan dan pengetahuan dalam mengontrol kerja lembaga. Setidaknya ada tiga sumber kuasa berbahaya dan sering disalahgunakan dalam proses penyelenggaraan kelembagaan, termasuk dalam hal ini lembaga penyiaran, yaitu kuasa finansial, kuasa politik, dan kuasa tokoh.
Pertama, kuasa finansial. Kecukupan finansial membuat problem kelembagaan serumit apa pun dapat diatasi. Namun, sebaliknya, kekuatan finansial dapat menyebabkan norma dan aturan lembaga justru sulit ditegakkan karena fakta dapat diputarbalikkan dan kebenaran dikalahkan. Saya ingin memersepsikan tulisan Paul tersebut sebagai pandangan laten yang sering digunakan sebagai parameter kelayakan dan kredibilitas lembaga publik, dalam hal ini LPP.
Baca juga : Eksistensi Radio Menghibur Pendengar di Era Digital
Dalam studi kasus LPP, sejak berdiri sampai hari ini, persoalan klasiknya adalah anggaran atau keuangan. Mulai dari biaya produksi, gaji karyawan, sampai ke soal dana research and development penelitian dan pengembangan (kalau ada). Fokus perhatian dan perdebatan selalu mengarah pada bagaimana mendapatkan anggaran besar, dan capaian anggaran besar itu selalu diklaim sebagai catatan prestasi yang bisa dipamerkan.
Padahal, Pasal 2 UU Penyiaran menegaskan bahwa anggaran itu tanggung jawab negara, jadi diperjuangkan atau tidak, sudah otomatis akan dikucurkan. Jangan sampai akibat ketergantungan anggaran pada APBN yang besar, kemudian kredibilitas lembaga justru dipertanyakan. Publik beranggapan LPP bisa di-remote oleh operator negara, dalam hal ini lembaga DPR atau kementerian terkait untuk ”boleh ini atau tidak boleh itu” dan sebagainya. Akhirnya mandul dari sikap kritis, jauh dari kata netral, apalagi independen. Jika ini benar, artinya telah terjadi pelanggaran besar terhadap prinsip penyiaran publik.

Kedua, kuasa politik. UU Penyiaran telah menegaskan tentang independensi dan netralitas LPP. Maka, setiap kebijakan yang diambil, apalagi menyangkut muatan program siaran, sedapat mungkin jauh dari muatan kepentingan bernuansa politis. Garis politik LPP sudah jelas, yaitu garis politik negara, berdiri di semua golongan dan kepentingan, seperti tertuang dalam kredo Tri Prasejarah RRI. Memang proses pemilihan organ LPP, yakni dewan pengawas, melalui proses politik, tetapi tidak kemudian praktik-praktik politik itu diimplementasikan di ruang-ruang kerja LPP sehingga proses penyelenggaraan manajemen berpotensi sarat dengan konflik kepentingan.
Proses pemilihan dewas melalui DPR tidak boleh didasarkan konsesi-konsesi kolektif yang dapat menyebabkan LPP RRI seolah-olah menjadi perwakilan atau cabang kepentingan para anggota legislatif. Demikian juga jika terjadi pertentangan dan perdebatan dalam penyelenggaraan praktik penyiaran, tidak boleh kemudian para individu yang masuk dalam jajaran dewas dan direksi menggunakan saluran kekuatan politik dengan cara ”merajuk” ke DPR.
Praktik-praktik semacam itu tidak boleh dilakukan guna menghindari perpecahan di tubuh ”kolegium” dewan pengawas ataupun dewan direksi. Termasuk kepada lembaga lain yang punya kekuatan pressure untuk menekan pihak tertentu, seperti Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, BPK, atau KPK. Jika perilaku buruk ini dilakukan, maka bisa jadi organisasi tidak harmonis, justru akan lebih karut-marut penuh kegaduhan.
Baca juga : Radio Republik Indonesia
Ketiga, kuasa tokoh. Penyusunan kebijakan siaran LPP sejauh mungkin jauh dari pengaruh ketokohan seseorang. Misalnya, tokoh organisasi, pemimpin massa, pejabat tinggi negara, pemilik modal, atau siapa pun yang punya pengaruh terhadap kebijakan siaran LPP, apalagi politisi. Ingat, tahun ini RRI memasuki tahun politik, bisa saja ada kekuatan kelompok tertentu yang mengiming-imingkan sejumlah posisi jika nanti kelompok itu memenangi kontestasi politik.
Oleh sebab itu, sedapat mungkin LPP menjauhkan diri dari pengaruh politik yang menggiring lembaga pada pilihan hitam putih. Untuk menghindari kondisi tersebut, idealnya RRI tidak terjebak dalam kebijakan siaran pemilu dengan menyelenggarakan quick report atau hitung cepat atau apa pun namanya. Lebih baik RRI fokus pada program literasi pemilu kepada pemilih pemula, misalnya.
Jika program hitung cepat pemilu itu dilakukan, dikhawatirkan RRI ikut dalam politik praktis karena bayangkan, andai RRI menampilkan live hitung cepat, dan menyatakan pasangan tertentu berada di urutan pertama atau menang sementara, maka lembaga mana yang berani berbeda? Tentu yang lain akan tunduk pada hasil RRI karena produknya dianggap tepercaya, karena RRI menyandang nama negara. Hal ini harus menjadi perhatian manajemen RRI agar tidak ada suara-suara sumbang bahwa ada pihak yang bermain dalam program hitung cepat itu untuk mendapat keuntungan politik.
Jadi, siapa pun mereka tidak boleh mencampuri urusan dalam LPP demi menjaga marwah dan independensi LPP. Sebab, apa pun, publik masih menaruh harapan besar bahwa RRI tidak boleh mati suri, maka harus terus dirawat agar tetap eksis di tengah persaingan media yang keras ini.
Selamat ulang tahun yang ke-78 Radio Republik Indonesia, RRI. Sekali di udara tetap di udara.
Eko Wahyuanto, Mantan Jurnalis RRI; Dosen STMM MMTC Yogyakarta

Eko Wahyuanto