Sabda Damalung
Kesimpulan van der Molen dan Wiryamartana, naskah-naskah Merapi-Merbabu tidak saja berkisar pada teks kepercayaan Hindu-Buddha pada masa Jawa Kuno, tetapi juga terdapat beberapa naskah Islami, salah satunya Tapel Adam.
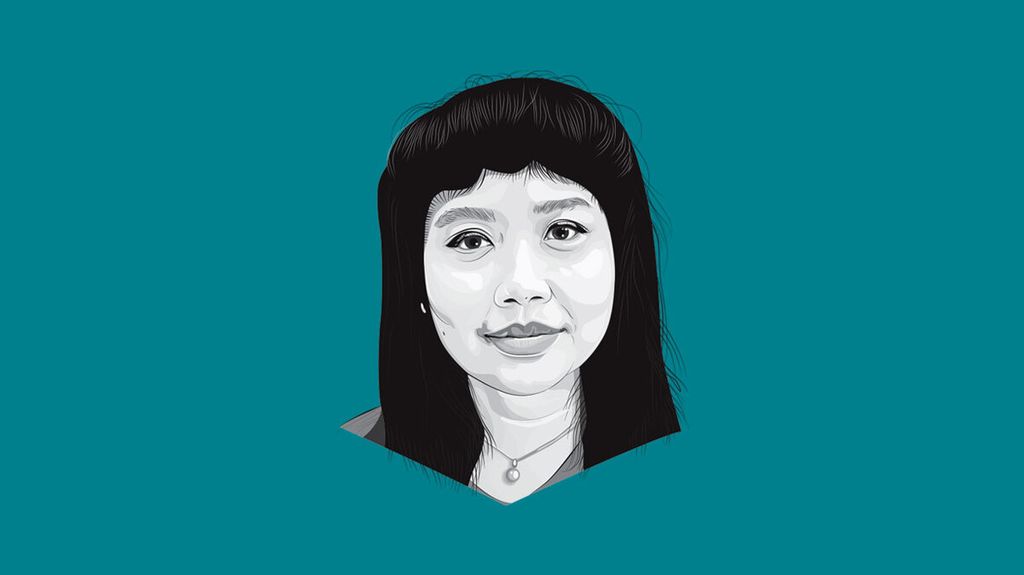
Saras Dewi
Gunung Merbabu tampak di ufuk, menjulang dengan selendang awan yang menyelubunginya. Merbabu adalah persemayaman bagi sabana yang lapang, kebebasan alap-alap, desiran lirih tembang edelweis, dan mata air yang memercik pencerahan bagi para pemujanya.
Gunung Merbabu adalah rajutan pengalaman bagi para penghayatnya, menyimpul pengetahuan sebagai gunung api dengan ekosistem yang khas. Ia sumber penghidupan sekaligus menjadi jangkar pengetahuan kosmologis.
Gunung Merbabu disebutkan dan diagungkan dalam berbagai lontar-lontar kuno dari abad ke-16 sampai ke-18, bahkan para pengkajinya menduga semenjak lampau lereng Gunung Merbabu merupakan tempat bertemunya para pemikir untuk mengembangkan pengetahuan tentang ajaran-ajaran kebatinan.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F12%2F29%2Fbff028f0-3818-42ca-bfeb-2f940d97e58d_jpeg.jpg)
Wisatawan mengunjungi salah satu kebun petik buah stroberi di Desa Banyuroto, Sawangan, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (29/12/2022). Sejumlah obyek wisata di kawasan kaki Gunung Merbabu dan Merapi menjadi tujuan alternatif bagi para pelancong yang hendak menikmati suasana liburan yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan.
Menilik dari penelitian yang telah dilakukan oleh Willem van der Molen dan Kuntara Wiryamartana, naskah-naskah Merapi-Merbabu merupakan naskah-naskah yang dilestarikan oleh seorang pendeta Buddha bernama Windusana yang dahulu bermukim di kaki Gunung Merbabu. Meski demikian, kedua peneliti ini menyatakan bahwa naskah-naskah tersebut berasal dari berbagai tempat tidak saja dari Gunung Merbabu, tetapi juga Gunung Merapi, Telamaya, Wilis.
Naskah-naskah itu beragam dari masa penciptaan hingga isinya. Semenjak terangkatnya naskah-naskah ini pada tahun 1822, tetap keberadaannya masih sarat akan teka-teki.
Baca juga: Nekropolitik
Sekitar 400an naskah-naskah yang saat ini tersimpan di Perpustakaan Nasional pun, hingga sekarang sebagian besar belum teridentifikasi penanggalannya maupun dikaji secara mendalam. Satu hal yang menarik, yakni simpulan dari van der Molen dan Wiryamartana, bahwa bermacam-macam naskah yang dikelompokkan sebagai naskah Merapi-Merbabu tidak saja berkisar pada teks kepercayaan Hindu-Buddha pada masa Jawa Kuno, tetapi juga terdapat beberapa naskah Islami yang salah satunya bertajuk Tapel Adam. Naskah ini membicarakan tentang kisah nabi Adam hingga perjuangan Nabi Muhammad, yang ditinggikan di dalam naskah sebagai Baginda Muhammad.
Para peneliti ini berpandangan bahwa kumpulan naskah Merapi-Merbabu menunjukkan bahwa teks-teks Hindu-Buddha dan Islam tersebut dipelajari dalam suatu komunitas intelektual yang menghormati beraneka ragam bentuk sastra dan mereka berjerih payah untuk melindungi tradisi itu.
Sebagai seorang peneliti dengan latar belakang ilmu filsafat, saya selalu mengagumi kepakaran para filolog khususnya kecermatan mereka saat menyelidiki sejarah dan struktur bahasa dalam teks-teks kuno. Hal ini yang disebut oleh Martin Heidegger seorang filsuf dari Jerman, yang juga mengutip Wilhelm van Humboldt seorang pengkaji Bahasa Jawa, bahwa penyelidikan terhadap kata-kata dan bahasa secara esensial, adalah penggalian untuk mengungkap konstruksi realitas manusia itu sendiri. Sehingga, filolog adalah orang-orang yang memiliki keterampilan untuk menyaksikan realitas ini tidak saja sebagai fenomena faktual sebagaimana kita semua mempersepsikannya, tetapi mereka juga teliti melihat kerangka, tulang-tulang dari bangunan yang kita sebut sebagai dunia atau buana.
Baca juga: Ekotopia
Heidegger menggarisbawahi bagaimana Humboldt memahami keunikan bahasa Jawa kuno yang dasarnya adalah tuturan. Humboldt menganggap bahwa bahasa sejatinya adalah suara yang diartikulasikan, ia berpendapat lebih lanjut, praktik berbahasa itu melingkupi ekspresi pikiran individu penuturnya, namun juga secara simultan hasrat untuk menjadi menyeluruh dalam kesatuan.
Heidegger memperkuat gagasan tentang bahasa dengan mengutip Aristoteles, seorang filsuf dari masa Yunani kuno, ia membahas keutamaan memahami bahasa sebagai suara yang dimunculkan dari kedalaman jiwa manusia untuk menunjukkan afeksi. Aristoteles merefleksikan, tidak ada bunyi dari suara yang sama sekali identik satu dengan yang lainnya, namun pada saat yang bersamaan, setiap insan memiliki kehendak berbahasa yang sama untuk menunjukkan apakah yang penting bagi kehidupan mereka.
Naskah-naskah kuno adalah rekaman tentang aktivitas berbahasa orang-orang dari masa lalu, meski berabad-abad telah berlalu, hal itu tidak menggerus kenyataan berbahasa yang menggambarkan kehidupan yang dinamis nan bermakna. Naskah-naskah ini menjembatani rentangan waktu, dan mempertemukan para pembaca dengan kepingan-kepingan petunjuk tentang dunia kala lampau.
Itulah yang dilakukan komunitas Cetak Biru Damalung, mereka terdiri dari antropolog, filolog, arkeolog, musisi, perupa, dan penari yang bertekad untuk membaca kembali naskah-naskah Merapi-Merbabu dan menerjemahkannya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Kata Damalung adalah penamaan lama yang disematkan pada Gunung Merbabu. Mereka membaca ulang Prasasti Ngaduman yang menyatakan, “Om Sri Sarasoti kreta wukir hadi Damalung//uriping buwana anakra murusa patirtan palemaran.” Terpujilah Saraswati, Terpujilah Maha Gunung Damalung, sumber kehidupan dunia.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F01%2F13%2F548da8b6-9ccb-44cb-b97f-20f220a93f35_jpeg.jpg)
Guguran lava pijar pada Gunung Merapi terlihat dari kawasan Bukit Turgo, Desa Hargobinangun, Pakem, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (13/1/2023) dini hari.
Apa yang dikembangkan oleh para peneliti ini bukan saja pada tahap penelusuran dan pelestarian semata, tapi menurut saya lebih radikal lagi, mereka mengajak generasi baru untuk menghidupi naskah. Memang benar, naskah-naskah ini sedemikian berharga, beragam manuskrip ini urgen untuk disalin, dipublikasi, dikatalogkan dengan baik, dan didigitalisasikan.
Itu semua menurut saya sangat penting, dan perlu semakin banyak para pelestari yang memperhatikan naskah-naskah kuno ini. Meski demikian, cara-cara peneliti Damalung berkolaborasi dengan seniman, menginterpretasikan naskah menjadi karya lukis, komposisi musik, bahkan menjadi karya wastra, menurut saya adalah ajakan untuk menelusupkan naskah kembali ke dalam jiwa dan laku sehari-hari kita.
Mengapa kita menengok kembali naskah kuno? Dibutuhkan kesabaran dan kerelaan dalam mempelajari lalu menghidupi naskah-naskah ini. Meresapi kembali naskah mengharuskan momen-momen meditatif. Terkadang saya sering merenungkan, bahwa dalam membaca teks Yoga oleh Patanjali, yang menguraikan 8 tahapan Yoga, sejatinya juga dibalik ‘pedoman’ itu, kita pun saat membacanya sedang melaksanakan Yoga.
Intinya dari perumpamaan ini, tidak ada jalan singkat, atau cepat, atau aturan-aturan yang membuat naskah jadi untaian deskripsi yang gamblang, sebab, dalam membaca naskah sesungguhnya seseorang juga sedang bermeditasi. Alangkah dibutuhkannya waktu-waktu kontemplatif itu, khususnya sekarang, saat marabahaya mengepung manusia dari segala arah; bencana lingkungan hidup, peperangan, kesenjangan, hingga wabah.
Pengajar Filsafat di Universitas Indonesia