RUU Kesehatan, Antara Esensi dan Urgensi
Apakah ada yang salah dari begitu banyak UU terkait kesehatan saat ini sehingga diperlukan suatu regulasi dalam bentuk lain? Ataukah para pelaksana di lapangan tak dapat bekerja maksimal dalam mengimplementasikan UU ?
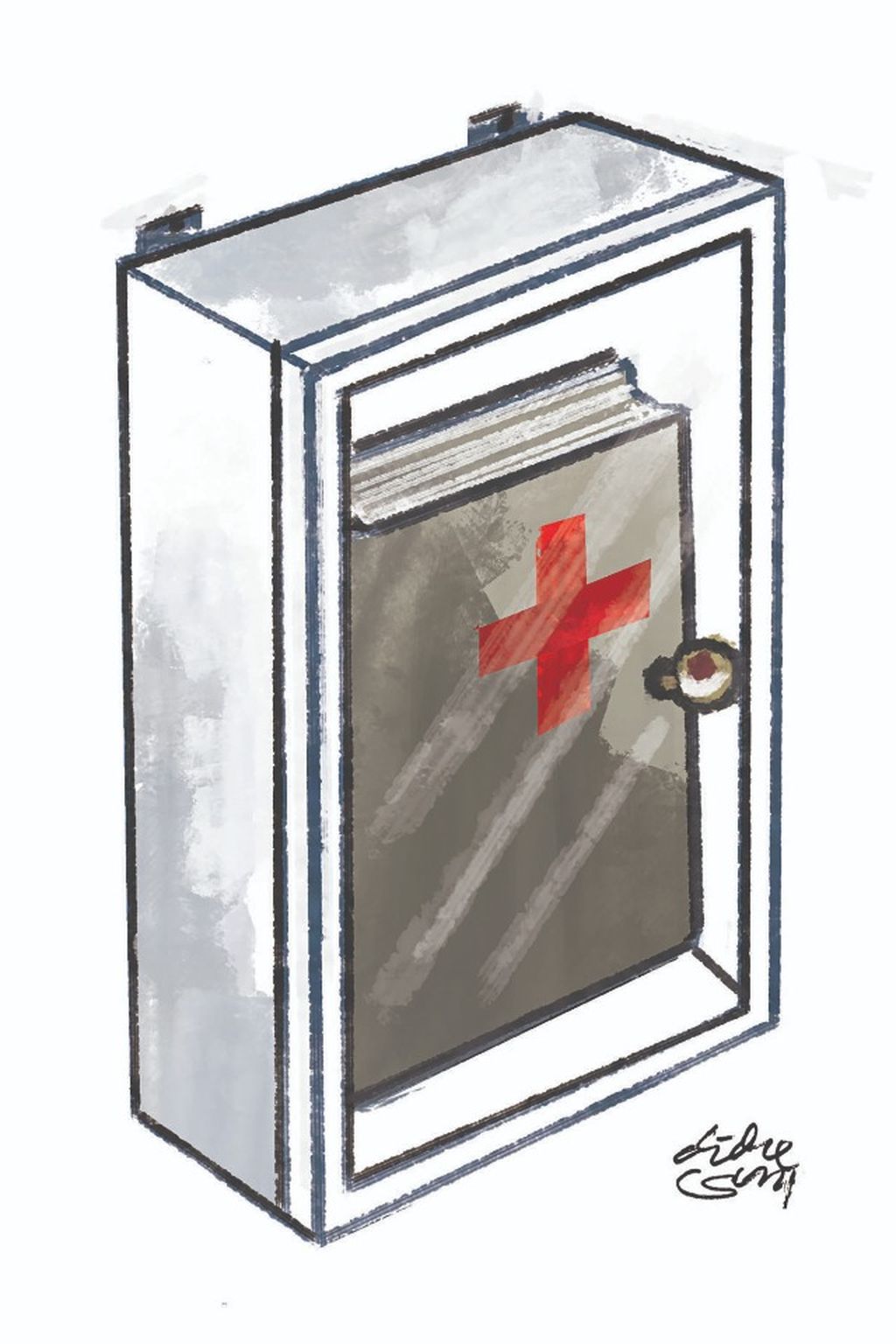
ilustrasi
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Demikian bunyi Pasal 28 (H) UUD 45 yang merupakan jaminan negara bagi setiap warga negara.
Namun, pemerataan pelayanan kesehatan dengan kualitas yang baik saat ini belum dapat dirasakan oleh banyak rakyat di negeri ini. Masih ada ratusan puskesmas yang tidak mempunyai tenaga dokter.
Selain itu, kurangnya fasilitas kesehatan berkualitas dengan anggaran biaya kesehatan yang masih rendah menyebabkan masalah kesehatan di negeri ini tak kunjung teratasi meskipun telah 77 tahun merdeka.
Hingga saat ini masih banyak masalah kesehatan yang serius di tengah masyarakat kita. Seperti angka tengkes (stunting) yang tertinggi di Asia Tenggara (29,4 persen), jauh lebih tinggi ketimbang negara-negara di Asia Timur (14,4 persen) dan Asia Barat (20,9 persen).
Selain itu, angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI) yang masih tinggi serta penyakit menular masih menghantui rakyat kita. Sistem rujukan dalam pelayanan kesehatan, mulai dari tingkat layanan primer sampai tersier, masih banyak masalah, yang sering kali menyulitkan.
Hingga saat ini masih banyak masalah kesehatan yang serius di tengah masyarakat kita.
Berbagai regulasi yang telah ada tentu bertujuan untuk mencapai kualitas pelayanan kesehatan yang baik dan merata. Sudah cukup banyak regulasi dalam bentuk UU disahkan DPR dalam kurun setidaknya dua dekade terakhir.
UU tersebut, antara lain, UU No 29/2004 tentang Praktik Kedokteran (Pradok), UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), UU No 44/2009 tentang Rumah Sakit, UU No 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), UU No 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran, tentang Tenaga Kesehatan, UU No 38/2014 tentang Keperawatan, UU No 4/2019 tentang Kebidanan, dan banyak lagi UU terkait kesehatan.
Esensi dari semua regulasi tersebut tidak lain bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan sebaik-baiknya yang bermutu dan merata, serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, sampai saat ini masih banyak warga yang belum terjangkau pelayanan kesehatan yang memadai.
Oleh karena itu, tidak heran ada yang beranggapan bahwa semua regulasi terkait kesehatan yang ada harus diubah dengan suatu metode regulasi yang saat ini sedang ”tren” yang dikenal sebagai omnibus law alias UU sapu jagat.
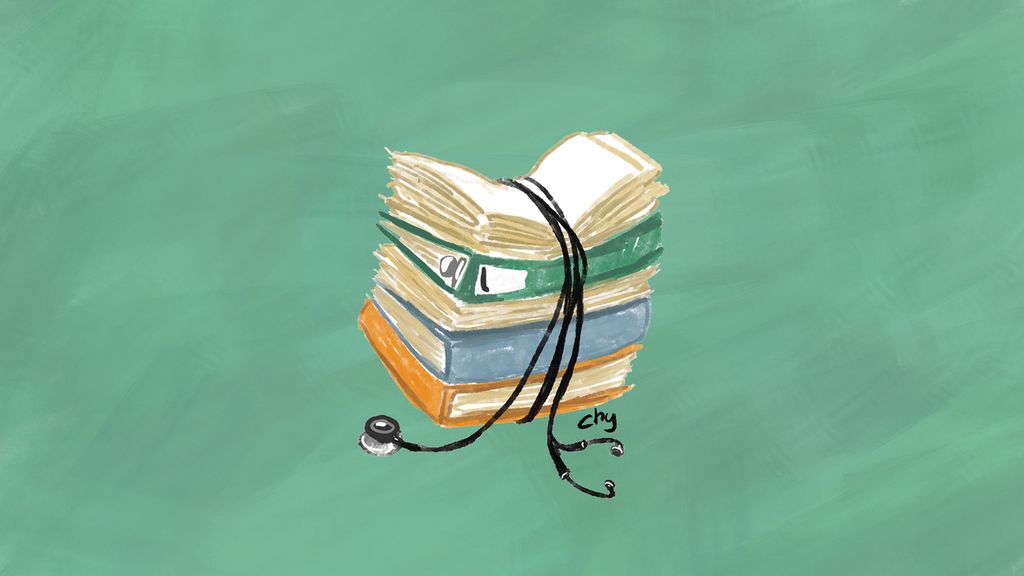
Apakah memang demikian? Pertanyaan yang mendasar adalah: apakah ada yang salah dari begitu banyak UU terkait kesehatan saat ini sehingga diperlukan suatu regulasi dalam bentuk lain? Ataukah para pelaksana di lapangan tak dapat bekerja maksimal dalam mengimplementasikan UU tersebut?
Perlu ”Omnibus”?
Akhir-akhir ini, khususnya di kalangan tenaga kesehatan, beredar draf RUU kesehatan yang dibuat dengan metode omnibus law, yakni suatu metode penyederhanaan sejumlah regulasi yang dinilai begitu panjang, berbelit, dan tumpang tindih menjadi suatu regulasi yang mengatur seluruhnya.
Omnibus berasal dari bahasa Latin yang artinya ’segalanya’. Setidaknya ada sembilan UU terkait kesehatan yang digabung jadi satu UU. Tentu saja ada pasal-pasal dengan muatan baru, perubahan materi muatan, dan pencabutan beberapa peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.
Munculnya draf RUU ini sangat mengejutkan banyak pihak, khususnya kalangan organisasi profesi, seperti dokter (Ikatan Dokter Indonesia/IDI), dokter gigi (Persatuan Dokter Gigi Indonesia/PDGI), perawat (Persatuan Perawat Nasional Indonesia/PPNI), bidan (Ikatan Bidan Indonesia/IBI), dan profesi kesehatan lain.
Penyebabnya, mereka merasa tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan RUU tersebut, seperti dikemukakan Ketua Umum Pengurus Besar IDI Dr Moh Adib Khumaedi dalam konferensi pers bersama beberapa organisasi profesi kesehatan lain di kantor IDI, 27 September lalu. Organisasi profesi kedokteran dan kesehatan sama sekali tak dilibatkan sebagaimana seharusnya dalam tata cara penyusunan suatu RUU.
Tak hanya itu, masyarakat sebagai masyarakat madani (civil society) tak pernah dilibatkan seperti yang disampaikan Tulus Abadi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Terkesan penyusunan RUU ini tidak membuka partisipasi masyarakat luas dan kalangan profesi di bidang kesehatan.
Organisasi profesi kedokteran dan kesehatan sama sekali tak dilibatkan sebagaimana seharusnya dalam tata cara penyusunan suatu RUU.
Hal ini sangat bertentangan dengan semangat reformasi dan akan menimbulkan dampak serius terhadap profesi dokter dan tenaga kesehatan lain dalam menjalankan tugasnya sesuai amanat UU. Sebenarnya, UU terkait profesi kesehatan yang ada saat ini secara umum sudah berjalan baik, khususnya dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat yang menerima layanan kesehatan. Dengan demikian, sejatinya tak ada urgensi menyusun UU baru dalam bentuk omnibus.
Menyederhanakan masalah
Dari segi substansi, RUU yang terdiri dari 20 bab dan 455 pasal ini terlihat menyederhanakan masalah kesehatan yang begitu luas dan kompleks.
Tidak jelas betul regulasi mana saja yang sekarang sudah tidak cocok atau saling tumpang tindih sehingga ada justifikasi untuk membuat UU baru dengan metode omnibus. Tentu saja hal ini harus dijelaskan dalam suatu naskah akademik yang baik dan transparan.
RUU ini terkait dengan tenaga-tenaga profesional kesehatan yang mempunyai tugas pokok dan wewenang serta kewajiban yang berbeda-beda dalam tugasnya sehari-hari.
Meskipun dokter dan dokter gigi sebagai tenaga medis termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) tidak dapat disatukan dengan konsil tenaga kesehatan lainnya karena mempunyai tugas yang lebih khusus terkait dengan keselamatan dan nyawa manusia. Hal ini sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No 82/2015.
Tidak sedikit isi dari beberapa pasal yang kurang tepat, bahkan bertentangan dengan kaidah profesi secara internasional, misalnya status KKI yang tak independen dan berada di bawah Kemenkes.

Pengambilalihan peran
Hal yang cukup penting untuk mendapatkan kritik serius adalah terjadi pengambilalihan peran dan kewenangan organisasi profesi oleh pemerintah, alias pemangkasan wewenang dan tugas profesi dalam pelayanan kedokteran dan kesehatan yang secara universal tidak boleh terjadi. Peran dan wewenang profesi yang diambil alih pemerintah merupakan salah satu muatan yang keliru dan kurang tepat, yang ditemukan dalam draf RUU ini.
Dalam dunia kedokteran internasional, pengakuan (rekognisi) kompetensi seorang dokter ataupun dokter spesialis adalah oleh otoritas badan khusus dalam profesi yang di Indonesia disebut kolegium, bukan oleh institusi lain atau suatu kementerian. Kolegium ini beranggotakan orang-orang terpilih dengan kapasitas yang mumpuni dan integritas tinggi.
Penyusunan materi tentang pendidikan profesi kedokteran dalam RUU Kesehatan ini, dengan cara melebur UU No 30/2013 tentang pendidikan profesi bidang kedokteran, juga hal yang keliru. Proses pendidikan dokter merupakan rangkaian kegiatan yang khusus dan terstruktur walaupun memang masih ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan.
Pendidikan profesi dokter, termasuk dokter spesialis, adalah ranah Kemendikbudristek dengan regulasi tersendiri. Namun, secara global, pengaturan pendidikan profesi kedokteran adalah otoritas dan tugas dari profesi yang bekerja sama dengan rumah sakit pendidikan karena terkait dengan kompetensi dan etika.
Baca juga : Kontroversi RUU Kesehatan
Sentralisasi pengaturan
Dalam RUU Kesehatan yang beredar terlihat terdapat pengaturan sentralisasi pengaturan terhadap peran profesi kedokteran, misalnya status Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).
KKI merupakan badan regulator profesi kedokteran yang dibentuk untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Dalam dunia internasional, konsil kedokteran dikenal sebagai professional medical regulatory authority (PMRA) yang berstatus independen.
Di banyak negara, konsil kedokteran diangkat dan bertanggung jawab kepada kepala negara seperti yang telah tercantum dalam UU No 29/2004 tentang praktik kedokteran. KKI merupakan suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen.
Karena status yang independen inilah, KKI dapat diterima dalam Asosiasi Konsil Kedokteran Internasional (International Medical Regulatory Authority/IAMRA). Dengan status yang independen inilah konsil kedokteran akan dapat meregulasi praktik kedokteran secara profesional untuk kepentingan masyarakat, tanpa intervensi dari pihak mana pun.
Namun, dalam RUU Kesehatan, Pasal 239 Ayat 2 berbunyi: ”Konsil Kedokteran Indonesia dan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada Menteri”.
Ini berarti KKI berada pada posisi yang tak independen dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Jika seperti itu, terjadi degradasi peran KKI. Akibatnya, bukan tak mungkin Indonesia dikeluarkan dari organisasi internasional IAMRA.
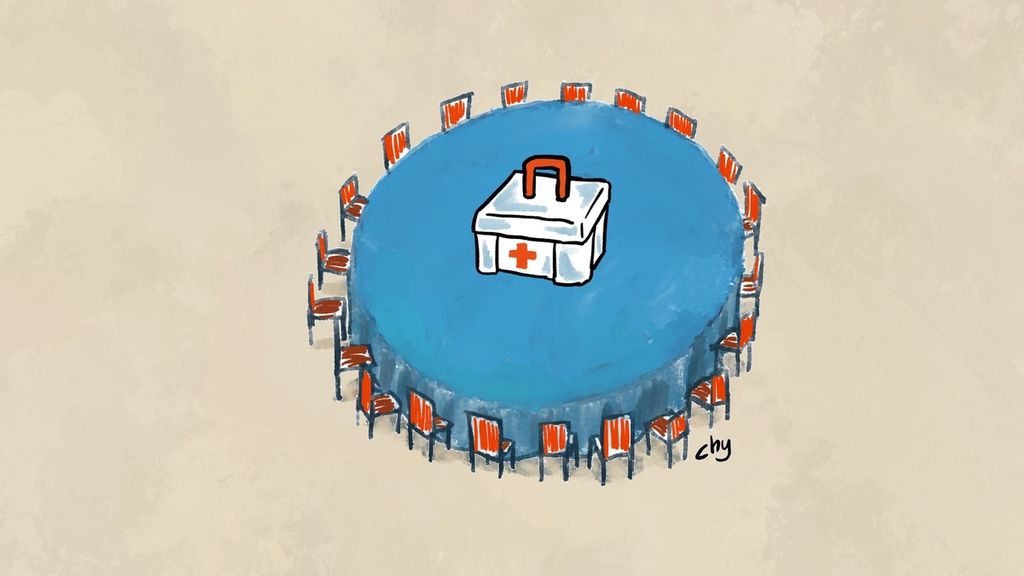
Di dalam UU No 29/2004 disebutkan bahwa surat tanda registrasi (STR) yang diterbitkan oleh KKI merupakan bukti bahwa seorang dokter mempunyai kompetensi yang sah untuk menjalankan praktik yang disebut sebagai lisensi yang berlaku selama lima tahun. Di dalam draf RUU Kesehatan ini penerbitan STR oleh KKI dalam pengawasan Kementerian Kesehatan.
Padahal, syarat penting dari penerbitan STR adalah sertifikat kompetensi yang merupakan otoritas profesi/kolegium. Disebutkan pula dalam salah satu pasal bahwa STR diberlakukan tanpa batas waktu akan membawa kita mundur ke situasi 30-40 tahun yang lalu.
Dengan tidak adanya resertifikasi dokter sama sekali setelah beberapa tahun, berarti tidak ada kewajiban bagi dokter untuk melakukan pemutakhiran ilmu dan keterampilannya secara berkesinambungan sehingga sangat berpotensi tidak ada jaminan perlindungan keselamatan bagi masyarakat.
Masih cukup banyak muatan lain yang perlu dikritisi dalam RUU Kesehatan ini. Jika RUU ini dipaksakan untuk disahkan, hal itu akan sangat berpotensi menimbulkan masalah dan kegaduhan di masyarakat, khususnya profesi kesehatan, seperti yang pernah terjadi pada UU omnibus law bidang lain.
RUU Kesehatan ini sebenarnya ”tidak urgen” karena UU yang terkait kesehatan yang ada sudah berjalan dengan baik dan hanya perlu perbaikan implementasinya.
RUU Kesehatan ini sebenarnya ”tidak urgen” karena UU yang terkait kesehatan yang ada sudah berjalan dengan baik dan hanya perlu perbaikan implementasinya. Dengan demikian, tak cukup alasan untuk menggabungkan UU terkait kesehatan yang ada ke dalam keranjang UU sapu jagat.
Yang diperlukan saat ini adalah suatu UU Sistem Kesehatan Nasional dengan fokus utama upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas fasilitas kesehatan serta meningkatkan anggaran biaya kesehatan untuk meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan, ketimbang menyusun UU ”sapu jagat”. Semoga.
Sukman Tulus PutraKetua Perhimpunan Kardiologi Anak Indonesia (PERKANI), Anggota Dewan Pertimbangan PB IDI, Ketua Divisi Pembinaan MKEK-IDI, Komisioner Konsil Kedokteran Indonesia 2014-2020

Sukman Tulus Putra