Ilmu Pengetahuan dan Kuasa Politik
Kebijakan nasionalisasi pada awal kemerdekaan turut mengubah tatanan sains. Namun pemerintah luput merasionalisasi kedudukan dan peran para ilmuwan agar tidak terikat oleh kepentingan politik dan birokrasi.
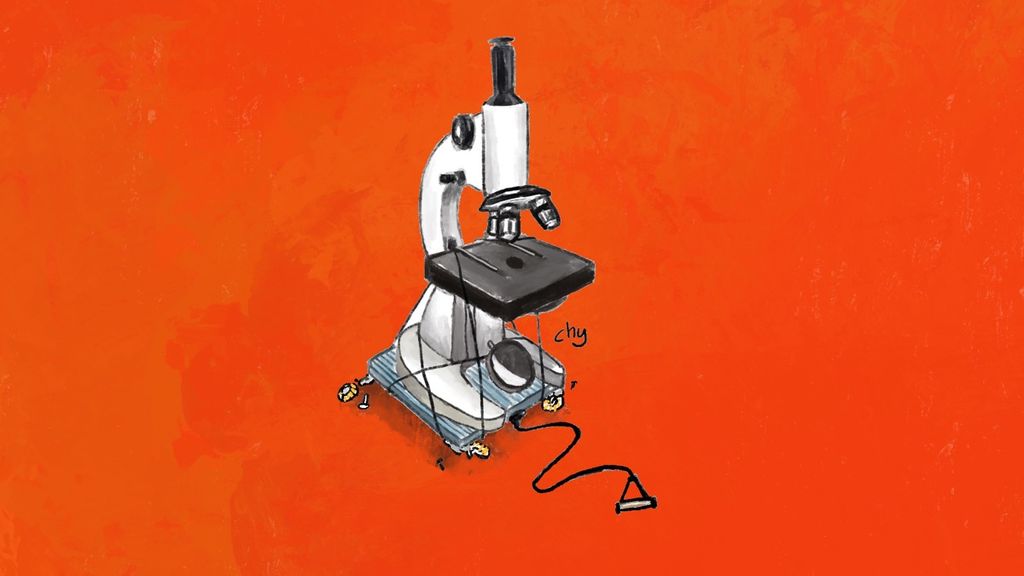
Polemik terkait peleburan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman dan beberapa lembaga riset ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) masih hangat diperbincangkan. Kesan politis di balik peleburan ini dikhawatirkan oleh sebagian kalangan ilmuwan dan peneliti dapat mengancam marwah riset berdasarkan spirit ilmu pengetahuan yang benih-benihnya telah dipupuk sejak lampau.
Ketika kabar peleburan beredar, nama Eijkman seketika mencuat. Ahli patologi dan bakteriologi Belanda Christian Eijkman dianggap sebagai tokoh penting dalam awal perkembangan sains (wetenschap) di Indonesia. Sejak ia menjejakkan kakinya di Hindia Belanda pada 1883, lalu menjabat sebagai Direktur Geneeskundig Laboratorium (Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat) pada 1888, riset penting yang dilakukan Eijkman adalah penyelidikan beri-beri.
Eijkman berjasa dalam memecahkan misteri beri-beri yang selama berabad-abad diderita oleh banyak penduduk di Nusantara. Ia membuktikan bahwa penyakit ini dikarenakan faktor kekurangan vitamin B1 (thiamine) dalam makanan. Kebiasaan orang-orang pribumi mengkonsumsi beras putih (tanpa kulit ari) ternyata menjadi penyebab hilangnya nutrisi dalam kandungan makanan mereka. Selain sebagai peletak dasar konsep vitamin yang membuatnya mendapat penghargaan Nobel pada 1929, pengaruh Eijkman juga dinilai penting dalam awal pengembangan bidang ilmu gizi di Indonesia dan dunia.
Baca juga: Independensi Lembaga Riset
Sains dan politik kolonial
Bukan hanya di bidang kedokteran. Legasi kolonialisme dalam riset ilmiah juga ada dalam bidang sains lainnya, seperti botani, agrikultur, zoologi, dan geologi. Kondisi geografis dan biodiversitas Nusantara telah menarik perhatian para saintis Eropa untuk menyelidikinya secara ilmiah. Bidang vulkanologi, misalnya, berkembang sebagai respons para ilmuwan terkait sering terjadinya erupsi gunung api di Nusantara.
Kepentingan politik dan ekonomi kolonial dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan pun tidak dapat dipungkiri. Eksploitasi pertambangan memiliki relasi erat dengan perkembangan riset geologi sejak dekade 1850-an. Pun Sistem Tanam Paksa dan Undang-Undang Agraria memiliki kaitan dengan perkembangan riset botani untuk komoditas ekonomi kolonial (economic botany).
/https%3A%2F%2Finr-production-content-bucket.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com%2FINR_PRODUCTION%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F02%2F01%2Fe42ccd6c-f100-4a97-8416-3e22305a1ea4_jpg.jpg)
Gedung Lembaga Biologi Melekuler Eijkman atau Lembaga Eijkman di Jakarta Pusat, Selasa (4/1/2022).
Sebagai negeri tropis dengan curah hujan tinggi, kepulauan Nusantara kaya akan potensi vegetasi. Pemanfaatan ragam jenis tanaman untuk kebutuhan sandang, pangan, dan papan telah dimanfaatkan oleh penduduk Nusantara jauh sebelum masuknya pengaruh Eropa. Semangat Renaisans orang-orang Eropa dalam misi emporium mereka ke Nusantara, turut mengemban pula ambisi sains. Seiring dengan eksplorasi rempah-rempah, sejak abad ke-16 hingga ke-17 riset botani di Kepulauan Nusantara mulai dirintis dan terus berkembang hingga mencapai puncaknya pada abad ke-19.
Pendirian Lands Plantentuin (Kebun Raya) di Buitenzorg (sekarang Bogor) pada 1817 yang digagas oleh Reindwardt menjadi bukti sejarah simbol kejayaan Indonesia sebagai laboratorium penelitian tanaman di dunia. Sepanjang abad ke-19 hingga awal abad ke-20 para botanis masyhur dari Eropa dan Amerika Serikat pernah melakukan penelitian tanaman-tanaman tropis di kebun raya Bogor untuk proyek riset botani mereka. Dalam kerja risetnya mereka dibantu oleh para asisten peneliti dari kalangan Bumiputera.
Pendirian Lands Plantentuin (Kebun Raya) di Buitenzorg (sekarang Bogor) pada 1817 yang digagas oleh Reindwardt menjadi bukti sejarah simbol kejayaan Indonesia sebagai laboratorium penelitian tanaman di dunia.
Tingginya intensitas penelitian turut memacu produktivitas karya-karya botani yang dihasilkan oleh para ilmuwan seperti Reindwardt, Treub, Heyne, dan Ochse. Karya-karya mereka menjadi fondasi penting dalam pemetaan tanaman-tanaman di kawasan biogeografis Malesia (mencakup Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, dan Papua Nugini) yang dihimpun oleh lembaga National Herbarium Belanda lalu diterbitkan pada 1950 dengan judul Flora Malesiana.
Dalam kasus di bidang botani, sebagaimana dikaji sejarawan Andrew Goss, The Floracrats: State-Sponsored Science and the Failure of the Englightenment in Indonesia (2011), para botanis masa kolonial menunjukkan kapasitas yang unik dalam mengelola kesenjangan antara birokrasi kolonial dan pengusaha perkebunan Belanda. Ini menjadi semacam model kolaborasi ketika para ilmuwan pada satu sisi diharapkan oleh pemerintah dapat mendukung kebijakan ekonomi kolonial, namun sisi lain melalui kepakaran keilmuannya mereka diharapkan dapat tetap mengkonservasi alam. Pada hakikatnya, eksploitasi alam dapat dikelola dengan tetap mengedepankan eksplorasi sains.

Gedung Lembaga Eijkman di Jalan Diponegoro 69, Jakarta Pusat. Dokumentasi Tropenmuseum, Belanda 30-01-2003
Nasionalisasi “ilmu pengetahuan”
Literatur-literatur sains pada era kolonial menjadi penanda keberlanjutan riset ilmiah yang berkembang secara progresif. Namun hal itu berubah sejak 1942 hingga awal kemerdekaan Indonesia. Kebijakan nasionalisasi pada awal kemerdekaan turut mengubah tatanan sains yang telah dikembangkan para ilmuwan pada masa kolonial. Istilah “ilmu pengetahuan” untuk pertama kalinya digunakan secara formal pada 1951 menggantikan istilah Belanda, wetenschap (science). Bagi Sukarno, ilmu pengetahuan adalah sarana untuk mencapai tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan berlandaskan pada ideologi kebangsaan.
Pandangan anti kolonial yang menyeruak pada era poskolonial telah mengubah pandangan terhadap berbagai produk ilmu pengetahuan warisan kolonial. Sukarno menilai ilmu pengetahuan kolonial lebih merupakan sains murni (pure science) yang hanya menghasilkan pengetahuan untuk orang-orang Eropa saja. Berbeda dengan kesan ilmu pengetahuan kolonial yang bertengger di menara gading, dalam pandangan Sukarno, ilmu pengetahuan di era kemerdekaan lebih ditujukan sebagai applied science untuk kemaslahatan rakyat demi memajukan kesejahteraan hidup bangsa Indonesia.
Baca juga: Robohnya “Eijkman” Kita
Kuasa politik pada awal kemerdekaan yang mengusung semangat dekolonialisasi terhadap berbagai aspek kehidupan, ditandai pula dengan nasionalisasi aset-aset bangunan dan lembaga riset warisan kolonial. Namun dalam proses nasionalisasi itu, mata rantai ilmu pengetahuan dari masa kolonial justru terputus. Sentimen anti kolonial turut mengorbankan literatur-literatur sains yang sejatinya sangat penting diterjemahkan pada era poskolonial, semisal empat jilid karya ensiklopedia botanis Heyne, Nuttige planten van Nederlandsch-Indië yang terbit secara berurut dari tahun 1913 hingga 1917.
Kitab yang mengandung pengetahuan lengkap tentang tanaman-tanaman bermanfaat di Indonesia tersebut pada masa pra kemerdekaan merupakan rujukan utama bagi para botanis. Namun sejak 1950-an, karya akbar Heyne yang dalam penyusunannya tidak lepas dari bantuan para asisten Bumiputeranya itu sempat dilupakan. Penerjemahannya ke dalam bahasa Indonesia baru terwujud pada 1987 berkat kerjasama antara Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan Belanda.
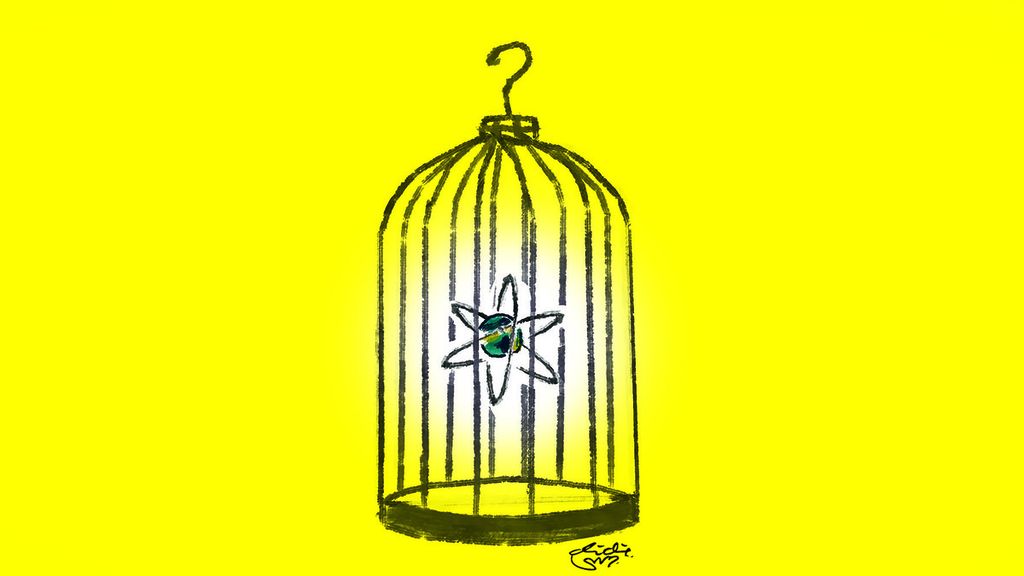
-
Kisah Heyne dan karyanya adalah sekeping permasalahan transisi ilmu pengetahuan dari masa kolonial ke masa awal kemerdekaan. Sebuah studi dari Adam Feeser, Effects of the Indonesian National Revolution and Transfer of Power on the Scientific Establishment (1994) patut direfleksikan untuk memahami akar permasalahan ketika kuasa politik pemerintah mengambil alih tongkat estafet sains kolonial. Feeser menilai ada fase yang belum selesai dalam transfer pengetahuan kolonial kepada rakyat Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Pemerintah memang menasionalisasi berbagai infrastruktur sains kolonial, namun menurut Feeser itu tanpa disertai “juru-juru kunci” yang terlatih untuk menjaga obor pengetahuan dapat tetap menyala dengan spirit baru (nasionalisme), tentu.
Interaksi politik dan ilmu pengetahuan setidaknya memberikan suatu gambaran transisi dari negara kolonial ke poskolonial. Alih-alih berfokus untuk menyejahterakan rakyat melalui pendekatan ilmu pengetahuan, pemerintah justru luput merasionalisasi kedudukan dan peran para ilmuwan agar tidak terikat oleh kepentingan politik dan juga birokrasi pemerintahan. Apa yang dikatakan Goss (2011) kiranya patut dicamkan, bahwa penggunaan teknokrasi kerap memunculkan distraksi. Kebijakan negara terhadap ilmu pengetahuan bukanlah perihal menciptakan solusi teknis semata tetapi tentang bagaimana menghasilkan sistem yang dapat dikelola secara efektif sehingga ilmu pengetahuan dapat memberikan kemaslahatan seluas-luasnya bagi kehidupan rakyat Indonesia.
Baca juga: Riset untuk Kemakmuran Bangsa
Jika ilmu pengetahuan memang memberikan kemaslahatannya, barangkali tidak pernah ada eksploitasi hutan yang merusak serta mengusir rakyat dari tanah ulayatnya. Keanekaragaman flora dan fauna yang didambakan oleh para naturalis sejatinya juga tetap lestari. Begitupun lahan-lahan pangan tetap terjaga ekosistemnya sehingga rakyat tidak perlu khawatir dengan ancaman krisis pangan. Dan, kekayaan potensi sumber daya mineral di setiap daerah yang ditambang betul-betul memberikan kesejahteraan bagi kehidupan rakyat. Bukankah demikian tujuan ilmu pengetahuan yang diidealkan oleh Sukarno?

Fadly Rahman, Dosen Departemen Sejarah dan Filologi Universitas Padjadjaran