Keluar dari Jebakan Stagnasi Pertumbuhan
Berdasarkan hasil studi, regulasi dan institusi merupakan penghambat utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Regulasi tak efisien ditambah pengawasan yang lemah dan praktik ”moral hazard”.

Presiden Joko Widodo dalam Pidato pengantar Nota Keuangan dan RAPBN 2024 pada 16 Agustus 2023 menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 sebesar 5,2 persen.
Di tengah situasi perlambatan ekonomi global dan resesi ekonomi di banyak negara, angka pertumbuhan sebesar itu memang masih salah satu yang terbaik di dunia. Namun, dengan target tersebut, berarti pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami stagnasi atau tidak bergerak secara signifikan dalam 10 tahun terakhir.
Perlu diketahui, APBN 2024 akan menjadi anggaran terakhir yang akan dijalankan oleh pemerintah saat ini sebelum nantinya terjadi peralihan kepemimpinan nasional pada Oktober 2024.
Dengan target pertumbuhan 2024 sebesar 5,2 persen, rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi 10 tahun terakhir adalah 4,23 persen. Jauh dari target optimistis yang disampaikan Presiden Jokowi pada awal masa kepemimpinan, yang sebesar 7 persen, atau target pertumbuhan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang 6,0-6,2 persen pada akhir 2024.
Tentu tidak bisa dimungkiri, selama dua tahun 2020-2022, perekonomian global menghadapi krisis multidimensi yang disebabkan pandemi Covid-19. Kondisi ini menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Pasca-Covid-19, pemulihan ekonomi Indonesia banyak terbantu oleh tingginya harga komoditas unggulan, seperti batubara, nikel, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Ujian sesungguhnya terlihat ketika harga komoditas mulai turun, sekitar pertengahan 2023.
Pasca-Covid-19, pemulihan ekonomi Indonesia banyak terbantu oleh tingginya harga komoditas unggulan, seperti batubara, nikel, kelapa sawit, dan komoditas lainnya.
Penyebab stagnasi
Persoalan stagnasi pertumbuhan bukan tanpa disadari oleh pemerintah. Kementerian PPN/Bappenas pernah membuat kajian mengenai kendala paling mengikat (most binding constraint) bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Kajian ini merupakan salah satu background study penyusunan RPJMN 2020-2024. Kajian ini menggunakan pendekatan yang populer dikenal dengan istilah growth diagnostics sebagai instrumen pengidentifikasi faktor yang paling menghambat laju pertumbuhan di suatu negara.
Pendekatan growth diagnostics pertama kali diperkenalkan oleh tiga pakar ekonomi, yaitu Ricardo Hausmann, Dani Rodrik, dan Andres Velasco, melalui artikel mereka berjudul ”Growth Diagnostics”. Melalui tulisan tersebut, ketiganya memperkenalkan pendekatan baru untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi sebuah negara hingga mengerucut pada beberapa isu yang dianggap sebagai penghambat utama dari lambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Studi ini menemukan bahwa regulasi dan institusi merupakan penghambat utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Regulasi yang tidak efisien menciptakan biaya tetap (fixed cost) yang tinggi. Begitu pula dalam hal institusi penyusun regulasi dan pengawasan yang sangat lemah serta praktik moral hazard.
Selain dua isu tersebut, hasil studi ini juga mengidentifikasi lemahnya modal manusia (SDM) sebagai penghambat utama di masa depan, khususnya dalam hal keterampilan dan pendidikan. Hal ini tak bisa dilepaskan dari kualitas pendidikan dan kesehatan yang tertinggal dibandingkan dengan negara berkembang lain (peers).
Terakhir, kurang efektifnya penerimaan dan belanja negara (APBN) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
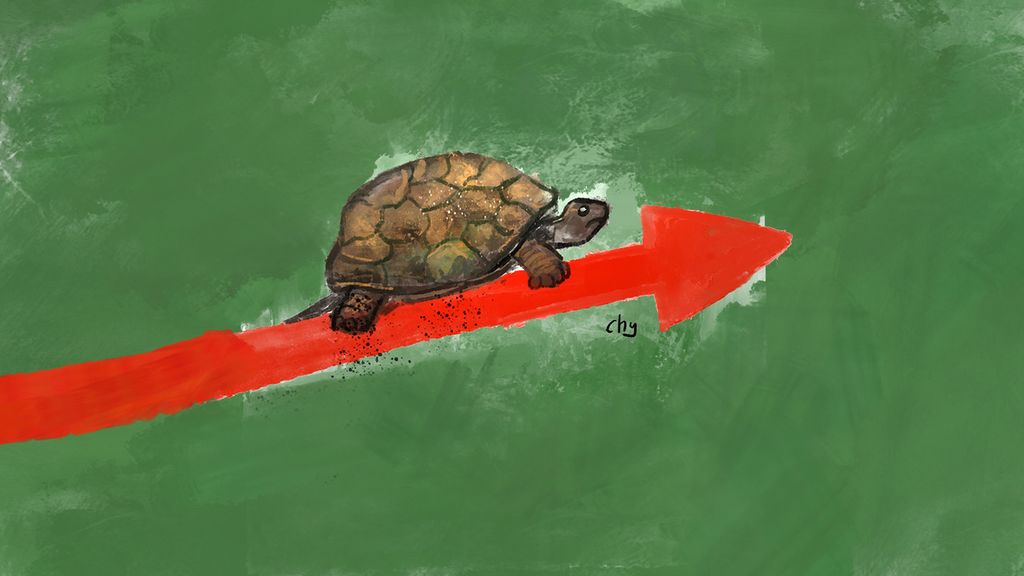
Menghilangkan faktor penghambat
Upaya untuk menyelesaikan persoalan regulasi yang cenderung bersifat restriktif dan tak mendukung penciptaan dan pengembangan dunia usaha sudah dilakukan pemerintah.
Kebijakan reformasi struktural dan percepatan transformasi ekonomi selalu menjadi tema yang dicanangkan pemerintah dalam APBN setiap tahunnya.
Mulai dari Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, UU No 2/2022 tentang Cipta Kerja, UU No 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), UU No 3/2022 tentang IKN, UU No 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), UU No 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), hingga UU No 17/2023 tentang Kesehatan.
Hampir semua regulasi dan peraturan perundang-undangan yang lahir pada periode tersebut bertujuan untuk memangkas banyak aturan agar menciptakan iklim kemudahan berusaha dan investasi yang menghambat dan tumpang tindih selama ini. Dengan demikian, bisa menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi.
Keinginan tersebut tidak sepenuhnya berjalan baik. Proses penyusunan sebagian regulasi tersebut berlangsung pada saat konsentrasi publik terkuras untuk menghadapi pandemi Covid-19, yang sedang berada pada puncaknya, sehingga meninggalkan banyak catatan untuk dilaksanakan.
Implementasi peraturan-peraturan tersebut belum teruji dan perlu waktu untuk membuktikannya.
Lahirnya UU No 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU merupakan respons dari keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan cacat formil dari UU tersebut.
Logikanya keputusan MK tersebut harus dijalankan pemerintah untuk memperbaiki kualitas UU Cipta Kerja tersebut. Namun, pemerintah malah menerbitkan perppu, langkah yang dianggap kontroversi dan tidak mengindahkan keputusan MK tersebut. Akibatnya, relasi hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha dan dengan pemerintah menjadi kurang harmonis dan saling curiga satu dengan yang lain.
Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan semangat untuk membangun iklim investasi yang kondusif.
Studi ini menemukan bahwa regulasi dan institusi merupakan penghambat utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir.
Belum optimalnya penerimaan sektor perpajakan dalam perekonomian nasional tergambar dari rasio pajak yang masih rendah, yakni 8-11 persen dalam 10 tahun terakhir. Angka ini salah satu yang terendah di kawasan negara ASEAN dan urutan ke-134 dari 143 negara di dunia.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, dalam 10 tahun terakhir capaian penerimaan pajak berkisar Rp 1.000 triliun hingga Rp 1.700 triliun, sementara produk domestik bruto (PDB) dalam 10 tahun terakhir berkisar Rp 10.000 triliun hingga Rp 20.000 triliun.
Berdasarkan data yang diolah dari penerimaan pajak tersebut (Hernowo, 2023), sektor usaha skala menengah dan besar berkontribusi lebih dari 95 persen terhadap total penerimaan pajak. Adapun penerimaan pajak dari sektor usaha menengah dan kecil (UMKM) berkontribusi kurang dari 5 persen dari total penerimaan pajak. Padahal, jumlah UMKM mencapai 99 persen dari total UMKM di seluruh Indonesia.
Lahirnya UU HPP tersebut ditujukan agar peran penerimaan perpajakan sebagai tulang punggung dalam pendanaan APBN dapat berjalan secara sehat dan berkesinambungan. Di sisi lain, UU HPP juga memberikan payung hukum dalam optimalisasi penerimaan perpajakan sehingga kontribusinya terhadap pendapatan negara semakin meningkat seiring dengan struktur perekonomian nasional.
Efektivitas belanja pemerintah
Setali tiga uang, belanja kementerian lembaga (K/L) juga belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal. Berdasarkan hasil studi Kementerian PPN/Bappenas, seharusnya setiap peningkatan anggaran belanja K/L sebesar 1 persen akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi sebesar 0,06 persen.
Sebagai contoh, pada 2018 hingga 2019 terjadi peningkatan anggaran belanja pemerintah pusat sebesar 2,8 persen, tetapi realisasi dampak pada pertumbuhan ekonomi negatif 0,20 persen, meleset dari target. Secara potensi, pada 2018 sampai 2019, dengan peningkatan anggaran belanja pemerintah pusat, dampak pada pertumbuhan ekonom nasional seharusnya 0,17 persen, tetapi faktanya negatif 0,20 persen.
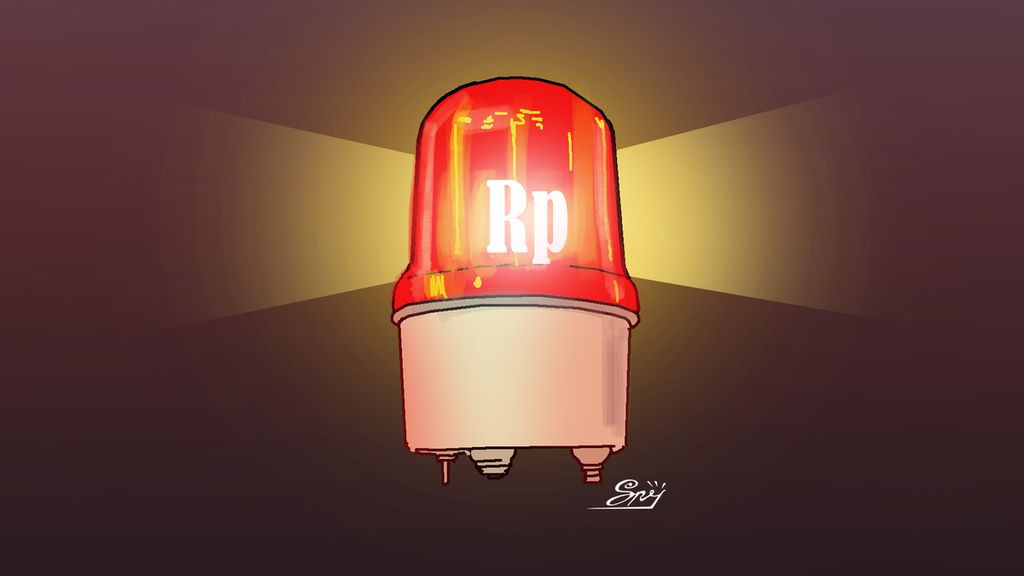
Sejatinya potensi tersebut bisa dimaksimalkan dengan beberapa upaya perbaikan. Misalnya, pendalaman instrumen belanja yang produktif, perbaikan akuntabilitas, dan transparansi dalam tata kelola belanja negara sehingga peningkatan anggaran yang dikucurkan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, faktor institusi dan birokrasi yang menghambat dan berbiaya tinggi sering kali menjadi persoalan dalam menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Masih tingginya angka incremental capital output ratio (ICOR), yakni 6,2 persen pada 2022, menunjukkan perekonomian nasional masih berbiaya tinggi dan kurang efisien. ICOR juga menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan masih kurang berkorelasi dengan penurunan biaya logistik.
Kajian mengenai kendala paling mengikat (most binding constraint) bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan pemerintah sudah memahami persoalan yang dihadapi.
Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, tema kebijakan fiskal selalu diarahkan untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka percepatan transformasi ekonomi. Jebakan pertumbuhan 5 persen sampai di pengujung periode pemerintahan 2024 membuat sulit bagi kita untuk berada pada jalur pertumbuhan 6 persen sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024.
Dengan berbagai fondasi yang sudah ada saat ini, harapan baru nantinya berada di pundak presiden terpilih kelak agar cita-cita menjadi negara maju bisa segera terwujud.
Baca Juga: Awas Jebak Stagflasi
Handi RiszaWakil Rektor Universitas Paramadina