”Angsa Hitam” Ekologi Kita
Pada relasi antara pembangunan ekonomi dan ekologi, realitas ”angsa hitam” kerap berawal dari hadirnya kebijakan-kebijakan pembangunan berlandaskan kajian akademis dan pertimbangan ilmiah, tetapi minim kalkulasi ekologi.
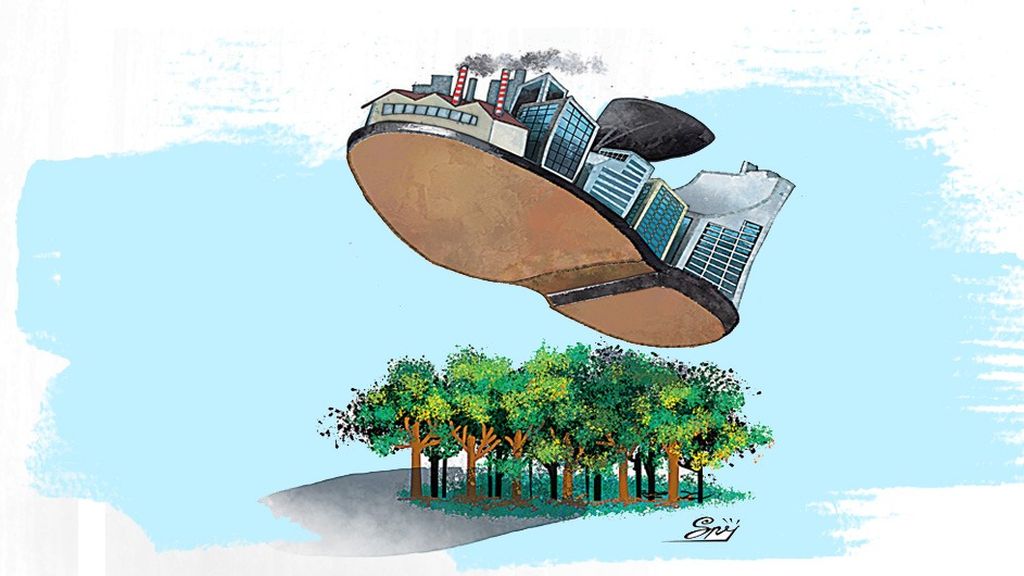
Ilustrasi
Sejak dekade 1990-an, kata ”keberlanjutan” mulai banyak diadopsi dalam perencanaan pembangunan, termasuk di Indonesia. Namun, seiring dengan itu, lingkungan hidup kita dalam kurun waktu hampir 30 tahun terakhir justru layaknya fenomena ”angsa hitam”: penuh ”ketidakterdugaan” berupa krisis iklim yang berakar pada krisis ekologi yang makin parah dan tak pernah kita bayangkan sebelumnya.
Meskipun ancaman krisis iklim bukan hal baru dalam beberapa dekade terakhir, laporan sintensis terbaru Panel Lintas Pemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC) Maret 2023 tetap membuat kita terenyak. Mereka mencatat, dalam rentang 2011-2020, suhu permukaan global telah mencapai 1,1 derajat celsius di atas tingkat pra-industri. Peningkatan itu disebut yang tertinggi dalam kurun 2.000 tahun. Peningkatan suhu tercepat terjadi sejak dekade 1970-an.
Laporan tersebut juga menyampaikan pesan kepada semua negara untuk bersama membatasi kenaikan pada 1,5 derajat celsius, dengan mengurangi emisi karbon setidaknya hampir setengah pada tahun 2030. Jika kenaikan suhu melebihi batasan tersebut, kehidupan di Bumi terancam punah.
Baca juga: Bumi dan Krisis Iklim
Dalam kehidupan nyata, laporan IPPC ini mengafirmasi gejala-gejala alam yang belakangan kita rasakan penuh anomali, seperti temperatur udara yang kian terasa gerah dan intensitas banjir yang terdengar makin sering terjadi di sejumlah daerah begitu hujan turun.
Ya, Indonesia memang tak lepas dari krisis iklim global itu. Dari hasi perhitungan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2019, tingkat emisi GRK pada 2019 sebesar 1.866.552 Gg CO2e (gigagram setara karbondioksida). Dari jumlah itu, 60 persen disumbangkan sektor kehutanan dan pertanian (Kompas, 29 Maret 2023).
Seiring pesatnya pembangunan ekonomi sejak 1970-an, sektor kehutanan kita merupakan salah satu yang paling terdampak. Berdasarkan data State of Indonesia’s Forest 2022 KLHK, kawasan hutan yang masih memiliki tutupan hutan seluas 88,1 juta hektar atau sekitar 46 persen dari luas daratan Indonesia.

Hasil investigasi Greenpeace yang menemukan deforestasi di Papua yang dijadikan kebun kelapa sawit.
Dengan luas hutan permanen yang diperkirakan 122 juta hektar pada 1970, luas tutupan hutan—area yang sangat penting bagi penyimpanan karbon dan keanekaragaman hayati—kita yang hilang dalam beberapa dekade ini sekitar 33,9 juta hektar. Angka ini belum termasuk luas hutan yang telah dilepaskan, yang menurut KLHK mencapai sekitar 7,4 juta hektar pada 1984-2020.
Faktor deforestasi, kebakaran hutan dan gambut, serta alih fungsi lahan hutan tak hanya berdampak pada emisi GRK Indonesia, tetapi juga menghadirkan kerugian tak kurang dari 62,7 miliar dollar AS atau senilai Rp 940 triliun per tahun (Food and Land Use Coalition, 2020). Kerugian tersebut setara dengan 54,7 persen penerimaan pajak nasional pada 2022.
Fakta dan data tersebut menunjukkan, apa yang selalu kita dengungkan sebagai ”pembangunan keberlanjutan” sejak bertahun-tahun silam, sebagian besar belum terimplementasi dengan semestinya.
Faktor deforestasi, kebakaran hutan dan gambut, serta alih fungsi lahan hutan tak hanya berdampak kepada emisi GRK Indonesia, tetapi juga menghadirkan kerugian tak kurang dari 62,7 miliar dollar AS.
Sayangnya, mimpi kesejahteraan yang kita beli dari rusaknya ekologi pun nyatanya masih jauh dari harapan. Eksploitasi kekayaan alam yang begitu besar, belum berimbas pada kemajuan ekonomi secara signifikan. Meski produk domestik bruto (PDB) per kapita naik berlipat dari 1.020 dollar AS (1995) menjadi 4.783,9 dollar AS (2022), belum membawa negeri ini keluar dari kuadran awal jebakan pendapatan menengah (Bank Dunia, 2022).
Lalu di mana sebenarnya masalah kita? Mengapa kita seperti gagal memprediksi dampak kebijakan ekonomi yang kita buat dengan membuat kebijakan pembangunan yang menyejahterakan sekaligus ramah lingkungan?
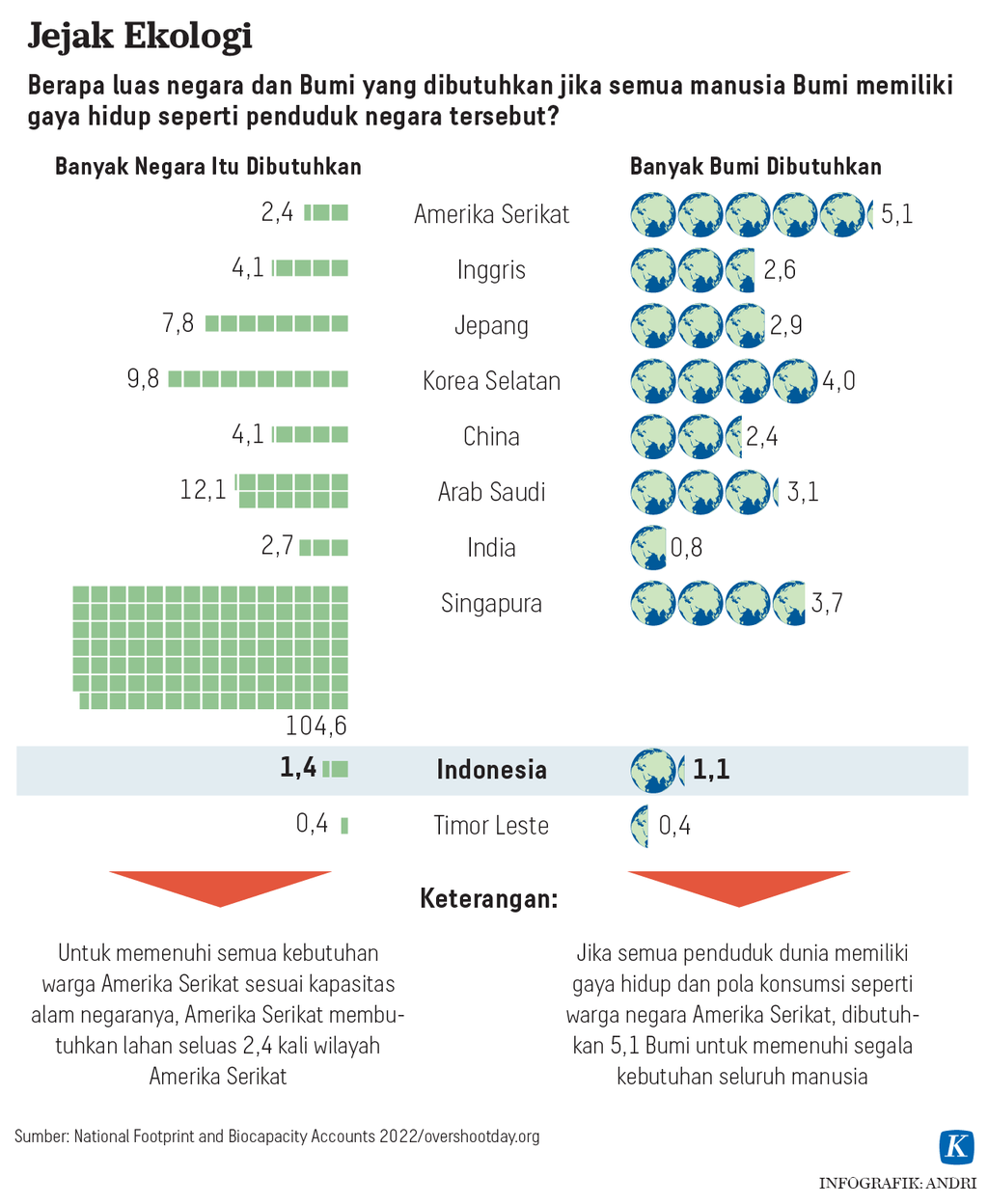
Fenomena ”angsa hitam”
Banyak peristiwa ataupun fenomena besar yang berdampak luas bagi kehidupan di dunia ini yang tak terprediksi atau setidaknya gagal diprediksi sekaligus mengejutkan, tetapi tak terjadi secara kebetulan, atau terjadi lebih dari yang diprediksikan. Dalam bukunya berjudul Black Swan (2007), Nassim Nicholas Taleb, menyebut hal ini sebagai fenomena ”angsa hitam”.
Fenomena ini bermula dari asumsi masyarakat Eropa pada abad ke-17 bahwa semua angsa berwarna putih. Padahal, ada angsa berwarna hitam hidup di alam liar yang jauh dari Eropa.
Meskipun pada awalnya ”angsa hitam” adalah untuk melihat banyaknya fenomena di luar dugaan di sektor finansial, Taleb melihat hal tersebut juga berlaku untuk peristiwa politik, bencana alam, kebangkitan keagamaan, dan kejadian pribadi.
Pandangan ”angsa hitam” Taleb berangkat dari asumsi bahwa banyak hal yang sesungguhnya tidak diketahui manusia. Namun, manusia berpikir bahwa mereka tahu lebih banyak daripada yang diketahui. Hal itu membentengi pikiran manusia dengan hal-hal yang tidak relevan dan tidak memiliki konsekuensi, dan kita tidak menyadarinya sejak awal.
Baca juga: Menyelaraskan Kebutuhan Ekologi dan Pembangunan
Di sinilah awal kegagalan manusia memprediksi banyak peristiwa di dunia ini. Bahwa meskipun pengetahuan kita maju dan berkembang, banyak hal yang tetap tak terprediksi karena sifat manusia dan intelektual kerap bersekongkol untuk menyembunyikan ide dan pengetahuan tertentu.
Dalam relasi antara pembangunan ekonomi dan ekologi, realitas ”angsa hitam” ini kerap bermula dari hadirnya kebijakan-kebijakan pembangunan yang dilandasi kajian akademis dan pertimbangan ilmiah yang minim akan perhitungan ekologi. Kita hanya peduli dan fokus untuk bagaimana mengejar pertumbuhan ekonomi. Sementara pertimbangan dampak ekologi kita sisihkan. Dalam situasi demikian, lahirlah banyak kebijakan ekonomi yang cenderung berseberangan dengan prinsip keberlanjutan, yang di kemudian hari menghadirkan krisis lingkungan yang mengejutkan, seperti halnya krisis iklim saat ini.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F11%2F17%2F91cfc455-da69-4db6-b58d-f07cfaa8b564_jpg.jpg)
Sejumlah pegiat lingkungan hidup berunjuk rasa di Jalan Balai Kota, Medan, Sumatera Utara, Kamis (17/11/2022). Mereka menyesalkan Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali yang dinilai tidak menghasilkan perubahan berarti dalam mengatasi krisis iklim.
Dalam buku ”25 Tahun KEHATI” (2022), Guru Besar IPB University, Prof Hariadi Kartodihardjo menyampaikan, di negeri ini—juga dunia—penuh dengan hikayat tentang rusaknya hutan dan lingkungan hidup (ekologi) ketika harus bertarung melawan kepentingan dan kekuatan ekonomi. Sementara ekologi dan lingkungan hanya menjadi pilihan ke-2 atau ke-4, atau bahkan, seringkali, yang terakhir. Karena itu, dalam setiap proses pembangunan, faktor ekologi selalu kalah, atau harus ”mengalah” demi pembangunan ekonomi.
Hal ini bukan semata soal kelalaian atau akibat terbatasnya pengetahuan, melainkan juga dapat terjadi akibat desain politik pembangunan. Politik seperti itu selalu mudah diterima karena dampak buruk kerusakan keanekaragaman hayati sebagaimana peran jasa lingkungan pada umumnya tidak terjadi seketika.
Di negeri ini—juga dunia—penuh dengan hikayat tentang rusaknya hutan dan lingkungan hidup (ekologi) ketika harus bertarung melawan kepentingan dan kekuatan ekonomi.
Kerusakannya bersifat kumulatif dan berdampak jangka panjang. Bahkan, tidak mudah diperkirakan kapan akan terjadi. Para pengambil kebijakan, seperti teknokrat dan politisi, lebih berfokus pada kepentingan-kepentingan ”trdekat” yang mudah mereka dan konstituen lihat, seperti angka pertumbuhan ekonomi berbasis PDB.
Kebijakan food estate pemerintah saat ini—yang mengulang kebijakan pemerintah Soeharto (1996-1997) melalui Proyek Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektar yang gagal total—barangkali merupakan contoh mudah tentang bagaimana ditinggalkannya kajian komprehensif, pengetahuan akademis, dan pengalaman detail dari masa lalu dalam pembuatan kebijakan. Alih-alih swasembada pangan, pembukaan lahan gambut untuk proyek tersebut kian menempatkan Kalimantan Tengah rawan bencana ekologis, seperti banjir, yang dulu tak pernah kita prediksikan.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2021%2F11%2F23%2Fc50da31a-f275-4dd0-a432-001d7db5786e_jpg.jpg)
Warga mengabadikan proyek penutupan kanal primer bekas Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) sejuta hektar di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (15/6/2017). Kanal itu ditutup setelah 20 tahun beroperasi. Penutupan dilakukan untuk memulihkan kembali lahan gambut.
Perkuat riset dan sains
Persoalan lain terkait kebijakan pembangunan di negeri ini adalah lemahnya dukungan riset yang baik. Pada 2019 hasil studi Doing Research Assessment yang dilakukan Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) menunjukkan, pembuatan kebijakan di Indonesia didominasi riset yang lemah secara teoretis tanpa tradisi penilaian sejawat (peer review) yang kuat dan dalam suasana kebebasan akademik terancam.
Mayoritas pembuat kebijakan (92,9 persen) juga mendaku menggunakan produk riset, seperti karya ilmiah, kertas kerja, presentasi, dan esai posisi. Namun, hubungan antara pelaku riset dan pembuat kebijakan itu tidak diiringi riset berkualitas tinggi dan kuat secara akademis melalui penilaian sejawat dan kolaborasi akademik.
Salah satu akibatnya, penggunaan ilmu pengetahuan belum memadai, terutama untuk memahami karakteristik dan manfaat keanekaragaman hayati. Kenyataan seperti itu membuat pembangunan ekonomi menjadi tampak lebih dominan dengan mereduksi keanekaragaman hayati sekadar komoditas untuk mendapat manfaat jangka pendek dan dalam waktu bersamaan mengabaikan fungsinya yang sejati. Kerusakan lingkungan sekadar dianggap biaya yang harus dibayar untuk ”manfaat” pembangunan ekonomi yang diperoleh masyarakat.
Baca juga: Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Tanpa Merusak Lingkungan
Oleh karena itu, ke depan, pengarusutamaan pengembangan ilmu pengetahuan atau sains melalui riset ilmiah harus menjadi langkah strategis untuk pengembangan sumber daya hayati bagi pembangunan ekonomi. Sebagai negara dengan kekayaan biodiversitas terbesar di dunia, Indonesia sesungguhnya mempunyai modal kuat untuk menggapai kemakmuran, sekaligus memiliki kapital
Syaratnya, kita harus berani memutus rantai pembangunan yang tak ramah lingkungan dan berpaling dari sumber daya alam tak dapat diperbarui yang kini kian terkikis habis, serta mengutamakan riset dan sains ilmiah untuk menemukenali dan berinovasi atas kekayaan biodiversitas yang ada. Jika tidak, kita akan terus-menerus menemukan ”angsa hitam” yang mengejutkan berupa ragam bentuk krisis ekologi, yang sebenarnya hadir akibat hilangnya kepekaan kita atas sifat dasar ibu kita, Bumi.
Muhamad Burhanudin, Spesialis Lingkungan dari Yayasan KEHATI

Muhamad Burhanudin