Mengurai Problem Kekurangan Dokter di Indonesia
Masalah kurangnya dokter dan tenaga kesehatan tidak hanya terkait aspek produksi dokter, tetapi juga dari sisi distribusinya. Selain mahalnya biaya pendidikan dokter, juga belum baiknya sistem penempatan tenaga dokter.
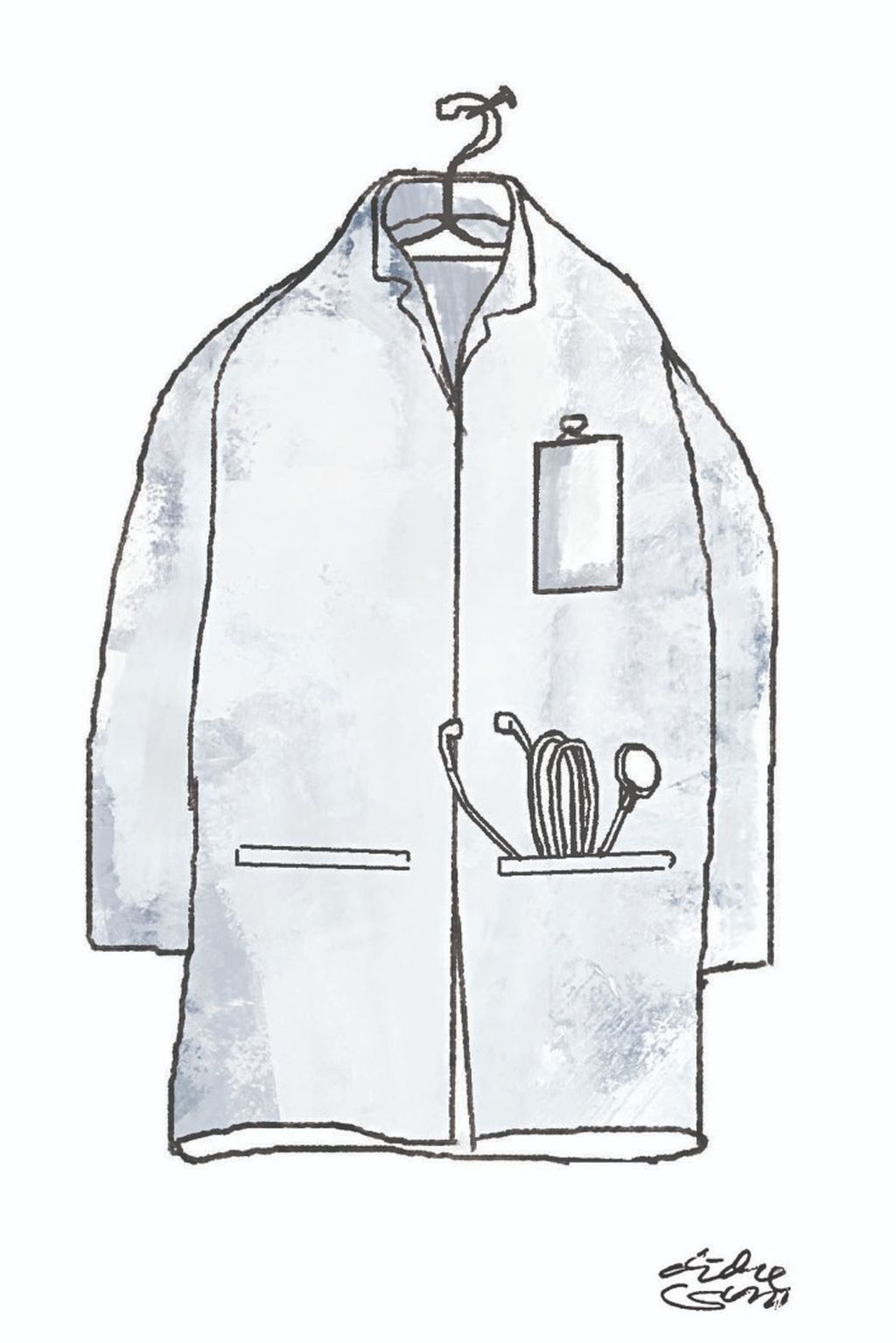
-
Isu klasik tentang kekurangan dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis, kembali mengemuka. Menurut Menteri Kesehatan, Indonesia kekurangan sekitar 160.000 dokter untuk memenuhi kriteria WHO, yakni setiap 1.000 penduduk tersedia satu orang dokter.
Dramatis dan mengejutkan. Betapa tidak, setelah 76 tahun merdeka, negeri ini masih kekurangan begitu banyak dokter. Dengan jumlah penduduk sekitar 270 juta jiwa, diperlukan 270.000 dokter. Indonesia saat ini disebutkan memiliki 110.000 dokter.
Dengan jumlah tersebut, rasio dokter per 1.000 penduduk di Indonesia saat ini hanya 0,6. Jauh di bawah Malaysia, yaitu 2,2 dokter, dan Thailand 0,95 dokter, per 1.000 penduduk. Sementara itu, dokter yang dihasilkan 92 fakultas kedokteran (FK)—baik perguruan tinggi negeri maupun swasta—yang ada di Indonesia saat ini berkisar 12.000-13.000 dokter per tahun.
Masih terdapat ratusan puskesmas yang tak mempunyai dokter. Dengan demikian, jika tak ada perubahan atau terobosan dalam sistem pendidikan, perlu lebih dari 14 tahun untuk memenuhi rasio yang dianjurkan WHO.
Data terakhir Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) menunjukkan, dokter Indonesia yang tercatat dan mempunyai surat tanda registrasi (STR) sampai pertengahan Juli 2022 sebanyak 185.547 orang, terdiri dari 142.558 dokter umum dan 43.989 dokter spesialis dari 36 jenis spesialisasi.
Di samping itu terdapat 39.738 dokter gigi. Ini berarti sebenarnya Indonesia masih kekurangan sekitar 85.000 dokter untuk melayani penduduk yang tersebar di seluruh negeri.
Betapa tidak, setelah 76 tahun merdeka, negeri ini masih kekurangan begitu banyak dokter.
Penambahan kuota penerimaan mahasiswa
Untuk mengatasi masalah ini, baru-baru ini diterbitkan surat keputusan bersama (SKB) dua menteri, Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 02/KB/22 tentang Peningkatan Kuota Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana Kedokteran, Program Dokter Spesialis, dan Penambahan Program Studi Dokter Spesialis.
Pokok isinya, kedua kementerian bersepakat meningkatkan kuota penerimaan calon dokter dan calon dokter spesialis dan penambahan program studi spesialis di beberapa FK melalui sistem kesehatan akademik (academic health system/AHS). Tentu dengan harapan agar produksi dokter dan berbagai dokter spesialis setiap tahun bertambah lebih cepat dibandingkan dengan yang ada selama ini.
Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Masalah kurangnya dokter dan tenaga kesehatan lainnya perlu ditinjau dan ditelaah secara cermat dari berbagai aspek. Tidak hanya dari aspek produksi dokter, tetapi juga dari sisi distribusinya.
Masalah utama yang melatarbelakangi tidak meratanya penyebaran dokter (maladistribusi) selama ini terkait dengan pembiayaan pendidikan kedokteran yang mahal dan harus menjadi beban sendiri bagi mahasiswa, atau kurangnya kesempatan untuk menjadi mahasiswa kedokteran.
Selain itu, perencanaan kebutuhan tenaga dokter di rumah sakit dan berbagai fasilitas kesehatan di daerah belum terkoordinasi secara optimal, terutama di daerah terpencil dan kepulauan.

Demikian pula sistem penempatan tenaga dokter dan spesialis dikaitkan dengan ketersediaan fasilitas kesehatan masih belum baik. Dokter spesialis yang sudah lulus tak jarang harus mencari tempat kerja ke sana-kemari, bahkan berpindah dari satu kota ke kota lain, mencari lowongan kerja di rumah sakit.
Meski nantinya jumlah dokter sudah cukup—sesuai rasio WHO—tak akan ada artinya jika distribusinya tidak merata di seluruh Tanah Air karena tetap saja banyak masyarakat kita yang tidak dapat menikmati pelayanan dokter.
Masalah utama maladistribusi
Masalah utama sekarang ini adalah ”maladistribusi” dokter, selain produksinya sendiri juga masih kurang. Sebagian besar, yakni lebih dari 70 persen, dokter spesialis dan subspesialis saat ini berada di Pulau Jawa dan kota-kota besar lain.
Masih ada ratusan puskesmas yang tak punya dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Kekurangan dokter spesialis masih dirasakan di banyak rumah sakit umum daerah (RSUD).
Maladistribusi dokter yang terjadi di negeri ini sebenarnya masalah lama yang telah berlangsung puluhan tahun. Masalah kronis, yang tak pernah terselesaikan.
Pendidikan kedokteran telah diketahui sebagai pendidikan berbiaya tinggi dalam waktu yang lama. Diperlukan waktu tidak kurang enam tahun untuk menjadi dokter, ditambah lagi satu tahun untuk mengikuti program wajib internship (untuk pemahiran).
Baca juga Waktu dan Biaya untuk Menghasilkan Seorang Dokter di Indonesia
Baca juga Dokter Spesialis di Indonesia Belum Merata, Kemenkes Buka Beasiswa
Masalahnya adalah biaya yang tinggi tersebut harus dikeluarkan sendiri (biaya mandiri) oleh mahasiswa, yang berarti bahwa kesempatan untuk mengenyam pendidikan dokter hanya dapat dinikmati oleh calon mahasiswa yang berasal dari keluarga mampu. Ini berarti telah terjadi seleksi awal secara ”finansial” sebelum ada seleksi kemampuan akademik. Calon yang mempunyai bakat dan cerdas, tetapi kurang didukung kemampuan ekonomi keluarga yang cukup, sangat kecil kemungkinan akan bisa masuk ke fakultas kedokteran jika tidak ada beasiswa.
Demikian pula untuk pendidikan spesialis yang ditempuh minimal delapan semester (empat tahun), peserta didik harus mengeluarkan biaya masuk dan biaya pendidikan (SPP) ratusan juta rupiah sampai selesai. Ini artinya, sebelum masuk juga terjadi seleksi ”finansial” untuk menjadi seorang dokter spesialis.
Masih beruntung bagi dokter yang mendapat biaya pendidikan dari instansi awal tempat mereka bekerja, seperti dokter TNI/Polri, dan setelah selesai pendidikan mereka pasti akan kembali ke instansi masing-masing.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2021%2F11%2F24%2F29f27c94-eb16-42e2-916e-021b20221a7b_jpeg.jpg)
Muhammad Asroruddin (baju batik), dokter spesialis mata di Rumah Sakit Universitas Tanjungpura (Untan), Pontianak, Kalimantan Barat, membimbing koasistensi (koas) sarjana kedokteran FK Untan, Senin (2/5/2015), di Pontianak. Koasistensi merupakan program pendidikan profesi yang harus ditempuh calon dokter setelah menyelesaikan program akademik.
Anomali pendidikan kedokteran
Cukup menggembirakan, belum lama ini ada program bantuan biaya pendidikan dokter spesialis tertentu dari Kementerian Kesehatan bagi dokter yang memenuhi persyaratan. Selain itu, ada bantuan dana pendidikan dari Kemendikbudristek melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Sayangnya, program ini baru dapat dinikmati oleh dokter dalam jumlah terbatas. Peningkatan jumlah dokter yang berkesempatan untuk mengikuti program beasiswa ini perlu segera diupayakan.
Berbeda sekali dengan sistem pendidikan dokter spesialis di banyak negara di dunia, seperti Malaysia, Thailand, Australia, dan AS. Di sana, dokter yang mengikuti pendidikan spesialis (residency training) tidak pernah membayar sepeser pun alias gratis.
Sebaliknya, semua peserta pendidikan dokter spesialis mendapat gaji (salary) yang cukup dan memadai setiap bulan dari rumah sakit tempat pendidikan mereka. Ini sangat beralasan karena selain belajar, residen atau peserta program spesialis juga bekerja melayani pasien di rumah sakit sesuai dengan bidang spesialisasinya.
Melihat perbedaan yang kontras ini, tak salah jika ada yang mengatakan bahwa kondisi ini salah satu ”anomali” dari pendidikan kedokteran di Indonesia.
Melihat perbedaan yang kontras ini, tak salah jika ada yang mengatakan bahwa kondisi ini salah satu ”anomali” dari pendidikan kedokteran di Indonesia.
Perencanaan kebutuhan dokter untuk seluruh negeri sampai saat ini tampaknya belum terlaksana dan terkoordinasi secara optimal meski Kemenkes pasti sudah membuat perencanaan yang baik tentang kebutuhan SDM kesehatan, termasuk dokter dan dokter spesialis. Lahirnya program bantuan biaya pendidikan dokter spesialis adalah salah satu upaya akselerasi penambahan dokter spesialis, untuk memenuhi kebutuhan secara nasional lebih cepat.
Sampai saat ini, pada umumnya produksi dokter hanya terfokus untuk memenuhi pelayanan kesehatan, baik untuk pelayanan di tingkat primer (dokter umum/dokter keluarga) maupun di tingkat lanjutan (spesialis). Padahal, dokter—khususnya dokter spesialis/subspesialis—sangat diperlukan untuk menjadi tenaga pengajar (dosen) dan peneliti. Penambahan jumlah dan kualifikasi dosen yang memadai sangat diperlukan.
Apalagi akan diadakan penambahan kuota penerimaan mahasiswa/peserta didik, sesuai SKB dua menteri. Penambahan dosen mutlak dilakukan untuk menjamin kualitas lulusan, baik dokter umum maupun spesialis. Jika jumlah peserta didik ditambah, tapi jumlah tenaga pengajar tak ditambah, sangat mungkin terjadi penurunan kualitas lulusan.
Perihal penambahan dosen sebagai pendidik di rumah sakit pendidikan memang telah termaktub dengan jelas dalam SKB dua menteri. Hanya saja, biasanya harus melalui suatu proses birokrasi yang panjang, yang seharusnya sudah tidak boleh lagi terjadi saat ini.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2020%2F05%2F26%2F20200526kord-dokter-di-rsud-tc-hillers_1590493088_jpg.jpg)
Dokter di RSUD TC Hillers Maumere sedang merawat pasien demam berdarah beberapa waktu lalu.
Sistem penempatan dokter serta tersedianya sarana dan fasilitas kesehatan juga faktor penting yang perlu dapat perhatian dari pengambil keputusan dan kebijakan. Tidak mudah bagi pemerintah untuk meminta dokter atau dokter spesialis yang baru lulus untuk dengan sukarela ditempatkan ke suatu daerah, apalagi daerah terpencil atau kepulauan. Alasannya, karena selama sekian tahun mengikuti pendidikan, mereka mengeluarkan biaya sendiri yang tidak sedikit.
Banyak pertimbangan bagi dokter yang baru lulus untuk menentukan ke mana mereka harus bekerja dan mengembangkan karier di kemudian hari. Tidak heran jika dokter mencari tempat bekerja di kota-kota besar atau minimal di daerah yang prospeknya baik, walaupun pasti di hati setiap dokter yang telah mengucapkan sumpah Hypocrates tetap ingin membaktikan hidupnya untuk kepentingan kemanusiaan.
Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan reward dan privilese dengan kemudahan tertentu, seperti prioritas untuk melanjutkan pendidikan spesialisasi bagi dokter-dokter yang telah bekerja dan mengabdi di daerah terpencil dan sulit dalam kurun waktu tertentu. Program bantuan pendidikan spesialisasi yang telah dimulai oleh Kemenkes harus diapresiasi dan diharapkan bisa terus dikembangkan dan ditingkatkan.
Tanpa penambahan tenaga dosen, akan sangat mungkin terjadi penurunan kualitas lulusan.
Apa selanjutnya?
Untuk mengatasi masalah kurangnya produksi yang dibarengi dengan ”maladistribusi” dokter, diperlukan suatu langkah strategis, bahkan terobosan.
Adanya program afirmasi untuk mahasiswa sarjana kedokteran dan bantuan biaya pendidikan untuk beberapa spesialisasi tertentu perlu disambut baik dan ditingkatkan. Namun, pengontrolan dan pengendalian terhadap biaya pendidikan kedokteran juga mendesak dilakukan pemerintah agar ada kesempatan yang sama bagi putra-putri bangsa ini untuk menjadi dokter atau dokter spesialis.
Berita bahwa untuk masuk FK swasta diperlukan uang muka Rp 300-Rp 400 juta sering kita dengar. Belum lagi uang kuliah setiap semester juga tak murah.
Pengangkatan tenaga pengajar/dosen kedokteran juga perlu dipercepat dan dipermudah untuk mengimbangi penambahan kuota mahasiswa, baik untuk sarjana kedokteran maupun spesialis. Tanpa penambahan tenaga dosen, akan sangat mungkin terjadi penurunan kualitas lulusan.

Penambahan kuota penerimaan mahasiswa kedokteran dan spesialis tak akan terlalu berarti jika tidak dibarengi sistem penempatan yang jelas untuk mengatasi masalah maladistribusi. Ketika masuk pendidikan dokter spesialis, hendaknya sudah diketahui setelah selesai pendidikan sekian tahun, ke mana akan bekerja atau ditempatkan.
Di dalam salah satu butir ketetapan dari SKB dua menteri (butir 9.b) tertera bahwa dalam melaksanakan keputusan bersama diperlukan koordinasi dengan pemda untuk mempercepat pendayagunaan dan distribusi lulusan program dokter spesialis melalui calon pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) serta program pendayagunaan dokter spesialis dan penugasan khusus.
Dalam kaitan ini, dalam pendayagunaan dokter spesialis mutlak diperlukan koordinasi dan pemahaman yang sama dengan unsur pemda. Oleh karena itu, menurut penulis, sangat beralasan dan tak berlebihan apabila SKB dua menteri diperluas dan dikembangkan menjadi SKB tiga menteri, dengan melibatkan Menteri Dalam Negeri.
Kita semua berharap, dalam waktu tak terlalu lama masalah ”malaproduksi” dan ”maladistribusi” dokter di negeri ini akan segera teratasi. Semoga.
Sukman Tulus Putra, Ketua Perhimpunan Kardiologi Anak Indonesia, Konsilor KKI 2014-2020, Anggota Dewan Pertimbangan PB IDI, Anggota MKEK Ikatan Dokter Indonesia

Sukman Tulus Putra