Dilema Tionghoa Menjadi Warga Negara Indonesia
Komunitas Tionghoa sering dipersepsikan sebagai bukan warga asli Indonesia. Perbedaan identitas berujung pada kebijakan diskriminatif yang membuat minoritas Tionghoa harus berjuang untuk mendapatkan status WNI.
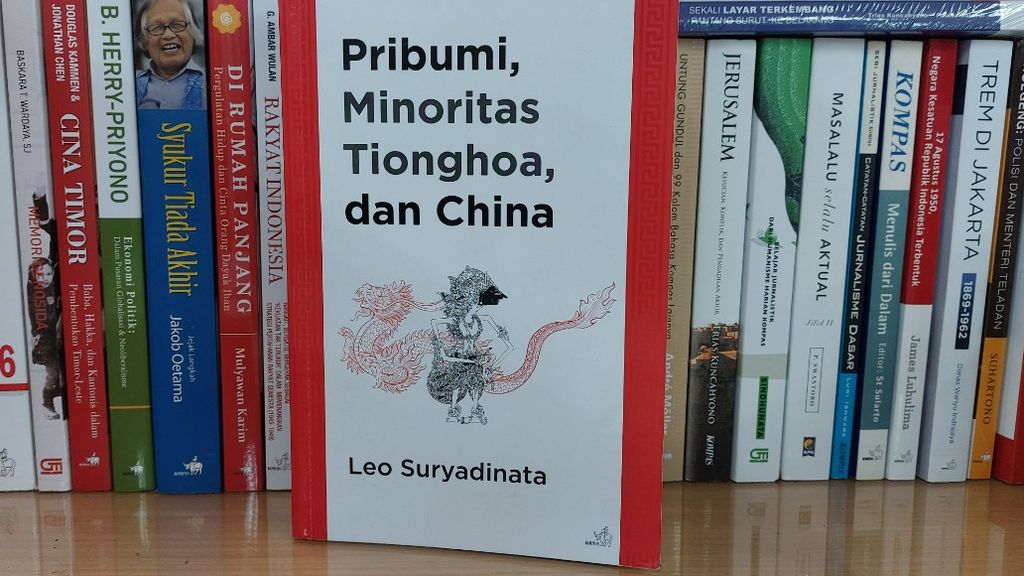
Kehidupan warga keturunan Tionghoa di Indonesia mengalami dilema sejak zaman kolonialisme Belanda hingga Indonesia modern saat ini. Munculnya pribumi dan nonpribumi yang disertai dengan masalah ekonomi, kewarganegaraan, dan budaya berdampak pada terjadinya diskriminasi. Warga Tionghoa pun kesulitan untuk diakui sebagai warga negara Indonesia.
Inilah yang menjadi permasalahan pokok dalam buku Pribumi, Minoritas Tionghoa, dan China (PBK, 2023) yang ditulis oleh Leo Suryadinata. Buku ini adalah penerbitan ulang dari judul Dilema Minoritas Tionghoa yang terbit pada tahun 1984 oleh penerbit Grafiti Pres.
Penerbitan ulang buku ini tidak hanya mengganti judul bukunya yang menyesuaikan dengan judul disertasi Leo Suryadinata, tetapi juga ada beberapa tambahan yang belum dimuat pada terbitan lama. Pada buku cetakan tahun 1984, penelitian Leo Suryadinata terbatas pada kurun waktu antara masa kolonialisme hingga Indonesia di tahun 1975. Namun, pada terbitan tahun 2023, Leo Suryadinata menambahkan postscript permasalahan Tionghoa tahun 1976-2021.
Penambahan ulang ini bagi Leo Suyadinata cukup penting karena posisi orang Tionghoa di Indonesia terus berkembang. Hal ini disebabkan dinamika persepsi masyarakat bumiputra terhadap komunitas Tionghoa. Aneka macam persepsi yang tercipta di dalam masyarakat membuat warga Tionghoa harus berjuang untuk mendapatkan status sebagai WNI sejak Indonesia berdiri di tahun 1945.
Keadaan inilah yang membuat warga Tionghoa harus menghadapi situasi dilematis, seperti perkataan dari Charles A Coppel yang mengibaratkan etnis Tionghoa bagaikan buah simalakama. Jika mereka terlibat dalam politik oposisi, maka mereka dicap subversif. Apabila mereka mendukung penguasa setempat kala itu, maka mereka akan dianggap oportunis. Namun, apabila mereka menjauh dari politik, mereka juga akan dianggap oportunis, terlebih mereka dikenal sebagai kelompok yang mencari keuntungan semata.
Penambahan ulang ini bagi Leo Suyadinata cukup penting karena posisi orang Tionghoa di Indonesia terus berkembang.
Orde Lama
Sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang berlandaskan pada asas ius soli dan ”sistem pasif”. Mayoritas komunitas Tionghoa lahir di Indonesia, secara otomatis mereka menjadi warga negara Indonesia. Hal serupa berlaku bagi mereka yang secara pasif tidak melakukan penolakan. Namun, orang Tionghoa yang menolak menjadi WNI atau ingin menjadi warga negara asing tetap diperbolehkan.
Undang-undang ini muncul karena Indonesia memiliki kepentingan akan dukungan orang Tionghoa untuk segera menyelesaikan urusan pemindahan kekuasaan dengan Belanda. Di samping itu, Pemerintah Indonesia membutuhkan komunitas Tionghoa yang mempunyai kekuasaan ekonomi untuk membangun Republik.
Setelah Indonesia mendapatkan kedaulatan lewat Konferensi Meja Bundar tahun 1949, Undang-Undang Kewarganegaraan kembali diubah menjadi lebih liberal dan menerapkan asas ius soli dua generasi bagi warga Tionghoa. ”Sistem pasif” pun diubah menjadi ”sistem aktif”, yaitu sistem yang mensyaratkan adanya pernyataan penerimaan kewarganegaraan Indonesia.
Rencana perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan ini memuat beberapa syarat bagi warga Tionghoa apabila ingin diakui sebagai WNI yaitu, pertama, memberikan bukti bahwa orangtua mereka dilahirkan dan tinggal di Indonesia sedikitnya selama 10 tahun. Kedua, menyatakan secara resmi menolak kewarganegaraan China.
Para nasionalis yang berpandangan sekuler menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertujuan untuk membentuk bangsa Indonesia yang homogen. Komunitas Tionghoa diminta untuk bergabung menyatukan diri dengan Republik. Namun, di sisi lain rencana ini ditentang oleh wakil-wakil kaum minoritas di parlemen.
Pemerintahan negara China saat itu masih berpegang teguh pada ketentuan bahwa warganya yang tinggal dan menetap di luar negeri dianggap sebagai warga China. Hal ini membuat warga Tionghoa di Indonesia masih menganut sistem dua kewarganegaraan, yakni sebagai warga negara Indonesia sekaligus warga negara China. Keadaan inilah yang ditakuti oleh sebagian masyarakat Indonesia karena menganggap China dapat mengintervensi melalui WNI keturunan Tionghoa.
Keadaan inilah yang ditakuti oleh sebagian masyarakat Indonesia karena menganggap China dapat mengintervensi melalui WNI keturunan Tionghoa.
Akhirnya, Jakarta dan Peking (sekarang Beijing) melakukan negosiasi pada 22 April 1955 bersamaan dengan berakhirnya Konferensi Asia-Afrika. Kedua negara kemudian bersepakat dalam Perjanjian Dwi Kewarganegaraan. Perjanjian tersebut mengatur tentang komunitas Tionghoa lokal yang oleh hukum Indonesia dianggap berkewarganegaraan Indonesia, tetapi juga berkewarganegaraan China menurut hukum China.
Ketentuan perjanjian tersebut mengatakan bahwa orang yang berkewarganegaraan ganda akan diberikan waktu dua tahun untuk memilih salah satu kewarganegaraan. Orang yang berkewarganegaraan ganda, tetapi mengabaikan ketentuan untuk memilih salah satu kewarganegaraan dalam waktu peralihan dua tahun itu, hanya akan memperoleh kewarganegaraan China.
Di sisi lain, pada tahun 1958, Pemerintah Indonesia meresmikan Undang-Undang Kewarganegaraan. Meskipun sudah ada Perjanjian Dwi Kewarganegaraan antara Indonesia dan China, orang yang berkewarganegaraan ganda perlu melampirkan pernyataan melepaskan kewarganegaraan China dahulu sebelum disahkan menjadi WNI.
Undang-undang ini juga mengatur, orang Tionghoa yang umurnya sudah 18 tahun dan orangtuanya lahir di Indonesia boleh mengajukan diri untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Namun, orang Tionghoa yang berumur 18 tahun dan orangtuanya tidak lahir di Indonesia harus mengajukan permohonan naturalisasi.
Melalui Perjanjian Dwi Kewarganegaraan, permasalahan status kewarganegaraan Indonesia bagi orang Tionghoa dapat diselesaikan. Mereka berhak untuk memilih antara menjadi warga negara Indonesia atau warga negara China sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini juga membuat hubungan Indonesia dengan China menjadi semakin erat. Apalagi, Soekarno dan Mao Tze Tung dikenal dekat.
Pemerintahan Soeharto ingin menghentikan praktik ini karena curiga akan orientasi politik orang Tionghoa. Apalagi, pemerintahan Soeharto menuduh China ikut membantu kudeta 1965.
Orde Baru
Kudeta 1965 membuat Perjanjian Dwi Kewarganegaraan tidak diberlakukan lagi. Pemerintah juga menyebutkan bahwa perjanjian ini sudah tidak berlaku karena sebagian besar orang yang berkewarganegaraan ganda telah memilih menjadi WNI pada akhir 1961. Namun, perjanjian itu tetap berlaku bagi anak-anak yang lahir sebelum 20 Januari 1962 untuk menentukan pilihan apakah ingin menjadi warga negara China atau Indonesia.
Leo Suryadinata menyatakan bahwa keadaan ini juga bermuatan politis. Perjanjian tersebut memberikan kesempatan kepada anak-anak yang orangtuanya memilih kewarganegaraan China untuk menjadi WNI tanpa penyaringan oleh pejabat Indonesia. Pemerintahan Soeharto ingin menghentikan praktik ini karena curiga akan orientasi politik orang Tionghoa. Apalagi, pemerintahan Soeharto menuduh China ikut membantu kudeta 1965.
Tidak berlakunya lagi perjanjian ini membuat anak Tionghoa di bawah umur 18 tahun tidak lagi mendapatkan kesempatan menjadi warga negara secara mudah. Pemerintah meminta mereka yang belum mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia menjalani proses naturalisasi. Prosedurnya cukup rumit, mereka memerlukan sedikitnya 14 dokumen untuk mengajukan permohonan dan membayar biaya berkisar antara Rp 100.000 dan Rp 300.000.
Penerapan kebijakan ini ternyata membuat komunitas Tionghoa kesulitan untuk mendapatkan status WNI. Apalagi, pemerintah meminta Kejaksaan Agung untuk menyaring latar dari tiap pemohon. Akibatnya, tidak banyak warga keturunan Tionghoa yang mengajukan diri sebagai WNI. Pada tahun 1975 tercatat sebanyak 914.111 orang warga negara China, 122.013 orang tanpa kewarganegaraan, dan 1.907 orang merupakan warga negara Taiwan.
Membeludaknya jumlah komunitas Tionghoa yang belum berkewarganegaraan Indonesia membuat pemerintahan Soeharto bimbang, apalagi saat itu pemerintah berencana untuk membuka kembali hubungan dengan China. Pemulihan hubungan ini didasarkan pada situasi internasional yang mana Indonesia tidak bisa bergerak dengan leluasa apabila tidak memiliki hubungan dengan China. Pengusaha Indonesia pun menuntut pemerintah untuk membuka hubungan dagang dengan China.
Presiden Soeharto pun mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2/1980 dan Keputusan Presiden Nomor 13/1980 agar komunitas Tionghoa yang belum mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia dapat diakui sebagai WNI dengan mendapatkan surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). Pemerintah memberikan wewenang kepada camat untuk mengeluarkan SBKRI agar prosesnya semakin cepat. Presiden Soeharto meminta dari 28 Februari 1980 sampai sebelum 17 Agustus 1980 urusan SBKRI harus selesai.
Banyak komunitas Tionghoa kemudian memanfaatkan momentum ini untuk mengajukan permohonan menjadi WNI. China juga mengeluarkan undang-undang kewarganegaraan yang baru pada 15 September 1980 yang isinya tidak mengakui lagi dwi kewarganegaraan. Sehubungan dengan itu juga hubungan antara Jakarta dan Beijing pulih kembali.
Meskipun mereka telah diakui sebagai WNI, mereka menjadi sasaran kekerasan. Banyak dari mereka yang menderita trauma dan memilih untuk meninggalkan Indonesia.
Reformasi
Tumbangnya Orde Baru pada Mei 1998 harus diawali oleh luka batin pada komunitas Tionghoa. Meskipun mereka telah diakui sebagai WNI, mereka menjadi sasaran kekerasan. Banyak dari mereka yang menderita trauma dan memilih untuk meninggalkan Indonesia.
Namun, naiknya BJ Habibie sebagai presiden membuat terobosan baru dalam hubungannya dengan komunitas Tionghoa lokal. Presiden Habibie mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 26/1998 yang menghentikan penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi. Momentum ini menjadi penanda bahwa komunitas Tionghoa diakui sebagai warga negara Indonesia secara penuh.
Tidak hanya itu, sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, komunitas Tionghoa diperbolehkan untuk merayakan Tahun Baru Imlek. Bahkan, di masa Presiden Megawati, perayaan Tahun Baru Imlek dinyatakan sebagai hari libur nasional. Di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, istilah China dan Cina kemudian diganti menjadi Tiongkok dan Tionghoa.
Baru pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo inilah keberadaan komunitas Tionghoa semakin kentara seiring dengan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Apalagi, saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama yang merupakan keturunan Tionghoa. Ini menunjukkan bahwa keberadaan Tionghoa semakin terbuka untuk turut memajukan Indonesia. (LITBANG KOMPAS)
Info Buku
Judul: Pribumi, Minoritas Tionghoa, dan China
Penulis: Leo Suryadinata
Penerbit: Penerbit Buku Kompas
Tahun terbit: 2023
Jumlah halaman: xxxiv + 386 halaman
ISBN: 978-623-346-965-4