Demokrasi dan Orang-orang Biasa
Demokrasi adalah kisahnya orang biasa. Demokrasi berlangsung efektif jika orang-orang biasa memiliki daya tawar kuat.
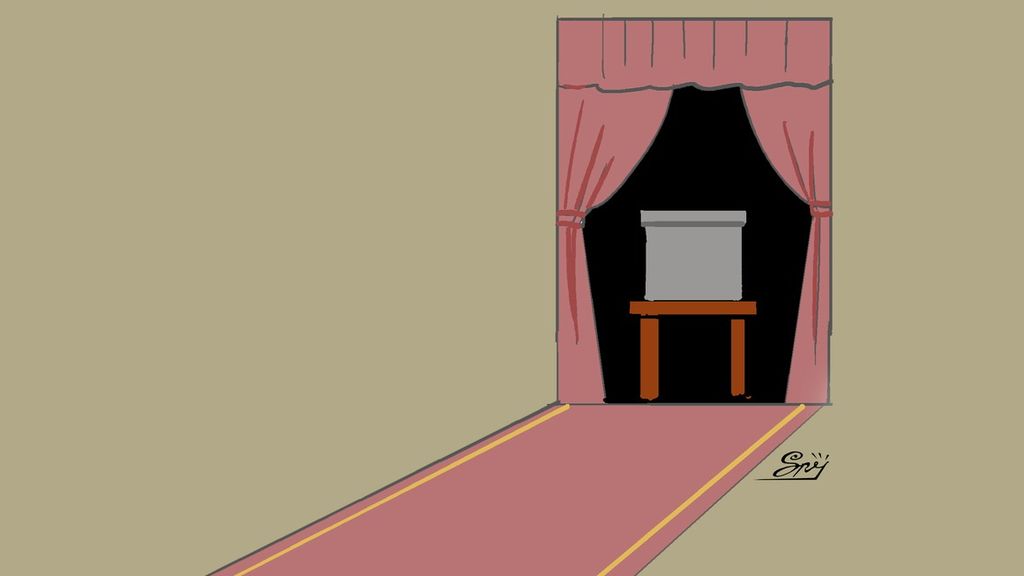
Ilustrasi
Kontestasi pemilu sedang memasuki tahap kampanye. Masa kampanye merupakan momen bagi para peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih melalui visi-misi, program, serta citranya. Dengan demikian, sudah sewajarnya apabila publik menjadi riuh membahas siapa sosok yang pantas menempati berbagai posisi strategis dalam kehidupan bernegara, baik pada rumpun eksekutif maupun lembaga perwakilan rakyat.
Di satu sisi, gegap gempita itu layak disyukuri sebagai wujud kesadaran dan kepedulian politik warga negara. Di sisi lain, perlu dicatat juga bahwa sebagian individu memiliki memori jangka pendek.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Bagi mereka, seperti yang sudah lampau, pemilu sebatas acara seremonial lima tahunan. Datang ke tempat pemungutan suara, mencoblos, lalu pulang. Tanpa insyaf bahwa aktivitas yang baru saja mereka lakukan akan menjadi penentu kualitas sistem pendidikan bagi anak-anak mereka, fasilitas pelayanan kesehatan macam apa yang akan mereka dapatkan, atau sejauh mana mereka bebas mengemukakan pendapat dan ekspresi kelak.
Bahkan, jumlah angka golput masih menyentuh 34,75 juta jiwa atau sekitar 18,02 persen dari daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu sebelumnya. Salah satu penyebabnya bisa jadi adalah karena keengganan mereka untuk terperangkap dalam siklus pengabaian.
Baca juga: Pemilu 2024 dan Roh Demokrasi
Dewasa ini, berbagai isu global makin lazim bermunculan. Eskalasi konflik antara Israel dan Palestina memicu respons beragam dari sejumlah negara, sedangkan perang antara Rusia dan Ukraina juga masih berkecamuk. Kombinasi perkembangan ilmu pengetahuan dan kecenderungan umat manusia untuk terus berpikir mengakibatkan perkembangan teknologi yang disruptif.
Akibatnya, frasa ”puncak peradaban” kian sulit ditebak karena dalam rentang waktu yang singkat umat manusia terus melakukan penelitian serta menghasilkan banyak temuan baru. Terlebih lagi, ada juga masalah krisis iklim yang perlu segera ditangani supaya tidak terus-menerus menghantui masa depan kita.
Karena itu, masuk akal apabila peserta pemilu kemudian menjadikan isu-isu krusial tersebut sebagai prioritas yang tertuang dalam rancangan program atau kebijakannya. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana cara para peserta pemilu memandang ”orang-orang biasa” (ordinary people) di dalamnya apabila terpilih nanti dan di mana letak orang-orang biasa itu dalam proses pengambilan kebijakan?

Penyempitan makna demokrasi
Pada awal kemunculannya, demokrasi dianggap sebagai suatu bentuk kemerosotan dari politeia. Politeia adalah suatu pemerintahan yang dijalankan oleh semua orang demi kepentingan rakyat. Akan tetapi, pemerintahan itu bisa saja berubah menjadi demokrasi saat dijalankan oleh orang-orang yang tidak kapabel. Seiring perkembangannya, demokrasi akhirnya dianggap menjadi suatu konsep ideal yang dipertentangkan dengan mobokrasi.
Kini, mayoritas negara yang menganut konsep demokrasi menggunakan pemilu sebagai mekanisme pengisian jabatan publik tertentu. Tujuannya agar salah satu syarat demokrasi berupa eksisnya partisipasi masyarakat dalam proses perebutan kekuasaan bisa terpenuhi. Dengan demikian, para penguasa tersebut mendapatkan legitimasi yang kukuh sehingga mempermudah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) jabatannya.
Namun, demokrasi bukanlah sekadar soal ada atau tidaknya hak pilih warga negara. Salah besar jika pemikiran tentang demokrasi terjerembab dalam suatu lembah bernama ”pemilu”. Mencari sejumlah individu pilihan, lalu membiarkan tindak-tanduk mereka ketika berkuasa. Lebih dari itu, demokrasi adalah soal adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan publik ketika para pemenang pemilu sudah menduduki jabatan-jabatan.
Namun, demokrasi bukanlah sekadar soal ada atau tidaknya hak pilih warga negara. Salah besar jika pemikiran tentang demokrasi terjerembab dalam suatu lembah bernama ”pemilu”.
Keterlibatan masyarakat pun tidak boleh formalitas belaka, tetapi mesti menjangkau aspek substansial pula supaya lebih bermakna. Hal tersebut disebabkan kebijakan publik dibuat oleh segelintir orang, tetapi hasilnya berdampak dan mengikat bagi setiap warga negara.
Setidaknya, para pemangku jabatan harus mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan masyarakat sekaligus menjelaskan keputusan yang mereka pilih secara transparan dan akuntabel kepada publik. Tanpa penjaringan aspirasi yang bermakna, jangan harap suatu produk kebijakan publik bisa sepenuhnya lepas dari segala rupa protes dan penolakan di belakang hari.

Orang-orang biasa dalam demokrasi
Kampanye Pemilu 2024 diwarnai dengan sejumlah pembahasan soal beberapa tantangan global yang sudah disebut pada bagian awal tulisan ini. Namun, isu-isu tersebut mungkin saja terasa begitu jauh untuk dimengerti oleh orang-orang biasa. Ya, dunia sedang mengalami perubahan disruptif diiringi dengan gumpalan masalah yang menyertainya. Ya, beragam artefak kekinian seperti senjata nuklir, kecerdasan buatan, atau kendaraan listrik sudah tidak asing di telinga khalayak ramai.
Masalahnya, bagaimana mungkin berharap orang-orang biasa bisa peduli terhadap eksistensi hal-hal tersebut apabila rutinitas sehari-hari mereka sudah cukup menjemukan dan melelahkan? Seorang pekerja komuter yang setiap hari berjibaku dengan kerumunan manusia saat subuh dan malam hari tentu wajar apabila kurang peka terhadap berkurangnya luas hutan.
Padahal, orang-orang biasa inilah yang berpotensi menjadi pihak paling rentan apabila sejumlah kekhawatiran umat manusia mulai bertransformasi menjadi kenyataan. Sementara itu, para elite sekurang-kurangnya masih bisa berlindung di balik modal politik ataupun modal kapital yang mereka punya.
Saat berbicara tentang demokrasi elektoral, peran para elite sangat menonjol dan tidak sebanding dengan suara orang-orang biasa.
Jika menilik fenomena lima tahun terakhir, pengabaian terhadap suara orang-orang biasa lumrah ditemukan. Dalam sektor hukum, misalnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Salah satu faktornya adalah karena pembentuk undang-undang tidak membuka ruang partisipasi bermakna kepada masyarakat.
Alih-alih merevisi muatannya sesuai jangka waktu yang diberikan, pemerintah justru menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang oleh DPR melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Pola pengabaian serupa dapat ditemukan pada sejumlah regulasi lainnya. Dengan dalih hukum prosedural, partisipasi publik dikesampingkan dan dinihilkan.
Saat berbicara tentang demokrasi elektoral, peran para elite sangat menonjol dan tidak sebanding dengan suara orang-orang biasa. Oleh sebab itu, dua profesor ilmu politik bernama Christian Welzel dan Ronald Inglehart berpandangan bahwa pemberdayaan manusia (human empowerment) berkembang menjadi kekuatan penggerak yang vital bagi upaya demokratisasi.
Pemberdayaan manusia yang dimaksud adalah distribusi sumber daya serta nilai-nilai kepada orang-orang biasa untuk menekan para elite. Dengan demikian, demokrasi dapat berlangsung secara efektif karena orang-orang biasa mau tak mau memiliki daya tawar kuat.
Baca juga: Mendewasakan Demokrasi Kita
Pada hakikatnya, kisah demokrasi memang adalah kisahnya orang-orang biasa. Dengan demokrasi, saya, pembaca tulisan ini, atau orang-orang biasa lainnya memiliki sarana untuk menyalurkan nilai dan aspirasi yang pantas diperhitungkan oleh pemangku jabatan. Dengan demokrasi, setiap orang berhak bersuara tanpa perlu merasa takut.
Pemilu seyogianya mampu menjadi jalan pembuka bagi orang-orang biasa untuk mulai dilibatkan dalam menghadapi tantangan berskala nasional ataupun global. Sudut pandang peserta pemilu terhadap orang-orang biasa mesti berubah melampaui urusan elektoral. Bukan sekadar suara, orang-orang biasa harus dibuat relevan dengan program dan kebijakan yang diusung.
Narasi gagasan-gagasan substansial harus lebih sering bergema daripada urusan sensasional kelas teri. Pemilu mungkin hanya berlangsung lima tahun sekali, tetapi masa depan umat manusia dan tujuan bernegara tidak mengenal batas waktu yang pasti.
Muhammad Bagir Shadr, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Instagram: mhd.bagir; Twitter: bagirshadrr

Muhammad Bagir Shadr