Hasrat, Moral, dan Kekuasaan
Terlalu dini menarik kesimpulan atas pilihan Jokowi karena membaca kompleksitas tak mungkin dalam waktu singkat dan dengan cara mudah. Yang utama adalah optimasi keuntungan dari cawe-cawe Jokowi untuk kepentingan bangsa.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F08%2F21%2F6646d497-99e2-4bef-822e-bdb4833774df_jpg.jpg)
Mengapa di banyak daerah, sirkulasi kekuasaan lokal terbatas dalam satu keluarga? Di mana posisi moral dalam politik demokrasi? Mengapa Presiden Joko Widodo mesti ikut cawe-cawe dalam proses politik 2024?
Setiap manusia, dalam dirinya, memiliki kehendak berkuasa yang disebut Friedrich Nietzsche (1844-1900) sebagai der Wille zur Macht (hasrat berkuasa).
Terkait hasrat itu, diskusi soal sirkulasi kekuasaan yang tersendat dalam praksis demokrasi modern selalu relevan—tak hanya pada era sebelum Gelombang Ketiga Demokratisasi yang bermula dari Revolusi Anyelir di Portugal tahun 1974 (Huntington, 1991).
Setelah suami menjabat, istri atau anak menyusul. Fenomena dinasti Banten, keluarga Ratu Atut, adalah contoh paling mudah. Di banyak daerah, gubernur atau bupati/wali kota yang gagal sekalipun berusaha keras mempertahankan status quo, kemapanan.
Baca juga: Melacak Akar Politik Dinasti
”Ini masalah moral politik. Istri saya orang cerdas. Apalagi, pendidikannya lebih tinggi dari saya. Tapi, dengan keras, saya menolak ide untuk mengusungnya sebagai pengganti di Jawa Tengah,” tutur Ganjar Pranowo (GP) dalam sebuah perbincangan warung kopi.
Sebetulnya, aliran kekuasaan dalam satu keluarga bukan masalah jika mereka betul dikehendaki rakyat. Demokrasi menjamin hak setiap warga untuk terlibat dalam kontestasi politik.
Hasrat diri vs hasrat sosial
Cerita GP memunculkan refleksi tersendiri. ”Moral politik” yang dimaksudnya sungguh konsep besar yang cair dan sumir. Hukum positif sering kali kesulitan cara dalam membatasi makna atau mematok ukuran dari ”moral politik” dalam implementasi.
Orang kemudian menerimanya sebagai kesadaran dan posisi batin yang mengandaikan adanya sensitivitas dengung nurani untuk membangun keseimbangan antara ”hasrat diri” dan ”hasrat sosial”.
Hasrat diri selalu tak berbatas dan terkadang melekat dengan ketamakan. Namun, ukuran hasrat sosial adalah kepentingan umum. Jarak antara hasrat diri dan kemaslahatan umum menentukan besaran moral dari hasrat sosial dalam diri manusia politik.

Pilihan atau tindakan moral
Tentu saja kekuasaan adalah perihal mulia—yang dengan dan di dalamnya orang dapat berpikir dan bertindak nobel dalam konteks kepentingan umum.
Thomas Hobbes (1588-1679) tentu saja rada skeptis dengan konsepsi moral. Bagi Hobbes, manusia sejatinya adalah makhluk buas yang hanya dapat diberadabkan oleh aturan yang kuat—untuk itulah negara ada!
Meski ada benarnya, Hobbes mengabaikan kenyataan eksistensial bahwa dalam diri manusia selalu ada pilihan moral. Pilihan moral tersebut termanifestasi dalam tindakan.
Immanuel Kant (1724-1804) dengan jelas memilah antara tindakan moral yang otonom dan tindakan yang heteronom. Manusia selalu ada di persimpangan antara ”berbuat baik karena kebaikan itu baik pada dirinya” dan ”berbuat baik karena ingin mendapatkan pengakuan dari pihak lain atau untuk menghindari sanksi”.
Di jalanan, ada dua tipe pengendara yang memakai helm: yang sadar keselamatan dan yang takut ditilang polisi. Dalam moral Kantian, tipe yang pertama adalah orang yang membuat pilihan moral secara otonom. Sebaliknya, tipe yang lain membuat pilihan moral heteronom yang kehilangan kemandirian karena membangun pilihan tindakan di atas argumen instrumental yang berada di luar ranah tindakan an sich.
Pilihan moral menuntun manusia pada penemuan makna ontologis keberadaannya.
Pilihan moral menuntun manusia pada penemuan makna ontologis keberadaannya. Sebab, menurut Hegel dalam Phaenomenologie des Geistes (1807), dalam diri manusia ada ”pribadi moral” yang disebut conscience, nurani.
Pilihan memangku jabatan publik dalam demokrasi perlu dipahami sebagai pilihan moral supaya rangkaian tindakan politik mengandung kualitas etis.
Ketika GP keberatan istrinya terjun ke ruang perebutan kekuasaan, dengan argumen moral politik, ia ingin menegaskan kekuasaan selalu memikat, tetapi kita makhluk moral harus mampu menertibkan hasrat.
Politik pengakuan
Dalam Republic, Socrates berbincang dengan dua aristokrat Athena, Adeimantus dan saudaranya, Glaucon, tentang kota (negara) yang adil.
Ada bagian di mana mereka membahas thymos—istilah Yunani kuno yang mengacu pada bagian dalam jiwa manusia yang mencari pengakuan atau penghormatan dari pihak lain (Fukuyama, 2018:19-20).
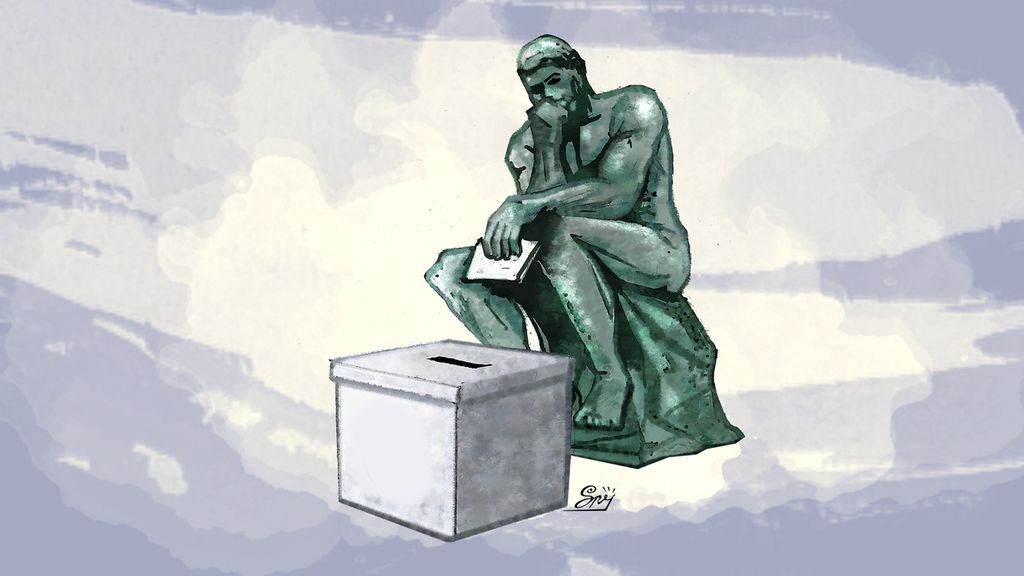
Sejarah manusia, kata Friedrich Hegel (1807), lebih banyak digerakkan oleh pertarungan pengakuan. Bangsa yang satu bertarung dengan bangsa yang lain untuk meraih pengakuan. Bahkan, Francis Fukuyama bilang, politik identitas dalam demokrasi modern bagian dari upaya mencari pengakuan atas martabat sebagai manusia.
Politik pengakuan membantu kita memahami ambisi Donald Trump untuk kembali maju dalam pemilihan presiden di Amerika Serikat tahun 2024 atau Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 di Indonesia.
Menguak spekulasi yang mensinyalir kegamangan sikap politik Presiden Joko Widodo hari ini, antara mendukung Prabowo dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, ada yang membaca itu sebagai upaya untuk mengamankan dirinya setelah berkuasa. Ia ingin menjadi penentu proses politik ke depan dalam konteks ”politik pengakuan”.
Penulis sendiri melihat pandangan ini sebagai bacaan yang lemah. Cawe-cawe versi Jokowi adalah kesatuan yang utuh antara ”politik pengakuan” dan ”pilihan moral” untuk menjaga kepentingan bangsa dan negara. Ia, sebagai manusia, tentu memikirkan masa depan keluarga. Namun, di atas segalanya, Jokowi menginginkan yang terbaik untuk Indonesia.
Sebagai warga negara, saya sulit membayangkan kepemimpinan baru nanti adalah antitesis dari rezim hari ini.
Sebagai warga negara, saya sulit membayangkan kepemimpinan baru nanti adalah antitesis dari rezim hari ini. Hal itu memicu arus balik yang bisa-bisa menyeret kita kembali ke zaman kegelapan. Sejarah harus terus melaju dalam gerak linear yang meyakinkan.
Maka, barangkali ”intervensi” Presiden Jokowi sebagai magnet utama dari proses politik hari ini memang diperlukan. Cawe-cawe adalah pilihan dan tindakan moral yang dibutuhkan oleh bangsa ini—bahkan ketika Jokowi tidak menghendaki itu, kita perlu memaksanya untuk itu karena tanpa campur tangan sosok sentral, proses politik bakal kehilangan orientasi.
Ketika RG berteriak dengan kata-kata kasar yang oleh massa pendukung dipahami sebagai penghinaan terhadap Presiden Jokowi, sebenarnya ia sedang menikmati ”pengakuan” atas dirinya oleh dan di tengah para pendukungnya.
RG menikmati kekuasaan sosial tertentu dan dengannya ia memainkan peran oposisi terhadap pemerintah. Pilihan moral RG tidak salah, tetapi tindakannya berpotensi problematis karena mengekspresikan pilihan dalam narasi yang bertentangan dengan kesadaran sosial banyak orang, termasuk menabrak norma ketimuran.

Apakah, lantas, penentangnya layak menghakiminya? Tidak! Demokrasi mengedepankan penegakan hukum. Biarkan negara yang menilai apakah tindakan itu layak dihukum. Massa tak mempunyai otoritas untuk menghakimi RG di luar jalur hukum negara.
Refleksi
Membaca sikap Presiden Jokowi, dalam sebuah wawancara media, penulis pernah menyampaikan ini. ”Memahami jalan pikiran Jokowi adalah memahami sebuah kompleksitas. Seperti lukisan Pollock yang tampak rumit, tetapi kualitas seninya begitu tinggi, demikianlah jalan pikiran Jokowi.”
Paul Jackson Pollock (1912-1956) memelopori aliran abstrak ekspresionis dalam dunia melukis. Ia menampilkan kompleksitas yang bermakna mendalam. Harga lukisannya bahkan mencapai Rp 2,8 triliun.
Pendukung Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sibuk mengklaim dukungan Jokowi dan hal itu tecermin dalam beragam hasil jajak pendapat.
Tentu terlalu dini menarik kesimpulan atas pilihan Jokowi karena membaca kompleksitas tak mungkin dalam waktu singkat dan dengan cara mudah. Bagi kita, yang utama adalah optimasi keuntungan dari cawe-cawe Jokowi untuk kepentingan bangsa dan negara.
Sebab, dalam hal itulah tindakan politik Jokowi hari ini akan dinilai sebagai tindakan moral yang layak atau tidak layak untuk dikenang dalam sejarah ke depan.
Boni Hargens,Analis Politik