Konstitusi dan Demokrasi
Kesinambungan demokrasi konstitusional membutuhkan pelembagaan oposisi. Pelembagaan oposisi akan membentuk keseimbangan kekuatan politik, menyuburkan deliberasi gagasan, memunculkan pilihan alternatif kebijakan publik.

Ilustrasi
Saat Era Reformasi dimulai pada 1998, banyak pihak percaya UUD 1945 adalah sumber utama otoritarianisme Orde Baru.
Undang-Undang Dasar 1945 dianggap telah memfasilitasi penguasa untuk menjadi otoriter.
UUD 1945 bukan konstitusi demokratis. Oleh karena itu, demokrasi hanya dapat tegak lurus dengan konstitusi demokratis. Demokratisasi Indonesia harus dilembagakan ke dalam konstitusi demokratis. Untuk itu, agenda prioritas saat instalasi demokrasi konstitusional awal Era Reformasi adalah amendemen UUD 1945.
Secara normatif-tekstual, UUD 1945 pasca-amendemen memang memenuhi standar modern konstitusi demokratis. Isinya menekankan prinsip negara hukum, supremasi konstitusi, distribusi kekuasaan, checks and balances, dan jaminan hak konstitusional.
Baca juga : Reformasi, Demokrasi, dan Korupsi
Bukan obat mujarab
Namun, setelah 21 tahun amendemen konstitusi, ternyata konstitusi demokratis tak pasti menjamin keberlanjutan demokrasi konstitusional. Konstitusi demokratis bukan garansi praktik kekuasaan demokratis. Konstitusi demokratis bukan obat mujarab (panacea) untuk memulihkan demokrasi.
Penjelasan UUD 1945 praamendemen menegaskan jika semangat penyelenggara pemerintahan baik, UUD yang tidak sempurna pun tidak akan merintangi jalannya negara.
Dalam argumentum a contrario, prinsip itu kontekstual untuk kondisi sekarang. Jika semangat penyelenggara pemerintahan tidak berkomitmen kuat menjunjung demokrasi konstitusional, UUD yang relatif sempurna (konstitusi demokratis) pun dapat direduksi dan dimanipulasi untuk melanggengkan kekuasaan dan kepentingan penguasa.
Para ahli, misalnya Thomas Power dan Eve Warburton (2020), dan lembaga survei kredibel, contohnya Freedom House, merilis analisis tentang regresi demokrasi Indonesia.
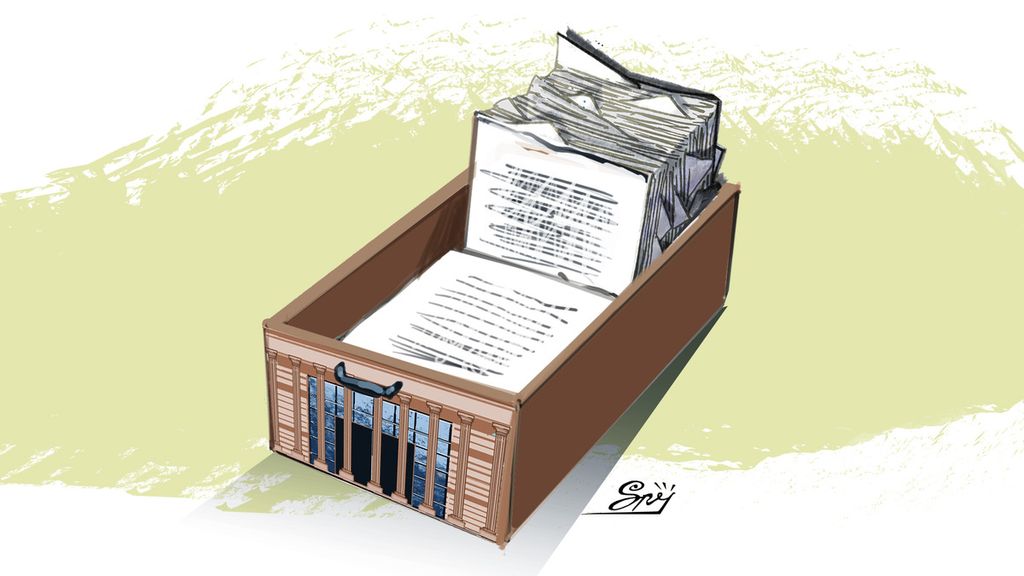
Ini mengafirmasi konstitusi demokratis bukan faktor otomatis yang menjamin kontinuitas demokrasi. Muatan materi UUD 1945 pasca-amendemen yang disebut sebagai konstitusi demokratis itu masih sama hingga kini, tetapi kualitas demokrasinya justru mundur.
Realitas itu tidak cukup dijelaskan hanya dengan pendekatan hukum tata negara, tetapi juga memerlukan pendekatan ilmu politik. Itulah mengapa, kalimat Jan Komarek (2021), ”Constitutional law is closely linked to politics”, Jan-Erik Lane (1996) mengingatkan, demokrasi konstitusional harus dicermati dari dua aspek, yaitu constitutional formalia (konstitusi tertulis) dan constitutional realia (praktik konstitusional).
Dinamika demokrasi konstitusional Indonesia kontemporer sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh preferensi subyektif para elite politik daripada oleh norma dan etika konstitusi. Masih ada ikhtiar mengutak-atik konstitusi demokratis.
Konstitusi demokratis bukan garansi praktik kekuasaan demokratis. Konstitusi demokratis bukan obat mujarab ( panacea) untuk memulihkan demokrasi.
Mencuatnya kehendak untuk jabatan presiden tiga periode, perpanjangan masa jabatan presiden, dan penundaan pemilihan umum adalah contoh konstitusi demokratis rentan diterpa abrasi kekuasaan.
Mayoritas elite politik berhasil menggerogoti kualitas demokrasi konstitusional, sehingga kini mengidap regresi. Sewaktu-waktu nanti mungkin dapat meruntuhkan bangunan demokrasi konstitusional.
Bukan karena konstitusi telah ketinggalan zaman, tetapi demi ambisi kekuasaan dan kepentingan. Demokrasi konstitusional kita menghadapi tantangan serius untuk mencapai tahap ”stability and persistence of democracy” (Diamond, 1999) dan ”the only game in town” (Linz dan Stepan, 1996).
Itu terjadi karena tak ada pelembagaan oposisi politik atau oposisi demokratik dalam sistem demokrasi konstitusional kita. Akibatnya, tak terbentuk keseimbangan kekuatan politik di level suprastruktur politik.
Partai politik cenderung ingin berkumpul dalam koalisi pemerintahan dengan segala perolehan insentifnya. Ketika berada di pemerintahan, kedudukan politiknya dikerdilkan jadi rubber stamp (stempel) titah penguasa, bahkan untuk mencederai konstitusi demokratis.
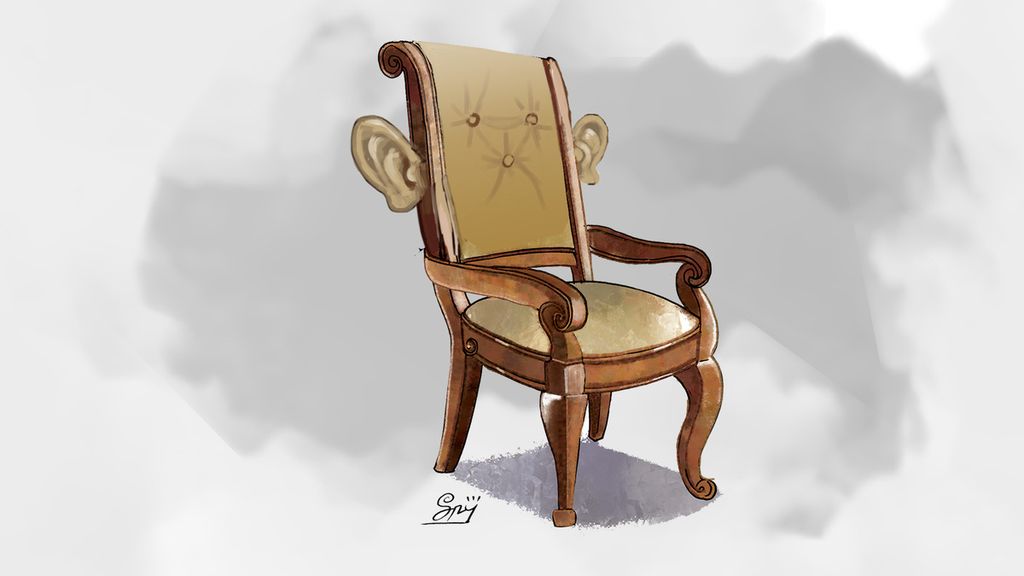
Ilustrasi
Pelembagaan oposisi
Dalam konteks itu, gagasan tentang pelembagaan oposisi yang pernah disuarakan almarhum Nurcholish Madjid relevan diwujudkan. Gagasan pelembagaan oposisi tidak untuk mengubah sistem presidensial menjadi sistem parlementer, tetapi menciptakan keseimbangan politik dan democratic polity jangka panjang.
Dengan format pelembagaan oposisi yang jelas, pilihan koalisi dalam pemerintahan atau koalisi luar pemerintahan tak dimotivasi oleh politik ”dagang sapi”, eksklusi politik, atau oportunisme politik. Di samping itu, pelembagaan oposisi akan membentuk keseimbangan kekuatan politik, menyuburkan deliberasi gagasan, memunculkan pilihan alternatif kebijakan publik, mencegah persekutuan menumbangkan demokrasi.
Sekalipun demikian, ada yang menyangka pelembagaan oposisi cuma berlaku di sistem pemerintahan parlementer dan dituding penyebab instabilitas politik. Sejarah demokrasi parlementer sejak awal kemerdekaan hingga akhir dekade 1950-an sering dijustifikasi untuk menolak pelembagaan oposisi.
Sesungguhnya, jika membaca saksama riset Herbert Feith berjudul The Wilopo Cabinet, 1952-1953: A Turning Point in Post-Revolutionary Indonesia (1958) dan The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (1962), ketegangan politik dan jatuh-bangun kabinet dipicu oleh perbedaan pendapat mengenai pilihan kebijakan.
Partai-partai politik masa itu tidak bersiasat mengutak-atik aturan main bersama ketika sedang di tampuk pemerintahan agar berkuasa lebih lama. Selanjutnya, penelitian Daniel S Lev berjudul The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957-1959 (1966) menjelaskan bubarnya demokrasi konstitusional zaman itu diorkestrasi oleh kekuatan eksternal partai politik untuk menampilkan demokrasi terpimpin.
Pelembagaan oposisi dapat diaplikasikan dalam sistem pemerintahan apa pun. Robert A Dahl dkk dalam Political Opposition in Western Democracies (1966) memaparkan, oposisi politik ada dalam sistem parlementer, sistem presidensial, dan sistem semi-presidensial.
Menurut Alfred Stepan dalam artikel ”Democratic Opposition and Democratization Theory” (1997), oposisi demokratik bisa membantu konsolidasi dan pendalaman demokrasi, menciptakan struktur partisipasi, transparansi, akuntabilitas.
Demokrasi konstitusional yang sehat tak hanya memerlukan konstitusi demokratis, tetapi juga membutuhkan pelembagaan oposisi. Ini agenda yang perlu direalisasikan agar kita tak cemas akan kesinambungan demokrasi konstitusional.
Munafrizal Manan,Alumnus Universiteit Utrecht dan University of Melbourne, Advokat