Puncak Labirin Ketimpangan
Saat ini tumbuh pesimisme yang kental untuk ”menyatukan” pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan. Pertumbuhan ekonomi yang beralas kelompok kaya menciptakan ketimpangan. Ketimpangan itu telah menjadi puncak labirin.
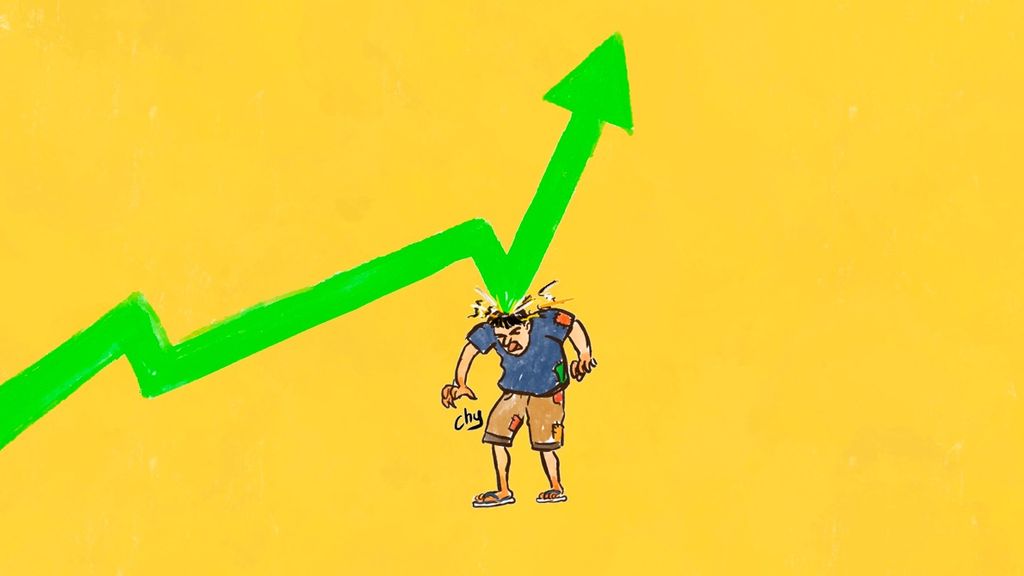
Ilustrasi
Martin Wolf dalam buku terbarunya, The Crisis of Democratic Capitalism (2023), menukilkan kembali kegagalan akut yang dibuat para pemimpin negara dan ekonom, yakni patologi ketimpangan ekonomi yang kian brutal.
Akibat dari perkara ini, kelas menengah mengidap penyakit ketidakpastian dan ketakutan atas potensi besar terjadinya keruntuhan sosial dan eksklusi kesempatan ekonomi.
Situasi ini menyasar hampir semua negara, termasuk negara maju yang disebut democratic capitalism. Sekadar ilustrasi, pada 1980 rasio gaji eksekutif top dengan karyawan terendah di AS baru 42 : 1. Namun, pada 2016 melonjak tak kepalang menjadi 347 : 1. Periode 1993-2015, kumulatif pertumbuhan riil pendapatan 1 persen kelompok terkaya di AS mencapai 95 persen, sementara 99 persen warga lain hanya tumbuh 14 persen. Fenomena ini hampir menyergap semua negara, tanpa kecuali.
Bencana kesenjangan
Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat pokok kemajuan ekonomi. Teori- teori ekonomi pembangunan dekade 1950-an dan 1960-an semuanya mempromosikan pertumbuhan ekonomi sebagai gagasan penopang utama pembangunan (ekonomi). Tingkat tabungan dan investasi menjadi amunisi pokok untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Implikasinya, kebijakan ekonomi diproduksi dengan jalan memberikan ruang yang lebih kecil bagi kelompok ekonomi bawah/menengah dan memperlebar luas kamar ekonomi kelompok atas.
Baca juga : Memperkuat Kebijakan Pemerataan Pembangunan Ekonomi
Argumennya lugas: kelas bawah tidak menciptakan nilai tambah dan penyebaran ekonomi yang cepat. Selebihnya para konseptor teori ekonomi pembangunan yakin bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi yang dihela kelas atas akan menarik gerbong kelompok ekonomi lain, lewat penciptaan lapangan kerja dan integrasi dengan usaha kecil. Inilah sumber awal bencana kesenjangan.
Saat ini tumbuh pesimisme yang cukup kental untuk ”menyatukan” pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan. Kelembagaan ekonomi (economic institutions) yang disusun puluhan tahun gagal mempertemukan dua capaian ideal pembangunan itu. Saat ini pilihannya ialah terciptanya perbaikan kesetaraan politik (political equality) untuk memperbaiki level permainan di lapangan ekonomi (pasar tenaga kerja, tata kelola korporasi, dan lain-lain) (Allen, 2021).
Opsi ini dikerjakan karena dampak dari pertumbuhan ekonomi yang beralas kelompok kaya mengakibatkan kekuasaan sebagian besar digenggam kelompok ini, termasuk di negara kapitalisme demokratik (yang saat ini sedang mengalami krisis ekonomi-politik yang hebat). Lebih mendasar lagi, jika kebijakan ini yang diambil, harga yang mesti dibayar adalah berakhirnya ideologi pertumbuhan ekonomi tinggi (degrowth).

Belum berhenti di situ, perkembangan pemanfaatan teknologi dan laju inovasi yang luar biasa pesat, khususnya sejak awal abad milenium, membuat pemerintah kesukaran menciptakan lapangan kerja sebab intensitas digitalisasi dan otomatisasi tak bisa dibendung.
Perkara ini tidak hanya menjadi kerisauan di negara berkembang, tetapi juga kecemasan di negara maju. Level pengangguran di negara mapan (Eropa dan AS) melesat tinggi beberapa dasawarsa terakhir. Bahkan, kelangkaan peluang kerja yang bermutu dan kegelisahan ekonomi telah memperbesar kelompok ekstrem (far right) yang mengganggu stabilitas sosial dan politik.
Apalagi ditambah dengan munculnya populisme otoritarian. Singkatnya, ketimpangan telah menjadi puncak labirin. Salah satu yang didesain oleh produsen kebijakan sekarang ialah pengurangan insentif kapital dan menambah subsidi bagi penggunaan tenaga kerja.
Kebijakan pemerintah yang tak merata di bidang pendidikan dan kesehatan menyebabkan kualitas keterampilan (juga dalam beberapa hal tertentu bakat) tak dapat dioptimalkan.
Trimatra produksi
Mata air asimetri kesejahteraan yang menggelayuti dunia bersumber dari trimatra produksi (Blanchard dan Rodrik, 2021). Pertama, ketimpangan praproduksi. Disparitas ini bersumber dari perbedaan keterampilan, bakat, akses pendidikan dan kesehatan, dan sebagainya.
Kebijakan pemerintah yang tak merata di bidang pendidikan dan kesehatan menyebabkan kualitas keterampilan (juga dalam beberapa hal tertentu bakat) tak dapat dioptimalkan.
Kasus tengkes (stunting) merupakan contoh yang bisa dirujuk, di mana literasi yang terbatas soal gizi dan perkembangan anak mengakibatkan sulitnya penurunan angka tengkes. Di Indonesia, sampai saat ini angka tengkes masih 21,6 persen (2022). Artinya, satu dari lima balita mengalami masalah ini (angka ini sudah turun drastis, pada 2013 masih 37,8 persen). Generasi ini dalam jangka panjang jadi salah satu sebab pemicu ketimpangan via daya saing yang rendah.
Kedua, disimilaritas tahap produksi. Problem divergensi ini sudah kerap diulas, yakni kepincangan ekonomi antara pemilik modal dan pekerja. Di negara-negara yang serikat kerjanya dilindungi dan dimapankan, kesenjangan ekonomi di korporasi bisa dikurangi karena akses pekerja untuk mengambil keputusan (khususnya penentuan upah dan bonus) cukup besar. Sebaliknya, di negara yang kurang menjamin serikat kerja, pengambilan keputusan dimonopoli oleh pemilik modal sehingga ketimpangan berpotensi membesar.
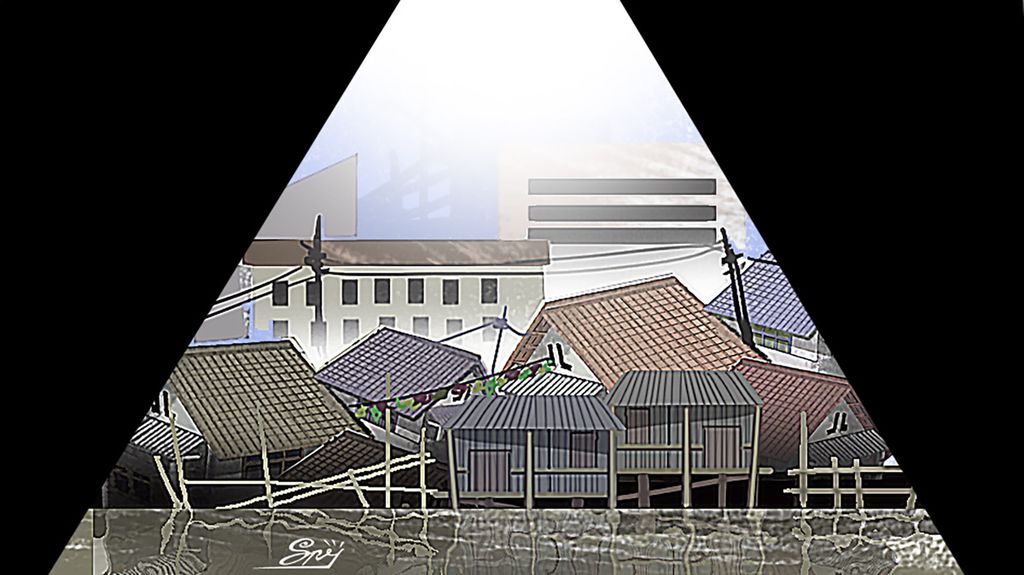
Hal lain, intervensi negara sangat vital terutama dalam penentuan upah minimum dan pendidikan vokasional (Dustmann, 2021). Kebijakan ini mencegah eksploitasi badan usaha dalam mengenakan tingkat upah yang (sangat) rendah sehingga praktik pengisapan/ekstraksi ekonomi bisa dihindarkan. Pada level meso ini, ”kebijakan industrial” (pemapanan serikat kerja dan keterlibatan pemerintah dalam penentuan upah) jadi kunci mencegah pendalaman disparitas.
Ketiga, ketidakseimbangan pascaproduksi. Perbedaan pendapatan ini merupakan konsekuensi dari munculnya ketimpangan di level praproduksi dan produksi. Jika di kedua level ini kepincangan berlangsung, dipastikan terjadi divergensi pascaproduksi. Kelompok yang menikmati pendidikan akan terus mengakumulasi kenaikan kesejahteraan (pendapatan) sehingga kelas masyarakat lain makin tertinggal.
Pendapatan kelompok kaya mengikuti deret ukur, sebaliknya kelas rentan naik mengikuti deret hitung. Pemilik modal memperoleh nisbah ekonomi yang jauh lebih besar dalam bentuk laba yang direnggut, juga gaji yang kian mengangkasa. Jika tak tersedia kebijakan pemangkas untuk membatasi kekayaan (misalnya pajak progresif) dan membantu beban kelompok paling rendah (seperti transfer pendapatan), ketimpangan akan merajalela.
Baca juga : Babak Pembangunan ”Pinggiran”
Penikmat liberalisasi
Di luar soal asimetri yang berakar dari fase produksi dan moda produksi, disparitas juga kerap ditelaah dari sumber lain. Pertama, demokrasi dianggap sebagai pilihan sistem politik yang masuk akal mencegah pembesaran kesenjangan karena menutup peluang penguasaan sumber daya secara monopolistik.
Perspektif ini mengandaikan ketimpangan ekonomi buah dari sistem politik yang tertutup. Keputusan alokasi sumber daya bisnis hanya diurus segelintir elite politik sehingga sekawanan pelaku ekonomi lain terlempar dari arena perburuan faktor produksi. Kasus di negara-negara Amerika Latin (Selatan), sebagian Asia, dan Eropa Timur di masa lalu sering dirujuk untuk memperkuat pandangan ini. Indonesia di masa silam juga menjadi referensi sahih dalam pembahasan terkait isu disekuilibrium ekonomi. Meski fondasi ide ini cukup kuat, rujukan riset mutakhir layak diselisik kembali guna menguji postulat ini.
Kedua, perayaan globalisasi/liberalisasi. Globalisasi mengubah secara mendasar lanskap (ekonomi) dunia. Interaksi antarnegara yang semula dijaga amat ketat dalam wujud proteksi (lewat aneka instrumen ekonomi: bea impor, kuota, dumping, dan lain-lain) dicairkan lewat pembukaan pasar ekonomi, kebebasan mobilitas penduduk antarnegara, investasi, perdagangan, dan seterusnya.
Harus diakui sejak dijalankan secara masif mulai dasawarsa 1980-an, terdapat beberapa negara penikmat liberalisasi, seperti China, Korsel, India, Vietnam, dan (dalam beberapa hal) Indonesia. Negara-negara ini melesat ukuran ekonominya (dilihat dari PDB) sehingga menjadi anggota G20 (kecuali Vietnam). Implikasinya, selisih kesejahteraan antara negara maju dan berkembang (ketimpangan eksternal) makin kecil.
Di sisi lain, pada tiap-tiap negara (internal) muncul ketimpangan yang membesar. Inilah dua paras globalisasi yang menjadi paradoks.

.
Ketiga, ekonom dan pemerintah memiliki keraguan akut menetapkan kebijakan progresif terkait ketimpangan, sejak dari hulu hingga hilir. Sirkulasi modal yang tak menyebar dan kepemilikan lahan yang memusat merupakan contoh yang kerap dikutip, di mana sangat sedikit negara yang secara terukur melakukan upaya pembatasan kepemilikan.
Kebijakan reforma agraria biasanya diterapkan hanya untuk memberi tanah bagi yang tak memilikinya (ini pun dalam jumlah sangat terbatas) tanpa memangkas pelaku ekonomi yang punya lahan di luar batas (ratusan ribu sampai jutaan hektar). Laba yang ditimbun, profit jumbo yang diperoleh dari transaksi derivatif di sektor keuangan, dan kekayaan besar dari warisan terhindar dari kebijakan pajak progresif, sehingga kelompok ini mengakumulasi kekayaan dalam jumlah yang gigantik (Piketty, 2014). Negara-negara Skandinavia termasuk kawasan yang relatif progresif dalam isu ini.
Pembangunan ilusif
Indonesia termasuk negara yang menyadari bahwa ketidakadilan ekonomi yang tak diurus secara militan akan mendorong pembangunan mengalami pembalikan. Kemajuan ekonomi yang disertai kenaikan kepincangan ekonomi membuat ikatan sosial mengalami korosi dan derajat kepercayaan politik terdelusi. Inilah yang disebut dengan pembangunan yang ilusif, yakni kemajuan ekonomi yang diikuti munculnya pelemahan sosial dan kerentanan politik.
Indonesia sedang berkejaran dengan perkara ini setelah pada periode sebelumnya ketimpangan ekonomi mengalami pemburukan. Rasio gini naik tangga demi tangga hingga menembus angka di atas 0,41. Maka, sejak 2015 dikerjakan langkah sistematis untuk menurunkan ketimpangan ini. Sejarah juga mencatat Indonesia sukses besar mengungkit cakupan warga yang terlindungi akses kesehatan dan pendidikan. Ini kesuksesan praproduksi yang amat vital.
Indonesia termasuk negara yang menyadari bahwa ketidakadilan ekonomi yang tak diurus secara militan akan mendorong pembangunan mengalami pembalikan.
Dari sisi investasi, salah satu pengungkit kepincangan bertumpu dari dominasi PMA sehingga Kementerian Investasi/BKPM diberi mandat meningkatkan porsi PMDN. Hasilnya amat menjanjikan, karena sejak 2020 porsi PMDN sudah hampir setara dengan PMA. Lebih dari itu, pada 2022 dominasi investasi yang selama ini hanya di Jawa (47,3 persen), sekarang sudah diimbangi investasi di luar Jawa (52,7 persen).
Kementerian Investasi juga mewajibkan setiap penanaman modal besar berkongsi dengan UMKM dan penduduk lokal. Investasi ini penting dikelola karena menjadi telaga terciptanya pelebaran disparitas antara pemodal besar dan kecil, domestik dengan luar negeri, dan Indonesia bagian barat dengan timur. Indonesia juga terus menjamin pemapanan serikat kerja serta campur tangan negara dalam penentuan upah minimum setiap tahunnya. Ini salah satu sebab mogok kerja bisa dihindari. Benih kebijakan tahap produksi yang bagus ini wajib terus dirawat dengan baik.
Pada pascaproduksi, kebijakan pajak progresif juga dimapankan, khususnya kenaikan (pajak) pemangkasan pendapatan tertinggi menjadi 35 persen (dari semula 30 persen). Ini diiringi dengan kenaikan pendapatan tidak kena pajak (PTKP) menjadi Rp 4,5 juta/bulan, sehingga warga berpendapatan di bawah Rp 54 juta/tahun tak dibebani pajak. Sungguhpun begitu, terkait pajak atas laba, profit transaksi di sektor keuangan, warisan dan aset lahan, dan lain-lain belum ada spirit progresivitas muncul.
Soal lainnya, kebijakan di sisi hulu, yakni pembatasan kepemilikan lahan dan kapital. Sampai sekarang isu ini masih jadi pekerjaan rumah yang besar. Dibutuhkan visi dan afirmasi politik yang kokoh untuk masuk ke arena ini karena pasti akan menghadapi arus kekuatan politik yang deras. Perang menghadapi ketimpangan adalah suara moral yang mesti dimenangi. ”If we fail, the light of political and personal freedom might once again disappear from the world,” demikian taklimat Wolf.
Ahmad Erani Yustika, Guru Besar FEB Universitas Brawijaya; Ekonom Senior Indef; Kepala Sekretariat Wakil Presiden
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2020%2F01%2F15%2Fd2f4bcfa-7359-41af-8f07-af6d9b8bea01_jpg.jpg)
Guru Besar Ekonomi Universitas Brawijaya Ahmad Erani Yustika