Negara Kesejahteraan, atau Masyarakat yang Sejahtera?
Banyak pemerintah di dunia ingin mengubah negaranya menyerupai negara kesejahteraan. Namun, apa yang ditawarkan negara kesejahteraan tidaklah gratis. Juga bukan berarti tidak ada gejala masyarakat yang tidak bahagia.
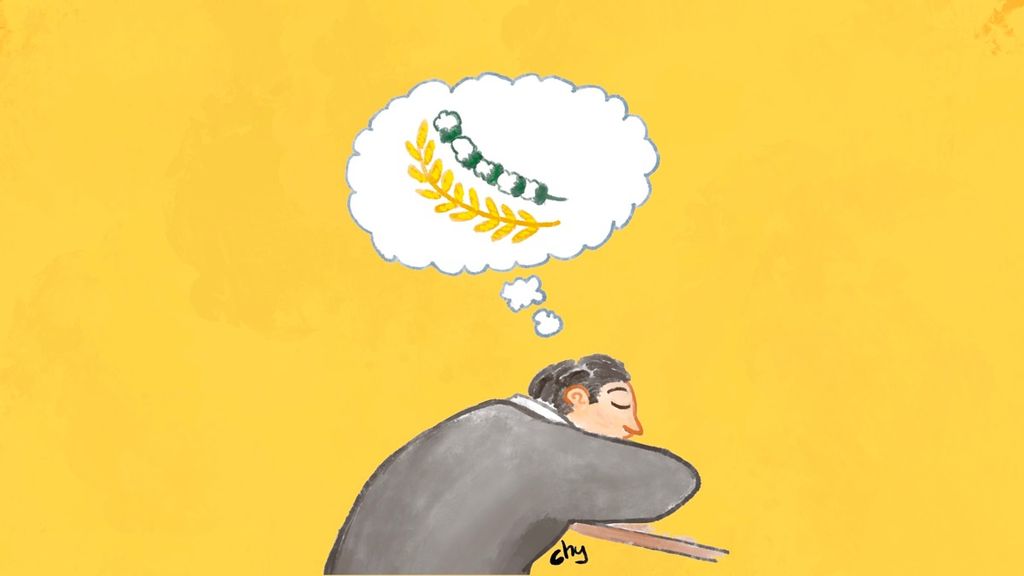
Ilustrasi
Opini Todung Mulya Lubis, ”Negara Kesejahteraan” (Kompas, 9/1/2023), mengangkat sebuah topik reflektif tentang wujud negara kesejahteraan (welfare state) Indonesia.
Lubis sampai pada kesimpulan bahwa konstitusi telah menetapkan Indonesia untuk berada di jalur negara kesejahteraan. Hanya saja, ada sejumlah inkonsistensi kebijakan ekonomi yang membuatnya tidak sepenuhnya koheren dengan visi negara kesejahteraan.
Topik yang dihadirkan Lubis relevan, terutama jika kita perhatikan rangkaian reformasi kebijakan sosial dan ekonomi yang tengah berlangsung baru-baru ini.
Diawali dengan diperkenalkannya program Kartu Prakerja pada gelombang pertama Covid-19, disusul UU Cipta Kerja yang ”kontroversial” di pengujung 2020. Tak lama setelahnya, pemerintah merencanakan restrukturisasi ketentuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mengubah manfaat pensiun jadi fully funded, tapi juga menginisiasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), sebuah manfaat pengangguran yang sebelumnya tampak di luar jangkauan.
Baca juga :Negara Kesejahteraan
Tidak ada makan siang gratis
Menurut penulis, apa yang saat ini dianggap inkonsisten kiranya dapat dilihat sebagai bagian dari proses pencarian ide negara kesejahteraan yang lebih kontekstual. Paralel dengan inkonsistensi yang ditunjukkan, muncul pertanyaan lain, apakah menjadikan Indonesia sebagai welfare state masih relevan?
Ibarat negeri impian dalam dongeng, negara-negara yang masuk dalam kategori welfare state (terutama sebagian besar Eropa wilayah Barat) selalu didambakan karena reputasinya sebagai negara dengan peringkat kualitas hidup teratas. Ini terutama karena peran sentral negara yang hampir penuh dalam menjamin hak sosial warganya.
Ketentuan itu juga berlaku kepada mereka yang menganggur karena negara kesejahteraan menjamin sejumlah kompensasi yang setara dengan 75 sampai 90 persen dari penghasilan individu selama bekerja dalam periode tertentu. Contoh paling ideal untuk mengilustrasikan ini adalah Denmark lantaran skema unemployment benefits yang diberikan kepada penganggur memungkinkan untuk dapat diklaim, sampai bahkan dengan dua tahun lamanya.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F02%2F17%2Fa2c30562-e472-44b9-9556-2be1c9edb06f_jpg.jpg)
Sejumlah pekerja proyek sibuk melihat gawai masing-masing saat jam isitirahat makan siang di salah satu lokasi pembangunan gedung bertingkat di Jakarta, Kamis (17/2/2022). Pemerintah diharapkan dapat menunda Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua untuk mengevaluasi kesiapan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai pengganti Jaminan Hari Tua (JHT).
Tampak sangat menarik, sampai membuat pemerintah di dunia mana pun berandai-andai mengubah negaranya menyerupai negara kesejahteraan.
Namun, perlu dicatat bahwa segala keterjaminan yang ditawarkan negara kesejahteraan tidaklah gratis. Sederhananya, kalau ada hak yang diterima, berarti ada kewajiban yang harus dipenuhi. Hukum ini berlaku linear: semakin besar hak diperoleh, semakin besar juga kewajiban yang dibebankan.
Analogi di atas mengeksplisitkan bahwa kebijakan sosial yang murah hati akan selalu bergantung pada ”pajak pendapatan” yang bisa sampai setengah dari pendapatan bulanan; dan kerelaan membayar pajak akan sangat tergantung pada keyakinan masyarakatnya, ”apakah kesejahteraan sosial mereka benar-benar akan dijamin?”
Pertanyaan ini dijawab dengan komitmen politik pemerintah mereka untuk mengalokasikan proporsi belanja perlindungan sosial yang dapat mencapai rata-rata 20 persen dari PDB. Sementara di wilayah Skandinavia sendiri, anggaran perlindungan sosialnya sudah di kisaran 25 persen-30 persen.
Namun, perlu dicatat bahwa segala keterjaminan yang ditawarkan negara kesejahteraan tidaklah gratis.
Bandingkan dengan Indonesia: belanja perlindungan sosial nasional, bahkan dalam kondisi darurat pandemi sekalipun, tak sampai 5 persen. Meskipun begitu, sejarah perlindungan sosial Indonesia sejak krisis moneter 1998 mencatat bahwa negara ini tak pernah kehabisan ide dan ambisi untuk menciptakan program-program sosial baru. Akibatnya, sesuai dengan analogi wide but not deep, ada banyak program, tapi tak pernah dapat memberikan penghidupan layak yang berarti bagi penerima manfaatnya.
Kenyataan ini juga dibayang-bayangi oleh fakta bahwa hampir 60 persen masyarakat Indonesia bekerja di sektor informal. Ini menyulitkan pemerintah mengumpulkan pajak penghasilan sebagai sumber pembiayaan utama negara kesejahteraan. Sudah begitu, banyak obyek wajib pajak juga sering lalai, bahkan lari dari tanggung jawabnya. Realitas ini menunjukkan kepada kita bahwa jalan untuk memenuhi prakondisi minimal bagi berdirinya sebuah institusi negara kesejahteraan masih teramat panjang.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F05%2F11%2Fd41078eb-39ed-46f8-9c06-bae8e2349ac8_jpg.jpg)
Pedagang makanan menjajakan dagangannya di trotoar di Jalan Tentara Pelajar, Jakarta di sekitar Stasiun Palmerah, Rabu (11/5/2022). Pulang kerja menjadi waktu yang paling dinanti para pedagang agar dagangannya laris.
Sisi gelap negara kesejahteraan
Tak banyak yang mengira bahwa di negara kesejahteraan terdapat gejala masyarakat yang tidak bahagia. Ini terungkap dari sebuah fakta tentang peningkatan penggunaan obat antidepresan pada sebagian besar masyarakat di 18 negara kesejahteraan Eropa yang mencapai hampir 2,5 kali lipat pada 2000- 2020 (OECD, 2022). Mengejutkannya lagi, masyarakat dengan konsumsi antidepresan tertinggi pada 2020 secara berturut-turut justru ditemukan di negara-negara yang sering dijadikan contoh ideal praktik negara kesejahteraan, seperti Eslandia, Swedia, dan Norwegia.
Sementara Denmark dan Finlandia dilaporkan berada di urutan ke-8 dan ke-9. Alasan untuk anomali ini belum diketahui, tapi yang pasti, tingginya penggunaan obat antidepresan bisa menjadi cerminan akses yang lebih baik ke perawatan kesehatan mental.
Kenyataan ini bertolak belakang dengan berbagai laporan, misalnya OECD Report atau The World Happiness Report (TWHR), yang menempatkan mereka sebagai negara dengan segala aspek kesejahteraan dan kebahagiaan teratas.
Tak banyak yang mengira bahwa di negara kesejahteraan terdapat gejala masyarakat yang tidak bahagia.
Dalam survei TWHR terbaru, negara- negara kesejahteraan Eropa Barat, seperti Finlandia, Denmark, Eslandia, Swiss, dan Belanda, memiliki skor tertinggi, rata-rata di atas 7 dari 10. Sementara Indonesia sejajar dengan negara Asia lain, seperti Malaysia, Thailand, China, dan Korea Selatan, berada dalam rentang skor 5-6.
Tren meningkatnya penggunaan obat antidepresan pada akhirnya menggoyahkan asumsi bahwa negara yang lebih kaya cenderung memiliki skor kebahagiaan rata-rata yang lebih tinggi.
Timbulnya gejala ketidakbahagiaan di sebagian besar masyarakat di negara-negara kesejahteraan patut kita cari tahu penyebabnya supaya menjadi pelajaran untuk negara kita yang kini mulai serius membangun sistem welfare state-nya.
Selama ini mungkin kita terkecoh bahwa negara kesejahteraan vis a vis dengan kapitalisme yang selalu kita kritik. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah ide negara kesejahteraan sama dengan istilah welfare capitalism (Esping-Andersen, 1990), atau dalam bahasa Indonesia sering diilustrasikan sebagai ”sistem kapitalisme baik hati”.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2021%2F11%2F23%2F700874e4-7f4e-4a03-ac26-d2fd32e7165a_jpg.jpg)
Sejumlah pasien sedang menjalani curi darah di Rumah Sakit Umum Daerah Dr Soegiri Lamongan, Jawa Timur Jumat (6/4/2018). Warga Lamongan telah memanfaatkan jaminan kesehatan nasional baik ikut serta kepesertaan secara mandiri maupun melalui skema penerima bantuan iuran (PBI).
Sistem ini merekayasa ambisi liberalisme pasar agar tumbuh beriringan dengan semangat redistribusi yang diatur negara. Fondasi sosial masyarakat mereka pun dibangun atas dasar paham materialisme, ciri khas masyarakat yang sudah terindividualisasi.
Materialisme, bagaimanapun, hanya akan dapat menambah perasaan kekurangan relatif pada diri seseorang. Seseorang akan selalu mengukur kebahagiaan tak hanya dengan seberapa banyak yang dimilikinya, tetapi seberapa banyak yang dimilikinya dibandingkan dengan orang lain. Karena itu, ketidakbahagiaan muncul karena ketidakmampuan seseorang mengonsumsi lebih banyak daripada yang ada di sekitar mereka.
Gejala masyarakat tak bahagia di negara kesejahteraan barangkali dapat dihubungkan dengan perasaan kekurangan relatif tadi. Ini logis karena ketentuan pajak progresif yang sangat tinggi akan membuat mereka yang memiliki kemampuan menghasilkan lebih banyak uang mau tak mau harus hidup dengan tingkat konsumsi yang tak jauh beda dengan mereka yang biasa-biasa saja. Jika hipotesis ini benar, kita bisa berargumen klaim solidaritas sosial yang selama dicitrakan hanyalah semu.
Fondasi sosial masyarakat mereka pun dibangun atas dasar paham materialisme, ciri khas masyarakat yang sudah terindividualisasi.
Dalam konteks masyarakat kita, fenomena ini bukanlah hal baru. Mereka yang masuk dalam kategori generasi sandwich, misalnya, harus rela membagi pendapatannya kepada keluarganya dengan proporsi yang mungkin lebih dari setengah pendapatan bulanan. Ini jelas membuat tingkat konsumsi mereka, mau tidak mau, juga ditekan, membuatnya tidak dapat spending di atas orang-orang sekitarnya.
Dalam literatur, proses transfer pendapatan ini yang kemudian disebut sebagai masyarakat sejahtera (welfare society), artinya sistem kesejahteraan yang diatur dengan ketentuan informal. Namun, apakah mereka bahagia? Teorinya iya, karena terdapat nilai-nilai kultural dan etika yang mendasari mereka berbagi. Akan tetapi, realitasnya, itu akan sangat subyektif sehingga perlu lebih banyak studi.
Kembali ke pertanyaan apakah mimpi untuk mengubah Indonesia menjadi negara kesejahteraan masih relevan? Mungkin relevan jika kita mulai berpikir bahwa kebahagiaan, sama dengan kesuksesan, tidak harus diukur dengan konsumsi materi lebih banyak dari orang sekitar kita. Hanya dengan begitu, ketentuan formal yang mengatur redistribusi sosial pada akhirnya dimaknai dengan apa yang kita selama ini praktikan sehari-hari sebagai bagian dari berderma.
Pertanyaan berikutnya adalah apakah kita benar-benar sanggup berkomitmen untuk negara kesejahteraan?
Tauchid Komara Yuda Dosen di Departemen Pembangunan Sosial & Kesejahteraan, UGM dan dosen tamu (kebijakan sosial) di Mahidol University, Thailand.

Tauchid Komara Yuda