Otonomi Strategis Indonesia
Indonesia dapat belajar dari Uni Eropa yang telah menerapkan pendekatan otonomi strategis sejak 2013. Bertindak mandiri di bidang kebijakan strategis, seperti pertahanan, ekonomi, dan penegakan nilai-nilai demokrasi.

Ilustrasi
Ada kebutuhan mendesak bagi Indonesia untuk merumuskan secara operasional konsep otonomi strategis guna menghadapi risiko-risiko geopolitik dan geoekonomi yang kian meningkat di tahun-tahun mendatang.
Otonomi strategis bukan berarti menafikan interdependensi atau menarik diri dari dunia internasional. Otonomi strategis merupakan perwujudan kepiawaian suatu negara dalam mengidentifikasi kehadiran titik rawan dalam suatu sistem rantai pasok global.
Tujuannya, untuk meningkatkan kesiagaan sekaligus tindakan mitigasi ketika menghadapi berbagai tantangan selama periode disrupsi, terutama terkait dengan risiko-risiko geopolitik dan geoekonomi yang semakin meningkat.
Baca juga : Dunia yang Semakin Kacau-balau
Geopolitik versus geoekonomi
Konsep geopolitik sendiri telah mengalami perluasan makna sejak pra-Perang Dunia I hingga saat ini. Kajian terhadap geopolitik klasik yang ditandai oleh tindakan okupansi atau pendudukan di suatu wilayah tak lagi menjadi instrumen tunggal bagi sebuah negara dalam menunjukkan kekuatannya.
Istilah geoekonomi, pengendalian wilayah melalui instrumen ekonomi dan keuangan, mulai dikenal dan marak di era pasca-Perang Dingin, bersamaan dengan mulai memudarnya relevansi ancaman serta aliansi militer.
Konflik Ukraina yang berlangsung hingga hari ini menjadi ilustrasi nyata pertarungan geopolitik klasik dan geoekonomi itu. Rusia melakukan tindakan operasi militer demi melindungi keamanan nasionalnya, yakni untuk memastikan Ukraina tak menjadi bagian dari aliansi militer NATO dan menghindari adanya keberadaan kekuatan asing di Ukraina. Sementara itu, AS memilih menggunakan instrumen nonmiliter dalam mencapai kepentingannya.

Rezim sanksi internasional yang diterapkan oleh AS bersama sekutunya saat ini menjadi bentuk dari excercise of power yang dilakukan AS. Sebagai gambaran, AS bersama sekutu melakukan pembekuan aset diaspora Rusia yang berada di wilayah yurisdiksinya.
Selanjutnya, AS mendepak bank terbesar Rusia dari SWIFT sehingga Rusia tak dapat memanfaatkan fasilitas pembayaran internasional ini. AS turut menggunakan instrumen embargo perdagangan terhadap Rusia. Terakhir, AS melalui G7 dan Australia menciptakan pembatasan tingkat harga minyak (oil price cap) terhadap ekspor minyak Rusia.
Beberapa kajian memang menunjukkan keyakinan bahwa pengenaan oil price cap ini akan mampu mengubah perilaku geopolitik klasik Rusia. Kajian Kelompok Kerja Internasional Stanford (November 2022), misalnya, meyakini penetapan harga di bawah 50 dollar AS per barel akan menggerus penerimaan devisa Rusia dan akan memaksa negara itu segera mengakhiri perang.
Beberapa kajian memang menunjukkan keyakinan bahwa pengenaan oil price cap ini akan mampu mengubah perilaku geopolitik klasik Rusia.
Pembatasan sepihak ini disertai pelibatan perusahaan keuangan/asuransi global dan maskapai perkapalan dunia yang dikendalikan G7 plus Australia.
Kondisi di atas menunjukkan, meskipun memiliki kemandirian dalam sektor pangan dan energi, Rusia tak memiliki kapasitas serupa dalam hal jejaring keuangan dan logistik internasional.
Selain itu, meski Rusia menyatakan bahwa saat ini negaranya telah mampu beradaptasi dengan perekonomian di masa perang, nyatanya beberapa studi lain menunjukkan bahwa berbagai sektor industrinya berada pada kondisi tertekan dibandingkan tahun lalu.
Hasil Triennial Central Bank Survey (Bank for International Settlements/BIS, 2022: 12) menunjukkan, nilai perputaran transaksi valuta asing (valas) di Rusia baru mencapai 0,6 persen dari global. Ini relatif kecil dibandingkan turnover valas di AS yang 19,4 persen dari global.

Rantai pasok global
Globalisasi menimbulkan sistem yang hari ini kita kenal sebagai Global Value Chain (GVC). GVC menghubungkan penciptaan nilai tambah di seluruh belahan dunia menuju sebuah kesatuan interdependensi yang kompleks. Oleh karena itu, tak ada satu negara pun yang dapat mandiri secara utuh dalam situasi saat ini.
Kabar baiknya, pola produksi Indonesia sedang bertransformasi menuju ke keluaran bernilai tambah yang tinggi. Selanjutnya, terdapat kecenderungan Indonesia bergantung kepada sumber domestik untuk input produksi, khususnya selama krisis berlangsung. Sebagai implikasi, proporsi barang jadi terhadap gross output Indonesia menunjukkan peningkatan 3,6 persen (Bank Dunia, 2019).
Namun, terdapat kabar buruk di mana Indonesia mengalami penurunan partisipasi dalam GVC selama lebih dari satu dekade terakhir. Salah satu penyebabnya, keterlibatan Indonesia dalam GVC yang didominasi oleh industri berteknologi rendah dan padat karya untuk bahan baku industri. Di sisi lain, Indonesia memiliki kebutuhan impor yang tinggi untuk menghasilkan barang jadi dalam rangka memenuhi kebutuhan domestik.
Namun, terdapat kabar buruk di mana Indonesia mengalami penurunan partisipasi dalam GVC selama lebih dari satu dekade terakhir.
Sebagai gambaran, Indonesia masuk dalam jajaran negara yang berpartisipasi dalam rantai pasok energi bersih, yakni pada komoditas nikel. Sejak 2015, Indonesia secara konsisten mencatat pertumbuhan produksi komoditas ini.
Akan tetapi, apabila ditinjau secara lebih jauh, Indonesia kembali hanya memainkan peran dalam sisi hulu, yakni tahapan penambangan dan pengolahan. Sementara itu, di sisi hilir, misalnya dalam hal produksi dan pengemasan baterai, masih didominasi negara maju seperti Jepang, Korsel, China, dan AS.
Oleh karena itu, patut didukung sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo ketika tetap bersikukuh untuk mengedepankan hilirisasi industri pertambangan nikel di Indonesia ketika menanggapi keputusan WTO yang menyebut kebijakan pembatasan ekspor bahan baku nikel Indonesia tak sesuai ketentuan WTO.
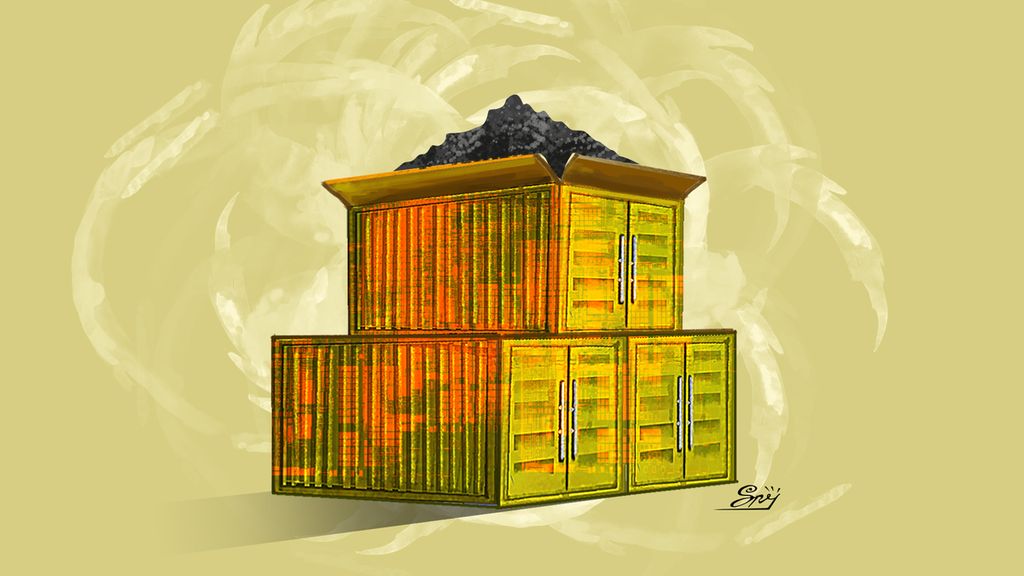
Namun, keterbatasan Indonesia dalam transaksi valas secara global menjadi salah satu rantai yang mengikat langkah kaki Indonesia dalam GVC. Merujuk pada Triennial Central Bank Survey (BIS, 2022: 12), nilai transaksi Indonesia terhadap perdagangan global baru mencapai 0,1 persen. Nilai tersebut sangat kecil dibandingkan Britania Raya, AS, Singapura, Hong Kong, dan Jepang yang masing-masing 38,1 persen, 19,4 persen, 9,4 persen, 7,1 persen, dan 4,4 persen dari jumlah perputaran valas global.
Ini menunjukkan peran kita yang sangat minimal dalam mengubah struktur aliran modal internasional dan peran dominasi dollar AS. Namun, harus pula kita catat, beberapa kajian (misalnya kertas kerja IMF oleh Serkan Arslanlp dkk, Maret 2022; dan Zongyuan Zoe Liu dan Michaela Papa, Cambridge, Februari 2022) memang menunjukkan dominasi dollar AS yang semakin berkurang.
Jika sebelumnya 80 persen cadangan devisa global adalah dalam dollar AS, kini angkanya di bawah 70 persen. Meski demikian, proses de-hegemonisasi dollar AS tak akan bisa dihindarkan di masa depan walau prosesnya masih akan panjang. Setidaknya proses itu akan tergantung dari beberapa variabel seperti orientasi wilayah perdagangannya, peg (pematokan) mata uang nasional, besaran utang luar negeri dalam dollar, dan invoicing transaksi internasional.
Indonesia bersama ASEAN bisa mengadopsi prinsip otonomi strategis sesuai kebutuhan, terutama dengan mempertimbangkan situasi ke depan yang kian tak menentu.
Tawaran otonomi strategis
Dalam kaitan otonomi strategis, Indonesia mungkin dapat belajar dari Uni Eropa (UE) yang telah menerapkan pendekatan otonomi strategis sejak 2013. EU Strategic Autonomy (EU-SA) mengacu pada kapasitas UE untuk bertindak secara mandiri di bidang kebijakan strategis, seperti pertahanan, ekonomi, dan penegakan nilai-nilai demokrasi.
Salah satu titik penting EU-SA adalah pengadopsian Deklarasi Versailles dalam pertemuan Dewan Uni Eropa, 10-11 Maret 2022. Deklarasi menyerukan kemandirian energi yang lebih besar dan basis ekonomi yang kuat. Sebagai tindak lanjut, Dewan memutuskan untuk menghapuskan ketergantungan UE terhadap komoditas energi Rusia.
Langkah ini diambil setelah tindakan Rusia yang memotong pasokan gas ke Polandia dan Bulgaria sebagai respons atas penolakan mereka untuk membayar gas dalam rubel. Tak berhenti sampai di situ, Komisi Eropa pada 18 Mei 2022 melakukan analisis terhadap EWPowerEU, yang terdiri atas tiga elemen inti, yakni menghemat energi, mendiversifikasi impor energi, dan mempercepat substitusi bahan bakar fosil dengan energi terbarukan (EU Strategic Autonomy Monitor, Juli 2022).

Indonesia bersama ASEAN bisa mengadopsi prinsip otonomi strategis sesuai kebutuhan, terutama dengan mempertimbangkan situasi ke depan yang kian tak menentu. Dalam hal ini, perlu dipahami, otonomi strategis bukan berarti tak memercayai interdependensi atau menutup diri dari dunia internasional, melainkan melihat adanya titik rawan pada rantai pasok global. Juga tak berarti globalisasi muncul tanpa kerawanan.
Keyakinan tersebut selanjutnya menjadi landasan untuk mengidentifikasi titik rawan dimaksud guna menghadapi fenomena disrupsi yang berlangsung. Otonomi strategis juga tampak selaras dengan kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia yang berarti kebebasan menentukan sikap dan kebijakan terhadap permasalahan internasional yang ditujukan untuk kepentingan nasional.
Sebagai gambaran, posisi cadangan devisa Indonesia akhir September 2022 sebesar 130,8 miliar dollar AS atau setara 5,9 bulan impor. Kondisi ini terbilang baik karena di atas standar kecukupan internasional, sekitar tiga bulan impor.
Dalam hal ini, Indonesia memiliki opsi untuk melakukan diversifikasi cadangan devisa dalam bentuk mata uang negara lain, seperti kelompok negara yang menjadi mitra perdagangan utama Indonesia.
Meski demikian, Indonesia terbilang memiliki ketergantungan pada dollar AS. Dalam hal ini, Indonesia memiliki opsi untuk melakukan diversifikasi cadangan devisa dalam bentuk mata uang negara lain, seperti kelompok negara yang menjadi mitra perdagangan utama Indonesia. Opsi lain, membuat kesepakatan penggunaan mata uang sesuai dengan mitra perdagangan internasional, misalnya dengan kelompok negara ASEAN.
Praktik ini telah dimulai melalui kesepakatan bank sentral lima negara ASEAN, yakni Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Filipina, dalam meluncurkan sistem pembayaran digital terintegrasi dalam salah satu agenda KTT G20 pada 14 November 2022.
Makmur KeliatStaf Pengajar Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI dan Penasihat Senior Lab45