Dampak Resesi Ekonomi Global
Apakah Indonesia akan resesi? Menurut M Chatib Basri tidak. Tapi pertumbuhan akan melambat. Kita tak boleh lengah. Amunisi kita terbatas. Karena itu, prioritas kebijakan jadi penting. Tak bisa semua hal dilakukan.
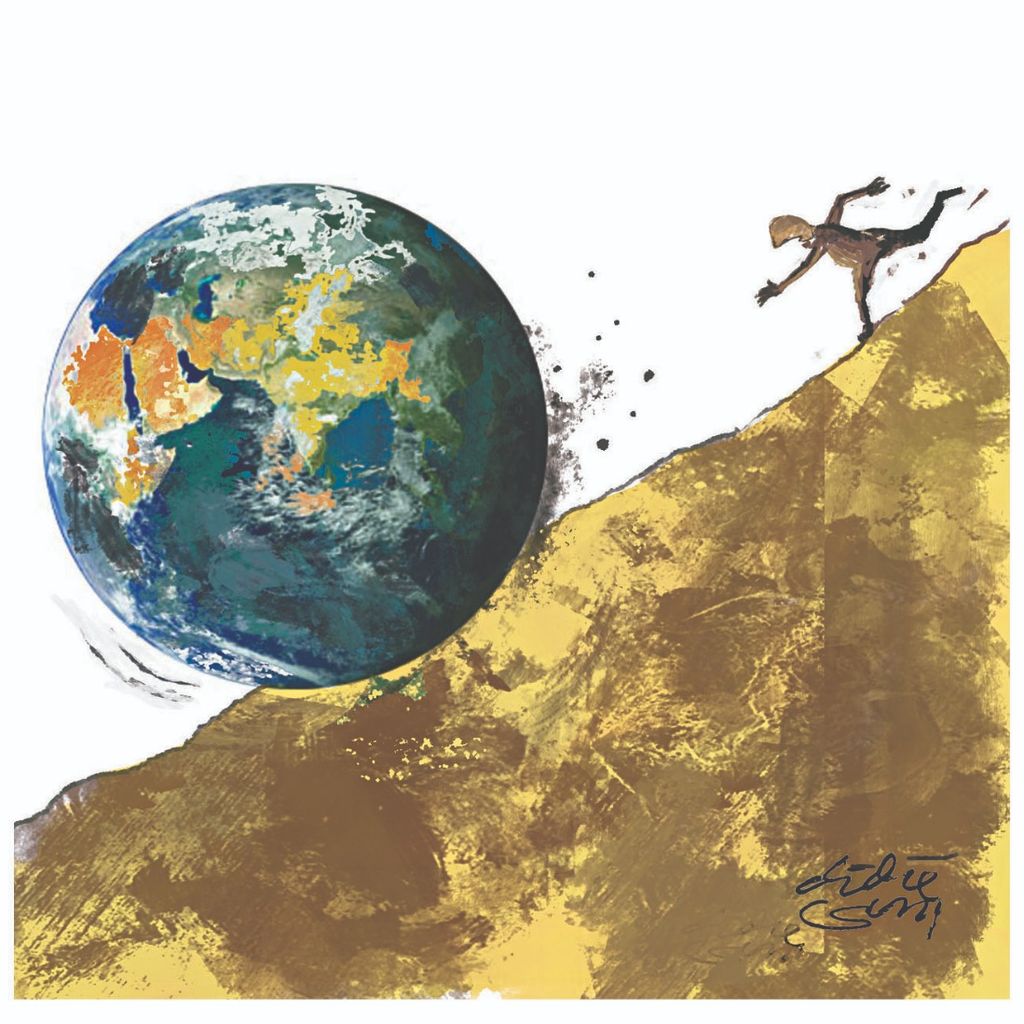
Didie SW
Ruang itu hening. Yang terdengar hanya suara goresan kapur di papan tulis. Pria di depan kelas itu sibuk menuliskan beberapa persamaan matematika.
Tubuhnya agak tambun, rambutnya tak tersisir rapi. Dengan aksen Australia yang kental ia menjelaskan berbagai teorema (proposisi) ekonometri yang ditulisnya. Kami semua terdiam, tak sepenuhnya paham.
Sebagian dari kami—setidaknya saya—pura-pura sibuk mencatat. Adrian Pagan memang nama besar dalam ekonometri. Ia datang memberikan kuliah di kelas ekonometri yang diampu bekas mahasiswanya, Trevor Breusch, di Australian National University (ANU), Canberra, waktu itu. Sebelumnya, saya hanya mengenal nama keduanya dari buku teks ekonometri: Breusch-Pagan test.
Saya tak tahu apakah saya beruntung atau tidak, mengambil kelas dua ahli ekonometri dunia itu. Namun yang justru saya ingat dari Pagan adalah ceritanya tentang salah satu pembimbing tesisnya: Alban William Housego Phillips, yang pindah dari London School of Economics lalu mengajar di ANU tahun 1967. Phillips—yang pernah tergabung dalam Angkatan Udara Inggris—pernah tiga tahun ditawan Jepang di Batavia (Jakarta) dan Bandung. Mungkin karena itu minatnya terhadap Asia cukup besar.
Melalui kurva Phillips, ia menjelaskan bahwa ada trade off (efek saling meniadakan) antara pengangguran dan inflasi dalam jangka pendek.
Kurva Phillips di AS
Nama Phillips kembali muncul di hari-hari ini. Ekonom, pelaku pasar keuangan, dan para pembuat kebijakan ekonomi kembali membahas studi seminalnya. Kita mengenalnya dengan terminologi Phillips Curve (Kurva Phillips). Melalui Kurva Phillips, ia menjelaskan bahwa ada trade off (efek saling meniadakan) antara pengangguran dan inflasi dalam jangka pendek.
Maksudnya: dalam jangka pendek, jika tingkat pengangguran rendah, inflasi akan tinggi, dan sebaliknya. Saya perlu menekankan aspek jangka pendek, karena ekonom Milton Friedman dan Edmund Phelps menunjukkan: dalam jangka panjang, tidak ada trade off antara pengangguran dan inflasi.
Konsep ini membutuhkan perhitungan kuantitatif cukup rumit, tetapi logika di balik itu sederhana. Begini: dalam situasi ekonomi yang tumbuh karena meningkatnya permintaan, dunia usaha akan melakukan ekspansi bisnis. Ia membutuhkan tambahan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja akan meningkat. Tingkat pengangguran akan menurun.
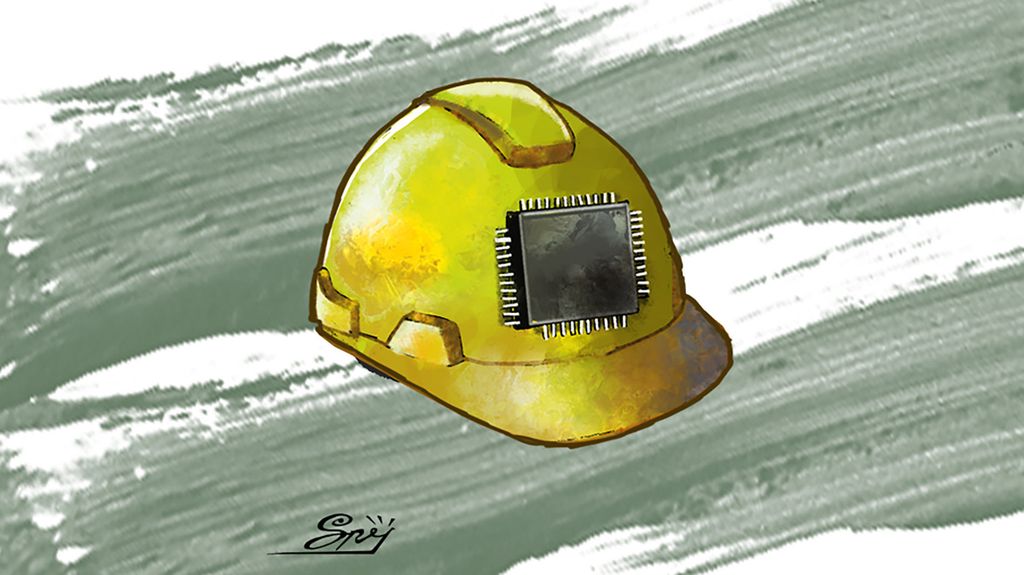
Supriyanto
Namun di sisi lain, kenaikan permintaan tenaga kerja akan mendorong kenaikan tingkat upah. Kenaikan upah ini akan mendorong kenaikan harga (inflasi). Inilah ciri dari perekonomian yang memanas (overheated). Implikasinya: dalam jangka pendek, ketika pengangguran menurun, tingkat inflasi akan naik, dan sebaliknya. Inilah esensi Kurva Phillips. Kurva Phillips—dalam versi modernnya—menunjukkan inflasi akan dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi, deviasi dari tingkat pengangguran dengan tingkat pengangguran alami atau NAIRU (non accelerating inflation rate of unemployment) dan supply shocks.
AS sekarang menghadapi situasi ini. Pengangguran mencapai tingkat terendah dalam 50 tahun terakhir (3,6 persen), tetapi inflasi juga tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Itu sebabnya, Kurva Phillips dibahas kembali. Larry Summers, guru besar ekonomi Harvard Kennedy School, sejak 2021 sudah mengingatkan risiko tekanan inflasi akibat ekonomi yang memanas. Di AS, NAIRU dianggap sekitar 5 persen. Jika pengangguran di bawah 5 persen, inflasi akan meningkat akibat ekonomi yang memanas, dan jika pengangguran di atas 5 persen, maka inflasi akan menurun.
Dalam sebuah konferensi di London School of Economics, Summers mengatakan, ”Untuk mengatasi inflasi, kita membutuhkan tingkat pengangguran di atas 5 persen selama lima tahun. Dengan kata lain, kita membutuhkan tingkat pengangguran 7,5 persen selama dua tahun; atau pengangguran 6 persen selama lima tahun, atau tingkat pengangguran 10 persen dalam satu tahun.”
Larry Summers, guru besar ekonomi Harvard Kennedy School, sejak 2021 sudah mengingatkan risiko tekanan inflasi akibat ekonomi yang memanas.
Sebuah pernyataan yang mematahkan semangat. Artinya, menurut Summers, AS membutuhkan resesi ekonomi untuk mengatasi inflasinya. Tak heran ia mendorong The Fed bertindak agresif menaikkan bunga. Kenaikan bunga akan menurunkan permintaan, yang pada gilirannya menurunkan inflasi. Tentu ada yang harus dikorbankan: pertumbuhan ekonomi. Summers tak sendirian.
Ekonom Harvard lainnya, Jason Furman, yang pernah menjadi chairman Council of Economic Advisers Presiden Obama, juga menunjukkan, tingkat upah riil mengalami penurunan akibat inflasi melonjak. Cara terbaik membuat upah riil meningkat, bukanlah dengan menaikkan upah nominal, melainkan menurunkan inflasi. Itu sebabnya, baik Summers maupun Furman melihat pentingnya upaya mengatasi inflasi
Implikasi bagi Indonesia
Lalu apa implikasinya bagi Indonesia? Apa yang harus dilakukan pemerintah dan BI? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pertumbuhan ekonomi di AS mengalami kontraksi dua triwulan terakhir. Artinya, secara teknis, AS memasuki resesi. Namun yang perlu dicatat, kontraksinya menurun. Karena itu, kita harus menunggu pertumbuhan triwulan III. Jika Summers benar, bahwa AS membutuhkan pengangguran di atas 5 persen selama lima tahun, kita akan melihat perlambatan ekonomi global. Resesi di AS akan menurunkan permintaan barang impor di AS.
Baca juga: Resesi sebagai ”Obat Keras” Inflasi Dunia
Implikasinya, ekspor ke AS, baik dari Eropa, China, maupun negara berkembang, termasuk Indonesia, akan melambat. Bisa diduga, perlambatan ekspor akan membuat pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara melambat, termasuk China. China memainkan peran penting bagi Indonesia, karena permintaan terhadap energi dan komoditas banyak berasal dari China. Jika pertumbuhan China melambat, permintaan energi dan komoditas akan menurun, harganya juga menurun. Kita mencatat, ancaman resesi menurunkan permintaan akan energi, termasuk minyak mentah.
Turunnya harga minyak mengakibatkan menurunnya permintaan akan biofuel, akibatnya kita mulai melihat harga sawit turun tajam. Tentu perlu dicatat, di sisi lain perang Ukraina membawa dampak kenaikan harga energi dan komoditas. Ada dua kekuatan tarik-menarik di sini. Akhirnya, harga energi dan komoditas akan ditentukan oleh dampak neto dari penurunan harga—akibat resesi—dan kenaikan harga akibat perang Ukraina. Jika perlambatan ekonomi global, khususnya China terjadi, Indonesia harus bersiap mengantisipasi penurunan ekspor. Artinya, ada risiko salah satu mesin pertumbuhan kita terganggu.

Kedua, dalam kondisi di mana ekspor terganggu, Indonesia harus mengandalkan dirinya pada sumber pertumbuhan domestik. Persoalannya ini tak mudah. Mengapa? Kita mungkin akan menghadapi kontraksi fiskal dan moneter secara bersamaan. Dari sisi moneter, kita melihat inflasi merangkak naik. BPS baru saja mengumumkan: inflasi mencapai 4,94 persen (Juli 2022), lebih tinggi dari target BI. Sebenarnya angka ini relatif rendah dibandingkan banyak negara lain seperti AS saat ini. Namun, kita perlu mencatat: inflasi harga produsen (IHP) sudah 9,06 persen kuartal I-2022.
Artinya, walau biaya produksi sudah naik, produsen belum membebankan sepenuhnya ke konsumen. Mungkin karena daya beli masih lemah. Yang dilakukan produsen, mengurangi margin keuntungannya. Ini tak bisa selamanya.
Satu saat harga harus dinaikkan. Terjadilah apa yang disebut inflation overhang (inflasi yang menggantung). Pelaku pasar menyadari, dengan IHP jauh lebih tinggi dari IHK, inflasi di level konsumen pun akan meningkat ke depan, begitu juga inflasi inti (core inflation). Artinya, ekspektasi inflasi akan meningkat. Kebijakan moneter amat sangat dipengaruhi ekspektasi inflasi. Dalam kondisi ini, BI dihadapkan pada dilema tak mudah.
Kebijakan moneter amat sangat dipengaruhi ekspektasi inflasi.
Apabila BI terlambat menaikkan bunga (behind the curve), mungkin BI harus mengejar keterlambatan ini dengan menaikkan bunga secara agresif tahun depan. Kita bisa membayangkan jika ini terjadi, kombinasi dari pengetatan giro wajib minimum (GWM) dan kenaikan bunga yang tajam akan memukul investasi. Sebenarnya, pengetatan GWM akan menaikkan bunga secara tak langsung tanpa BI menaikkan policy rate.
Pengetatan GWM akan menekan likuiditas. Untuk bank skala besar, ruang likuiditas mungkin masih agak lapang. Namun untuk bank skala relatif kecil, pengetatan likuiditas akan memaksa mereka memobilisasi dana. Caranya, menaikkan bunga. Jadi walau BI tak menaikkan BI Rate, saya tak akan terkejut, bila bank-bank ukuran kecil mulai menaikkan bunga. Alternatif kebijakan bagi BI, melakukan forward guidance (sinyal ke depan) pengetatan siklus moneter dengan menaikkan bunga. Ini dibutuhkan untuk menjaga jangkar ekspektasi inflasi. Tapi ada yang harus dikorbankan: pertumbuhan ekonomi tahun ini.
Ketiga, dari sisi fiskal kita melihat APBN semester I-2022 malah mengalami surplus atau prosiklus. Penyebabnya windfall (rezeki nomplok) karena kenaikan harga energi dan komoditas. Pertanyaannya apakah windfall ini bisa dimanfaatkan untuk kontrasiklus?

Seperti pernah saya tulis di harian ini (2/6/2022), kenaikan harga pangan berisiko memukul kelompok rentan, jatuh ke dalam kemiskinan. Prioritas kebijakan fiskal harus diberikan untuk membantu mereka yang rentan. Bagaimana jika windfall income digunakan untuk menambal subsidi BBM dan listrik?
Di sini kita harus hati-hati. Suatu hari, bom komoditas dan energi akan berakhir. Namun subsidi BBM dan listrik—yang berbeda dengan BLT yang sifatnya sementara—secara politis sulit dicabut. Benar bahwa beban subsidi akan berkurang jika bom SDA berakhir. Namun itu artinya, penurunan belanja mengikuti penurunan penerimaan negara. Ia bersifat prosiklus. Ruang fiskal tetap tak bertambah dan kemampuan mendorong pertumbuhan terbatas.
Di sisi lain, kita tahu, penerimaan negara bersifat fluktuatif jika bersumber pada SDA. Sebaliknya belanja cenderung stabil atau meningkat. Artinya, ketika penerimaan turun dan belanja tetap, defisit fiskal akan meningkat. Padahal kita ingin mengembalikan defisit anggaran ke 3 persen di 2023. Artinya pemerintah harus memotong belanja produktif, melakukan kontraksi fiskal, pada saat yang sama BI juga harus menaikkan bunga akibat tekanan inflasi.
Baca juga: ”Boom” Komoditas dan Energi, Pedang Bermata Dua
Pertumbuhan melambat
Dengan gambaran ini kita melihat bahwa sumber pertumbuhan domestik, seperti investasi dan pengeluaran pemerintah, juga akan melambat. Apabila mesin pertumbuhan eksternal dan internal melambat, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan melambat.
Apakah kita akan resesi? Menurut saya tidak. Tapi pertumbuhan akan melambat. Kita tak boleh lengah. Amunisi kita terbatas. Karena itu, prioritas kebijakan jadi penting. Tak bisa semua hal dilakukan. Dalam hal ini, windfall dari komoditas dan energi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tambahan pendapatan ini harus dialokasikan untuk pembangunan yang inklusif, tepat sasaran, dan sektor yang punya dampak besar untuk pertumbuhan ekonomi.
Indonesia memang tak semuram AS atau Eropa, tapi begitu banyak ketidakpastian, begitu banyak hal yang kita tak tahu di depan. Ada baiknya kita mengingat apa yang dikatakan ekonom Paul Samuelson, What we know about the global financial crisis is that we don’t know very much.
Muhamad Chatib BasriPengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2018%2F02%2F23%2F7dd5ca98-8284-4fa2-bd98-c12f2d195a5d_jpg.jpg)
Muhamad Chatib Basri