Menilik RKUHP dari Lensa Demokrasi Konstitusional
Rancangan KUHP yang nanti menjadi hukum pidana diharapkan bukan menjadi instrumen hukum yang efektif dalam memangkas demokrasi konstitusional di Indonesia. Karena itu, ruang partisipasi masyarakat menjadi krusial.
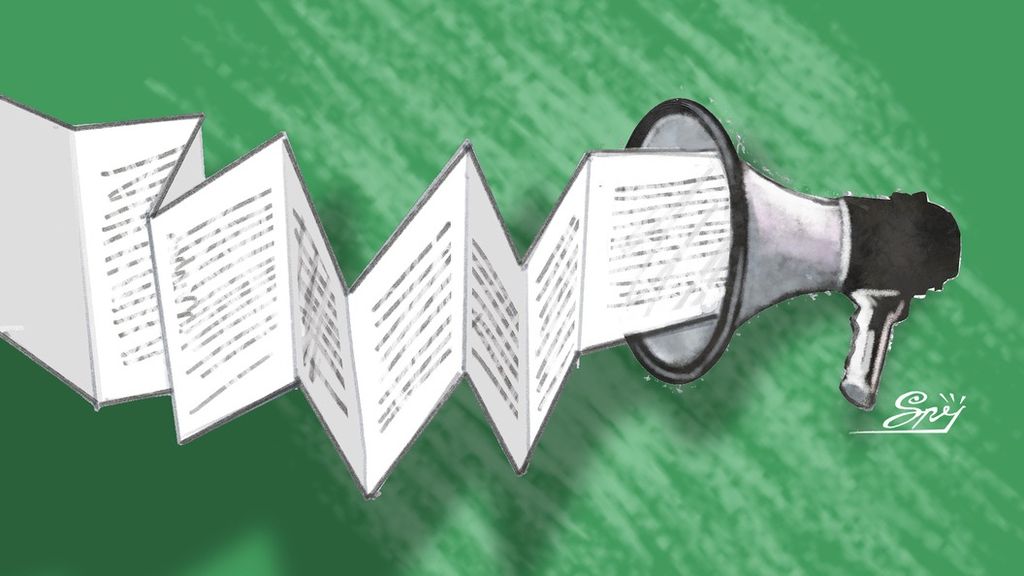
Ilustrasi
Proses pembentukan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP merupakan kebijakan hukum prestisius pemerintahan Presiden Joko Widodo yang bersandingan dengan kebijakan hukum prestisius lain, seperti UU KPK, UU Cipta Kerja, dan UU Ibu Kota Negara. Sifat prestisius tersebut juga dipengaruhi konteks kesejarahan, bahwa pembentukan RKUHP telah memakan waktu panjang, dari masa kepresidenan Soekarno yang dimulai pada tahun 1963 hingga masa kepresidenan Jokowi.
Sifat prestisius tersebut juga tercantum dalam empat misi utama RKUHP, sebagaimana tercantum dalam bagian penjelasan (versi September 2019). Bertolak dari keempat misi RKUHP tersebut, misi demokratisasi hukum pidana menjadi isu sentral dalam tulisan ini. Hal ini berkaitan sejauh mana nanti misi tersebut selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis.
Namun, meskipun RKUHP mengusung misi yang mengarahkan pada semesta pembangunan hukum nasional, secara praktik pembentukan dan substansi merefleksikan pesan yang mengabaikan prinsip supremasi konstitusi, partisipasi publik, dan kehatian-hatian, antara lain sebagai berikut. Pertama, terhambatnya masyarakat dalam mengakses draf RKUHP terbaru. Kedua, terbatasnya ruang partisipasi masyarakat di dalam pembahasan, meskipun pemerintah berdalil telah melakukan sosialisasi.
Baca juga : ”Hukum yang Hidup” dalam Rancangan Hukum Pidana
Terakhir, masih terdapat nuansa antidemokrasi dalam RKUHP (versi September 2019), antara lain dalam Pasal 240, 241, 353, dan 354. Keempat pasal tersebut secara garis besar menempatkan penghinaan terhadap pemerintahan yang sah serta penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara sebagai suatu perbuatan yang dilarang. Di sisi lain, yang membedakan pasal-pasal tersebut dengan Pasal 154 KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) adalah dihapusnya istilah permusuhan dan kebencian.
Lalu perbedaan lain, pembentuk RKUHP menempatkan delik materiil sebagai titik tumpu dalam keempat pasal tersebut. Oleh karena itu, akibat yang ditimbulkan dari adanya penghinaan terhadap pemerintah yang sah, kekuasaan umum, dan lembaga negara, yaitu kerusuhan dalam masyarakat, menjadi unsur penting.
Selain itu juga, penempatan delik aduan dalam Pasal 353 merupakan pembeda dengan Pasal 154 KUHP. Namun, secara keseluruhan apabila diteropong lebih jauh, keempat pasal tersebut tetaplah merupakan batu sandungan dalam terwujudnya ekosistem demokrasi konstitusional, di mana kemerdekaan berpendapat baik secara lisan maupun tulisan adalah unsur yang mendasar.

Catatan penting
Karena itu, kemunculan kembali wacana pengesahan RKUHP dalam waktu dekat ini, yakni bulan Juli, sebagaimana dipublikasi harian Kompas, ”DPR Kebut Pembahasan, RKUHP Ditargetkan Bulan Juli” (24/5/2022), perlu mendapat perhatian khusus dalam ruang publik. Oleh karena itu, tulisan ini akan memberikan tiga catatan penting yang menggarisbawahi seberapa konsisten misi demokratisasi hukum pidana, di mana tidak hanya diartikan bahwa hukum pidana yang dihasilkan sejalan dengan demokrasi, tetapi prosedur yang dijalankan dalam pembentukan juga senapas dengan prosedur yang demokratis.
Baca juga : DPR Kebut Pembahasan, RKUHP Ditargetkan Disahkan Juli
Catatan pertama, terkait akses masyarakat dalam memperoleh draf RKUHP terbaru pasca-pembahasan 14 isu krusial perubahan substansi RKUHP. Sejatinya, akses terhadap rancangan undang-undang (RUU) merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak warga negara untuk mendapatkan informasi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945.
Selain itu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), draf RKUHP merupakan informasi publik yang tidak berhubungan dengan informasi yang dikecualikan. Dalam arti lain, bukan informasi yang dapat membahayakan negara. Karena itu, tidak terbukanya akses terhadap draf RKUHP terbaru adalah suatu kondisi yang tidak selaras dengan jaminan dalam UUD 1945 dan UU KIP.
Akses terhadap rancangan undang-undang merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak warga negara untuk mendapatkan informasi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945.
Catatan kedua, ketentuan penghinaan terhadap pemerintah dan tindak pidana terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara kepada masyarakat sejatinya telah menyentuh eksistensi struktur dasar negara hukum demokratis. Laporan harian Kompas yang berjudul ”Buka Partisipasi Publik Bermakna dalam Pembahasan RKUHP di DPR" (Kompas.id, 16/6/2022) menunjukan adanya pasal-pasal yang belum dikomunikasikan kepada masyarakat di luar 14 pasal-pasal krusial yang sudah disampaikan pemerintah, antara lainnya Pasal 240, 241, 353, dan 354.
Apabila kita meneropong lebih jauh keempat pasal tersebut, secara mendasar telah menandakan adanya suatu konsep tersembunyi, yakni adanya pertautan yang kuat antara politik dan hukum. Konstruksi pasal-pasal tersebut mengarahkan hukum pidana yang dibentuk bertujuan untuk memastikan praktik politik diarahkan sebagai perilaku yang benar. Tentu menjauhi gravitasi demokrasi yang bercirikan pandangan liberal. Dalam hal ini, tindakan penghinaan terhadap pemerintah, kekuasaan umum, dan lembaga negara adalah praktik politik yang harus ditaklukkan.
Martin Loughlin dalam Sword and Scales (2000) memberikan suatu gambaran atas hubungan politik dan hukum. Bahwa hukum menunjukkan dirinya sebagai seperangkat prinsip dasar yang menyediakan kerangka kerja bagi politik yang akan dijalankan. Dengan demikian, hukum mengungkapkan suatu landasan rasional dan memiliki legitimasi yang mengatur atau menetapkan prasyarat pelaksanaan politik.

Maka, apabila Pasal 240, 241, 353, dan 354 tetap dipertahankan oleh pembentuk UU, misi yang diemban RKUHP, seperti demokratisasi hukum pidana, pada akhirnya nanti akan menemukan jalan buntu di kemudian hari dan menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem demokrasi konstitusional.
Dampak tersebut berupa kondisi kemunduran dalam demokrasi konstitusional. Studi Azis Huq dan Tom Ginsburg (”How to Lose a Constitutional Democracy”, 2018) memberikan analisis kemunduran demokrasi sebagai proses pembusukan yang berjalan secara bertahap.
Dalam konteks keempat pasal RKUHP tersebut, itu akan berdampak pada penurunan kualitas pada hak berbicara atau berpendapat. Ketika kemunduran tersebut semakin dalam,hal itu akan mengurangi kinerja demokrasi serta menyusutnya ruang publik, lalu disusul dengan adanya pergeseran demokrasi liberal konstitusional ke arah demokrasi non-liberal konstitusional.
Apabila Pasal 240, 241, 353, dan 354 tetap dipertahankan oleh pembentuk UU, misi yang diemban RKUHP, seperti demokratisasi hukum pidana, pada akhirnya nanti akan menemukan jalan buntu.
Dalam studi Drinóczi & Bien-Kacala (”Illiberal Constitutionalism: The Case of Hungary and Poland”, 2018), memberikan pemetaan bergesernya rezim demokrasi liberal konstitusional di Hongaria dan Polandia, dimulai ketika menggunakan instrumen hukum yang memiliki legitimasi, lalu memangkas pilar-pilar demokrasi konstitusional, seperti prinsip negara hukum demokratis, HAM, dan kebebasan sipil menjadi tidak mutlak, dengan tetap mempertahankan ciri demokrasi konstitusional secara formal. Dalam konteks Polandia, upaya pembentukan ekosistem demokrasi nonliberal konstitusional telah melahirkan suatu peran negara yang semakin kuat dalam relasinya dengan warga negara.
Catatan terakhir terkait partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pembahasan RKUHP. Dalam hal ini, pasca-Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020, doktrin partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) sebagaimana menjadi ratio decidendi Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pengujian UU Cipta Kerja telah menjadi mantra kuat masyarakat sipil dalam mengawasi jalannya pemerintahan terhadap pembentukan kebijakan.
Apabila ditelusuri lebih dalam doktrin tersebut, terkandung tiga prasyarat agar partisipasi yang bermakna dapat terimplementasi. Pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya. Kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya. Terakhir, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.
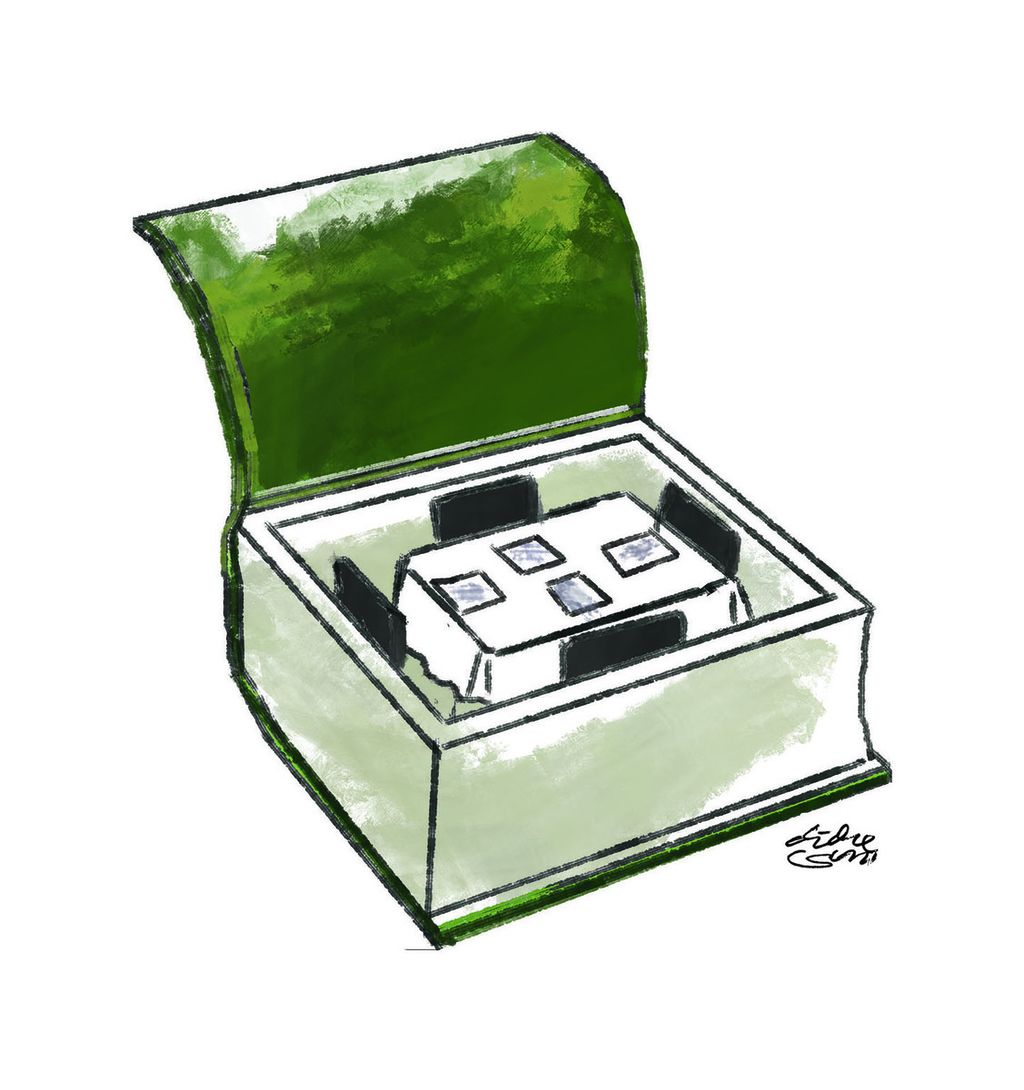
Dengan demikian, semakin terpenuhinya unsur ketiga prasyarat tersebut, akan terbentuk komunikasi yang efektif antara masyarakat, DPR, dan pemerintah. Berangkat dari komunikasi efektif tersebut, kita dapat menghasilkan hukum pidana nasional yang memiliki legitimasi politik dan hukum.
Lalu, memenuhi nilai rasionalitas, imparsial, fair, dan konsisten terhadap prinsip demokrasi dan HAM serta memiliki daya tahan terhadap perubahan dinamika masyarakat. Selain itu, secara tidak langsung doktrin meaningful participation turut serta mencegah menyusutnya ruang publik, sebagai dampak dari tertutupnya ruang partisipasi dan menguatnya kekuasaan negara atas masyarakat.
Baca juga : Buka Partisipasi Publik Bermakna dalam Pembahasan RKUHP di DPR
Sebagai penutup, misi demokratisasi hukum pidana merupakan misi yang berat dan krusial. Hal ini berkaitan dengan adanya beban bahwa hukum pidana nasional di masa depan tidak mencederai prinsip negara hukum demokratis, HAM, dan kebebasan sipil.
Dalam arti yang krusial, RKUHP yang nanti menjadi hukum pidana diharapkan bukan menjadi instrumen hukum yang efektif dalam memangkas demokrasi konstitusional di Republik Indonesia. Oleh karena itu, ruang partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan masukan menjadi krusial karena berdampak langsung terhadap perbaikan RKUHP agar menjadi hukum yang konsisten terhadap prinsip demokrasi dan HAM serta turut menyempurnakan semesta pembangunan hukum nasional.
D Nicky Fahrizal, Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta