Kecerdasan Buatan dan Masa Depan Kemanusiaan
Agen robotik bernama Gato disebut-sebut sebagai awal lahirnya teknologi kecerdasan buatan yang mampu menyamai kecerdasan manusia. Yang perlu diwaspadai, teknologi kecerdasan buatan tak menjadi bumerang bagi kemanusiaan.
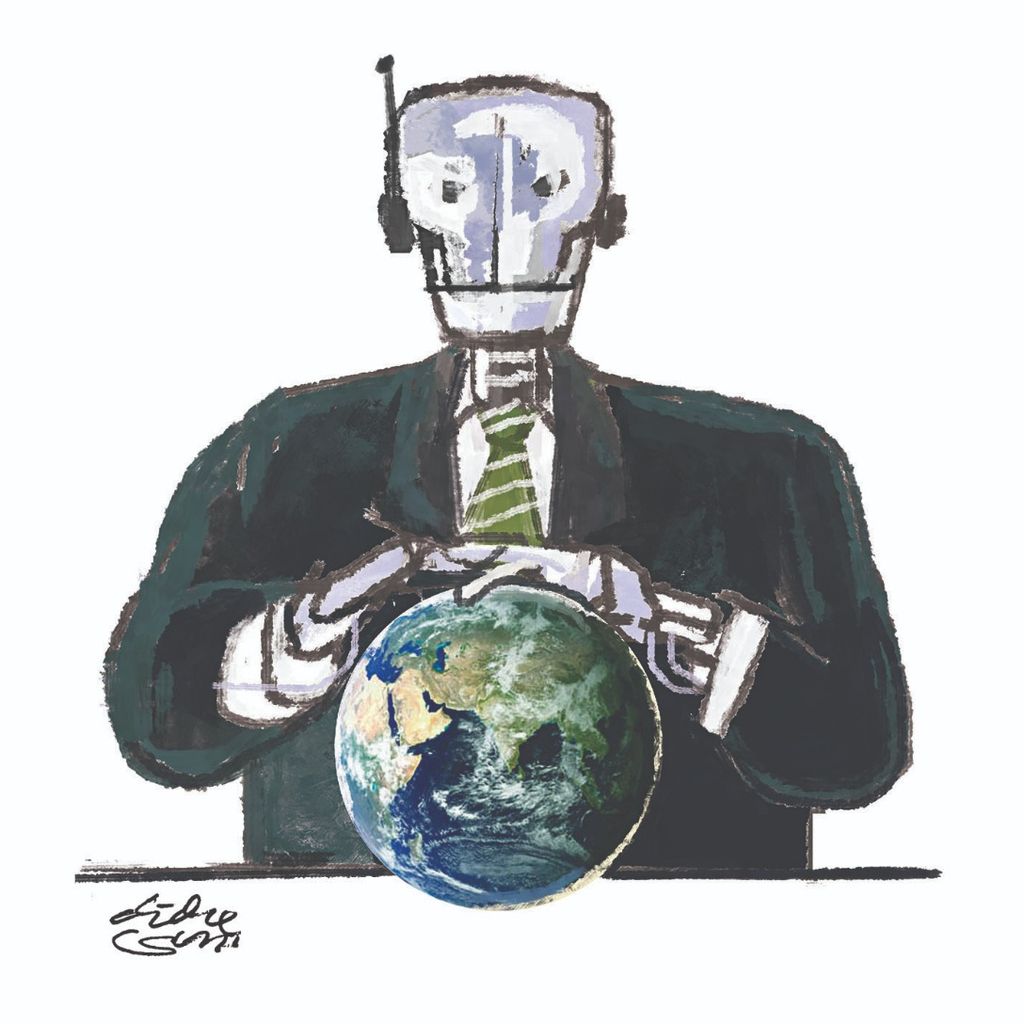
Pada 12 Mei 2022, dua puluh peneliti dari DeepMind, sebuah perusahaan teknologi yang berusaha mengembangkan teknologi kecerdasan buatan, menerbitkan laporan perihal perkembangan mutakhir dari apa yang telah mereka upayakan selama ini.
Dalam makalah yang berjudul ”A Generalist Agent” itu, mereka melaporkan bahwa mereka telah berhasil menciptakan sebuah agen robotik yang dinamai Gato, yang mampu melakukan banyak tugas seperti halnya manusia, mulai dari bermain gim video, memberi keterangan gambar, mengobrol, menata batu, hingga memberikan respons teks sesuai konteks.
Terciptanya Gato disebut-sebut merupakan awal bagi lahirnya teknologi kecerdasan buatan yang mampu menyamai tingkat kecerdasan manusia.
Menanggapi pendapat orang yang pesimistis terhadap pengembangan Gato, Nando de Freitas, Direktur Riset DeepMind, bahkan mengatakan di akun Twitter-nya: ”The Game is Over! It’s about making these models bigger, safer, compute efficient, faster at sampling, smarter memory, more modalities” (Semua sudah selesai! Ini tinggal membuat modelnya lebih besar, lebih aman, bisa berhitung secara efisien, lebih cepat dalam membuat sampel, memorinya lebih pintar, dengan modalitas yang lebih banyak).
Diskursus soal kecerdasan buatan ini sejak awal memang dibangun dengan standar manusia.
Tantangan untuk kemanusiaan
Secara sekilas, proyek kecerdasan buatan itu memang tampak merupakan ”ancaman” bagi masa depan manusia.
Bayangkan, ada robot yang tersinggung oleh ucapan atau tindakan kita dan, karena ia tidak dilengkapi oleh program moral untuk memaafkan kesalahan-kesalahan kecil, ia tiba-tiba menggampar kita dari belakang. Berapa banyak orang yang akan tiba-tiba digampar oleh robot yang dipekerjakan sebagai penjaga toko hanya karena mereka menawar barang terlalu murah.
Diskursus soal kecerdasan buatan ini sejak awal memang dibangun dengan standar manusia. Turing Test, misalnya, yang didesain oleh Alan Turing untuk menguji kecerdasan mesin, menjadikan ketakberbedaannya dari manusia sebagai standar. Artinya, jika kita tidak mampu lagi membedakan mana perilaku mesin dan mana perilaku manusia, berarti mesin di situ memiliki kecerdasan yang sama dengan manusia.
Baca juga Membaca Peluang pada Era Kecerdasan Buatan
Dengan kata lain, mesin dikatakan cerdas jika dan hanya jika ia mampu mengimitasi perilaku manusia sehingga kita yang mengamati tidak lagi mampu membedakannya. Dengan standar ”imitasi” tersebut, proyek kecerdasan buatan seolah-olah memang didesain untuk menyaingi, atau bahkan menggantikan, posisi manusia. Mesin diproyeksikan bisa mengerjakan banyak pekerjaan yang sama dengan lebih baik daripada manusia.
Bayangkan, berapa banyak tenaga kerja yang akan jadi penganggur jika roda ekonomi dunia sebagian besar sudah bisa digerakkan mesin. Ini akan menjadi satu distopia tersendiri bagi masa depan para pekerja.
Tantangan untuk filsafat
Selain untuk kemanusiaan, perkembangan mutakhir kecerdasan buatan juga memberikan tantangan untuk filsafat sebagai sebuah disiplin ilmu yang memikirkan banyak sekali hal. Untuk merespons tantangan itu, sekarang sudah muncul cabang baru filsafat yang disebut ”Filsafat Kecerdasan Buatan” (Philosophy of Artificial Intelligence).
Dalam konteks keilmuan, perkembangan teknologi kecerdasan buatan ini mendesakkan pertanyaan-pertanyaan baru yang belum pernah muncul sebelumnya dalam sejarah filsafat: apa itu hakikat kecerdasan? Apakah beda status ontologis kecerdasan alamiah (natural intelligence) yang dimiliki oleh spesies manusia dan kecerdasan buatan yang dimiliki oleh mesin?
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2021%2F08%2F25%2F20210825-iLustrasi-ekonomi-9_color_1629899411_jpg.jpg)
Heryunanto
Apakah informasi yang diperoleh dari proses kerja kecerdasan buatan dapat disebut sebagai ”pengetahuan”? Apakah keputusan-keputusan moral yang didasarkan pada pemrosesan informasi oleh kecerdasan buatan juga mengandung satu imperatif etis yang harus dipatuhi? Apakah adanya kecerdasan menunjukkan adanya pikiran/kesadaran? Atau kecerdasan hanya soal perilaku dan pemrosesan informasi dan tak terkait dengan fenomena mental sama sekali?
Pertanyaan-pertanyaan itu adalah beberapa kawasan baru yang muncul akibat perkembangan kecerdasan buatan yang memerlukan telaah dan eksplorasi dari para filsuf.
Dalam diskursus Filsafat Kecerdasan Buatan saat ini, ada satu pembedaan dasar yang diterima secara cukup luas, yaitu pembedaan antara kecerdasan buatan versi kuat (strong AI) dan kecerdasan buatan versi lemah (weak AI).
Kecerdasan buatan versi kuat adalah satu program yang bertujuan untuk menciptakan mesin yang sepenuhnya bisa menyerupai manusia, termasuk aspek mentalnya. Artinya, kecerdasan buatan versi kuat ini tidak hanya pandai berhitung dan membuat keputusan strategis, tetapi juga bisa merasakan pengalaman batin layaknya manusia.
Kecerdasan buatan versi lemah, sebaliknya, bertujuan untuk menciptakan mesin pemroses informasi yang hanya tampak sama seperti manusia, tetapi hakikatnya tidak sama sebab ia tidak memiliki aspek mental dan kesadaran seperti halnya kita.
Kemampuan untuk memahami inilah yang tidak akan pernah bisa diimitasi oleh mesin.
Beberapa orang tampak optimistis bahwa kecerdasan buatan versi lemah ataupun kuat itu pasti dapat dicapai suatu saat nanti—jika bukan saat ini. Namun, seorang filsuf Amerika Serikat, John Searle, membuat satu eksperimen pikiran yang membuktikan bahwa kecerdasan yang kita miliki itu bukan sekadar kemampuan untuk menampilkan perilaku cerdas, melainkan juga kemampuan untuk memahami. Kemampuan untuk memahami inilah yang tidak akan pernah bisa diimitasi oleh mesin.
Komputer bisa saja menunjukkan perilaku cerdas dengan merespons permintaan kita secara tepat. Semisal, jika kita menanyakan sesuatu kepada komputer, ia bisa menjawab dengan benar. Namun, ia tidak akan pernah bisa memahami makna dari apa yang kita tanyakan dan juga jawaban yang ia sendiri berikan—persis seperti orang yang tidak paham bahasa Mandarin, tetapi bisa menjawab pertanyaan orang China berdasarkan buku panduan.
Komputer bekerja hanya sesuai program, seperti halnya orang yang tidak paham bahasa Mandarin itu menjawab pertanyaan tertulis orang China sesuai panduan. Keduanya sama-sama tidak paham dengan apa yang ia terima dan sampaikan meskipun mampu melakukan tugasnya dengan benar.
Eksperimen Searle itu menjadi tantangan tersendiri bagi proyek kecerdasan buatan: apakah kecerdasan komputer masih bisa disebut kecerdasan meskipun tidak disertai dengan pemahaman seperti halnya kecerdasan manusia?
Kolaborasi antardisiplin ilmu
Eksperimen Searle itu menjadi tantangan tersendiri bagi proyek kecerdasan buatan: apakah kecerdasan komputer masih bisa disebut kecerdasan meskipun tidak disertai dengan pemahaman seperti halnya kecerdasan manusia? Artinya, itu adalah interupsi filsafat untuk proyek kecerdasan buatan. Filsafat merespons balik; begitulah salah satu cara berfilsafat di tengah perkembangan teknologi yang semakin gila ini.
Dalam konteks itu, filsafat berfungsi sebagai kritik. Namun, filsafat bukan hanya sebagai kritik. Filsafat juga mesti bersifat konstruktif—dengan, misalnya, menawarkan gagasan atau menyelesaikan problem konseptual dalam proses pengembangan teknologi. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang saya sebutkan di atas, ada banyak sekali problem konseptual terkait pengembangan kecerdasan buatan yang perlu ditangani filsafat.
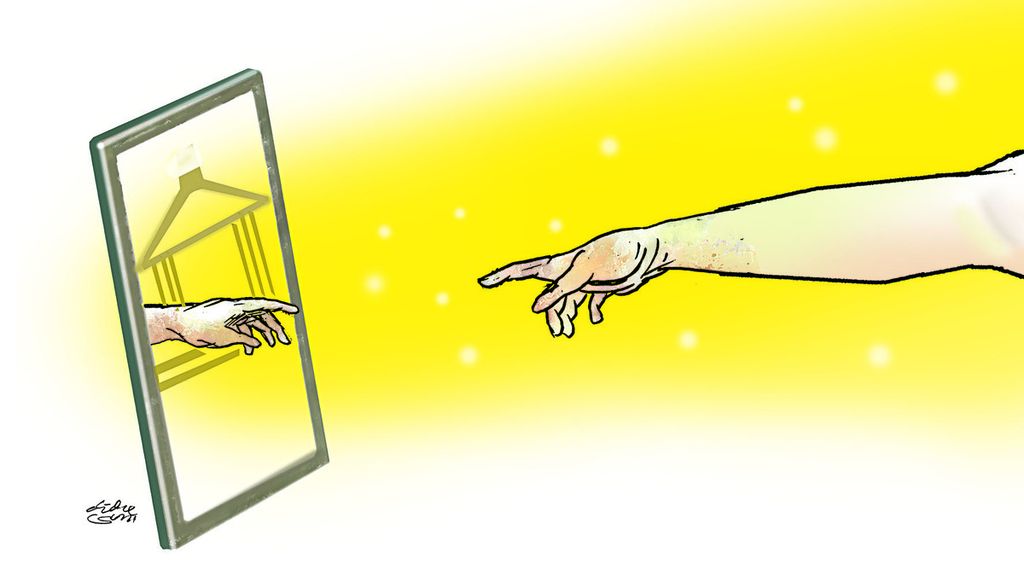
Didie SW
Oleh karena itu, agar pengembangan teknologi kecerdasan buatan ini tidak justru menjadi bumerang bagi kemanusiaan, filsafat perlu menjalankan fungsinya sebagai kritik dan sekaligus pemberi arahan konstruktif. Namun, untuk melakukan ini semua, filsafat juga perlu sadar bahwa ia tidak bisa bekerja sendirian. Filsafat perlu berkolaborasi dengan para ahli dari bidang-bidang ilmu lain, seperti psikologi, biologi, ilmu komputer, antropologi, dan sosiologi.
Dengan demikian, filsafat bisa menjadi ”jembatan ilmu-ilmu” seperti yang saya cita-citakan dan menjadi bagian pokok dari pembangunan ide ”universitas”: sebuah lembaga pendidikan yang menyatukan banyak ragam keilmuan.
Siti Murtiningsih,Dekan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada

Siti Murtiningsih