Krisis Lingkungan dalam Perubahan Peradaban
Perubahan peradabanlah yang yang mengubah lingkungan bergitu drastis. Peradaban baru yang bertumpu pada teknologi mekanik yang canggih memungkinkan lingkungan alam dieksplorasi dan dieskploitasi besar-besaran.

Supriyanto
Tanpa perilaku manusia pun lingkungan alam tidaklah diam, statis, dan final. Pasti akan mengalami perubahan, hanya geraknya relatif lambat, tidak begitu terasa, mungkin hasil perubahan itu baru akan terlihat setelah puluhan atau ratusan tahun. Akselerasi perubahan lingkungan alam lalu menjadi lebih cepat dan bahkan selanjutnya mengalami devaluasi dan degradasi karena kemudian banyak dicampuri ulah-tingkah manusia, terutama ketika potensi keserakahan manusia menemukan artikulasinya lewat penemuan dan pengembangan teknologi masinal.
Ketika kelompok manusia hidup dalam peradaban yang sederhana, katakanlah waktu masih menggunakan teknologi yang manual untuk mengolah dan mengelola sumber-sumber daya yang tersedia dalam lingkungan alam, perubahan lingkungan alam itu belumlah begitu besar dan arah perubahannya pun belum menuju ke penurunan nilainya. Ciri teknologi manual adalah kemampuannya yang terbatas dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam.
Masyarakat petani tradisional di Jawa, misalnya, dengan teknologi pertanian yang mereka kuasai, seperti cangkul, golok, dan bajak yang ditarik hewan, serta belum memakai pupuk kimiawi-biologi, mereka rada kesulitan untuk bisa memperluas lahan pertanian dan memperbesar jumlah produksi, sehingga mereka pun sukar untuk bisa mencapai surplus, kelebihan hasil produksi. Lewat teknologi sederhana yang dikuasainya mungkin petani hanya bisa mengubah lingkungan alam yang ada di sekelilingnya sekadar untuk pemenuhan kebutuhan atau bertahan hidup. Itulah yang dikategorikan sebagai pertanian subsistensi!
Baca juga: Angan-angan Lumbung Pangan
Saat masih dalam peradaban sederhana, jumlah penduduk Jawa pun belum banyak dan padat. Padahal, pemakaian teknologi untuk intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian itu apabila ingin sedikit mendapatkan hasil yang lebih hanya dimungkinkan dengan bantuan jumlah tenaga kerja yang banyak. Dengan jumlah penduduk yang masih sedikit, sementara sumber daya alam yang tersedia dan yang perlu diolah masih cukup ”melimpah”, jadinya memungkinkan hampir setiap orang dapat menguasai dan mengelola sumber daya alam tersebut, meski hasilnya masih jauh dari dapat meraih surplus.
Pada komunitas-komunitas petani tradisional di Jawa di masa lalu tentu akan ditemukan orang-orang serakah, yang ingin menguasai dan memiliki sumber daya alam yang lebih banyak serta ingin mengatasi posisi sosial-ekonomi warga masyarakat lainnya. Namun, mereka dihadapkan pada kendala untuk dapat mewujudkan keserakahan itu, yakni oleh perangkat teknologi pertanian dan jumlah tenaga kerja yang terbatas.
Dalam batas-batas tertentu, peradaban itu sendiri yang membatasi hasil dari pengelolaan dan pengolahan sumber daya alam, bukan karena tidak adanya manusia-manusia serakah.
Karena itu, dalam batas-batas tertentu, peradaban itu sendiri yang membatasi hasil dari pengelolaan dan pengolahan sumber daya alam, bukan karena tidak adanya manusia-manusia serakah. Keterbatasan teknologi, pengetahuan yang masih terbatas, serta jumlah dan kepadatan penduduk yang sedikit itulah yang menjadikan lingkungan alam relatif terpelihara, belum mengalami banyak degradasi dan disfungsional.

Petani di Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Selasa (18/9) sedang merawat tanaman kentang yang ditanam di tanah dengan kemiringan lebih dari 30 derajat. Nampak dari kejauhan lereng perbukitan di Dieng yang sudah gundul akibat penebangan hutan menjadi lahan pertanian semusim yang menyebabkan degradasi lahan.
Dinamika peradaban
Kira-kira sampai masa pra-kolonial, di wilayah-wilayah perdesaan Jawa umpamanya, masih cukup tersebar komunitas petani yang hidup dalam peradaban sederhana itu. Karena itu, lingkungan alam yang ada di sekeliling komunitas tersebut cukup terpelihara: gunung dan bukit terlihat hijau; hutan cukup lebat; sawah, kebun, atau ladang masih berada dekat dengan lingkungan permukiman petani. Meski musim kemarau sudah berlangsung agak lama persediaan air masih cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan mengairi tanaman; juga udara masih cukup bersih dan sejuk; serta longsor dan banjir bandang jarang terjadi; dan secara sosio-kultural masih dapat ditemukan petani-petani yang lugu dan konservatif.
Namun, ketika peradaban berubah, dan memang perubahan itu sendiri adalah suatu kepastian, terjadi dampak yang cukup drastis. Peradaban baru ini bertumpu pada teknologi mekanik yang canggih serta pengetahuan yang dilandasi disiplin keilmuan yang metodis (ilmu pengetahuan). Teknologi masinal dan canggih merupakan produk ilmu pengetahuan yang kapasitasnya jauh mengatasi teknologi manual.
Baca juga: Teknologi dan Kuasa di Tanah Raja
Melalui teknologi baru itulah kemudian lingkungan alam dieksplorasi dan dieskploitasi besar-besaran. Hasilnya tidak saja menjadi jauh lebih banyak, tetapi juga dialihbentukkan menjadi ragam komoditas yang dapat dipertukarkan dalam transaksi ekonomi di pasar-pasar lokal, nasional, dan bahkan global.
Inilah gerak peradaban industrial, di mana sumber-sumber daya alam, baik yang bisa diperbaharui maupun yang tidak, dikomodifikasikan. Sumber daya alam yang mentah diolah menjadi bahan baku dan kemudian menjadi bahan jadi yang bisa dijual, dibeli, atau dimiliki untuk dikonsumsi atau sekadar untuk simbol status. Kayu, bahan-bahan tambang, daun-daunan, biji-bijian, daging dan kulit binatang, dan banyak lagi, diolah, direkayasa, dan dikelola untuk diberi nilai ekonomi, lalu dipertukarkan di pasar.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F06%2F34d4d242-9807-427c-9fb6-ccbdc7111baf_jpg.jpg)
Nanas yang telah dipetik dari perkebunan berada di pabrik pengolahan PT Great Giant Pinneapple (GGP), Lampung Tengah, Lampung, Rabu (16/6/2021). Nanas menempati posisi pertama untuk ekspor buah nasional. Sentra nanas tersebar di sejumlah provinsi seperti Lampung, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Dalam peradaban industrial ekosistem ”alamiah” diubah secara masif menjadi perumahan, perkantoran, pabrik-pabrik, tempat-tempat rekreasi, jalan-jalan raya, kebun-kebun dan ladang-ladang yang terhampar sampai menuju ke puncak-puncak bukit, yang semua perubahan itu berfungsi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, baik untuk kepentingan perseorangan maupun kelembagaan. Itulah peradaban yang memang pada dirinya selalu ingin mengubah sesuatu, termasuk lingkungan alam beserta sumber-sumber daya yang terkandung di dalamnya, ke dalam satuan-satuan yang dapat memiliki nilai ekonomi tinggi.
Sudah tentu tanpa pengendalian yang ketat atas gerak peradaban industrial, lingkungan alam kian rusak dan kerusakan itu akan terus berkelanjutan, yang dampak besarnya adalah bencana. Dan, memang di banyak tempat di Jawa sudah sering dan banyak terjadi bencana.
Sudah tentu tanpa pengendalian yang ketat atas gerak peradaban industrial, lingkungan alam kian rusak dan kerusakan itu akan terus berkelanjutan, yang dampak besarnya adalah bencana.
Sekarang ini umpamanya, dalam satu tahun suatu wilayah bisa terkena banjir beberapa kali dan durasinya juga menjadi lebih lama. Banjir bandang juga kerap terjadi, yang memakan korban jiwa, sementara harta benda yang hilang tak terhitung, termasuk longsor juga sering menimbun perkampungan, tidak hanya satu dua rumah atau hanya menutup jalan.
Kemarau yang baru berlangsung sebentar saja telah membuat kali, telaga, dan mata air menjadi kering, sehingga tanaman-tanaman pertanian menjadi tidak dapat tumbuh secara semestinya, bahkan mengalami puso. Air untuk kebutuhan rumah tangga pun harus dicari di tempat-tempat yang jauh dari pemukiman.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2Ff08fd72a-4d8d-40ed-984f-ff6eea216af0_jpg.jpg)
Warga Desa Sirnajati, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mencuci pakaian di sisa aliran air Kali Cipamingkis, Kamis (22/8/2019). Bencana kekeringan akibat musim kemarau di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terus meluas. Dari lima kecamatan yang dilanda kekeringan, tiga kecamatan di daerah itu masuk kategori wilayah siaga darurat kekeringan. Ribuan warga di daerah itu krisis air bersih.
Keterlibatan negara
Seiring dengan gerak peradaban industrial yang memang pada dirinya serakah, ada suatu institusi yang bernama negara, yang pada dirinya negara ini sesungguhnya memiliki kuasa dan kewenangan untuk memaksa warga negaranya tunduk pada aturan-aturan formal-rasional yang dibuatnya. Karena itu, idealnya melalui negaralah keserakahan peradaban industrial bisa dikendalikan dan dalam penerapan kontrol itu aparat atau instansi negara yang diberi otoritas dan tugas khusus dapat mengatur dan memaksa warga negara atau kelompok masyarakat atau korporat untuk tidak secara sembarangan mengelola, mengeksploitasi, dan mengekstraksi sumber-sumber daya alam dan mengalihfungsikan fungsi ekosistem.
Namun sayangnya institusi negara ini, lebih khususnya para aparaturnya sebagai pelaksana eksekusi bagi warga negara yang melanggar peraturan, belum sepenuhnya konsisten mau dan dapat menerapkan aturan-aturan yang telah dibuatnya, malah di antara aparatur tersebut ada yang ikut terlibat dalam pengeksploitasian dan pengekstraksian sumber-sumber daya alam. Karena itu, secara tidak langsung, dalam kerusakan lingkungan alam ini pemerintah pun ikut terkait di dalamnya, apakah karena keterlibatan aparaturnya atau, sengaja atau tidak, ”membiarkan” warga masyarakat perseorangan atau kelompok menguras sumber-sumber daya alam secara serampangan.
Baca juga: Agama-agama yang Ramah Lingkungan
Nah, di situlah yang menjadi persoalannya, kenapa peradaban industrial ini dengan kasat mata telah menunjukkan kinerja keserakahannya yang merusak dan menjadikan lingkungan alam dalam kondisi yang amat kritis, karena pemerintah kurang memiliki konsistensi dalam menegakkan peraturan. Kalau demikian masalahnya karena secara bersamaan masyarakat dan pemerintah juga terlibat dalam prilaku keserakahan peradaban industrial, katakanlah menjadi bagian dari devaluasi, degradasi, dan bencana lingkungan, siapa yang harus bertindak?
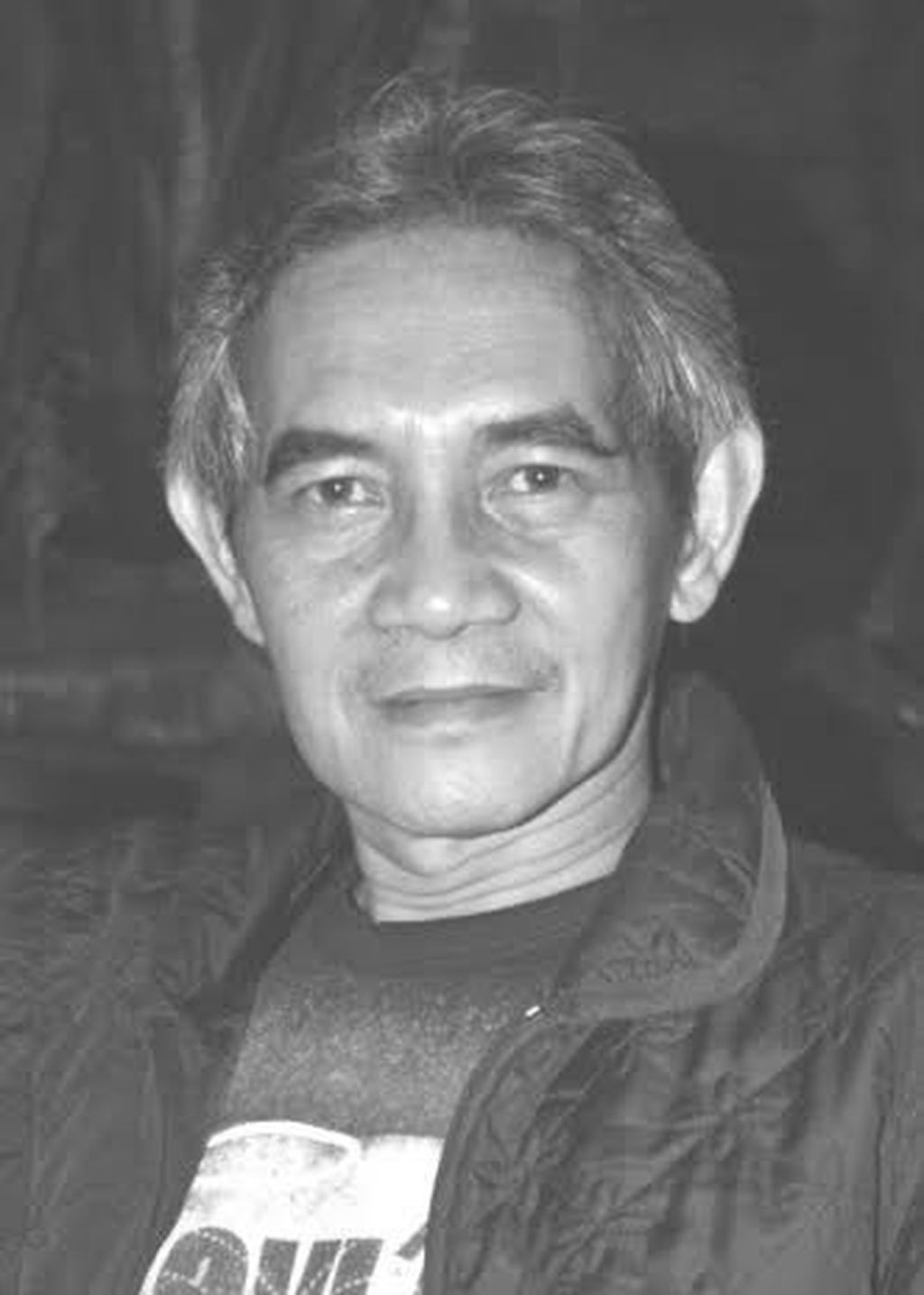
Budi Rajab
Idealnya, penyelesaian itu harus dikembalikan ke peran negara. Tetapi prasyaratnya, negara mesti menyelesaikan persoalan yang menghinggapi dirinya. Negara terlebih dahulu harus keluar dari keterlibatannya dalam gerak keserakahan peradaban industrial. Negara melalui pemerintahannya harus mau dan sanggup menempatkan dirinya dalam posisi sebagai pengontrol dan pelaksana eksekusi yang berpegang pada prinsip-prinsip dasar tentang fungsi lingkungan alam yang berkelanjutan.
(Budi Rajab, Pengajar di Jurusan Antropologi, FISIP Universitas Padjadjaran)