G-20 dan Momentum Transformasi
Presidensi G-20 harus dimanfaatkan untuk mempercepat transformasi ekonomi pascapandemi, terutama melalui perumusan strategi industrialisasi berbasis digital dan berperspektif lingkungan serta sistem pembiayaan hijau.
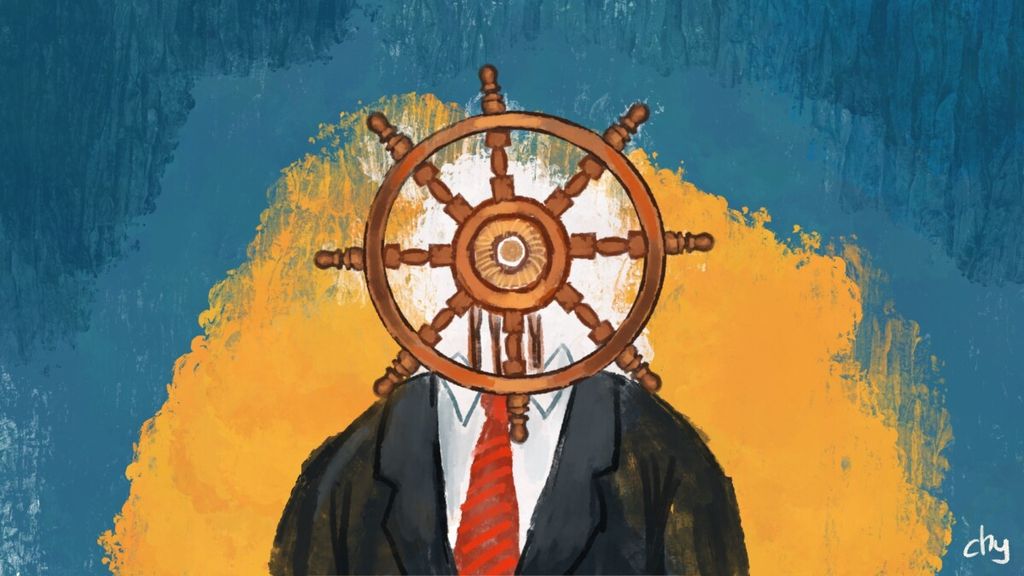
Heryunanto
Berita baik bagi satu negara bisa menjadi berita buruk bagi negara lain. Situasi inilah yang terjadi pada perekonomian global belakangan ini.
Pemulihan ekonomi di negara maju, seperti Amerika Serikat (AS), diiringi dengan peningkatan inflasi yang pada gilirannya akan diikuti pengetatan likuiditas. Dampaknya, pasar keuangan di negara berkembang berpotensi tertekan. Selain cenderung tidak merata dan diwarnai ketidakstabilan pasar keuangan, pemulihan global juga dihadapkan pada situasi ketidakpastian.
Memasuki akhir tahun, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kembali mengumumkan kemunculan varian baru SARS-CoV-2 dari Afrika dengan galur Omicron. Banyak negara kembali menutup perbatasan dan melakukan pengetatan mobilitas domestik.
Akibatnya, perekonomian kembali lesu dan prospek pertumbuhan 2022 menjadi serba tak menentu. Harga minyak di pasar global merosot tajam dan pasar keuangan kembali bergejolak. Minyak jenis Brent mengalami penurunan dari 82 dollar AS menjadi sekitar 70 dollar AS per barel.
Sementara itu, para investor mulai melepas kepemilikan saham perusahaan berbasis penerbangan, perhotelan, dan sektor lain terkait dengan pariwisata. Biaya logistik juga terus merangkak naik sehingga mendorong kenaikan harga barang kebutuhan konsumsi sehari-hari.
Pandemi telah mengakselerasi gejala proteksionisme yang sudah muncul di era-Trumpisme.
Penutupan jalur distribusi utama global, selain meningkatkan biaya logistik, juga mendorong perubahan peta rantai pasok global yang pada gilirannya akan meningkatkan biaya produksi. Pandemi telah mengakselerasi gejala proteksionisme yang sudah muncul di era-Trumpisme. Tampaknya, perekonomian ke depan akan diwarnai dengan pertumbuhan rendah yang disertai kenaikan harga (stagflasi) sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat menurun.
Dalam situasi seperti inilah, Indonesia memegang posisi presidensi negara kelompok dua puluh (G-20) sepanjang 2022. Berbagai tantangan global punya implikasi beragam (timpang) bagi negara anggota G-20. Karena itu, Indonesia harus mampu menjadi penyeimbang antara kelompok negara maju (G-7) dan kelompok negara berkembang yang berada dalam satu wadah G-20.
Ketimpangan
Munculnya varian Omicron menyadarkan kita adanya tantangan kesehatan yang bersifat jangka panjang. Tak tertutup kemungkinan setelah ini akan muncul varian berikutnya, pi, rho, sigma, dan lainnya. Sementara itu, kita tahu pemulihan ekonomi hanya mungkin terjadi jika pandemi bisa dikendalikan.
Salah satu kendala penanganan pandemi secara global adalah akses vaksin yang tak merata. Karena itu, G-20 merupakan salah satu forum terbaik untuk mendiskusikan distribusi vaksin yang lebih adil.
Selain itu, mengingat virus terus bermutasi, cara paling baik adalah mengembangkan vaksin secara mandiri di tiap negara yang mampu melakukannya. Pembebasan hak paten atas vaksin yang sudah ada, paling tidak untuk sementara, akan membantu pengembangan lebih banyak vaksin.
Baca juga : Stagflasi dan Disrupsi Rantai Pasok
Selain persoalan vaksin, pemulihan ekonomi yang tak merata juga disebabkan ketimpangan dalam stimulus fiskal. Publikasi Forum Ekonomi Dunia menunjukkan betapa timpangnya besaran stimulus fiskal di antara kelompok negara G-20.
Pada Juli 2020, tiga negara dengan stimulus fiskal terbesar adalah Jepang sebesar 21,1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), Kanada 15 persen, dan AS 13,2 persen. Tiga negara dengan jumlah stimulus fiskal terendah adalah Meksiko (0,7 persen), Arab Saudi, dan Rusia (3,4 persen). Indonesia berada pada posisi moderat dengan stimulus setara 4,4 persen PDB.
Besaran stimulus fiskal akan menentukan seberapa cepat pemulihan ekonomi terjadi. Meski begitu, besaran stimulus juga akan memengaruhi struktur pasar finansial global yang jika tak dikelola dengan baik bisa jadi sumber ketidakstabilan pasar keuangan, khususnya di negara berkembang. Forum G-20 perlu mendiskusikan mendalam berbagai skenario dan strategi pemulihan ekonomi yang lebih berkesinambungan.
Di antara negara G-20, tiga negara dengan stimulus fiskal terbesar merupakan kelompok negara dengan jumlah utang tertinggi. Menurut catatan Dana Moneter Internasional, pada 2021 Jepang akan memiliki rasio utang terhadap PDB 256 persen, Kanada 109 persen, dan AS 133 persen. Rasio ini diperkirakan akan bertahan dalam kisaran yang sama hingga 2026. Sementara Indonesia pada periode itu di kisaran 35-40 persen.
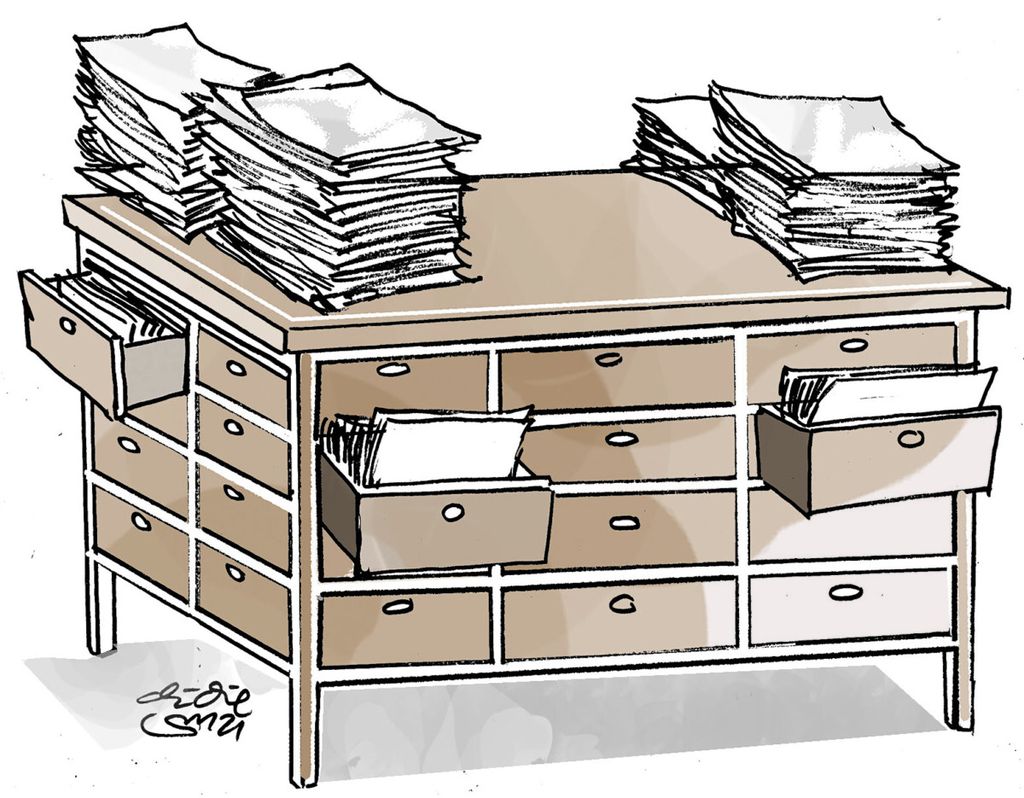
Didie SW
Di negara maju, peningkatan beban utang diikuti dengan penurunan beban pembayaran bunga akibat kebijakan moneter ultra-longgar. Itulah mengapa otoritas moneter di negara maju terlihat enggan menaikkan suku bunga, karena kenaikan suku bunga akan menambah beban pembayaran bunga surat utang pemerintah yang sudah begitu besar.
Tampaknya, rezim suku bunga rendah di negara maju akan cenderung jangka panjang. Masalahnya, suku bunga rendah yang terjadi terlalu lama juga akan meningkatkan risiko akibat begitu besarnya likuiditas yang sebagian mengalir ke negara berkembang.
Perubahan arah kebijakan moneter akan punya implikasi, baik pada pasar obligasi di negara maju maupun pasar keuangan di negara berkembang. Kenaikan suku bunga negara maju akan menimbulkan bond tantrum. Karena itu, perlu dirumuskan strategi keluar dari stimulus, baik fiskal maupun moneter, agar tak menimbulkan guncangan, khususnya di negara berkembang.
Peran Indonesia
Kelompok G-20 merepresentasikan lebih dari 60 populasi global, 75 persen perdagangan dunia, dan lebih dari 80 persen perekonomian dunia. Dalam posisinya sebagai presidensi G-20, Indonesia punya tanggung jawab jadi penyeimbang (kepentingan) kelompok negara maju dan berkembang yang juga bisa disinergikan dengan agenda domestik.
Tampaknya, rezim suku bunga rendah di negara maju akan cenderung jangka panjang.
Pertama, distribusi vaksin yang lebih adil juga akan mempercepat pemulihan domestik. Apalagi jika upaya merelaksasi paten vaksin bisa terjadi paling tidak secara temporer selama pandemi, tentu akan mempercepat realisasi vaksin dalam negeri. Presidensi G-20 juga harus dimanfaatkan untuk mendorong transformasi sektor kesehatan (termasuk farmasi) dengan memanfaatkan rantai pasok di antara negara G-20.
Kedua, potensi ekonomi digital yang sudah dimiliki Indonesia diharapkan menjadi portofolio penting dalam bernegosiasi antarnegara G-20. Perkembangan sektor digital kita termasuk yang menjanjikan sehingga bisa jadi posisi tawar yang baik dalam pengembangan ke depan.
Hasil kajian Google, Temasek, dan Bain & Company memperkirakan sepanjang 2021 ekonomi digital Indonesia memiliki nilai penjualan 70 miliar dollar AS atau mengalami pertumbuhan CAGR 49 persen dibandingkan 2020.
Pada 2025 ekonomi digital Indonesia diproyeksikan bisa mencapai 146 miliar dollar AS. Apalagi jika digitalisasi bisa diperluas di berbagai aspek, seperti sektor pertanian, kelautan, dan kehutanan yang potensinya juga sangat besar.
Baca juga : Meneguhkan Komitmen Masa Depan Ekonomi Hijau
Ekonomi hijau
Ketiga, sebagai negara dengan luasan hutan hujan tropis ketiga terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi tawar kuat dalam diskusi mengenai pendanaan iklim. Hutan berfungsi sebagai paru-paru dunia, menyerap karbon (yang banyak dihasilkan negara maju) dan mengeluarkan udara bersih. Konsep ini telah dituangkan dalam prinsip carbon sink sebagai ukuran seberapa banyak negara mampu menyerap CO2 secara alamiah, baik melalui hutan maupun lautan.
Persoalannya, bagaimana prinsip ini dituangkan dalam standar akuntansi pelaporan keuangan sehingga bisa dikapitalisasi. Selama ini, standar akuntansi dunia diatur oleh International Financial Reporting Standards (IFRS).
Baru-baru ini, mereka mengumumkan rencana pembentukan International Sustainability Standards Board (ISSB) yang akan mengeluarkan standar akuntansi pelaporan keuangan yang berorientasi pada keberlanjutan. Forum G-20 juga perlu dimanfaatkan untuk memengaruhi arah prinsip dan standar akuntansi berorientasi lingkungan dengan mengadopsi prinsip carbon sink.
Komunitas G-20 juga bisa dimanfaatkan untuk menyepakati prinsip pengelolaan surat utang untuk mendanai kegiatan berorientasi lingkungan (green bond). Jeffrey Sach mengusulkan skema pendanaan green bond yang lebih adil. Selama ini, surat utang yang dikeluarkan negara berkembang cenderung mahal karena dianggap risiko tinggi. Sementara negara maju diuntungkan dengan penerbitan surat utang yang dibeli warganya sendiri dengan bunga sangat rendah.
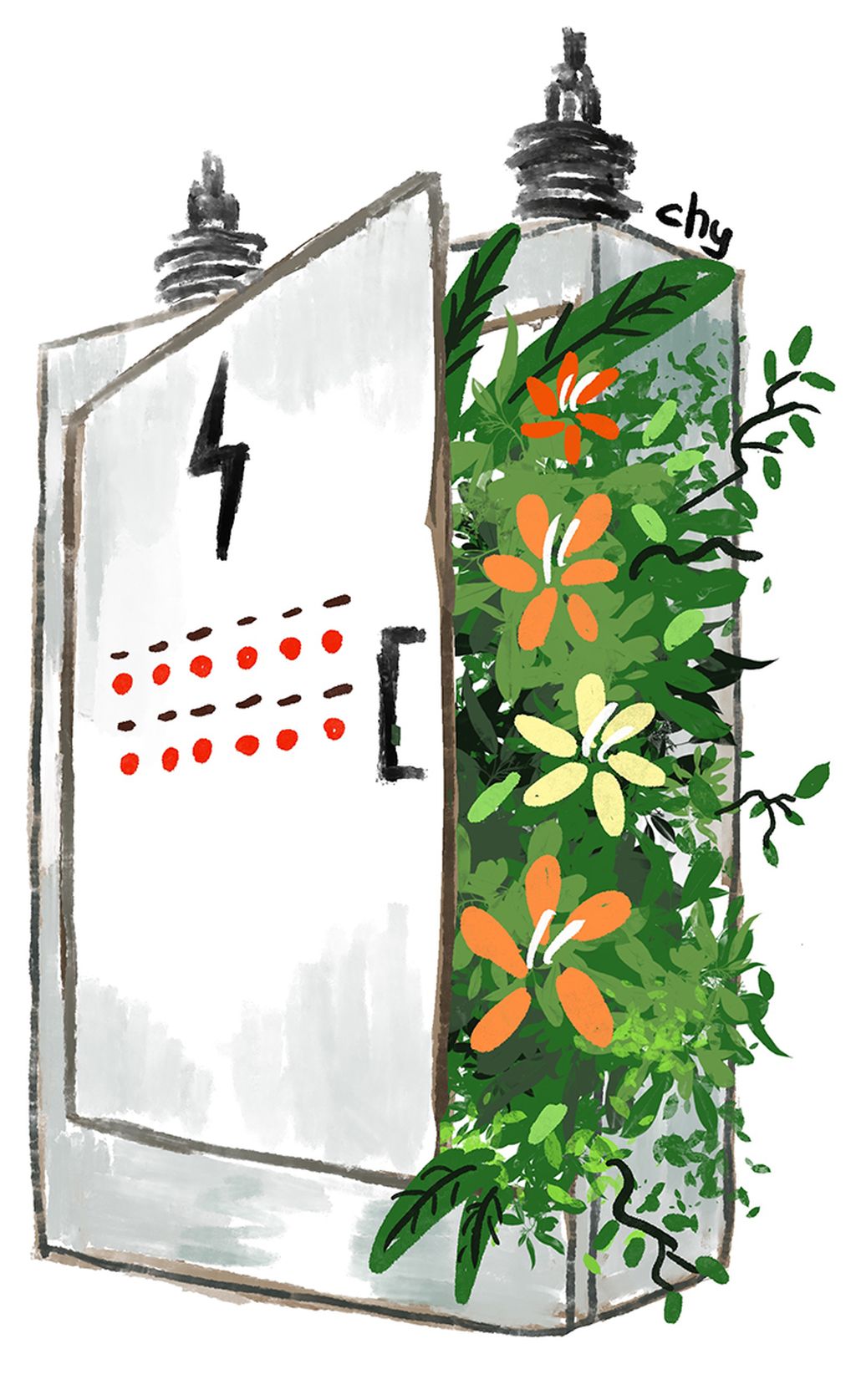
Untuk mendukung penguatan ekonomi hijau di negara berkembang, green bond perlu didorong perkembangannya dengan cara menurunkan imbal hasilnya. Lembaga pemeringkat juga punya peran penting, misalnya dengan menempatkan luasan hutan sebagai salah satu basis penilaian risiko.
Pendekatan ini sekaligus memberi disinsentif bagi deforestasi. Semakin besar upaya mereka mengonversasi hutan, semakin tinggi jaminan yang dimiliki dan semakin rendah imbal hasil green bond yang diterbitkan pemerintah setempat.
Presidensi G-20 harus dimanfaatkan untuk mempercepat transformasi ekonomi pascapandemi, terutama melalui perumusan strategi industrialisasi berbasis digital dan berperspektif lingkungan serta sistem pembiayaan hijau (green financing).
Tak bisa dihindari, perekonomian ke depan akan ditentukan oleh adopsi teknologi dan mengarah pada sistem ekonomi rendah karbon. Kebijakan industrial yang sesuai diperlukan agar produktivitas ekonomi juga punya ciri serupa, berbasis teknologi dan berorientasi lingkungan.
Faktor produksi (hijau) harus terus-menerus dikembangkan, mulai dari kualitas dan kapasitas manusia, modal dan pembiayaan, serta faktor alam yang tak lagi serta-merta menjadi input produksi. Faktor alam yang selama ini terlalu banyak dieksploitasi pada gilirannya harus menjadi orientasi upaya konservasi. Pada gilirannya, akan terbentuk mata rantai pasok (hijau) yang perlahan terbentuk, diawali dengan inisiatif dari G-20.
Menghadapi mutasi virus yang masih akan terjadi era epidemi, perekonomian global akan cenderung tumbuh lebih rendah dengan inflasi relatif tinggi. Masih ditambah dengan perhatian pada keseimbangan lingkungan, pola pertumbuhan akan mengalami perubahan di masa depan. Karena itu, perlu kebijakan industri sekaligus strategi pendanaan yang berorientasi keberlanjutan.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F01%2F2cf749f7-d86d-45c6-9176-93e4ec5adf74_jpg.jpg)
A Prasetyantoko
Forum G-20 menjadi salah satu inkubasi terbaik untuk mengembangkan inovasi, transformasi, dan bahkan disrupsi bagi perekonomian hijau pascapandemi. Indonesia punya peran penting menavigasi arah pemulihan ekonomi serta watak perekonomian pascapandemi berciri digital dan berperspektif keberlanjutan.
A Prasetyantoko Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya