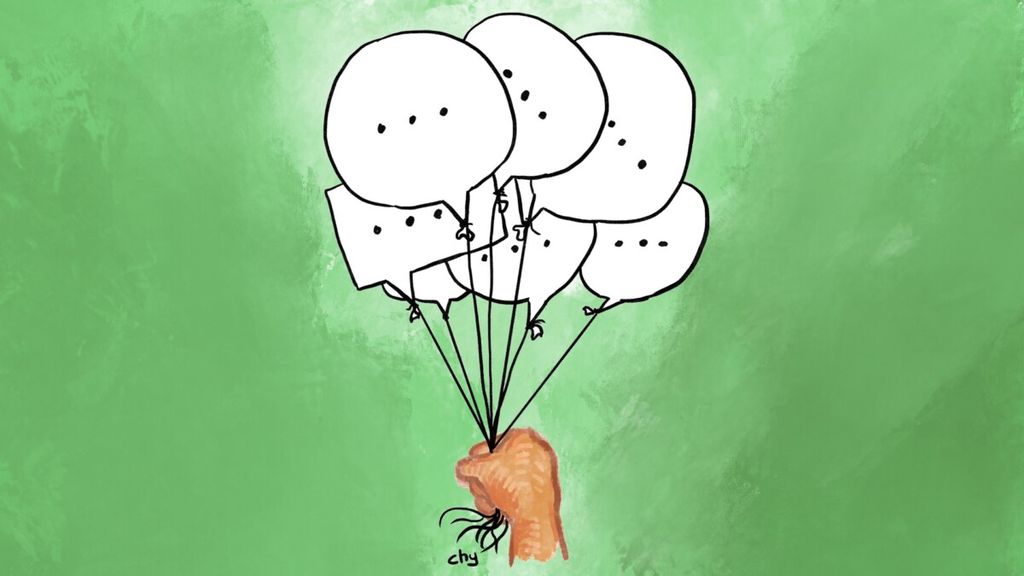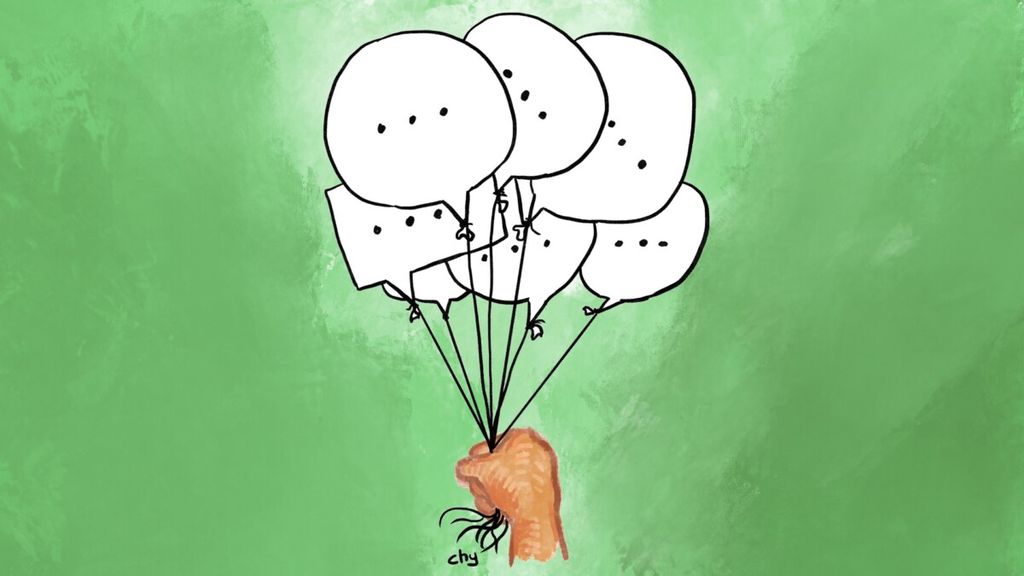
Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Begitulah seruan Sumpah Pemuda pada 1928. Seruan ini lalu berkumandang di segala pelosok negeri ini. Dengan sukses. Hingga bahasa Indonesia kini menjadi juga ”bahasaku”, bule yang terlahir 15.000 kilometer dari ”tanah dan air” Indonesia ini. Namun, muncul pertanyaan. Apakah seruan ”satu bahasa” telah meraih sukses terlalu besar di negeri ini?
Empat puluh tahun yang lalu, ketika saya mulai bermukim di Bali, ruang penggunaan bahasa dan budaya Bali luas sekali. Pewayangan menjadi sarana utama penurunan sistem nilai. Pengetahuan agama masih di dalam kuasa kalangan brahmana. Kaum intelektual berpendidikan modern berjumlah segelintir saja. Belum ada peziarah ke Sungai Gangga dan Jamuna: konsep keumatan internasional Hindu belum terpikir oleh si wong cilik Bali yang kebanyakan masih petani itu. Pendeknya, budaya Bali masih bersifat lokal, dan berbahasa lokal, untuk melayani mentalitas lokal.
Kini situasi berubah total. Bahasa Bali mundur drastis. Di ruang perkotaan, penggunaannya menyusut dengan cepat. Ratusan ribu pendatang tidak tahu-menahu bahasa Bali. Bahasa nasional merajai pergaulan, media, dan sistem pendidikan. Tak sedikit orang Bali tak bisa berbahasa Bali. Hampir semua rumusan sistem nilai agama dilakukan di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Sanskerta. Dari fokus lalu ke ritual pemujaan leluhur yang lokal, agama kini telah beralih ke fokus filsafat kosmologis yang lintas suku dan bahkan lintas bangsa.
Pokoknya perluasan tanpa henti dari ruang sosio-ekonomi modern telah mentransformasi identitas orang Bali sambil kian memojokkan bahasanya. Bahkan tak jarang terjadi juga bahwa diskusi sastra Bali diselenggarakan tanpa bahasa Bali digunakan sama sekali. Atau bahasa Bali hanya digunakan pada bagian sambutan awal, yang sarat ungkapan kesopanan.
Penyusutan bahasa dan budaya Bali ini tidak hanya bersifat sosiologis, tetapi juga linguistik. Penutur bahasa Bali cenderung menyisipkan kian banyak kata Indonesia di dalam ungkapannya sehingga bahasanya bersifat gado-gado, separuh Bali, separuh Indonesia. Hal ini kian terlihat di siar-siar agama Hindu pendeta-pendeta.
Menariknya, penyusutan penggunaan bahasa Bali ini tampak diterima masyarakat. Mengapa? Apakah sistem tingkat (unggah-ungguh) bahasa ”mengganggu” dan dihindari dengan beralih ke bahasa Indonesia, yang lebih demokratis itu? Bisa jadi. Apakah pesatnya modernisasi dan urbanisasi—dari 15 persen tahun 1970-an menjadi lebih dari 50 persen kini—tak memberikan peluang pada kultur yang pada dasarnya agraris ini untuk beradaptasi dengan menciptakan konseptualisasi kata abstrak secara lokal? Bisa jadi juga. Akan tetapi, mungkin sebab utamanya lain: segi ikonik (tari dan musik) budaya Bali sedemikian diagung-agungkan sehingga penentu kebijakan telah abai terhadap landasan linguistiknya.
Alhasil, bahasa, budaya, dan agama dibiarkan berpisah satu sama lainnya. Tindakan perlindungan yang diambil hanya bersifat simbolis, seperti mempromosikan penggunaan aksara Bali, atau membuat airport mengumumkan pemberangkatan dalam bahasa Bali. Namun, apa faedahnya apabila bahasa dibiarkan merosot dengan begitu saja jumlah penuturnya?
Pendeknya, budaya Bali tengah tertransformasi dengan beralih bahasa.
Apakah ada resistensi? Di perdesaan masih terdapat seka pesantian pembaca sastra. Bahkan ada grup radio antarpeminat. Masih ada penulis naskah geguritan. Surat kabar Pos Bali mempunyai halaman sastra Bali mingguan dengan cerpen dan perbincangan filsafat agama. Jurusan bahasa Bali di beberapa universitas menghasilkan penulis muda yang canggih. Namun, apakah terlambat?
Mungkin ya, mungkin tidak. Sepuluh tahun lalu muncul ”perlawanan” modern, di dalam bentuk Yayasan BasaBali, pimpinan Alissa Stern, yang kini kian mekar kegiatannya: kamus, metode pelajaran bahasa Bali-Inggris-Indonesia, penyuluhan bahasa dan lain-lain, dengan internet-Youtube sebagai sarana penyebaran. Bahkan puri-puri kini turut serta membela bahasa. Di Ubud tak kurang dari dua puri setempat, Puri Agung dan Puri Kauhan, menyelenggarakan diskusi dan penerbitan bahasa Bali.
Semoga kegiatan-kegiatan di atas mampu menghentikan pemerosotan bahasa Bali di tanahnya sendiri, dan dengan demikian menghentikan proses pemisahan antara bahasa, budaya, dan agama. Hal ini penting: budaya tanpa bahasa adalah hampa, dan agama tanpa landasan lokal kokoh cenderung menjadi dogmatis dan identiter.
Bukan itu yang dihendaki tokoh-tokoh Ubud dan seluruh Bali ketika, dua minggu lalu, pada peluncuran buku-bukunya, saya menyaksikan mereka menyanyikan dengan khidmat lagu ”Indonesia Raya”: tak dapat diragukan bahwa mereka menginginkan suatu keindonesiaan yang tetap Bhinneka Tunggal Ika. Amin lan astungkara.