Tiga Tahun Mendatang
Tiga tahun masa pemerintahan yang tersisa akan menjadi ujian. Apakah kredibilitas kepemimpinan dan konsolidasi elite masih efektif untuk meredam tantangan struktural dan kelembagaan tersebut menjadi tanda tanya besar?
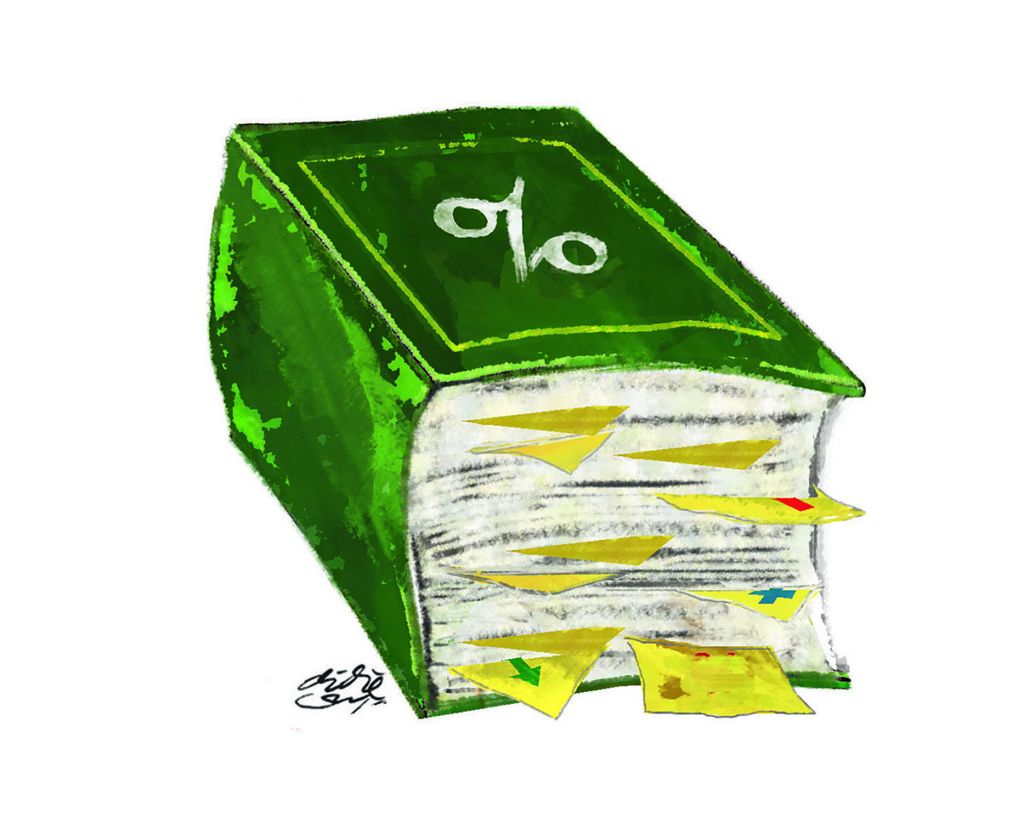
Didie SW
Tanggal 20 Oktober, genap dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin untuk periode jabatan kedua. Jika tak ada aral melintang, tiga tahun mendatang transfer kekuasaan akan terjadi.
Tulisan ini mencoba mengidentifikasikan beberapa tantangan utama dari tiga tahun yang masih tersisa itu. Tantangan-tantangan itu, baik dalam watak struktural maupun kelembagaannya, muncul dari dua ranah kebijakan: fiskal dan moneter.
Dari perspektif ekonomi politik, dua ranah kebijakan itu bukan sekadar memuat isu stabilitas ekonomi makro dan sumber daya ekonomi nasional. Dua ranah kebijakan itu juga berguna untuk lebih mengenal ”wajah”, kapasitas, dan keterbatasan kewenangan negara yang akan diwariskan kepada pemerintah berikutnya. Dengan mengenal ”wajahnya” secara lebih konkret, harapan-harapan kita juga menjadi lebih membumi.
Tidak ada keraguan apa pun Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berhasil menciptakan warisan politik yang sangat khas.
Kredibilitas dan konsolidasi
Tidak ada keraguan apa pun Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berhasil menciptakan warisan politik yang sangat khas. Dari sisi kepemimpinan, Presiden Jokowi terlihat sebagai pemimpin yang sangat dekat dengan rakyatnya.
Gaya kepemimpinannya hampir tidak berjarak dengan rakyat. Blusukan sebagai metode komunikasi dan interaksi dengan rakyat terlihat sebagai inovasi politik yang mencengangkan.
Muatan kebijakan yang bernuansa ”populis”, seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, ataupun melalui peningkatan anggaran bantuan sosial dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional, juga telah menjadi branding kepemimpinan Presiden Jokowi.
Seperti proses mengubah besi menjadi sebuah keris, persepsi publik terhadap karakter Presiden Jokowi sebagai pemimpin yang hampir tak berjarak dengan rakyatnya itu telah memasuki fase akhir pendinginan dan penempaan.
Karakter menonjol lainnya adalah kecerdasan politik untuk melakukan konsolidasi elite. Di tengah spektrum politik yang sangat beragam, hampir tak terlihat kesulitan untuk mewujudkan suatu pemerintah yang efektif. Hampir nihil tekanan-tekanan signifikan dari legislatif ataupun dari kekuatan ekstra-parlementer terhadap Presiden Jokowi.

Presiden Joko Widodo mengawali kunjungan kerja di Provinsi Papua Barat dengan menanam benih jagung di Kabupaten Sorong, Senin (4/10/2021).
Proses legislasi tampak relatif mudah. Paling spektakuler misalnya kerja ”raksasa” menghasilkan UU Cipta Kerja. Ada kesan kuat sebagian besar legislatif ”mengikuti” arahan eksekutif (jika bukan terkooptasi).
Penyebabnya mungkin sederhana. Sebagian besar kekuatan partai di parlemen telah terwakili dalam struktur kabinet. Ringkasnya, pemerintah efektif bukan menjadi sesuatu yang luxurious dalam tujuh tahun terakhir.
Fiskal yang sehat?
Namun, dua karakter ini, kredibilitas kepemimpinan ataupun konsolidasi elite yang kuat itu, mungkin memiliki keterbatasan untuk mengubah tantangan-tantangan struktural dan kelembagaan untuk tiga tahun ke depan. Tantangan struktural pertama terkait dengan masalah defisit fiskal sebagai akibat respons kebijakan terhadap pagebluk Covid-19.
Norma defisit fiskal 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) telah tidak lagi dianut secara ketat untuk sementara waktu (berdasarkan UU No 2 Tahun 2020). Analisis singkat yang dilakukan menunjukkan bahwa pemerintah hanya memiliki waktu satu tahun lagi untuk mengembalikan defisit anggaran sebesar 3 persen itu.
Di sisi lain, besaran defisit anggaran pada APBN 2022 telah disepakati Rp 868,019 triliun atau 4,85 persen dari PDB. Simulasi sederhana yang dilakukan menunjukkan kesimpulan berikut. Jika memang bermaksud untuk mengembalikan komitmen kebijakan defisit fiskal itu, dan jika asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen pada tahun 2022 terjadi, maka kapasitas fiskal yang dibiayai oleh defisit anggaran pada 2023 hanya Rp 564,84 triliun.
Baca juga : Pembiayaan Defisit Perlu Diatasi dengan Fokus Anggaran
Tantangan struktural lainnya untuk mendapatkan fiskal yang sehat itu berasal dari sisi politik. Pemerintah dihadapkan dengan suatu dilema: melanjutkan kebijakan ekspansif infrastruktur atau pilihan lainnya memprioritaskan kesehatan fiskal. Fakta yang ada menunjukkan bahwa dalam enam tahun terakhir, proyek infrastruktur tidak pernah dianggarkan lebih kecil dari Rp 280 triliun.
Saat ini anggaran tersebut berada pada posisi tertingginya sebesar Rp 417,4 triliun (15,2 persen dari total belanja negara tahun 2021). Perintah untuk melanjutkan proyek-proyek yang kerap mendapat banyak kritik, seperti ibu kota negara baru dan kereta cepat Jakarta-Bandung, menyisakan tiga jalan keluar hingga tahun 2024.
Pertama, seluruh proyek yang berlangsung saat ini harus selesai sebelum habis periode masa jabatan. Kedua, menghapus tekanan politik dari proyek infrastruktur yang menjadi prioritas. Ketiga, mencari sumber pendanaan baru di luar APBN.
Euforia menyambut Pemilu 2024 juga memberikan sinyal adanya tantangan struktural politiknya yang tak dapat diabaikan. Walau konsolidasi politik sangat kuat, mungkin hanya berlangsung sampai tahun depan. Pengusulan penambahan anggaran pemilu menjadi 350 persen dari pagu anggaran yang sebelumnya sudah tercantum dalam surat bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas adalah salah satu sinyal yang mencemaskan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/9/2021). Pada rapat tersebut DPR menyepakati Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Pendapatan negara ditetapkan Rp 1.846,14 triliun, belanja negara Rp 2.714,16 triliun, dan defisit APBN Rp 868 triliun.
Penambahan tersebut diakui telah melewati proses cermat dan efisiensi dari usulan tambahan yang sebelumnya sebesar Rp 10,842 triliun atau sekitar 442 persen dari pagu. Anggaran ”fantastis” ini pun sudah termasuk pengadaan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di sejumlah daerah sehingga anggaran pengadaan pemilu serentak diramalkan akan cukup besar memberikan tekanan terhadap kesehatan fiskal.
Sebagai gambaran, KPU mengusulkan total anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 86,2 triliun atau tiga kali lipat lebih besar dari anggaran Pemilu 2019 sebesar Rp 27 triliun.
Dari sisi pendapatan, pemerintah telah melakukan upaya untuk memperluas cakupan pajak dengan kembali mengadakan tax amnesty (pengampunan pajak) pada tahun 2022 dengan harapan penerimaan terkerek naik menjelang upaya penyehatan fiskal satu tahun berikutnya.
Namun, jika melihat indikator rasio pajak terhadap PDB dalam sepuluh tahun terakhir, maka terjadi tren penurunan dibandingkan dengan sebelum adanya amnesti pajak yang pertama pada 2016. Oleh karena itu, harapan peningkatan penerimaan pajak tampaknya perlu disandingkan dengan kenyataan dari pembelajaran masa lalu.
Sentralisasi kewenangan moneter?
Tantangan berikutnya adalah di sisi moneter. Sejauh mana peran kelembagaan Bank Indonesia (BI) diharapkan untuk membantu pemulihan ekonomi nasional? Apakah peran kelembagaannya saat ini sudah on track, yang terkesan menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah? Apakah peran kelembagaan baru ini bersifat sementara saja?
Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan mengingat ada kesan intensi kebijakan yang sangat kuat dari BI akhir-akhir ini. Tidak cukup menjalankan peran di sisi makroprudensial dengan membeli obligasi yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.
BI tampak juga telah masuk ke ruang mikroprudensial sejalan dengan penetapan adanya target baru bagi bank umum untuk menyalurkan kredit ke UMKM 30 persen dari total kreditnya pada 2024. Padahal, ke depan, alokasi kredit ini berpotensi menjadi kredit macet yang justru akan memberatkan tugas dan fungsi pengawasan yang dijalankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sejauh mana peran kelembagaan Bank Indonesia (BI) diharapkan untuk membantu pemulihan ekonomi nasional?
Pertanyaan ini tentu saja tidak mudah dijawab. Ketidakpastian pemulihan ekonomi yang ditandai oleh ancaman inflasi global tentu saja akan memengaruhi respons kebijakan yang diberikan (lihat IMF, 14 Oktober 2021).
Ancaman inflasi global disinyalir tidak hanya berasal dari masalah logistik sebagai akibat dari disrupsi pagebluk dalam jalur mata rantai pasokan global. Sebab lainnya diduga berasal dari kebijakan intervensi pemerintah di banyak negara yang terlalu besar pada masa pandemi ini.
Kebijakan itu telah menciptakan mismatch antara likuiditas yang berlebih yang tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas produksi. Jika ini terjadi, rezim suku bunga murah mungkin akan segera berakhir. Kebijakan peningkatan tingkat bunga untuk mengendalikan inflasi tentu saja tidak populer secara politik.
Ketidakpastian global yang tinggi tentu saja juga membutuhkan respons kelembagaan yang berbeda. Pilihan rasional biasanya adalah memusatkan kewenangan kelembagaan daripada melakukan penyebaran kewenangan. Kata ”independensi” dari otoritas moneter kemungkinan akan dikesampingkan.
Namun, sentralisasi kewenangan di sisi lain akan memuat bujukan untuk politisasi kebijakan moneter terhadap tekanan.
Sejauh yang dapat dicermati, seluruh tantangan struktural dan kelembagaan yang telah diuraikan di atas telah hadir bersama kita dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kredibilitas kepemimpinan dan konsolidasi elite yang solid tampak efektif untuk menjadi ”bumper” atau untuk meredam tantangan-tantangan itu.
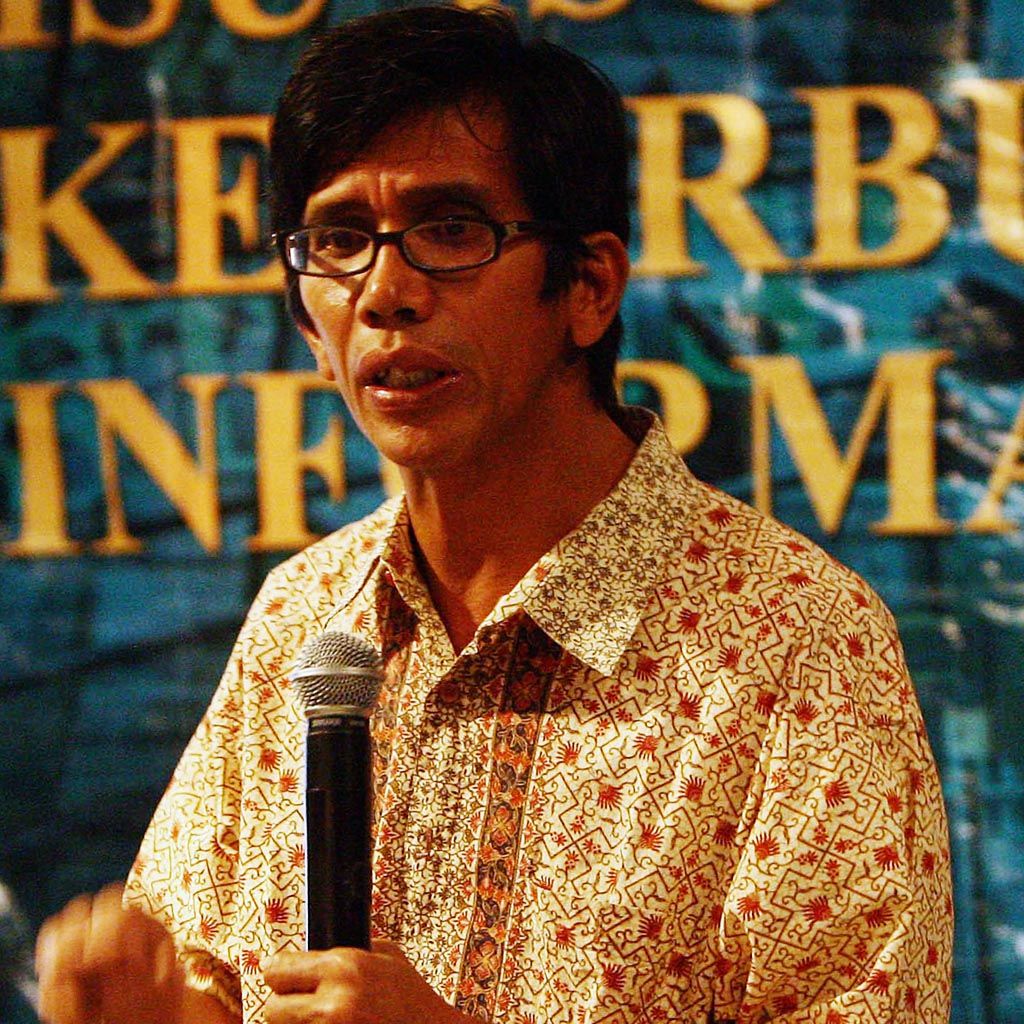
Makmur Keliat
Dengan demikian, kita juga bisa menyatakan bahwa tiga tahun yang tersisa juga akan menjadi ujian berikutnya. Apakah kredibilitas kepemimpinan dan konsolidasi elite itu masih cukup efektif untuk meredam tantangan struktural dan kelembagaan tersebut masih akan menjadi misteri dan tanda tanya besar .
Makmur Keliat, Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia dan Analis Utama Lab45