Membangkitkan Sastra Maritim
Kejayaan maritim bangsa-bangsa di Indonesia pada masa silam meredup dalam ingatan kolektif bangsa Indonesia. Membangkitkan sastra maritim menjadi jalan untuk memulihkan ingatan kolektif bangsa tersebut.
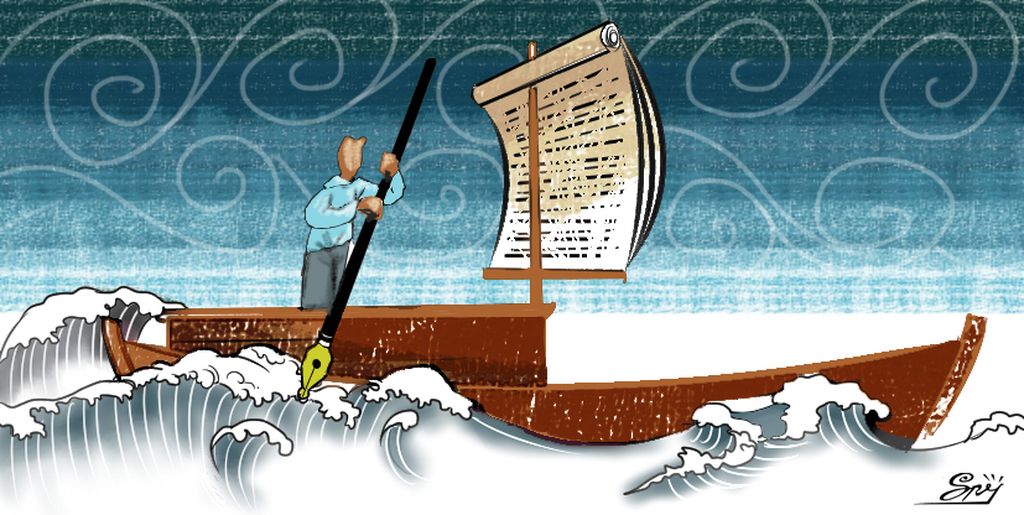
Supriyanto
Para sastrawan Indonesia sedang berjuang untuk membangkitkan sastra maritim. Melalui karya sastra dapat terungkap kejayaan maritim bangsa-bangsa di Indonesia pada masa silam. Kini kejayaan itu sudah hilang dari ingatan kolektif bangsa Indonesia.
Secara geografis perairan di wilayah Indonesia lebih luas dibandingkan daratannya. Luas perairan Indonesia 3.110.000 kilometer persegi (km2), sedangkan luas daratan hanya 1.916.906,77 km2 yang terdiri dari 17.504 pulau.
Kondisi geografis ini bersesuaian dengan catatan sejarah bahwa bangsa-bangsa di Indonesia pada masa silam dikenal sebagai bangsa maritim. Mereka bertebaran menguasai pesisir pantai timur dan barat Pulau Sumatera, pantai utara dan selatan Pulau Jawa, pantai barat, selatan, dan timur Pulau Kalimantan. Bangsa maritim juga terdapat di Pulau Madura, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kepulauan Maluku.
Kejayaan bangsa-bangsa maritim di Indonesia pada masa silam terekam dalam peninggalan budaya tak benda ataupun kebendaan. Para arkeolog dan sejarawan sangat berjasa dalam menemukan kembali fakta-fakta kejayaan maritim pada masa lalu dan merekonstruksikannya sebagai narasi sejarah. Mereka berhasil menemukan kembali jejak-jejak kejayaan maritim di Indonesia sejak abad ke-7 Masehi.
Baca Juga: Tamadun Maritim: Spiritual Nawacita
Nama George Coedes (1886-1969) harus disebutkan sebagai ilmuwan paling berjasa. Ia adalah arkeolog dan sekaligus sejarawan dari Perancis. Publikasi hasil penelitiannya pada tahun 1918 memecahkan misteri tentang keberadaan kerajaan maritim Sriwijaya yang berpusat di Palembang (Le Royoume de Criwijaya Buletin de l’Ecole francais d’extreme Orient, 18 (6): 1-36). Penelitiannya menjadi monumental karena dijadikan rujukan pertama dan yang utama tentang Kerajaan Sriwjaya yang terdapat dalam laporan-laporan kekaisaran China.
Berdasarkan hasil penelitian Coedes dan penelitian selanjutnya bahwa Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim pertama di Indonesia yang berdiri pada abad ke-7 M. Apabila dihitung dari sekarang, maka kejayaan maritim sudah ada 1.400 tahun yang lalu. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya menguasai jalur laut dan menjalin hubungan diplomatik dengan dua kerajaan besar yang berada di China dan India.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F02%2F57706979-cc3d-4597-abfc-46c6750c3d82_png.jpg)
Letak situs-situs Kerajaan Sriwijaya di Palembang dalam presentasi arkeolog Balai Arkeologi Sumsel Retno Purwanti saat webinar Bincang Pusaka bertema Talang Tuo: Warisan Sejarah dan Sains bagi Palembang yang digelar Sahabat Cagar Budaya Sumsel, Sabtu (6/2/2021).
Ilmuwan lain yang berjasa menemukan kembali jejak kejayaan maritim di Indonesia adalah Anthony Reid. Sejarawan dari Australia ini pada tahun 1988 menerbitkan hasil penelitiannya yang berjudul Southeast Asia in the Age of Commerce 1450 to 1680. Buku rujukan utama sejarah Asia Tenggara ini terdiri dari dua jilid, yakni The Land Below The Wind dan Expansion and Crisis. Kedua jilid memberikan informasi bahwa kawasan Asia Tenggara merupakan bagian terpenting dalam menciptakan jalur perdagangan laut yang menghubungkan perdagangan dunia, menjadi jalur distribusi komoditas perdagangan yang menggantikan perdagangan jalur darat yang dikenal sebagai jalur sutra.
Perdagangan jalur laut diciptakan oleh kerajaan-kerajaan maritim di sepanjang jalur laut di Asia Tenggara. Di antara kerajaan maritim tersebut berada di wilayah yang saat ini dikenal sebagai Indonesia. Mereka adalah pemasok utama rempah-rempah, komoditas perdagangan yang terlaris pada saat itu. Anthony Reid berhasil menjelaskan distribusi rempah-rempah dari Indonesia hingga ke Eropa melalui pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia Tenggara. Dari penelitiannya terbentuk narasi jalur rempah.
Sebagian besar rempah-rempah dihasilkan dari Kepulauan Maluku. Para pedagang membelinya dari petani dan membawanya ke Pelabuhan Makassar. Rempah-rempah kemudian didistribusikan ke Pelabuhan Malaka melalui beberapa pelabuhan di sepanjang pantai utara Pulau Jawa dan pantai timur Pulau Sumatera. Malaka adalah pelabuhan besar yang menjadi salah satu pusat perdagangan dunia yang mempertemukan seluruh pedagang.
Baca Juga: Jalur Rempah
Masa kurun niaga, meminjam istilah Reid (The Age of Commerce) menciptakan kebudayaan maritim yang berpusat di kota-kota pelabuhan yang tumbuh berkembang di Kepulauan Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara, Jawa, dan Sumatera. Kurun niaga menciptakan stratifikasi sosial: penguasa (raja, bangsawan, agamawan), pedagang (masyarakat kota Pelabuhan), dan nelayan. Ketiga lapisan sosial ini berinteraksi menghasilkan kebudayaan maritim.
Stratifikasi sosial yang tercipta pada masa kejayaan maritim mempunyai ciri mobilitas sosial yang terbuka sehingga setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mengubah kedudukan dan peranan sosialnya. Cerita rakyat dari Sumatera Barat tentang keluarga Malin Kundang merupakan contoh dari stratifikasi sosial terbuka itu.
Diceritakan bahwa Malin Kundang berasal dari keluarga yang sangat miskin. Untuk mengubah nasibnya, Malin Kundang merantau, bekerja pada saudagar kaya. Ia memulai bekerja sebagai pembersih kapal. Kinerjanya sangat bagus sehingga kariernya terus meningkat menjadi orang kepercayaan saudagar kaya.
Singkat cerita Malin Kundang naik kelas sehingga kedudukan dan status sosialnya menjadi sangat terhormat. Perubahan ini hanya dimungkinkan terjadi pada masyarakat yang menganut stratifikasi sosial yang terbuka.
Stratifikasi sosial yang tercipta pada masa kejayaan maritim mempunyai ciri mobilitas sosial yang terbuka.
Dalam stratifikasi sosial terbuka, keberadaan seseorang tidak ditentukan oleh faktor keturunan, tetapi oleh kinerjanya atau prestasinya. Malin Kundang bukanlah berasal dari keturunan terhormat, tetapi ia memiliki kinerja yang sangat baik.
Cerita kesuksesan Malin Kundang dalam stratifikasi sosial yang terbuka tertutupi dengan penekanan yang berlebihan pada pesan moral yang ingin disampaikan, yakni penghormatan kepada orangtua sehingga Malin Kundang bukanlah teladan yang baik, tetapi menjadi contoh keburukan anak sukses yang durhaka kepada ibunya.
Pesan moral dalam cerita Malin Kundang memberikan informasi proses perubahan sosial yang dialami masyarakat pada waktu itu, yakni dari masyarakat agraris dengan stratifikasi sosial yang tertutup menjadi masyarakat maritim dengan stratifikasi sosial yang terbuka.

Pengunjung melihat sejumlah benda koleksi yang dipamerkan di Museum Bahari, Jakarta, Minggu (30/11/2014). Museum Bahari menyimpan sejumlah benda dan memiliki informasi sejumlah catatan sejarah kejayaan kemaritiman Indonesia di masa lalu.
Memulihkan ingatan kolektif bangsa
Kini proses perubahan menuju masyarakat maritim tersebut menjadi cerita rakyat untuk pelipur lara. Fakta-fakta kejayaan maritim menjadi mitos dan legenda serta hiburan pada waktu kecil ketika menyanyikan lagu ”nenek moyangku orang pelaut...”.
Beranjak dewasa, kita mengenang lirik lagu tersebut sambil tersenyum malu karena berbeda antara imajinasi pada masa anak-anak dan kenyataan yang dialami sehari-hari pada masa dewasa. Setiap hari yang tersaji adalah budaya yang tidak berorientasi pada lautan. Realitas sosial pada masa kini membuat kita berkesimpulan bahwa nenek moyangku ternyata bukanglah orang pelaut.
Lagu ”Nenek Moyangku” menjadi pengingat bahwa bangsa Indonesia adalah keturunan bangsa maritim. Namun, lagu yang diciptakan oleh Ibu Sud pada tahun 1940 ini pun turut dilupakan pada saat ini karena anak-anak generasi milineal sudah tidak menyanyikannya ketika mereka mengikuti pendidikan anak usia dini. Akibatnya, mereka kesulitan sekadar membayangkan bahwa dirinya adalah keturunan bangsa maritim.
Lagu ’Nenek Moyangku’ menjadi pengingat bahwa bangsa Indonesia adalah keturunan bangsa maritim.
Pada kondisi seperti ini, kegiatan webinar Sastra Maritim dan Ritual Laut yang digagas oleh Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia dan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta pada 9 Agustus 2021 menjadi sangat penting karena memunculkan harapan baru untuk membangkitkan kejayaan maritim melalui karya-karya sastra.
Zaman telah berganti. Sastra maritim sesungguhnya sudah meredup dalam ingatan kolektif bangsa Indonesia. Kini hanya tersisa setitik api dengan pancaran sinar yang sangat lemah. Diperlukan kepedulian kita semua untuk memperbesar pancaran sinarnya hingga dapat menerangi jalan menelusuri kelampauan yang gelap gulita.
Sinar yang kian terang itu secara perlahan memulihkan ingatan kolektif bangsa Indonesia terhadap kejayaan budaya maritim pada masa silam. Kegiatan para sastrawan dalam webinar ini sangat penting untuk mencegah lenyapnya kejayaan sastra maritim karena tertiup angin perubahan zaman.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F09%2F2019%2F09%2F73%2Fee0%2FGOPR2269JPG%2FGOPR2269SILO.jpg)
Tim Gabungan Arkeologi Universitas Jambi dan Universitas Indonesia merekam data ekskavasi kapal kuno di Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Timur, Jambi, Sabtu (31/8/2019). Ekskavasi menjadi upaya menyingkap kebesaran wilayah itu sebagai jalur utama perdagangan di Asia Tenggara.
Sekadar memberikan contoh, kebangkitan sastra maritim di Amerika Serikat dan Inggris sudah dimulai 20 tahun yang lalu. Pada 2001, John Peck mengawalinya dengan memublikasikan kembali cerita-cerita fiksi tentang pelaut dan lautan dalam novel-novel karya penulis Inggris dan Amerika dalam kurun dua abad, dari tahun 1719-1917. Peck menyelamatkan ingatan kolektif bangsa Inggris dan Amerika terhadap cerita-cerita fiksi tersebut yang menggambarkan suasana zaman dan realitas sosial kehidupan para pelaut Ingris dan Amerika serta pandangan mereka terhadap lautan.
Buku Peck (Marittime Fiction: sailors and the Sea in British and American Novels, 1719-1917, New York: palgrave) membahas cerita-cerita lautan yang poluper di Inggris, seperti kisah Robinson Crusoe, Kapten Singleton, dan kisah para penjahat di lautan serta pertemuan mereka dengan pejabat tinggi Angkatan laut Kerajaan Inggris Sir John Franklin (1786-1847).
Peck membahas cerita-cerita fiksi penulis Amerika pada dua bab terpisah. Satu bab membahas cerita fiksi penulis James Fenimore Cooper (1789-1851), Edgar Allan Poe (1809-1849), dan Richard Henry Dana (1818-1852). Peck menggunakan pendekatan kronologi dalam pembahasannya dengan membahas cerita fiksi popular paling awal yang ditulis Cooper, The Pilot and the red Rover dan Afloat and Ashore dilanjutkan dengan karya Poe, The Narrative of Arthur Gordon Pyn dan Dana, Two Years Before the Mast.
Baca Juga: Jaga Optimisme Kejayaan Maritim Indonesia
Peck memberikan pembahasan tersendiri untuk cerita fiksi karya Herman Melville (1819-1891), seorang pelaut Amerika yang menjadi penulis berdasarkan pengalaman hidupnya. Cerita fiksi pertama yang ditulisnya berjudul Typee (1846) yang mengisahkan pengalaman hidupnya dengan penduduk asli suatu pulau. Pada tahun yang sama juga menulis kisah hidupnya di Tahiti dalam cerita fiksi Ommo.
Pada tahun 1848 ia menuliskan pengalaman pertamanya berlayar dari Amerika ke Inggris dalam certita fiksi, Redbust. Dua tahun kemudian menerbitkan cerita fiksinya yang berisi protes terhadap perlakuan yang sangat kejam dari Angkatan Laut Amerika terhadap para pelaut
Buku Peck, Maritime Fiction: sailors and the Sea in British and American Novels tersebut telah memberikan inspirasi penulis lain untuk melakukan kajian serupa yang beroirentasi lautan. Pada tahun 2011 terbit kumpulan tulisan yang diedit oleh Sebastian I Sobecki, The Sea and Englishness in the Middle Ages; Shin Yamashiro (2014), American Sea Literature: Seascapes, Beach Narrative, and underwater explorations; Brian Bernard (2015), Writing the South Seas: Imagining the Nanyang in Chinese and Southeast Asian Postcolonial Literature; Charlotte Mathieson (2016), Sea Narratives: Cultural Responses to the Sea, 1600-Present.
Abdul Syukur, Dosen Prodi Pendidikan Sejarah Korpus Penelitian Sosial, Ekonomi, dan Humaniora Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNJ