Mimpi Indonesia yang Berkelanjutan
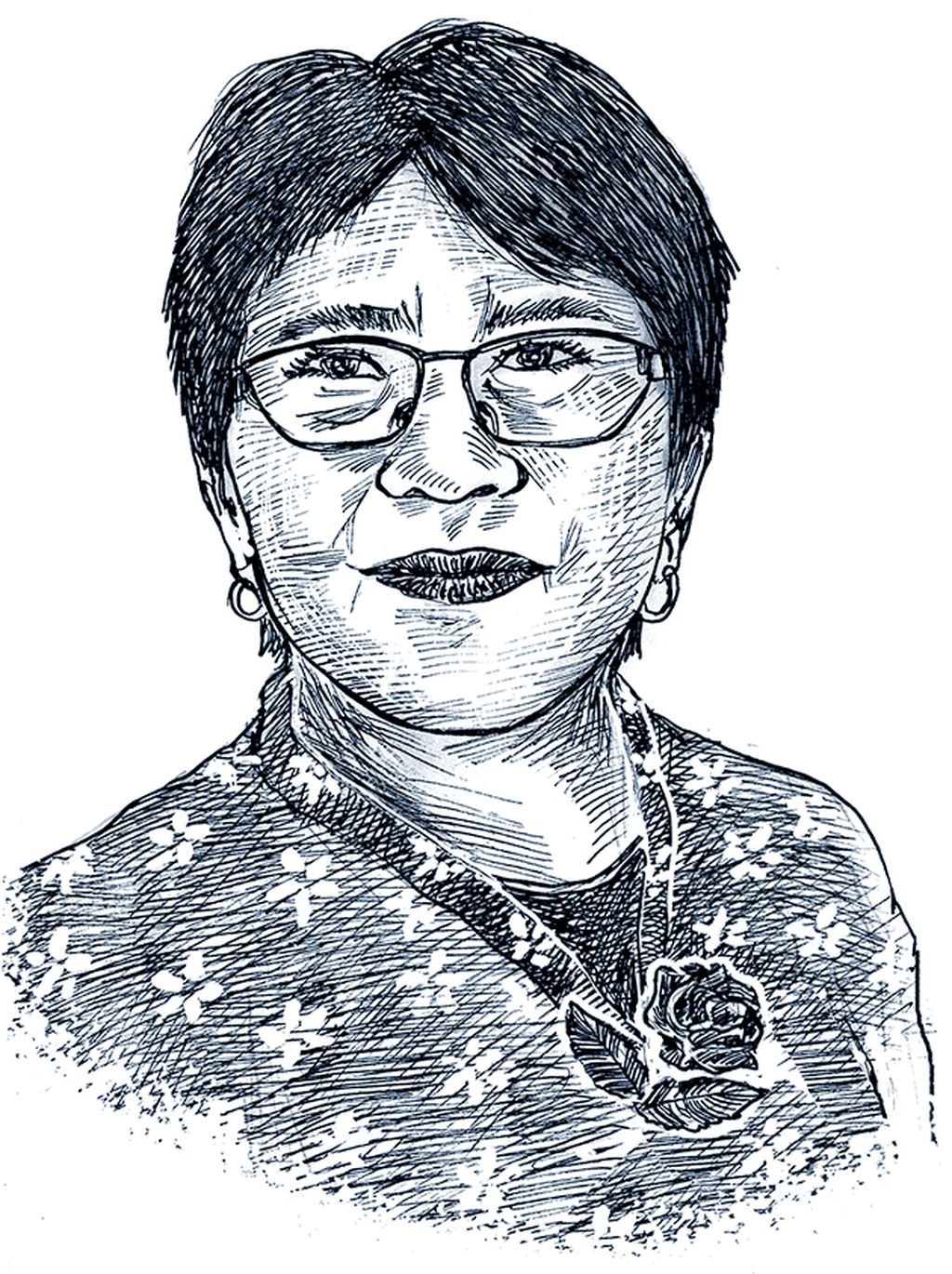
Brigitta Isworo Laksmi, wartawan senior Kompas
Indonesia tahun 2045 harus tetap ada. Pada tahun itu, Indonesia genap berusia 100 tahun. Untuk mencapai usia seabad, prasyarat utama adalah keberlanjutan yang berlangsung di semua sisi. Ini sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 PBB.
Pada suatu seminar di Jakarta lima tahun lalu, menteri lingkungan hidup pertama Indonesia, Emil Salim, menyatakan harapannya: Indonesia tetap ada setelah 100 tahun merdeka, sejahtera, adil dan makmur, gemah ripah loh jinawi, dengan syarat jika rakyatnya ada dan wilayahnya ada.
Modal utama Indonesia adalah wilayahnya yang kaya akan sumber daya alam. Modal lainnya adalah sumber daya manusia. Kekayaan alam Indonesia ditunjang oleh keluasan bentang alamnya, posisi geografisnya, dan kondisi geologisnya. Luas wilayah Indonesia sekitar 7,8 juta dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Sementara dengan sekitar 265 juta penduduk, terbanyak nomor empat di dunia, itu merupakan modal luar biasa.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2F20180122NUT005.jpg)
Pemandangan hijaunya hutan terlihat jelas melalui jendela pesawat dalam penerbangan dari Asmat menuju Timika, Papua, Senin (22/1/2018). Salah satu modal pembangunan Indonesia adalah wilayahnya yang kaya akan sumber daya alam.
Negeri ini negara terpanjang yang dilalui garis khatulistiwa yang melahirkan hutan hujan tropis yang amat luas. Negara kepulauan dengan pulau terbanyak, sekitar 17.000 pulau. Secara geologis, Indonesia berada di atas tiga lempeng bumi, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Karena posisi tersebut, Indonesia masuk dalam kawasan ring of fire, Indonesia memiliki gunung api terbanyak di dunia dan kaya akan sumber minyak bumi, gas bumi, dan aneka mineral.
Baca juga:
Pembangunan Rendah Karbon dan Pekerjaan Rumahnya
Dari hutan hujan tropis yang luas dan pertemuan dua samudra: Lautan Hindia dan Samudera Pasifik, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati (kehati) di darat dan di laut yang luar biasa. Maka, sering disebut sebagai negara megabiodiversity.
Dengan segala keunikan dan kekayaan itu, Indonesia sering kali menjadi sorotan di panggung internasional ketika berbicara isu-isu lingkungan atau isu-isu pembangunan berkelanjutan. Sadar akan sorotan dunia internasional, Indonesia membuat berbagai komitmen, di antaranya Paris Agreement terkait dengan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), Konvensi Keanekaragaman Hayati PBB, dan Stockhlom Convention on Persistent Organic Pollutant, serta masih banyak lagi. Sejumlah provinsi pun membuat komitmen global.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F04%2F70161065.jpg)
Perairan Morotai di Maluku Utara masih memiliki kesehatan ekosistem terumbu karang yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan kehadiran ikan hiu sirip hitam (black tip) dalam penyelaman di beberapa titik selam, Kamis (13/9/2018), di perairan Pulau Mitita. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, baik di darat maupun di laut.
Dengan meratifikasi Paris Agreement, Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi pada upaya global menahan kenaikan suhu bumi agar tidak melampaui batas 2 derajat Celsius (dan dengan upaya keras menahan tidak lebih tinggi dari 1,5 derajat Celsius). Hutan menjadi ekosistem krusial bagi Indonesia.
Dalam dokumen Komitmen Nasional yang Diniatkan (NDC) yang pertama, November 2016, sebesar 63 persen emisi GRK Indonesia dari alih fungsi lahan serta kebakaran hutan dan gambut. Di berbagai forum global, Papua dipandang sebagai benteng pertahanan terakhir dunia. Sangat penting sebagai pertahanan dari ancaman pemanasan global dan perubahan iklim.
Di berbagai forum global, Papua dipandang sebagai benteng pertahanan terakhir dunia.
Di sisi lain, masih di tingkat global, Indonesia sering kali dipuji sejumlah pihak karena telah menelurkan berbagai regulasi dan lembaga. Untuk gambut, misalnya, regulasi moratorium gambut dan pembentukan Badan Restorasi Gambut mendapat apresiasi, juga Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang evaluasi dan penundaan perizinan perkebunan kelapa sawit. Dalam inpres ditekankan langkah evaluasi dan verifikasi data serta koordinasi, tetapi ketiganya tidak jelas sampai di mana hasilnya.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F12%2F73779321_1544712505.jpg)
Hamparan perkebunan kelapa sawit di kawasan Sei Mangkei, Kecamatan Bosar Maligas, Simalungun, Sumatera Utara, Senin (12/3/2018).
Yang terjadi justru, dalam waktu sekitar dua bulan dari penerbitan inpres, justru terjadi pelepasan dan penetapan batas areal untuk perkebunan kelapa sawit sekitar 10.000 hektar. Pelepasan ini kini menjadi perkara sengketa perundang-undangan melalui jalur nonlitigasi karena gugatan Pemkab Buol dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi). Tiga kata kunci: penundaan, evaluasi, dan peningkatan produktivitas sampai saat ini belum terdengar hasilnya.
Itu hanya sebagai contoh dari sorotan pada salah satu komitmen, yaitu menurunkan emisi GRK. Bagaimana dengan komitmen lainnya? Untuk isu penyelamatan biodiversitas, misalnya, juga tak terdengar kabarnya, misal soal clearing house data kehati dan sebagainya. Sebaliknya justru jenis satwa dan spesies tumbuhan dilindungi dikurangi jumlahnya. Kebijakan yang kemudian menuai banyak kritik.
Secara umum, paradigma pembangunan berjalan tampak seperti business as usual, sesuatu yang seharusnya diubah sesuai dengan komitmen penurunan emisi GRK. Komitmen tersebut disandarkan pada langkah meninggalkan business as usual. Pencapaian yang terjadi hanya berskala kecil, misalnya, beberapa kabupaten menerapkan pelarangan kantong plastik, kemenangan tuntutan pada pelanggaran UU terkait lingkungan hidup, dan penangkapan usaha penyelundupan satwa dan tumbuhan dilindungi.

Dua individu orangutan diselamatkan dari kebun sawit warga di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, karena keluar dari habitatnya beberapa waktu lalu. Usaha perlindungan hewan terancam punah harus terus digalakkan.
Langkah mewujudkan berbagai komitmen global amat dinanti oleh masyarakat di dalam negeri dan masyarakat dunia. Jangan sampai terus muncul pertanyaan di bawah panggung, ”Mana realisasi komitmen Indonesia?” Jangan sampai Indonesia dipandang sebagai bermanis wajah di dunia internasional—sebagai negara yang memiliki komitmen tinggi terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Sementara, di sisi lain, mengerjakan hal sebaliknya.
Jika pemerintahan tetap melanjutkan pekerjaan business as usual tersebut, jangan heran jika target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 tidak akan tercapai. Penandanya jelas: bencana semakin masif, tingkat konflik berbasis lahan tak berkurang atau justru bertambah, masyarakat kelompok miskin bertambah, dan tingkat kesehatan masyarakat menurun.
Yang dibutuhkan bukan Indonesia menjadi ”anak manis” di level internasional. Yang dibutuhkan adalah bagaimana menciptakan Indonesia yang berkelanjutan 100 tahun mendatang. Bagaimana menjamin kehidupan generasi mendatang, anak-anak Indonesia pada masa depan, menjamin kesejahteraan masyarakat warga negara. Semoga harapan Emil Salim tak hanya tinggal menjadi mimpi seorang perintis….