Tantangan Realitas Geopolitik Baru
Hingga kini institusi-institusi internasional belum efektif mengatasi kelabilan global sebagai akibat dari tindakan perang dan agresi militer. Ada sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia di masa depan.
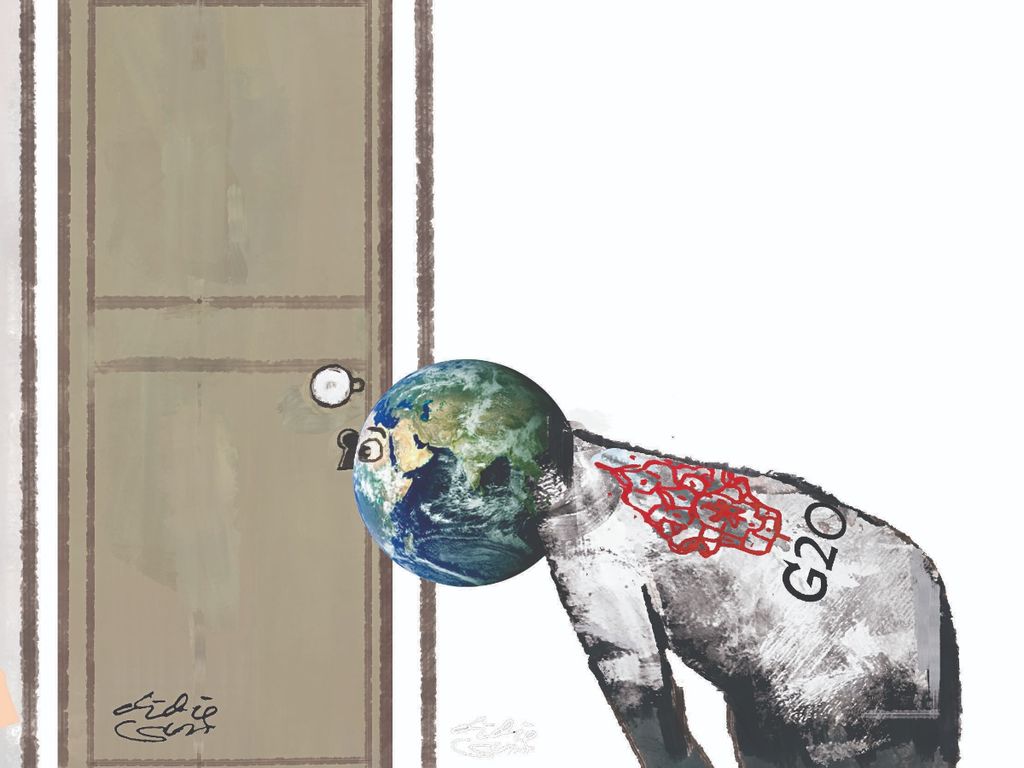
Didie SW
Ada tiga tantangan realitas geopolitik baru yang dihadapi Indonesia di masa depan. Ketiga tantangan ini muncul segera setelah terjadi perang Rusia- Ukraina dan membutuhkan tanggapan kebijakan yang jelas.
Tiga tantangan ini diyakini akan tetap menjadi problematik bagi Indonesia seandainya pun perang itu selesai dalam waktu dekat ini.
Asumsi dasarnya adalah hingga kini institusi-institusi internasional belum efektif untuk mengatasi kelabilan global sebagai akibat dari tindakan perang dan agresi militer.
Tiga tantangan
Tantangan pertama, bagaimana mengatasi gangguan mata rantai pasokan global (supply chain disruption), terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan dan esensial lainnya, ketika perang terjadi. Beberapa negara berkembang telah merasakan dampak gangguan ini.
Sebagai misal adalah Mesir. Hampir 80 persen gandum negeri ini dilaporkan berasal dari Rusia dan Ukraina. Tentu saja gudang-gudang penyimpanan gandum di Mesir segera mengalami gangguan pasokan dengan perang Rusia-Ukraina ini.
Tanggapan kebijakan Pemerintah Mesir terhadap situasi ini sangat keras. Para petani gandum diwajibkan menjual sebagian dari hasil panennya kepada pembeli yang sudah ditunjuk pemerintah. Pelanggaran untuk memenuhi kewajiban ini akan mendapatkan hukuman penjara.
Namun, konsekuensi dari situasi Ukraina dan Rusia juga pasti terasa di Indonesia.
Tentu saja Indonesia tidak seperti Mesir. Namun, konsekuensi dari situasi Ukraina dan Rusia juga pasti terasa di Indonesia. Misalnya untuk gandum dan pupuk. Jika kita merujuk pada catatan informasi Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), 8 Maret 2022, tingkat ketergantungan Indonesia terhadap pasokan gandum dari Ukraina sekitar 30 persen.
Di sisi lain, tingkat ketergantungan Indonesia terhadap Rusia untuk menghasilkan pupuk berada pada angka sekitar 15 persen. Risiko gangguan pasokan ini tentu saja perlu segera diatasi.
Gangguan di sisi pasokan niscaya memicu kenaikan harga. Setelah gangguan pasokan yang bermuasal dari pandemi Covid-19, laporan-laporan internasional hampir semua sepakat bahwa perang Rusia-Ukraina telah meningkatkan inflasi global yang tinggi dan sedang menjalar ke banyak negara. Turki, misalnya, dilaporkan mengalami inflasi hampir sekitar 60 persen pada bulan Maret ini.
Baca juga BPS: Dampak Konflik Rusia-Ukraina terhadap Kinerja Perdagangan RI Kecil
Kecemasan terhadap dampak inflasi global ini sangatlah serius. Tidak semua negara memiliki kapasitas fiskal yang sama untuk melembagakan tradisi intervensi dalam subsidi harga pangan, misalnya. Pilihannya memang tidak mudah. Risiko fiskal, seperti meningkatnya beban utang, pasti akan meningkat jika pemerintah tetap melakukan intervensi. Namun, jika intervensi tidak dilakukan, risiko politik juga meningkat, misalnya aksi protes mempertanyakan legitimasi dan kredibilitas untuk memerintah.
Tantangan kedua, bagaimana mengatasi gangguan aliran modal internasional yang disebabkan oleh dinamika geopolitik global. Walaupun Moskwa belum menjadi salah satu pusat keuangan global seperti New York, London, ataupun Tokyo, penggunaan instrumen keuangan (financial statecraft) untuk menekan Rusia sedikit banyak telah mengganggu aliran modal internasional.
Penggunaan instrumen financial statecraft terhadap negara-negara yang tidak disukai untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya tampak semakin sering dilakukan Amerika Serikat (AS).
Pelarangan penggunaan fasilitas pembayaran internasional antarbank melalui The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) terhadap Rusia sebenarnya pernah juga dilakukan terhadap Iran pada 2018.

Toto Sihono
Terdapat skenario bahwa situasi ini kemungkinan besar dalam jangka menengah dan panjang akan mendorong beberapa negara untuk menciptakan kerangka kerja sama keuangan tandingan.
Tindakan pembekuan aset dan penghentian fasilitas SWIFT tampaknya tidak hanya membuat cemas Rusia, tetapi juga banyak negara lain. Walaupun tidak dinyatakan secara terbuka, sebagian negara merasa betapa rentannya mereka terhadap tindakan-tindakan sepihak dari AS dan sekutunya.
Tidak hanya dalam soal perdagangan dan investasi, beberapa negara juga mengalami kesulitan untuk melanjutkan kemitraan dalam pengembangan industri pertahanan dengan Rusia.
Indikasi terhadap kebutuhan untuk menciptakan kerangka tandingan ini misalnya terlihat dari dorongan untuk penggunaan mata uang non-dollar AS dalam transaksi bisnis internasional. Usaha ini tentu saja tidak mudah. Merujuk informasi yang diberikan Dewan Gubernur The Fed, diperkirakan sekitar 60 persen cadangan devisa negara-negara di seluruh dunia masih dalam bentuk mata uang dollar AS. Namun, lembaga itu juga menyebutkan bahwa telah terjadi penurunan.
Tujuh tahun sebelumnya berkisar pada angka 71 persen. Dalam kaitan ini, Rusia sebenarnya bukanlah pelopor untuk melakukan perlawanan terhadap dominasi dollar AS ketika pemimpin negeri tersebut baru-baru ini menyatakan adanya keharusan penggunaan rubel dalam transaksi bisnis energi dengan Rusia.
Tantangan ketiga terkait dengan peta pusat-pusat geopolitik dan geoekonomi global di masa depan.
Kajian yang dilakukan Lun Cao dalam Currency Wars and the Erosion of Dollar Hegemony (2016) menunjukkan bahwa keluhan terhadap dominasi dollar AS itu sudah berlangsung sejak lama dan semakin kuat pemikiran di lingkaran pembuat kebijakan strategis di banyak negara untuk meminggirkan dominasi dollar AS tersebut. Ia lebih jauh menyatakan, ”perang” mata uang secara besar-besaran tinggal masalah waktu saja dan jika ini terjadi akan menciptakan guncangan luar biasa dalam arus modal internasional.
Tantangan ketiga terkait dengan peta pusat-pusat geopolitik dan geoekonomi global di masa depan. Suka atau tidak suka akan terjadi perubahan peta tersebut. Kekuatan politik kolektif tandingan terhadap Pax-Americana melalui kehadiran Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan ( BRICS) yang dibentuk pada tahun 2006 memang tampak belum sepenuhnya efektif.
Namun, harus pula disebutkan bahwa kecuali Brasil, tiga anggota BRICS lainnya, yaitu India, China, dan Afrika Selatan, telah mengambil posisi abstain dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB yang mengecam Rusia pada awal Maret lalu. Posisi ini menyampaikan pesan terdapat silent opposition terhadap resolusi yang diusulkan AS itu.
Baca juga Kenaikan Harga, Ruang Substitusi, dan Daya Beli
Dalam konteks konfigurasi politik baru ini, penyelenggaraan G20 menjadi problematik. Jika Rusia tidak dilibatkan dalam G20, tantangan diplomatik baru akan muncul bagi Indonesia dalam hubungannya dengan China, Afrika Selatan, dan India. Adalah sebuah fakta bahwa G20 bukan sekadar agenda teknokratik terkait isu keuangan, pembangunan, energi, infrastruktur, ataupun perubahan iklim.
Di luar agenda teknokratik seperti itu, G20 merupakan agenda politik besar yang dirancang sejak awal untuk mengakomodasi realitas geopolitik baru setelah berakhirnya perang dingin. Karena itu, tanpa kehadiran Rusia, perimbangan kekuatan di dalam G20 akan lebih bergeser ke kubu negara-negara maju yang ada di G20 atau sering disebut sebagai kelompok G7 (AS, Inggris, Perancis, Italia, Jepang, Kanada, dan Jerman).
Tidak hanya itu. Agenda atau semangat untuk mereformasi institusi-institusi warisan Bretton Woods untuk kepentingan negara-negara berkembang, mungkin akan melemah.
Opini Indonesia dalam Diskursus Indo-Pasifik
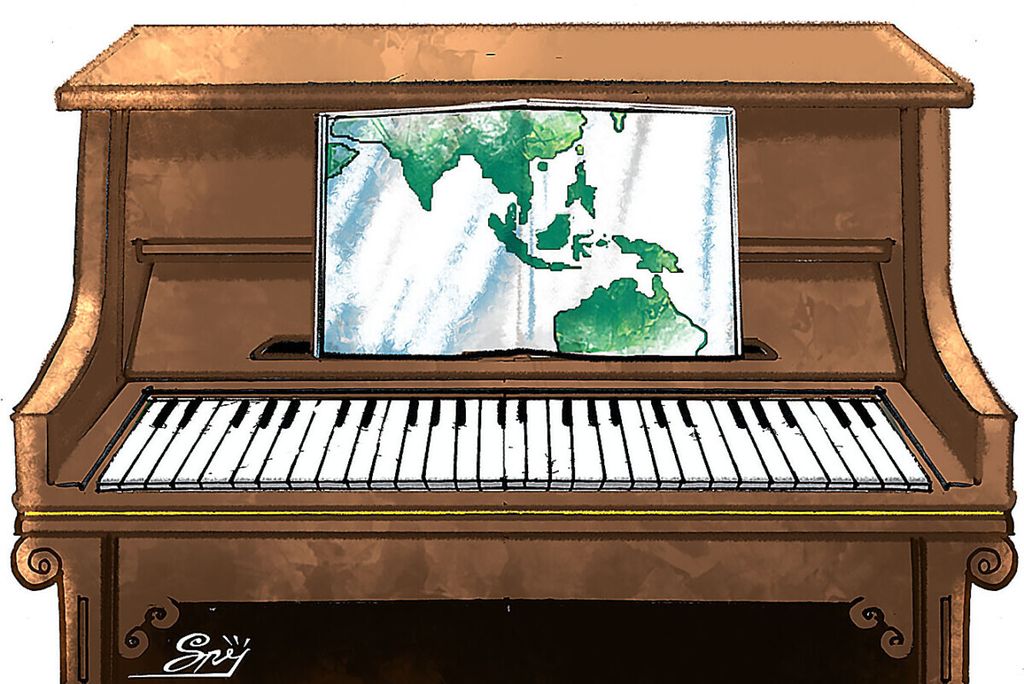
Supriyanto
Tanggapan kebijakan
Rusia kemungkinan telah menggunakan kerangka geopolitik klasik untuk melindungi kepentingan keamanan nasionalnya. Intinya adalah kontrol melalui pendudukan militer terhadap wilayah yang dianggap mengancam adalah suatu keharusan.
Di sisi lain, AS dan sekutunya telah menggunakan kerangka geoekonomi, terutama melalui instrumen keuangan, untuk mengendalikan dan mendorong Rusia masuk ke meja perundingan. Mencari titik tengah dari dua pendekatan yang berbeda ini adalah suatu proses yang tengah berlangsung.
Apakah instrumen geopolitik klasik dan atau geoekonomi yang lebih banyak digunakan, ada tiga usulan kebijakan yang ingin disampaikan.
Pertama, dinamika politik global yang tinggi pada tahun-tahun yang akan datang tampaknya mengharuskan kita untuk meluncurkan kebijakan dan regulasi yang kuat untuk lebih melihat ke dalam (inward looking policy), terutama untuk komoditas yang sangat penting bagi publik, seperti pangan, energi, dan obat-obatan, ataupun untuk pengembangan industri pertahanan.
Rusia kemungkinan telah menggunakan kerangka geopolitik klasik untuk melindungi kepentingan keamanan nasionalnya.
Kebijakan seperti ini tidak harus ditafsirkan sebagai perdebatan pro-negara atau pro-pasar, tetapi prioritas diarahkan untuk memenuhi kebutuhan domestik dan meningkatkan ketahanan nasional.
Untuk tujuan tersebut, di samping peningkatan di sisi produksi, kapasitas untuk public stockpiling untuk pangan, misalnya, dan jumlah hari untuk protokol cadangan energi perlu ditingkatkan.
Di sisi fiskal muncul juga pertanyaan lain, misalnya apakah norma ambang batas defisit 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) masih akan tetap dianut? Secara praktis norma ini sebenarnya telah diterobos dalam masa pandemi dan akan kembali pada tahun depan. Namun, apakah angka ini sebaiknya tidak ditingkatkan melalui regulasi baru di tataran undang-undang menjadi 4 persen?
Kedua, mengingat kemungkinan adanya guncangan dalam bentuk “perang” mata uang, Indonesia perlu menyebarkan risikonya dengan mendiversifikasikan cadangan devisa mata uang yang dimiliki tak lagi mayoritas dollar AS dan memperbanyak kesepakatan bilateral untuk penyelesaian melalui mata uang lokal (local currency settlement) dengan mitra dagang utama kita.
Ketiga, tetap melibatkan Rusia dalam kerangka kerja sama G20. Dinamika politik global akan sangat ditentukan juga bagaimana Rusia menjalin hubungan, khususnya dengan China. Karena itu, hubungan segitiga Rusia-China-AS patut untuk terus dicermati, terutama dalam kaitannya dengan upaya reformasi terhadap lembaga-lembaga internasional dan juga untuk menjaga tradisi politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
Makmur Keliat, Pengajar Ilmu Hubungan Internasional UI, Senior Fellow di Lab45