Jembatan Ilmu yang Rapuh
Para akademisi filsafat diharapkan mampu memasuki ilmu-ilmu baru, seperti ”data science”, teknobiomedik, dan ”marketing”. Mereka berperan memberi pendasaran keilmuan yang kuat, juga agar filsafat tidak merapuh.
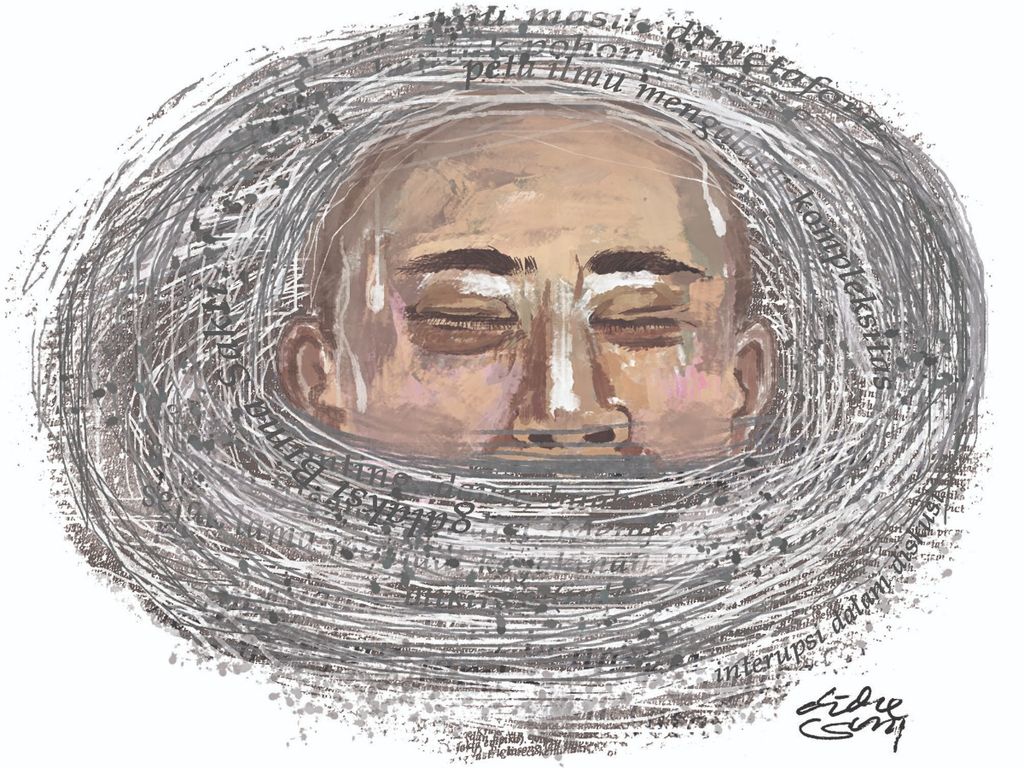
Benarkah hanya filsafat yang bisa menjadi jembatan bagi banyak disiplin ilmu? Pertanyaan ini jadi respons epistemik bagi tulisan Siti Murtiningsih di Kompas (25/3/2022) berjudul ”Jembatan Ilmu-ilmu”.
Sebelum mendedah pemikiran Murtiningsih lebih jauh, saya terlebih dahulu memberi ”duduk perkara inti” dari tulisannya, untuk kemudian menjadi status quaestiones (state of investigation). Murtiningsih memulai tulisannya dengan berangkat dari situasi formal, bahwa ada itikad baik dari pemerintah untuk mengantisipasi spesialisasi ilmu dengan multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner. Ketiga yang disebut terakhir ini menjadi semacam jembatan antarilmu.
Murtiningsih kemudian mengonstruksi tesis, bahwa filsafat menjadi jembatan ilmu tersebut. Tesis berangkat dari keterbelahan antara ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu humaniora. Ia membuktikan, pertama CP Snow telah membangun jembatan agar ilmu bisa ”berdamai” antara satu dan yang lain. Kedua, usulan Veit dan Ney bahwa metafora bisa jadi landasan bersama bagi seni dan sains.
Ada kenaifan repetitif dalam tesis Murtiningsih.
Ada kenaifan repetitif dalam tesis Murtiningsih. Kenaifan repetitif oleh karena, pertama, filsafat dengan segala kebesarannya di masa lalu hingga saat ini masih diyakini dan sebagian besar masih diagung-agungkan para punggawa yang berumah di fakultas filsafat. Kedua, filsafat yang dalam arti luas sebagai pemikiran, nalar, bisa menjadi solusi atas problem hidup beserta detail-detail kerumitannya. Untuk itu, filsafat, bagi Murtiningsih, perlu mengambil posisi sebagai teman bagi ilmu-ilmu lain.
Kompetisi ilmu-ilmu
Pertanyaan awal, benarkah filsafat bisa menjadi jembatan (atau teman) bagi banyak disiplin ilmu? Dari ajuan proposal Murtiningsih, jawabannya: tidak. Hal ini disebabkan pemikirannya secara de facto kurang menyadari bahwa ilmu-ilmu masih dimetaforakan dalam bentuk pohon rindang, dengan ranting, daun, buah, yang akarnya adalah filsafat sendiri. Metafora ini sudah sejak lama menjadi keyakinan bagi alam pemikiran (interioritas) mereka yang sebagian besar pernah belajar di fakultas atau jurusan filsafat. Ini sudah rapuh.
Kerapuhan itu oleh karena ilmu-ilmu lain sudah berkembang dengan pesat dan berada pada kompleksitas. Antarilmu berkompetisi untuk menjadi pemegang mandat atas otoritas kebenaran. Matematika, misalnya, bagi Eric Temple Bell, menjadi ratu dan pelayan ilmu. Jika matematika menjadi raja, fisika kemudian didaulat oleh peraih Nobel, David J Gross, adalah raja dari semua ilmu pengetahuan. Asumsi-asumsi ini menjadi lanjutan dari ide Immanuel Kant bahwa metafisika pada masa pencerahan adalah ratu ilmu-ilmu.
Baca juga Jembatan Ilmu-ilmu
Pertanyaan lanjutan adalah bagaimana ilmu saling berhubungan? Apakah jembatan (seperti yang dibayangkan Murtiningsih) masih cukup menjadi penghubung bagi begitu banyaknya ilmu? Peta keterhubungan paradigma bisa menjadi alternatif solusi. Situasi mutakhir yang diungkap oleh para peneliti di Los Alamos National Laboratory, bahwa peta ilmu mengalami kompleksitas.
Peta ilmu-ilmu dalam gambaran mereka tidak lagi ada dalam metafora pohon rindang, tetapi seperti galaksi Bima Sakti. Topografi pengetahuan kemudian bergantung pada basis data ilmu alam dengan berjejaring pada Thomson Scientific, Elsevier, Jstor, Ingenta, dan beberapa kampus Universitas Texas dan California State University. Selain itu, mereka memetakan pola perhatian, minat pada kutipan lintas jurnal.
Imajinasi filsafat sebagai jembatan dan teman, dengan demikian, kurang adekuat untuk menjadi paradigma keterhubungan ilmu. Apakah dengan begitu, filsafat kemudian tiba pada titik nadir untuk tiba pada kematiannya seperti yang didengungkan fisikawan seperti Stephen Hawking dan dilanjutkan Lawrence Krauss? Tentu tidak! Filsafat, bagi saya, tetap memiliki daya pikat dengan melakukan interupsi dialektis.
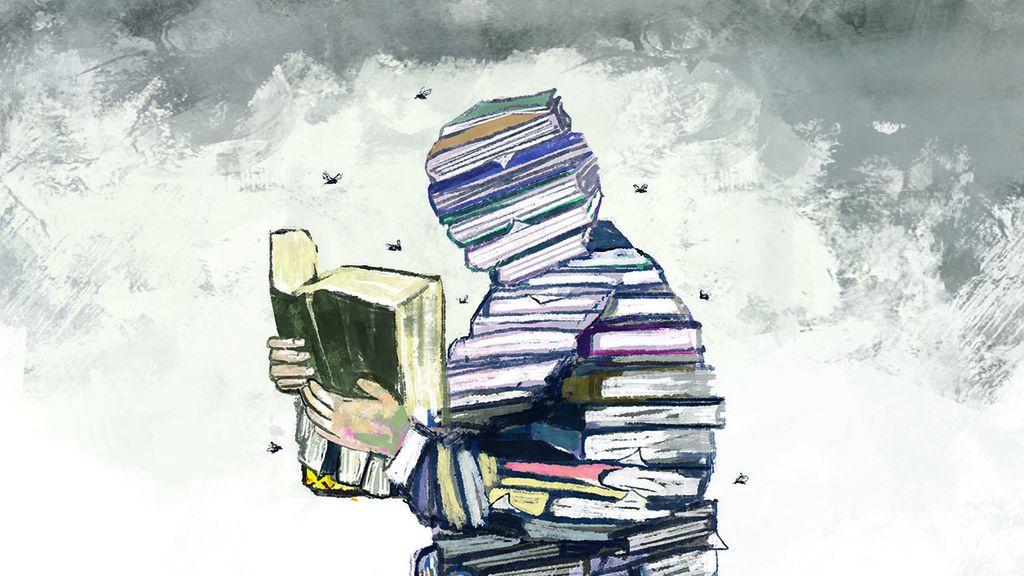
Dalam suatu diskusi panel tentang The Limit of Science, Krauss diinterupsi oleh Massimo Pigliucci dan Daniel Dennett. Krauss meyakini bahwa sains secara keseluruhan didasarkan pada fakta-fakta empiris, termasuk juga matematika (dan fisika). Pigliucci menegaskan pernyataan tersebut sebagai suatu kemenangan palsu yang justru kosong (an empty pyrrhic victory). Pigliucci kemudian menegaskan bahwa filsafat adalah tentang berpikir.
Krauss melanjutkan bahwa kebanyakan para saintis tidak lagi membaca filsafat. Pernyataan Krauss dibalas dengan telak oleh Daniel Dennett, ”You can’t do science without doing philosophy.” Ungkapan Dennett sesungguhnya menegaskan bahwa ”bagaimana kita bisa berpikir tanpa melalui filsafat?”
Poin penting yang ingin saya ajukan, pertama, filsafat hadir tidak sekadar menjadi teman, tetapi lebih sebagai seorang interuptor. Jika hanya sebagai teman dengan tiga peran (mendengarkan, merasa paling tua, dan menjadi jembatan penengah), filsafat memang menjadi ketinggalan dan tidak menarik. Apalagi jika seorang pelajar filsafat, misalnya, dalam diskusi, hanya menjalankan tiga peran tersebut, maka filsafat akan terbungkam, didominasi, dan hanya mencoba mengambil jalan ”berdamai-damai” saja. Filsafat menjadi rapuh dan tidak asyik.
Dalam kurikulum pendidikan di perguruan tinggi, keterbelahan antara ilmu pasti dan ilmu humaniora sebenarnya telah lama dijembatani.
Problem mengasyikkan
Filsafat justru perlu mengambil jalan lain, yaitu melakukan interupsi dalam diskusi, seperti yang dilakukan Pigliucci dan Dennett, agar diskusi menjadi diskursus dengan tegangan-tegangan dialektis hingga tiba pada suatu kenikmatan berpikir.
Jika terjadi kebuntuan (aporia), tidak perlu menjadi kekhawatiran karena, dalam filsafat, ”tidak menemukan suatu jawaban adalah suatu jawaban”. Interupsi dilakukan pertama-tama untuk memancing pertanyaan-pertanyaan baru untuk hadir. Untuk itu, dalam filsafat, bukan jawaban, melainkan problem dalam suatu pertanyaan yang menjadi suatu kenikmatan berpikir.
Reposisi filsafat, bagi saya, tidak perlu, terutama dalam kurikulum. Hal ini kurang disadari oleh Murtiningsih. Reposisi sebagai suatu pengandaian menyimpan suatu sakit (karena terjadi pergeseran, atau karena patah tulang persendian). Dalam kurikulum pendidikan di perguruan tinggi, keterbelahan antara ilmu pasti dan ilmu humaniora sebenarnya telah lama dijembatani.

Di Institut Teknologi Bandung (ITB), misalnya, program studi Ilmu Seni Rupa dan Desain menjadi bukti bahwa keterbelahan ilmu tidak lagi menjadi problematis. Ilmu Filsafat di ITB diajarkan dengan sangat menantang dan mengasyikkan oleh Profesor Bambang Sugiarto. Bambang menjangkarkan spirit kampusnya dengan ungkapan In Harmoniae Progressio (Kemajuan dalam Keselarasan). Situasi ini, de facto, diabaikan oleh Murtiningsih.
Hal yang perlu disadari bahwa dalam lingkup humaniora pun, ilmu-ilmu saling berkompetisi. Bidang atau rumpun ilmu yang dibentuk dan dikonstruksi para desainer kurikulum tidak lantas meredakan atau bahkan menghasilkan konvensi bulat dan permanen antarilmu yang satu dengan ilmu yang lainnya. Ilmu hukum tentu memiliki pendasaran-pendasaran ilmu yang berbeda secara paradigma dengan ilmu sosial-politik.
Begitu pula dengan percabangan ilmu-ilmu humaniora yang semakin kompleks hingga saat ini.
Kasus pawang hujan, yang dicontohkan Murtiningsih, justru bukan hanya ada dalam pertentangan antara ilmu humaniora dan eksakta. Sesama ilmu dalam humaniora justru memiliki keberagaman pola pikir untuk melihat fenomena pawang hujan di Mandalika.
Ilmu filsafat dan ilmu budaya mungkin bisa dengan mengungkapkan ada dimensi kearifan lokal yang diyakini ada untuk mengendalikan hujan. Namun, dalam teologi yang masih setia pada dogma-dogma revelasionis (pewahyuan), pawang hujan terkadang dipahami sebagai bentuk tindakan syirik, melawan kehendak takdir, dan perlu dijauhi.
Relasi ilmu-ilmu humaniora dengan eksakta pun tak selalu berjalan langgeng. Filsafat biologi, misalnya, diajarkan di fakultas biologi, tetapi pengajarnya dipilih dari dosen internal fakultas itu sendiri. Pengandaiannya, jika dosen biologi yang sudah memperoleh pendidikan formal strata tiga, maka sudah mendapat mata kuliah filsafat (baik itu dasar-dasar filsafat maupun filsafat ilmu).
Akademisi filsafat berperan untuk mengajukan ”status quaestiones”, memberikan pendasaran-pendasaran dari ilmu-ilmu baru tersebut.
Jadi, filsafat biologi pun kemudian menjadi suatu bentuk pengajaran yang amat standar karena eksplorasi filosofisnya kurang mendalam, dan kurang kuat. Imbas tersebut yang terjadi saat filsafat bertemu dalam pengajaran pada bidang-bidang eksakta.
Terakhir sebagai tantangan, para akademisi filsafat diharapkan mampu memasuki ilmu-ilmu baru yang bermunculan, seperti aktuaria, data science, teknobiomedik, dan pemasaran digital. Akademisi filsafat berperan untuk mengajukan ”status quaestiones”, memberikan pendasaran-pendasaran dari ilmu-ilmu baru tersebut.
Namun, yang tidak kalah pentingnya, pemerintah perlu diajak berdialog bahwa filsafat justru berfungsi untuk memberikan suatu pendasaran keilmuan yang kuat, dan bila perlu pada tahap sekolah menengah atas, agar filsafat tidak merapuh.
Andri Fransiskus Gultom, Dosen Filsafat Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dan Pendiri Institut Filsafat Pancasila

Andri Fransiskus Gultom