Jembatan Ilmu-ilmu
Seruan Presiden dan juga kebijakan Kemendikbudristek itu merupakan iktikad baik pemerintah untuk memoderasi spesialisasi ilmu yang terlampau ekstrem. Filsafat dibutuhkan sebagai penengah perbedaan bidang-bidang ilmu.
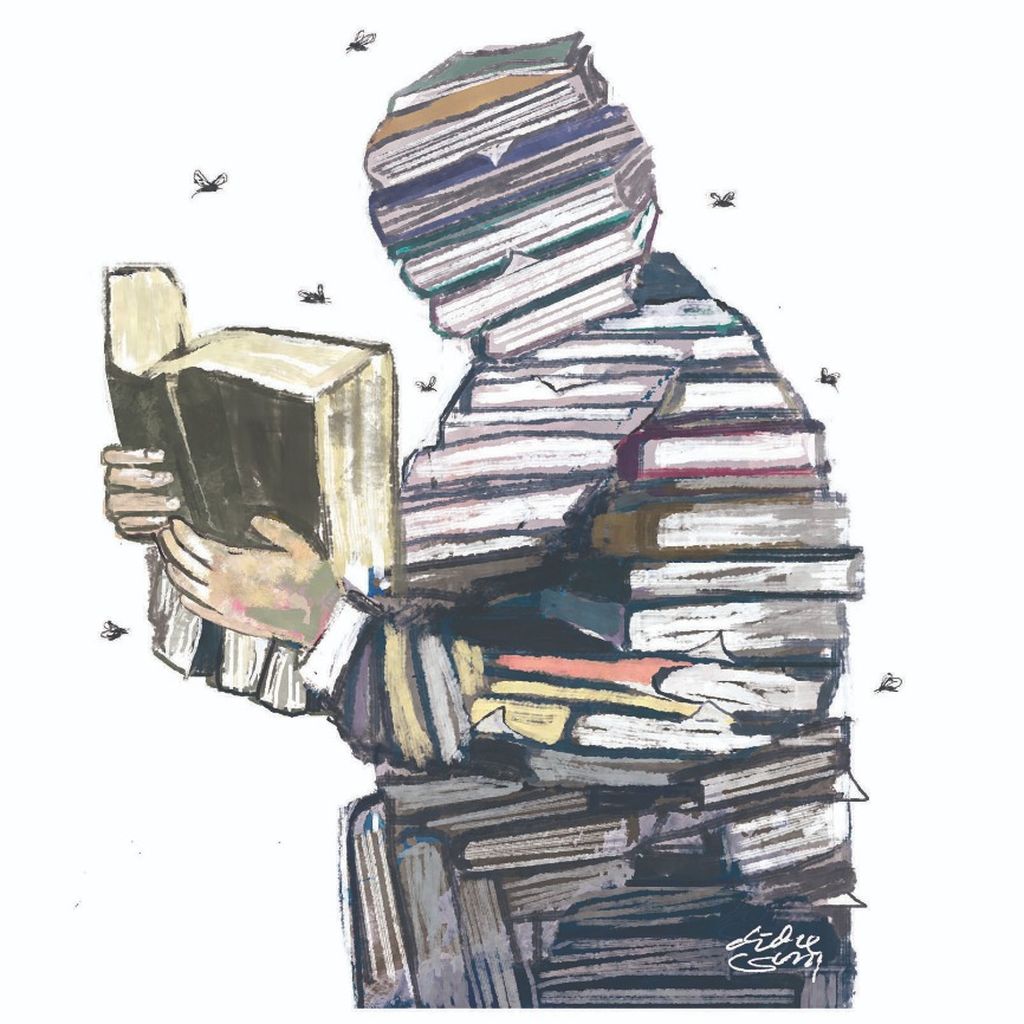
Presiden Joko Widodo meminta kampus agar jangan memagari mahasiswa dengan terlalu banyak program studi. Permintaan Presiden yang disampaikan dalam sambutannya di Dies Natalis salah satu perguruan tinggi negeri pada 17 Januari 202, ini senada dengan salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
Pernyataan Jokowi dan juga kebijakan Kemendikbudristek itu bisa dilihat sebagai respons terhadap dua hal. Pertama, respons terhadap spesialisasi ilmu yang terlampau ekstrem. Kedua, respons terhadap perkembangan zaman yang persoalan-persoalannya tak hanya menuntut solusi-solusi multidisipliner, tetapi juga interdisipliner, bahkan transdisipliner.
Dua budaya
Di Eropa, fenomena spesialisasi ilmu secara ekstrem itu terjadi pada abad ke-20. Fenomena itu dipotret dengan sangat baik oleh seorang ilmuwan dan sekaligus sastrawan asal Inggris, CP Snow. Dalam ceramahnya yang disampaikan di Universitas Cambridge, Snow (1959) menggambarkan kehidupan intelektual masyarakat Barat yang terbelah dua antara bidang ilmu alam dan humaniora. Ia menyebutnya sebagai fenomena ”Dua Budaya” (Two Cultures).
Presiden Joko Widodo meminta kampus agar jangan memagari mahasiswa dengan terlalu banyak program studi.
Snow mengalami sendiri betapa lebarnya jurang antara dua jenis kehidupan intelektual ini. Sebagai ilmuwan alam sekaligus sastrawan, ia harus bolak-balik di antara keduanya seperti sedang melintasi samudra. Ia bekerja dengan koleganya dari ilmu alam pada waktu siang dan bertemu teman-temannya sesama sastrawan pada waktu malam. Di antara dua kelompok pertemanan Snow itu tak ada yang saling mengenal.
Bahkan, kata Snow dalam ceramahnya, di antara mereka bukan hanya tak saling mengenal, melainkan juga ”terkadang (terutama di antara yang muda-muda) ada permusuhan dan kebencian”. Orang-orang dari lingkar ilmu alam menganggap orang-orang humaniora tak ilmiah, politis, dan sering kali punya pandangan suram serta pesimistik terhadap kemajuan sains, sedangkan orang-orang humaniora menganggap para ilmuwan terlalu optimistik dan tidak mengerti kondisi manusia.
Melihat jurang pemisah di antara dua bidang keilmuan itu yang teramat lebar sehingga menciptakan kecurigaan, stigma, dan bahkan kebencian, Snow berusaha membangun jembatan yang memungkinkan orang-orang dari dua bidang tersebut bisa saling bertemu, saling memahami, dan berdialog satu sama lain. Apa yang diusahakan oleh Snow ini semestinya juga dilakukan oleh orang-orang terdidik di Indonesia.
Baca juga:Mengurangi Kesenjangan antara Kemajuan Sains dan Pendidikan Sains
Namun, sayangnya, sampai kini kita masih menyaksikan fenomena Dua Budaya dalam kehidupan intelektual kalangan terdidik Indonesia, seperti terjadi di Eropa seabad silam. Orang-orang yang berlatar belakang ilmu alam atau eksakta jarang sekali yang mau tahu dengan isu-isu seputar humaniora atau—paling tidak—membaca karya sastra. Demikian juga orang-orang dari bidang humaniora jarang sekali yang mau mengikuti dan bersikap apresiatif terhadap apa yang diupayakan para ilmuwan.
Akhirnya, dua kelompok dari dua latar belakang keilmuan ini cenderung berbicara sendiri-sendiri dalam konteks bidang keilmuan masing-masing. Contoh mutakhir yang bisa kita lihat langsung adalah bagaimana mereka merespons aksi pawang hujan dalam acara MotoGP Mandalika, Minggu (20/3/2022).
Sebab, di luar soal ilmiah/tidak ilmiah, ada soal-soal antropologis dan sosiologis yang tidak bisa dinafikan.
Orang-orang dari latar belakang ilmu alam cenderung bersikap negatif terhadap aksi itu dan menganggapnya klenik, mistik, tak ilmiah. Dari sudut pandang ilmu alam, aksi itu memang tak ilmiah sehingga wajar jika ilmuwan alam bersikap tak simpatik sama sekali.
Namun, di sisi lain, orang-orang dari latar belakang ilmu humaniora cenderung lebih simpatik dan apresiatif terhadap aksi pawang hujan itu serta menganggap koleganya dari ilmu alam sebagai berpandangan positivistik. Dari sudut pandang humaniora, aksi pawang hujan itu tak bisa dinilai semata soal ilmiah atau tak ilmiah. Sebab, di luar soal ilmiah/tidak ilmiah, ada soal-soal antropologis dan sosiologis yang tidak bisa dinafikan. Semisal, soal pewarisan pengetahuan lokal, penghormatan kepada leluhur, dan mata pencarian.
Kecenderungan untuk berbicara sendiri-sendiri dari sudut pandang bidang keilmuan masing-masing ini tampaknya sudah terkondisikan sejak dari kehidupan kampus. Mahasiswa sosial-humaniora dikondisikan untuk hanya fokus pada bidangnya sendiri tanpa harus tahu dan berdialog dengan perkembangan ilmu alam serta eksakta. Demikian juga mahasiswa ilmu alam dan eksakta dikondisikan untuk hanya fokus pada bidang keilmuannya sendiri tanpa perlu peduli dengan persoalan-persoalan humaniora.

Pengondisian semacam itu akhirnya menciptakan lulusan-lulusan yang berkacamata kuda dengan imajinasi yang naif nan sempit. Mereka cenderung menjadi orang yang tak terbiasa dengan sudut pandang berbeda dan akhirnya rentan terpolarisasi oleh perbedaan-perbedaan. Kondisi itulah yang coba direspons oleh Presiden Jokowi dan kebijakan Kemendikbudristek.
Teman Ilmu-ilmu
Seruan Presiden Jokowi dan juga kebijakan Kemendikbudristek itu merupakan iktikad baik pemerintah untuk memoderasi spesialisasi ilmu yang terlampau ekstrem. Namun, untuk sampai pada tujuan yang baik, tidak cukup hanya dengan iktikad baik. Kita juga perlu cara yang baik dan benar.
Membongkar pagar-pagar bidang keilmuan, selain bisa menetralisir spesialisasi ekstrem, juga bisa melahirkan ekses negatif berupa apa yang oleh Tom Nichols (2017) disebut :matinya kepakaran: (the death of expertise). Hanya karena pernah mengikuti satu mata kuliah pengantar ekonomi makro, misalnya, seorang lulusan teknik nuklir bisa merasa punya otoritas untuk berkomentar (sesuai keyakinan personalnya) tentang krisis ekonomi selama pandemi.
Atau seorang lulusan psikologi yang, karena selama kuliah pernah mengambil satu mata kuliah di prodi biologi, merasa punya otoritas untuk berkomentar tentang penularan virus. Lebih buruk lagi, jika publik percaya begitu saja pada orang-orang semacam itu.
Tawaran solusi ini juga memerlukan upaya untuk mereposisi filsafat itu sendiri dalam kaitan dengan bidang-bidang keilmuan lain.
Bagaimana cara menghindari ekses negatif itu? Salah satu—atau mungkin satu-satunya—cara adalah dengan melibatkan satu bidang yang usianya sudah sangat tua, yaitu filsafat. Namun, ini bukan tawaran instan. Tawaran solusi ini juga memerlukan upaya untuk mereposisi filsafat itu sendiri dalam kaitan dengan bidang-bidang keilmuan lain.
Di antara para penekun filsafat, ada sebuah ”dogma” yang selalu diulang-ulang dengan penuh kebanggaan bahwa filsafat adalah ibu segala ilmu (the mother of sciences). Dengan ”dogma” ini, para penekun filsafat sering kali merasa jemawa mengingat bidang yang ditekuninya berada di puncak piramida keilmuan. Sikap jemawa ini sering kali juga membuat penekun filsafat sibuk dengan klaim-klaim besar, tetapi sebenarnya kosong dan menganggap remeh bidang-bidang ilmu lain yang dianggapnya hanya turunan dari filsafat.
Karena itu, untuk menghilangkan sikap jemawa ini, kita perlu mereposisi filsafat. Seharusnya kini filsafat tidak lagi dipahami sebagai ”ibu segala ilmu”, tetapi ”teman ilmu-ilmu”.
Sebagai teman, filsafat tak seharusnya bersikap jemawa terhadap bidang-bidang ilmu lain. Ia seharusnya mau mendengarkan apa saja yang telah ditemukan, dipelajari, dan diperdebatkan oleh teman-temannya itu. Dan, sebagai yang paling tua di antara teman-temannya, filsafat memiliki tanggung jawab untuk menjadi semacam jembatan penengah.
Dan, sebagai yang paling tua di antara teman-temannya, filsafat memiliki tanggung jawab untuk menjadi semacam jembatan penengah.
Jika, misalnya, ada pertentangan di antara dua bidang keilmuan, maka filsafat memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan dua-duanya dan kemudian berusaha menciptakan dialog agar tercipta landasan bersama (common ground). Salah satu contohnya adalah apa yang dilakukan oleh Walter Veit & Milan Ney dalam artikelnya yang berjudul ”Metaphor in Arts and Science” (2021).
Ilmuwan umumnya memandang kerja ilmiah hanya berkaitan dengan nilai epistemik (apa yang benar?); sedangkan seniman umumnya memandang kerja artistik hanya berkaitan dengan nilai estetik (apa yang indah/elok/elegan/membangkitkan pengalaman estetik). Dalam beberapa hal, yang indah kadang bertentangan dengan yang benar sehingga seni sulit bertemu dengan sains. Veit & Ney, yang sama-sama akademisi filsafat, berusaha menjembatani dua bidang yang tampak tak dapat disatukan itu.
Bagi mereka, landasan bersama bagi seni dan sains adalah metafora. Di dalam seni, metafora tak hanya memiliki fungsi estetik, tetapi juga fungsi epistemik. Demikian juga di dalam sains, metafora tak hanya memiliki fungsi epistemik, tetapi juga fungsi estetik. Begitulah fungsi filsafat sebagai teman ilmu-ilmu: mendengarkan dan mempelajari problem-problem ilmu-ilmu lain untuk membuka kemungkinan dialog lintas keilmuan.
Begitulah fungsi filsafat sebagai teman ilmu-ilmu: mendengarkan dan mempelajari problem-problem ilmu-ilmu lain untuk membuka kemungkinan dialog lintas keilmuan.
Namun, di kalangan orang yang menekuni bidang ilmu nonfilsafat, terutama ilmu-ilmu alam, filsafat ini tampak seperti mobil tua yang sudah ketinggalan zaman. Mereka menganggap filsafat sudah tak dibutuhkan lagi untuk mengembangkan bidang keilmuan mereka.
Mereka benar jika filsafat tetap dengan kejemawaannya. Oleh karena itu, untuk memoderasi spesialisasi ilmu yang ekstrem itu tanpa ekses matinya kepakaran, perlu ada kebijakan baru tentang kurikulum pendidikan di perguruan tinggi dengan mempertimbangkan secara serius posisi filsafat. Di setiap bidang keilmuan perlu diajarkan filsafat tentang ilmu terkait. Misal, filsafat biologi untuk bidang ilmu biologi; filsafat fisika untuk fisika; filsafat psikologi untuk psikologi; dan lain sebagainya.
Filsafat-filsafat tentang bidang ilmu tertentu itulah yang akan memungkinkan mahasiswa/dosen ilmu terkait untuk berdialog dan mencari landasan bersama dengan ilmu-ilmu lain yang relevan (misal: biologi dan psikologi). Mengapa harus melalui filsafat? Karena hanya filsafat yang secara metodologis mungkin untuk menjangkau banyak sekali disiplin. Melalui reposisi filsafat itulah nanti akan terbentuk jembatan ilmu-ilmu.
Siti Murtiningsih, Dekan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada

Siti Murtiningsih