Pendidikan Pancasila di Kurikulum Merdeka
Mata pelajaran PPKN di struktur Kurikulum Merdeka hilang, diganti Pendidikan Pancasila yang esensi muatannya Pancasila dan Kewarganegaraan. Sejauh ini belum belum ada naskah akademik mengenai konsep Pendikan Pancasila.
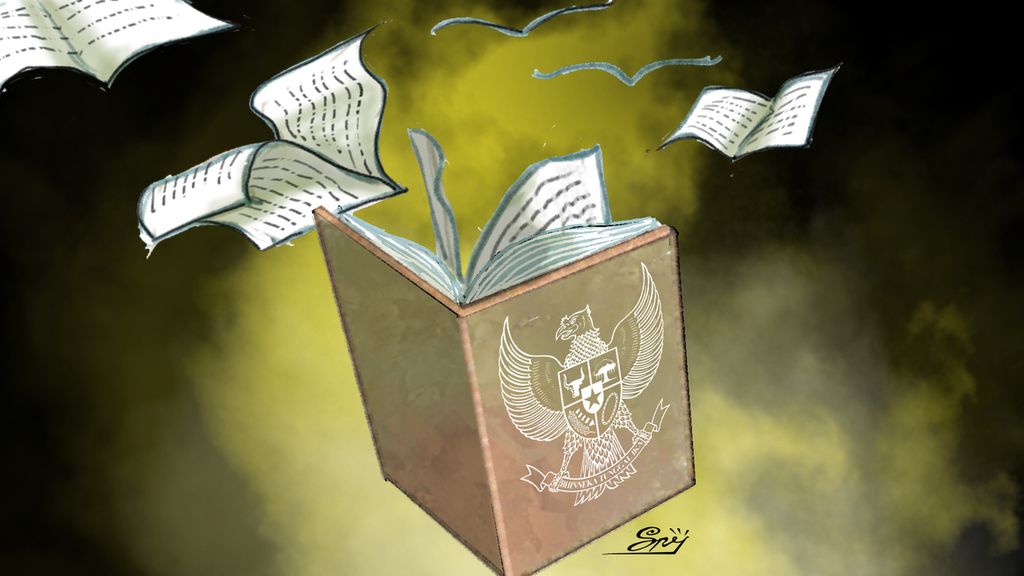
Ilustrasi
Satu perkembangan yang menarik dan patut ditelaah dalam Kurikulum Merdeka adalah hilangnya nomenklatur mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), berganti Pendidikan Pancasila.
Dalam sejarah kurikulum, PPKn paling sering berganti-ganti sejak Orde Lama hingga kini. Masa Orde Baru, pelajaran ini bernama Pendidikan Moral Pancasila atau PMP (Kurikulum 1975 dan 1984). Kedudukannya diperkokoh melalui Tap MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4).
Dalam Kurikulum 1994, PMP beralih nama ke PPKn. Melalui 36 butir nilai Pancasila (yang mesti dihafalkan siswa), PMP/PPKn menjelma sebagai unavoidable indoctrination (Udin S Winataputra, 2012).
Dijelaskan oleh pakar Pendidikan Kewarganegaraan Winarno (2006), PMP masa Orde Baru tidak memiliki vitalitas, tidak berdaya, dan tidak dapat berfungsi dalam meningkatkan kompetensi kewarganegaraan siswa. Siswa banyak tak suka karena merasa bosan. Guru bingung, sebab materi yang diajarkan tidak jelas dasar keilmuannya.
Baca juga: Persoalan Pendidikan Pancasila di Sekolah Dasar-Menengah
Materi pelajarannya nilai karakter normatif idealistik. Ruang lingkup materi sekitar kerukunan, persatuan, tenggang rasa, dan sejenisnya. Sekadar pengetahuan nilai yang dipaksa dikognitifkan, lalu direduksi berupa hafalan untuk diujikan. Tak terpadu dari aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Wajah PMP/PPKn tidak ilmiah.
PPKn tidak berkembang karena pendekatan dalam pembelajaran bersifat indoktrinatif, regimentatif, monologis, dan tidak partisipatif (Azyumardi Azra, 2008).
Pelajaran yang berorientasi membentuk “kepatuhan” ketimbang “kecerdasan” warga negara. Warga negara yang pasif dan penurut daripada aktif, partisipatif, dan demokratis. Siswa sekadar obyek bukan subyek pembelajaran. Tak heran membuat siswa mengantuk.

Siswa peserta Upacara Peringatan Hari Lahirnya Pancasila memerhatikan lukisan anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang terpasang di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (1/6). Gedung Pancasila merupakan saksi bisu kelahiran Pancasila pada 1 Juni 1945.
Kurikulum PPKn pascareformasi
Pasal 37 ayat 2, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyebutkan: “Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: (b) Pendidikan Kewarganegaraan.”
Untuk mengganti PPKn Kurikulum 1994, diliputi semangat pasca reformasi, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) lahir dengan materi dan pendekatan baru. Nama PKn sejak Kurikulum 2004 dan makin ajek di Kurikulum 2006.
Wajah PKn terasa “muda dan bergairah”, menonjolkan civics-nya. Bertujuan menyiapkan warga negara yang demokratis. Fokus agar warga negara memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya. Demi terbentuknya warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter seperti amanat UUD 1945.
Wajah PKn terasa “muda dan bergairah”, menonjolkan civics-nya. Bertujuan menyiapkan warga negara yang demokratis.
Materi dan ruang lingkup PKn: demokrasi, hak asasi manusia, konstitusi, persatuan dan kesatuan, kedudukan warga negara, sistem politik dan pemerintahan, ketatanegaraan, norma dan hukum, hubungan internasional, globalisasi, dan Pancasila.
Tampak basis keilmuannya, PKn dipandang disiplin ilmu sendiri, di negara lain disebut civic education atau citizenship education.
Praktiknya PKn terasa cognitive oriented (pengetahuan). Bergeser dari ruh pedagogis yang tak hanya menggerakkan olah pikir, tetapi juga olah rasa dan olah hati. PKn gagal merajut “tali tiga sepilin”: sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terintegrasi.
Kekurangan lainnya, Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara hanya diletakkan dalam satu materi pokok bahasan. Pancasila dilemahkan dan tersisih ke pojok rumah kurikulum nasional.
(Pendidikan) Pancasila perlahan kabur dalam ingatan kolektif anak bangsa, karena sudah kerdil dalam struktur kurikulum. Ekosistem sekolah berpancasila secara minimalis.
Baca juga: Nestapa Pendidikan Pancasila
Tujuh tahun umur Kurikulum 2006 pun diperbaiki, Kurikulum 2013. PKn turut pula beralih sebutan, balik ke PPKn meskipun terlahir dari regulasi selevel peraturan menteri. Dengan kompetensi serta karakteristik berubah.
Dasarnya lebih filosofis, terasa Indonesia-nya, dengan ruang lingkup paket lengkap: Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pengembangan materi PPKn berdasarkan -jika boleh disebut- empat konsensus kebangsaan di atas. Lebih kuat landasan filosofis, pedagogis, historis, dan sosiologisnya.
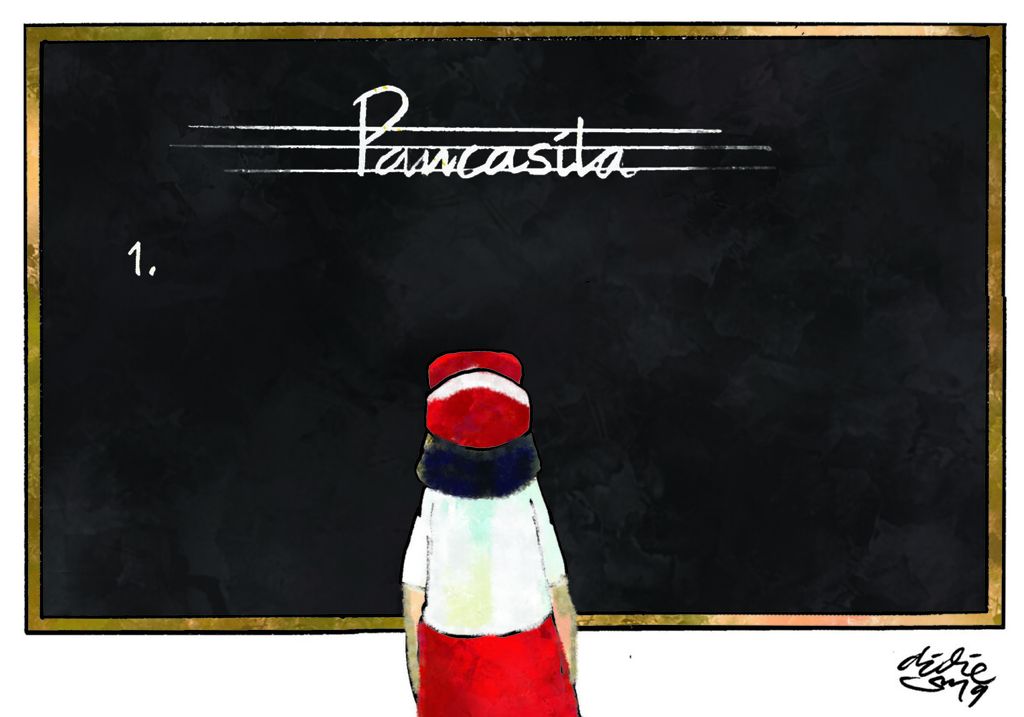
Pancasila dalam Kurikulum Merdeka
Seiring perkembangan politik pemerintahan, BPIP meminta Kemdikbudristek memasukkan Pendidikan Pancasila dalam kurikulum nasional. Pada 2017 wacana tersebut digaungkan pula oleh Menko PMK Puan Maharani, kemudian Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Desakan demikian lebih terasa pesan politisnya, ketimbang pedagogisnya.
“Memasukkan” Pendidikan Pancasila dalam kurikulum, punya celah hukum. Sebab UU Sisdiknas tidak mengenal Pendidikan Pancasila, hanya tertulis muatan Pendidikan Kewarganegaraan. Formula “menghidupkan kembali” PMP lebih problematik, sebab reinkarnasi PMP Orde Baru di sekolah tentu mengkhawatirkan akan memicu resistensi.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 diperbarui PP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan. Akhirnya menyebut eksplisit Pendidikan Pancasila,
Baca juga: Pancasila, Tidak Kurang Tidak Lebih
Muatan wajib dalam struktur kurikulum pendidikan dasar menengah di samping Pendidikan Kewarganegaraan (Pasal 40 ayat 2). Lebih dari itu, Pendidikan Pancasila naik kelas jadi Mata Pelajaran Wajib (Pasal 40 ayat 4).
Bahkan konsideran PP poin “menimbang”, tertulis: a) bahwa dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu menegaskan Pancasila sebagai muatan wajib dalam kurikulum setiap jenjang pendidikan.
Awal PP ini lahir, banyak misinterpretasi di kalangan guru PPKn dan dosen program studi PPKn. Mereka beranggapan PPKn dibagi ke dalam dua mata pelajaran berbeda terpisah: Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.
Padahal PPKn sekadar beralih nama jadi Pendidikan Pancasila, yang esensi muatannya ya Pancasila dan Kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila di sekolah pengguna Kurikulum Merdeka. Sementara itu, sekolah yang masih Kurikulum 2013 tetap PPKn.
Pendidikan Pancasila di sekolah pengguna Kurikulum Merdeka. Sementara itu, sekolah yang masih Kurikulum 2013 tetap PPKn.
Dalam Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi, elemen dalam Pendidikan Pancasila sama persis dengan ruang lingkup PPKn, yaitu empat konsensus tadi.
Isi dan karakteristik Pendidikan Pancasila tak ubahnya PPKn. Kendati isinya itu-itu juga, terkesan mengubah merek lebih menguntungkan (secara politik?) untuk klaim inovasi.
Desain tak memisahkan mata pelajaran (separated subject curriculum) Pancasila dan Kewarganegaraan di Kurikulum Merdeka, mengandung keuntungan sekaligus dilema.
Pertama, jumlah beban belajar siswa tak bertambah, andai terpisah tentu memberatkan, apalagi kelompok pelajaran umum di sekolah kita terlampau banyak dari pelajaran peminatan.
Kedua, guru Pancasila dengan satu pelajaran bisa lebih berkonsentrasi menghadirkan pembelajaran kreatif dan bermakna.
Ketiga, dilematis mengingat Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa kembali disejajarkan posisinya dengan UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, bagian dari elemen pembelajaran.
Baca juga: Inovasi Kurikulum Merdeka
Semestinya Pancasila dasar pengembangan, diarusutamakan, dan core pelajaran, saya pernah utarakan di harian ini (Kompas, 21/1/2022).
Keempat, belum ada naskah akademik Kemdikbudristek mengenai konsep Pendidikan Pancasila itu sendiri, yang mampu menjawab pertanyaan fundamental.
Bagaimana konstruksi keilmuan Pendidikan Pancasila? Apakah PKn bagian dari Pendidikan Pancasila? Atau Bagaimana hubungan PKn dengan Pendidikan Pancasila, dua disiplin berbeda dengan irisan persamaan atau memang menyatu?

-
Tantangan kebaruan guru
Namun, setidaknya terdapat dua perbaikan dalam struktur Kurikulum Merdeka perihal Pancasila. Pertama, proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila dengan skema project based learning, untuk semua mata pelajaran bersifat kolaboratif, kontekstual, dengan alokasi waktu dan rapor tersendiri. Pancasila ditempatkan menjadi asas pengembangan pendidikan dan kurikulum.
Kedua, fokus kepada materi esensial dalam pengembangan kompetensi siswa. Materi bahasan Pancasila tidak segemuk PPKn, karena kontennya makin sederhana dengan kompetensi terintegrasi.
Sehingga, guru dan siswa lebih fleksibel, kelonggaran waktu mengelaborasi kedalaman materi dan capaian pembelajaran, serta membangun pengalaman belajar yang variatif. Guru tak lagi dikejar-kejar penuntasan materi. Dibingkai teaching at the right level, yaitu pendekatan belajar yang tidak mengacu pada tingkat kelas, melainkan tingkat kemampuan siswa.
Setidaknya terdapat dua perbaikan dalam struktur Kurikulum Merdeka perihal Pancasila.
Lebih penting dan mendesak lagi, bagaimana pemahaman (mindset) guru terhadap paradigma dan spirit yang diusung sebuah kurikulum, apapun namanya. Jangan sampai konsep kurikulum bagus, yang ditangkap guru banyak reduksi bahkan distorsi, akibatnya gagal dalam implementasi.
Penting diinsafi, bagaimana cara guru membangkitkan gairah belajar, menghadirkan pembelajaran mengundang, menumbuhkan hasrat siswa mencintai ilmu, rakyat, lingkungan, dan negara, termasuk metode dalam membangun relasi pedagogik.
Baca juga: Pendidikan Kreatif
Pendidikan Pancasila akan terasa “baru”, jika guru meninggalkan pola ceramah satu arah dan indoktrinasi. Menuju praktik pembelajaran dialogis, kritis, demokratis, partisipatif, dengan mengedepankan tanggung jawab kewargaan (civic responsibility).
Demikian catatan yang menyisakan pekerjaan rumah bagi Kemdikbudristek dan guru Pancasila (PPKn). Bagaimanapun dinamika dan politisnya pertukaran nama pelajaran dan merek kurikulumnya.

Satriwan Salim, Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G); Wakil Ketua Umum Asosiasi Guru PPKn Indonesia (AGPPKnI)